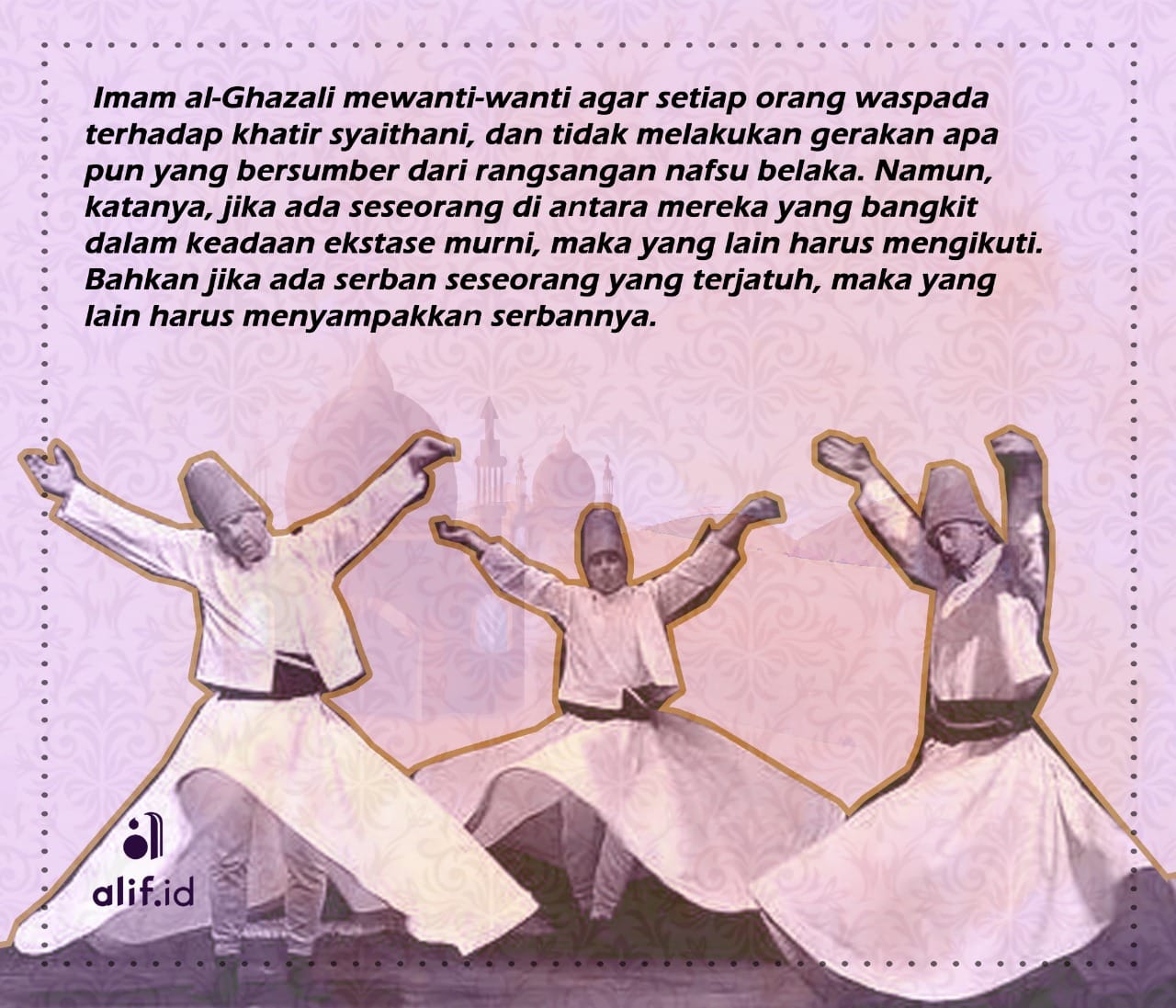Ada berbagai model tarian sufi. Dari yang dipengaruhi tarian perang, di negeri-negeri Afrika, hingga yang mendayu-dayu dan rampak mengikut suara kendang. Dua di antaranya, yang kemudian memikat banyak orang melintasi suasana ritmis keagamaan (tasawuf), dan bisa berfungsi sekadar kesenian profan, adalah tari Saman dan tarian Maulawi (para darwis yang berputar). Keduanya telah menjadi warisan dunia tak benda yang diakui UNESCO.
Tarian sufi, atau sema (sama’), lahir dari penghayatan keagamaan yang mendalam. Ketika zikir dan selawat dikumandangkan, para sufi yang mengonsentrasikan dirinya melalui hatinya—kepalamenunduk ke arah hati ruhani (dua jari di bawah puting susu)—kemudian bergerak secara perlahan namun pasti, ritmis, ke dalam penghayatan akan kehadiran Tuhan melalui zikir (syair) dan selawat yang dilantunkan nasyid. Para murid (tarekat) Maulawiyah “masuk” lebih ke dalam, mereka hanyut dalam putaran dan diam (tak bersuara).
Para “penari” Saman bergerak rancak sambil menyanyikan selawat. Sedangkan di Sudan, para murid Sammaniyah melompat-lompat semangat sambil menyerukan dzikir nafi itsbat, “La ilaha illa Allah” hingganya sekadar hembusan keras nafas “Ah, ah, ah!”
Gerakan mereka tampak ritmis dengan dipandu para mursyid atau wakil mursyid. Dikendalikan intuisi yang dalam, mereka bergerak serentak dan padu. Mereka menyimak (sama’ berarti mendengar atau menyimak) syair-syair ketuhanan, semua indera ditutup kecuali pendengaran.
Terkait hal ini al-Ghazali dalam Kimya’ as-Sa’adah menyebutkan,
“Dalam pertemuan-pertemuan semacam itu (Sema) perhatian ditentukan sesuai keadaan tempat dan waktu. Dan tak pantas, orang yang hatinya kotor berada di sana. Orang-orang yang ikut serta hendaknya duduk berdiam diri, tidak saling melihat, menundukkan kepala dan memusatkan pikiran mereka kepada Allah.”
Imam al-Ghazali mewanti-wanti agar setiap orang waspada terhadap khatir syaithani, dan tidak melakukan gerakan apa pun yang bersumber dari rangsangan nafsu belaka. Namun, katanya, jika ada seseorang di antara mereka yang bangkit dalam keadaan ekstase murni, maka yang lain harus mengikuti. Bahkan jika ada serban seseorang yang terjatuh, maka yang lain harus menyampakkan serbannya.
Tentu saja yang demikian tidak ada contohnya dari Nabi saw. Karenanya para ulama Zhahiri mengutuk perbuatan ini. Menurut mereka, ekspresi kecintaan kepada Tuhan yang bersifat ekstatif hanyalah proyeksi khayalan belaka. Cinta kepada Allah menurut mazhab Zhahiriah hanya berarti (melalui) ketaatan dan ibadah.
Mengkonter hal ini al-Ghazali, secara syariat berpendapat, musik dan tari sekadar membangunkan emosi (perasaan cinta kepada Allah), dan karenanya diperbolehkan (dihukumi mubah). Bahkan kata a-Ghazali, dapat dihukumi sunnah (patut dipuji) jika dapat menambah kecintaan kepada Allah, dengan catatansi pelaku dapat memurnikan hati dari pengaruh nafsu indrawi. Ia mendasarkan pendapatnya pada hadis Aisyah, dan mengqiyaskannya dengan “nyanyian” orang yang menjalankan ibadah haji, musik pembangkit semangat perang, serta kidung Nabiyullah Daud.
Bagi pemerhati Barat ekspresi “seni” agama, seperti pada the whirling dervishes, yang demikian memiliki nilai keindahan yang eksotis. Tidak heran, bentuk-bentuk semacam itulah yang memancing perhatian mereka pertama kali pada sufisme.
Penelusuran mereka yang mendalam hingga kepada bentuk-bentuk nyanyian (syair) bagaimana yang dapat memotivasi gerakan-gerakan yang awalnya janggal bagi mereka itu. Mereka heran, seperti halnya para reformis Islam abad ke-20, mengapa dari agama yang sangat menekankan disiplin baku (dalam syariat) bisa lahir ekspresi sedemikian rupa, dan ini terkesan paradoks bagi mereka.
Hal ini setidaknya dapat terbaca melalui laporan-laporan para peneliti Asing (Barat) pada abad ke-18hingga pertengahan abad ke-20. Demikian dinyatakan Carl W. Ernst, dalam Shambhala Guide to Sufism (1997).
Syekh Abdul Qadir al-Jilani dalam al-Ghunyah menyatakan bahwa kaum sufi ahli tarekat tidak berpura-pura mengalami sama’, dan tidak menerimanya dengan sengaja. Meski demikian, mereka yang mengalaminya harus tetap menjaga adab, berzikir kepada Allah dalam batinnya, dan sibuk menjaga batinnya dari kelalaian dan kealpaan.
Jika dalam perhelatan itu ia mengalami kondisi seolah-olah lisan sang pembaca, yang disimaknya, adalah lisannya dan seolah-olah ia sedang berbincang dengan al-Haq melalui bacaan itu, maka apa yang dirasakan hatinya sudah sesuai dengan hak kehambaan dan etika syariat.
Sema yang sesungguhnya, menurut Syekh al-Jilani, adalah perasaan ekstase ketika mendengar Kalam Allah, yang menjadi tradisi para ulama ahli makrifat dan kaum khas dari kalangan wali, abdal, dan tokoh-tokoh spiritual.