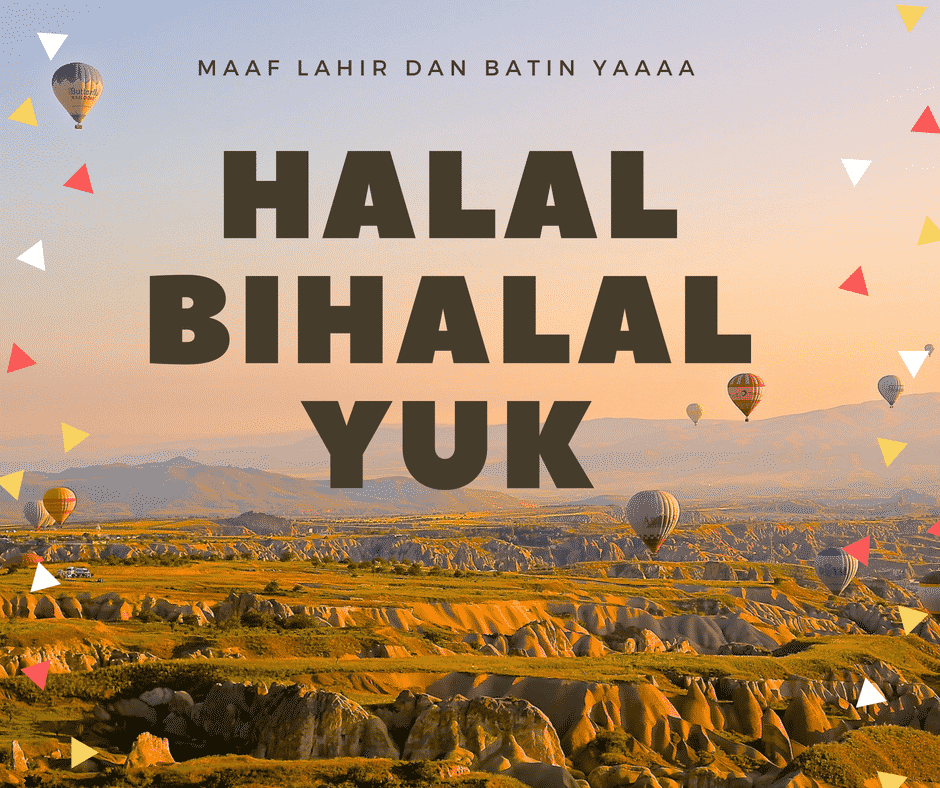Ada sesuatu yang tak pernah berubah dari Lebaran: rindu untuk pulang. Rindu pada aroma tanah dan dapur rumah ibu, pada suara takbir di mushala/surau kampung, atau sekadar rindu duduk di beranda rumah tua sambil mendengarkan obrolan tetangga yang tak pernah lekang oleh waktu. Mudik, lebih dari sekadar perjalanan fisik, adalah pulang batin. Ia menyambungkan manusia pada akar, pada kenangan, dan pada siapa diri kita sebenarnya.
Tapi Lebaran tahun ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Data Kementerian Perhubungan mencatat, jumlah pemudik 2025 mengalami penurunan signifikan: dari 193,6 juta orang tahun lalu menjadi 146,48 juta orang. Penurunan sekitar 24 persen ini bukan sekadar angka, melainkan cerita diam-diam tentang realitas baru.
Saya bertanya pada seorang rekan yang tahun ini tak jadi mudik. Alasannya sederhana: tiket moda transportasi terlalu mahal, cuti pendek, dan ia ingin “irit” dulu. Ia bukan satu-satunya. Harga tiket melonjak tajam, terutama untuk arus balik. Rute Medan–Jakarta, misalnya, bisa mencapai tiga kali lipat dari tarif biasa. Bus antarkota pun ikut naik sejak pertengahan Maret. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, mudik menjadi keputusan yang perlu dipertimbangkan matang-matang, bukan sekadar dorongan emosional. Apalagi ditambah dengan perekonomian negara yang kurang stabil karena melakukan efisiensi anggaran, dampak yang dirasakan mudik tahun ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya..
Situasi ekonomi yang menantang juga tampak dari proyeksi perputaran uang selama musim Lebaran 2025 yang mencapai Rp137,9 triliun, turun dari Rp 157,3 triliun tahun lalu. Banyak keluarga harus mengencangkan ikat pinggang. Rindu pun harus bernegosiasi dengan realitas. Tak sedikit yang akhirnya mengganti mudik dengan “pulang virtual”. Panggilan video dari ruang keluarga di Jakarta ke meja makan di kampung halaman. Kiriman hampers sebagai pengganti pelukan. Semuanya terasa baik, praktis, dan cukup. Tapi benarkah cukup?
Sementara itu, generasi muda yang lahir dan besar di kota, kadang mengalami jarak emosional dengan kampung halaman orang tuanya. Mereka datang, tapi tidak benar-benar merasa pulang. Pulang menjadi agenda, bukan kebutuhan batin. Kampung jadi tempat singgah, bukan tempat kembali. Padahal, urgensi mudik bukan hanya pada pertemuan fisik, tapi pada penguatan identitas. Di sana, anak-anak mengenal tanah kelahiran orang tuanya, mencicipi makanan yang tak ada di ibu kota, dan belajar menyapa tetangga dengan dialek yang khas. Mudik menjadi sarana pewarisan nilai yang tidak bisa diajarkan di kelas atau sekolah mana pun. Ia membangun rasa keterikatan, rasa memiliki, dan dalam banyak kasus, rasa tanggung jawab.
Dalam banyak cerita orang Jawa, mudik sering kali dimaknai sebagai bentuk ruwatan—pembersihan diri dari beban lahir batin. Bukan sekadar pulang secara fisik, melainkan pulang untuk melepaskan kepenatan hidup, membersihkan luka batin, dan memohon restu agar perjalanan hidup ke depan lebih ringan. Mudik menjadi ruang spiritual yang tak tergantikan: tempat seseorang menundukkan diri di hadapan orang tua, mencium tangan mereka dengan penuh haru, dan dalam diam menyampaikan rasa syukur sekaligus permohonan ampun. Di sana, ada perasaan diterima kembali tanpa syarat, sesuatu yang sering hilang dalam hiruk-pikuk kota.
Bagi banyak orang, mudik juga menjadi proses merawat diri—menyegarkan kembali jiwa yang aus oleh rutinitas. Di kampung, waktu berjalan lebih lambat. Obrolan tak diburu, makan bersama lebih sering terjadi, dan senyum datang tanpa basa-basi. Kita kembali belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu harus mahal; cukup dengan duduk bersama keluarga sambil menyesap teh hangat dan mendengarkan suara jangkrik di malam hari. Mudik menjadi jeda yang menyadarkan kita bahwa dalam diri yang terus mengejar, ada sisi lain yang perlu dipeluk: sisi yang hanya bisa tenang saat berada di rumah, dalam arti yang paling dalam.
Begitu pula halalbihalal. Tradisi yang katanya hanya ada di Indonesia ini memegang peran penting sebagai ruang pemulihan relasi sosial. Dalam suasana Lebaran yang khusyuk, halalbihalal memberi waktu untuk menyambung kembali hubungan yang sempat renggang—baik dalam keluarga, tetangga, komunitas, hingga sesama rekan kerja. Ia mengajarkan bahwa memaafkan bukan tentang menghapus kesalahan, tapi tentang membangun ulang jembatan yang sempat runtuh.
Kita sering lupa bahwa nilai-nilai seperti menghormati orang tua, menjaga silaturahmi, atau merawat persaudaraan adalah kekayaan tak ternilai dalam budaya kita. Di tengah dunia yang makin kompetitif dan individualistik, tradisi seperti mudik dan halalbihalal menjadi ruang resistensi kecil terhadap keterasingan. Di saat banyak orang merasa kesepian meski dikelilingi teknologi, tradisi ini memberi tempat untuk merasa didengar, dilihat, dan diterima. Namun tentu saja, bentuknya tak harus selalu seperti dulu. Yang penting bukanlah apakah kita duduk di ruang tamu atau di grup Zoom, melainkan apakah kita sungguh hadir. Apakah kita mau membuka hati, bukan hanya kamera. Apakah kita menyampaikan maaf dengan suara, bukan hanya stiker.
Jika mudik adalah perjalanan, maka halalbihalal adalah perhentian. Di sanalah orang-orang saling menundukkan ego, meminta maaf atas luka lama, menyambung kembali simpul-simpul hubungan yang sempat renggang. Dulu, acara halalbihalal berlangsung dari pagi sampai malam. Siapa pun boleh datang, tak perlu undangan, cukup ketuk pintu, duduk, makan, dan saling memaafkan.
Kini, halalbihalal juga mulai berubah. Grup WhatsApp keluarga menjadi tempat ucapan maaf kolektif. Beberapa cukup dengan mengunggah foto keluarga dan menulis “mohon maaf lahir batin”. Simbolik, cepat, tapi sering terasa hampa. Ada momen yang luput: tatapan mata, senyum canggung, atau tangan yang menggenggam erat sambil berucap tulus. Namun kita juga tak bisa menghakimi. Hidup bergerak cepat. Waktu berkumpul menjadi barang mewah. Tapi justru karena itulah, nilai-nilai di balik tradisi ini semakin layak diperjuangkan.
Beberapa keluarga mulai menyiasati hal ini dengan cara kreatif. Ada yang mengadakan halalbihalal bertema—di taman, dengan aktivitas sosial, atau sekadar piknik santai. Ada pula komunitas yang mengemasnya sebagai ruang untuk berbagi kisah dan belajar memahami perbedaan.
Halalbihalal bukan soal meja panjang berisi kue kering dan sirup warna-warni. Ia tentang niat untuk hadir—secara utuh—di tengah orang-orang yang pernah dan masih menjadi bagian penting hidup kita. Teknologi bisa menjadi alat, bukan pengganti. Video call tak akan bisa menggantikan pelukan ibu, tapi bisa menjembatani jarak. Grup keluarga tak akan menggantikan percakapan di ruang tamu, tapi bisa menjaga koneksi saat dunia sedang bergegas.
Menjaga yang Layak Dijaga
Tradisi, pada akhirnya, bukan benda mati yang harus dibingkai dalam bentuk lama. Ia adalah makna yang terus hidup, yang bisa kita rawat dalam cara baru. Kita tak perlu bersikukuh bahwa mudik harus lewat jalan tol atau halalbihalal harus dalam ruang tamu rumah besar. Yang penting adalah alasan kita melakukannya: karena kita ingin pulang, dan ingin saling memaafkan.
Generasi hari ini perlu tahu bahwa dalam segala gempuran dunia modern, ada sesuatu yang layak dijaga: rasa memiliki, rasa pulang, dan rasa terhubung. Bukan karena tradisi itu romantis, tapi karena ia manusiawi. Karena di balik semua perbedaan zaman, semua orang tetap butuh tempat untuk kembali—meski hanya lewat suara, tawa, atau cerita.
“Tradisi bukan tentang berulang-ulang melakukan hal yang sama, tapi tentang mengingat siapa kita, dan untuk siapa kita selalu ingin pulang.”