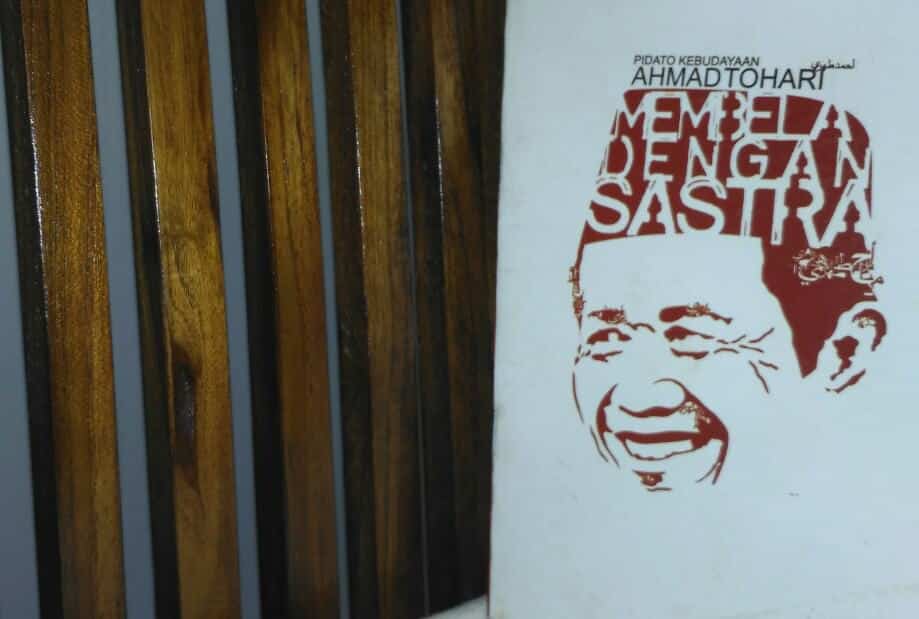“Penyuluh agama diibaratkan sebagai anak sulung dalam keluarga,” tulis di Republika, 18 Januari 2019. Dua halaman penuh membahas peran penyuluh agama di Indonesia. Pengibaratan anak sulung itu mungkin berlebihan dalam menjelaskan peran terpenting penyuluh agama adalah dekat dengan warga atau umat.
Mereka menjadi penjelas atau pengisah segala hal. Berkeliling dan bertemu warga bermisi penerangan, dakwah, dan konfirmasi. Penyuluh agama itu pekerjaan di naungan Kementerian Agama. Di Indonesia, ada puluhan ribu penyuluh agama. Kini, peran mereka semakin besar gara-gara radikalisasi dan hajatan demokrasi.
Pemberian peran itu baku. Di Republika, kita disodori pengertian: “Penyuluh agama menjadi struktur paling bawah yang bertugas memberi penyuluhan agama di tingkat kecamatan dan desa. Mereka menjadi corong pemerintah sebagai penyampai pesan kepada masyarakat sekaligus sumber informasi pemerintah pusat.” Sebutan atau predikat penyuluh itu bersumber dari kata suluh. Kata khas dan puitis. Sebutan sudah lama berlaku di Indonesia, sejak puluhan tahun silam.
Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) mengartikan suluh: “barang jang dipakai untuk menerangi.” Pengertian mengejutkan di penyuluh: “pengintai, penjelidik, mata-mata.” Kamus lawas itu memang belum memberi latar agama bagi predikat penyuluh agama. Pengertian berbeda dari pekerjaan itu dibuat oleh pihak pemerintah. Pejabat di Kementerian Agama memberi keterangan tentang penyuluh agama di abad XXI: “Keberadaan penyuluh agama sudah ada sejak 1951. Para penyuluh agama pada dasarnya adalah dai dan ustaz yang juga sering memberikan dakwah di masyarakat. Di luar tugasnya sebagai penyuluh, mereka bebas menjalankan pekerjaannya sendiri tanpa intervensi pemerintah.”
Dua halaman mengulas penyuluh agama di Republika itu sulit memanggil sejarah atau mengingatkan ke pembaca cara pemaknaan di masa 1950-an. Masa itu Indonesia sedang berdemokrasi dengan seribu bantahan dan keberanian. Ulasan tak lengkap. Di luar ulasan, kita membuka kembali majalah-majalah masa 1950-an. Dulu, umat mendapat bacaan rutin berupa majalah bernama Penjuluh Agama. Di Bilik Literasi (Solo), kita masih bisa membaca puluhan edisi Penjuluh Agama masa 1950-an sampai 1960-an.
Kita pantas memuji bahwa tata cara berdakwah atau penerangan dari misi-misi pemerintah di masa lalu memilih suguhan majalah. Nama majalah itu kentara menjelaskan keinginan pemerintah di pembesaran dakwah dan tebar pengertian ke umat. Majalah Penjuluh Agama memiliki pengenalan sebagai “madjalah pengetahuan, keagamaan, kesusilaan dan pembangunan pribadi.” Majalah diterbitkan oleh Kementerian Agama. Majalah itu dijual, bukan dibagikan gratis.
Kita simak Penjuluh Agama edisi Maret 1955. Edisi di “tahun demokrasi” itu mengulas perkawinan, dakwah, pendidikan, sastra, filsafat, dan sejarah. Tulisan-tulisan berbobot dihidangkan ke pembaca. Pilihan menerbitkan majalah berlatar masa 1950-an memang memungkinkan ada kepahaman kolosal jika ribuan orang mau tekun membaca. Di situ, kita membaca puisi panjang berjudul: “Kepada Pangeran Dipanegara Abdul Hamid Sajidin Penatagama.” Puisi gubahan Bahrum Rangkuti itu berkesan sejarah dan berkaitan keinginan orang-orang Indonesia mendapatkan tokoh heroik. Puisi pun ingin jadi suluh atau menerangi.
Bahrum Rangkuti menulis: Kami dengar lagi derap kudamu/ Kjahi Gentaju sekita sungai Bogowonto/ desing melontjati tubir-tubir batu/ kedalam semak belukar/ dan pandangmu tadjam memantjar/ untuk membina kedjajaan bangsa/ untuk menjebar ajat Ilahi Jang Maha Esa. Bait menggugah bagi pembaca mau meneladani Pangeran Diponegoro dalam pengertian politik dan agama. Puisi itu membarakan keinginan orang-orang Indonesia memajukan negara-bangsa dengan ingin dan keinsafan atas demokrasi. Pada masa 1950-an, simbol-simbol Islam pada sosok Pangeran Diponegoro masih menguat, “suluh” bagi keinginan mewarisi heroisme dan religiositas.
Di majalah, orang mendapat penerangan secara “baru”, tak melulu para penyuluh agama wajib selalu bertemu dan menerangkan dengan lisan. Penerbitan Penjuluh Agama sudah memastikan ada keinginan besar mengetahui pelbagai tanggapan umat. Tulisan demi tulisan itu suluh. Tata cara lama itu mungkin sudah tak dilanjutkan. Kenangan pun sulit lengkap dengan bukti tak ada Penjuluh Agama di ulasan dua halaman di Republika.
Kita menengok ke Penjuluh Agama edisi Mei 1956. Indonesia masih negara muda. Ingatan-ingatan masih pendek atau ringkas memerlukan ada peringatan secara bermutu. Kita di hadapan tulisan berjudul “Peringatan 10 Tahun Berdirnja Kementerian Agama.” Sejarah belum jauh tapi pantas dituliskan dan disampaikan ke umat menjadi kenangan bersama. Kita di babak permulaan Kementerian Agama: “Di waktu kita memperingati 10 tahun berdirinja Kementerian Agama pada saat ini, kami menganggap penting sekali untuk mengetengahkan sikap atau pendirian pemerintah tentang politik keagamaan dalam negara Republik Indonesia.
Buaian sastra tetap disajikan bermaksud menjadikan penyuluh agama mengerti siasat berkomunikasi dengan tebaran makna. Pemuatan terjemahan dari puisi gubahan Muhammad Iqbal. Puisi berjudul “Pesan kepada Pemuda Islam” terasa seruan atau anjuran pada kebangkitan berlatar abad XX. Puisi cocok membekali penyuluh agama menemui umat di desa atau kota: Bangkitlah kau, oleh tjinta, semua soal-soal remeh/ Pada kedjajaan dan kemasjhuran:/ Suluh kau dunia jang meraba-raba ini/ Dengan nama Muhammad saw. Pekerjaan di naungan Kementerian Agama itu boleh diwujudkan secara puitis ketimbang bahasa-menerangkan cenderung politis.
Penjuluh Agama termasuk majalah rutin terbit melewati tahun demi tahun. Pada masa 1960-an, majalah keluaran pemerintah itu tetap diminati pembaca. Penjuluh Agama edisi Maret-April 1961 dimulai dengan kutipan dari pidato Soekarno. Bereferensi Al Quran, Soekarno berseru: “Quran telah membawa suatu revolusi jang mahahebat, bukan hanya revolusi seperti kita, tapi lebih hebat lagi. Ia membawa revolusi bathin, revolusi pandangan manusia, revolusi ekonomi, revolusi hubungan manusia dengan manusia. Revolusi jang berupa perubahan-perubahan mutlak dari bentuk manusia baru didunia, revolusi moral dan lain-lain sebagainja.” Petikan itu mungkin menggugah bagi parfa penyuluh agama tak lupa mengingatkan Islam dan revolusi pada umat.
Sekian ingatan dan cuplikan dari majalah Penjuluh Agama masa 1950-an dan 1960-an agak membenarkan peran besar penyuluh agama dalam penerangan ke umat. Majalah Penjuluh Agama sudah masa lalu. Kini, para penyuluh agama melalui ketentuan-ketentuan dari pemerintah mulai menerapkan penerangan mutakhir. Mereka tentu membekali kerja dan dakwah itu dengan gawai, tak lagi wajib bermajalah bercap literasi lawas. Begitu.