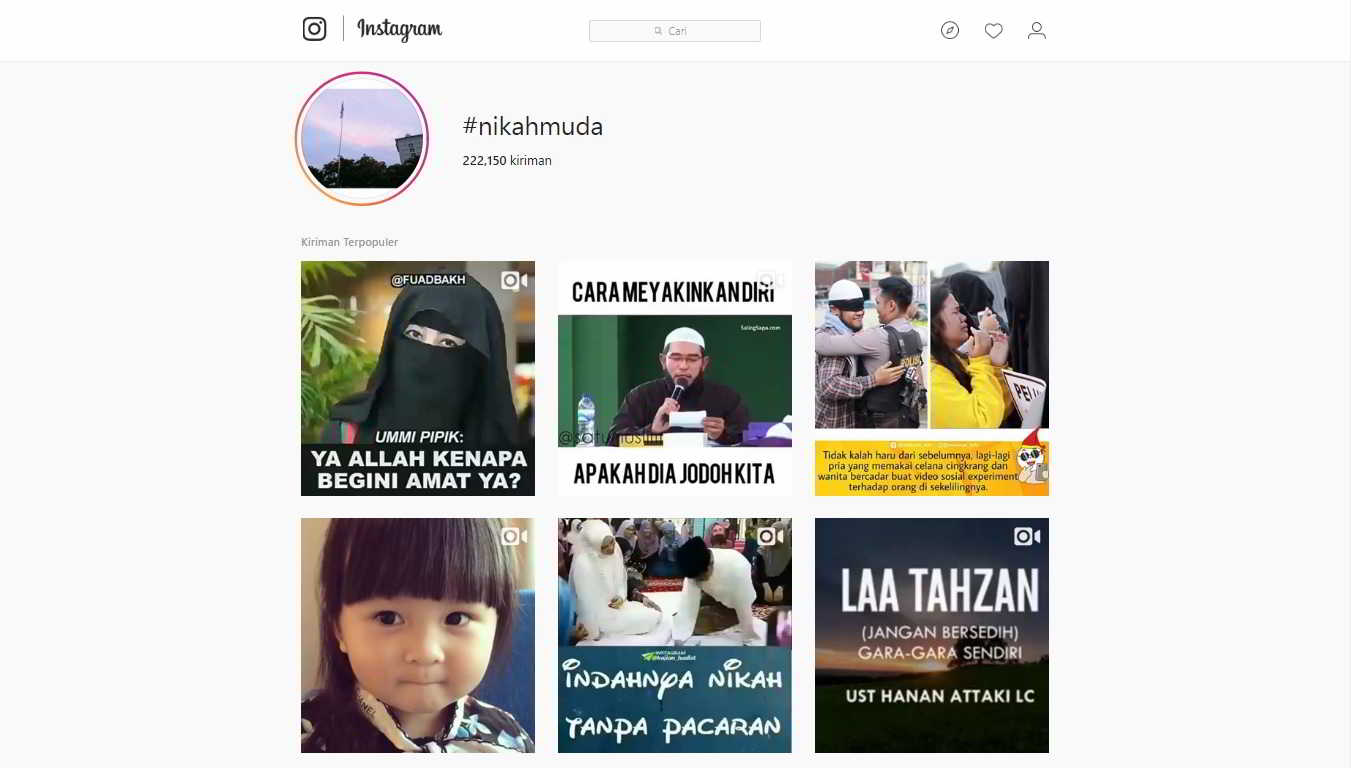Barangsiapa yang mengenal nama KH. Ahmad Dahlan sudah seharusnya juga tahu nama Nyai Ahmad Dahlan. Jika Kiai Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, maka istrinya tersebut merupakan pelopor Aisyiyah, orgonasisasi otonom ibu-ibu di kalangan ormas Islam berlambang matahari tersebut.
Nyai Dahlan bukan sekadar konco wingking bagi sang kiai. Ia juga turut aktif berjuang membesarkan organisasi.
Nyai Dahlan bernama asli Siti Walidah. Lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 3 Januari 1872. Ia adalah putri dari seorang penghulu di Keraton Yogyakarta bernama KH. Muhammad Fadhil bin KH. Ibrahim bin Kiai Muhammad Hasan Pengkol bin Kiai Muhammad Ali Ngraden Pengkol.
Orang tuanya yang merupakan seorang ulama ternama, menjadi guru pertama Siti Walidah. Seperti halnya membaca al-Quran dan berbagai kitab agama. Meskipun ia menjalani kehidupan yang tertutup (dipingit) semasa kecilnya, namun tak membuat Siti Walidah kehilangan teman dan beraktivitas sosial. Sebagaimana ditulis Suratmin dalam bukunya, Nyai Ahmad Dahlan (1981), Siti Walidah pandai mengorganisir kawan-kawannya yang mengaji kepada orang tuanya agar lebih antusias belajar.
Bakat kepemimpinan Walidah yang telah menonjol sejak belia itu, membuat Muhammad Darwisy - nama asal KH. Ahmad Dahlan - kepincut. Sutrisno Kuntoyo dalam "Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah (1998)" menulis demikian:
"Kiai Haji Ahmad Dahlan tertarik pada Siti Walidah bukan semata-mata kecantikan lahiriah, tetapi terutama sekali sebagai seorang wanita yang dapat dijadikan teman seperjuangan bagi cita-citanya."
Apa yang ditulis oleh Sutrisno Kuntoyo tersebut, bukan sekadar kesimpulan serampangan. Namun, Siti Walidah benar-benar menjadi pendamping yang ideal bagi Ahmad Dahlan. Ia turut terlibat dalam berbagai gerakan sosial keagamaan yang dirintis suaminya. Mulai dari mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah di Kauman yang terus berkembang, hingga mendirikan organisasi Muhammadiyah.
Ketika Kiai Dahlan berfokus menggarap kaum bapak, Nyai Dahlan mengurus kaum ibu-ibunya. Ia mendirikan kelompok pengajian Sopo Tresno pada 1914. Awalnya pesertanya hanyalah kalangan ibu-ibu buruh batik yang awam. Mereka belajar agama kepada Nyai Dahlan. Seiring tahun, gerakan tersebut semakin besar. Tak hanya kalangan buruh batik yang ikut, tapi juga ibu-ibu dengan beragam latar belakang.
Gerakan tersebut kemudian dilirik oleh sejumlah pengurus Muhammadiyah. Lantas, pada 1917 disepakati jika Sopo Tresno menjadi bagian resmi dari Muhammadiyah dengan nama Aisyiyah. Awalnya hanya berupa bagian, namun seiring meluasnya keanggotaan Aisyiyah sendiri, pada 1927 dinyatakan sebagai majelis tersendiri. Aisyiyah menjadi organisasi otonom Muhammadiyah yang memiliki kepengurusan pusat (hoofdbestuur) tersendiri.
Dalam Aisyiyah, Nyai Dahlan memang tak pernah menjabat sebagai ketua. Ia hanyalah menjabat sebagai penasehat (adviseur). Namun, dedikasi dan pengaruhnya di organisasi perempuan tersebut, sangatlah besar. Nyaris setiap kongres, ia selalu datang. Tercatat hanya sekali beliau absen, yakni saat pelaksanaan Kongres Muhammadiyah dan Aisyiyah di Medan pada 1939. Selain itu, senantiasa hadir, hatta tubuhnya dibekap sakit reumatik. Seperti saat Kongres di Jakarta pada 1940.
Tak hanya di acara-acara besar seperti Kongres, Nyai Dahlan juga turut datang ke berbagai acara Aisyiyah di cabang-cabang. Ia menjadi mubalighah kondang yang kehadirannya senantiasa dinantikan dan dielukan oleh warga persyarikatan.
Di tengah aktivitasnya berkeliling menemui warga Muhammadiyah tersebut, seringkali terselip kisah-kisah yang heroik dan mengharu biru. Namun, juga terjadi kejadian-kejadian yang jenaka. Kocak. Seperti halnya aksi spontan Nyai Dahlan yang diceritakan oleh Muhammad Yunus Anis (Ketua Umum PP Muhammadiyah 1959-1962) dalam bukunya, "Riwajat Hidup Njai Ahmad Dahlan (1968)".
Suatu hari pada 1927, Hoofdbestuur Muhammadiyah dan Aisyiyah menghadiri acara di Boyolali. Kedua rombongan tersebut terdiri dari Nyai Ahmad Dahlan beserta utusan Aisyiyah lainnya. Sementara dari Muhammadiyah turut hadir Yunus Anis yang masih menjadi anggota muda kala itu.
Rombongan tersebut mengendarai kereta api. Utusan Aisyiyah berada di depan, sementara yang Muhammadiyah berada di deretan kursi belakangnya. Kereta api pada masa itu, tak sebaik saat ini. Masih bebas untuk melakukan berbagai aktivitas. Jendelanya pun bisa dibuka untuk mengalirkan udara segar. Penumpang pun bisa leluasa mengeluarkan tangan atau meludah keluar.
Nyai Dahlan yang kala itu mengunyah sirih pun dengan santai meludahkan liur sisa menyirihnya keluar jendela. Pada saat bersamaan, ternyata Yunus Anis mengeluarkan lengannya kaluar jendela. Tak ayal ludah Nyai Dahlan itu pun mengenai lengan Yunus Anis. Baju putih yang membungkus tangannya itu pun terdapat bercak merahnya.
"Dengan diam-diam sesampai di Bojolali, saja berkata kepada Utusan H.B (hoofdbestuur/ Pengurus Pusat, pen) jang saja iringinja bahwa saja tidak turut hadir apa lagi berpidato dalam openbare vergedering (rapat terbuka) jang diadakan, karena malu lengan badju kemudahan sirih dan tidak membawa badju untuk ganti."
Pada pagi harinya menjelang acara openbare tersebut, Nyai Dahlan mendapat laporan perihal halangan yang ditanggung Yunus Anis. Mendengar kabar tersebut, spontan Nyai Dahlan mencari Yunus Anis.
"Tidak sengadja, jang kena ludah sirih hanja sedikit," ujar Nyai Dahlan sembari menggunting kertas berwarna putih dan menempelkan ke lengan baju Yunus Anis yang terkena noda dan kebetulan juga berwarna putih.
Lucunya, kertas tersebut bukan ditempel menggunakan lem atau selotip sebagaimana umumnya. Nyai Dahlan tak ambil pusing, mengambil ketupat yang jadi bekalnya untuk merekatkan kertas tersebut. Jadilah potongan kertas dengan perekat ketupat itu menempel di lengan baju Yunus Anis. Menutup bercak merah ludah sirih.
"Nah, sudah tidak nampak. Kalau pidatomu nanti lantang dan berkobar-2, orang kan tidak melihat tambalan kertas ini," ungkap Nyai Dahlan.
Berkat aksi spontan Nyai Dahlan yang cukup kocak tersebut, ternyata membuat Yunus Anis tak lagi malu. Ia pun berpidato pada openbare vargedering yang dihadiri ribuan warga Muhammadiyah di Boyolali itu. "Saja sendiripun turut berpidato dengan tidak malu sedikit djuga, karena mendapat dorongan dari Njai A. Dahlan jang pandai membesarkan hati," aku Yunus Anis.
Memang demikian seharusnya seorang pemimpin besar. Pandai membesarkan hati dan cepat mencari solusi atas berbagai permasalahan secara tangkas, efisien dan spontan. Hehehe.
Pada 31 Mei 1946 pukul satu siang, Ibu Muhammadiyah tersebut menghembuskan napas terakhirnya.
Al-Fatihah..