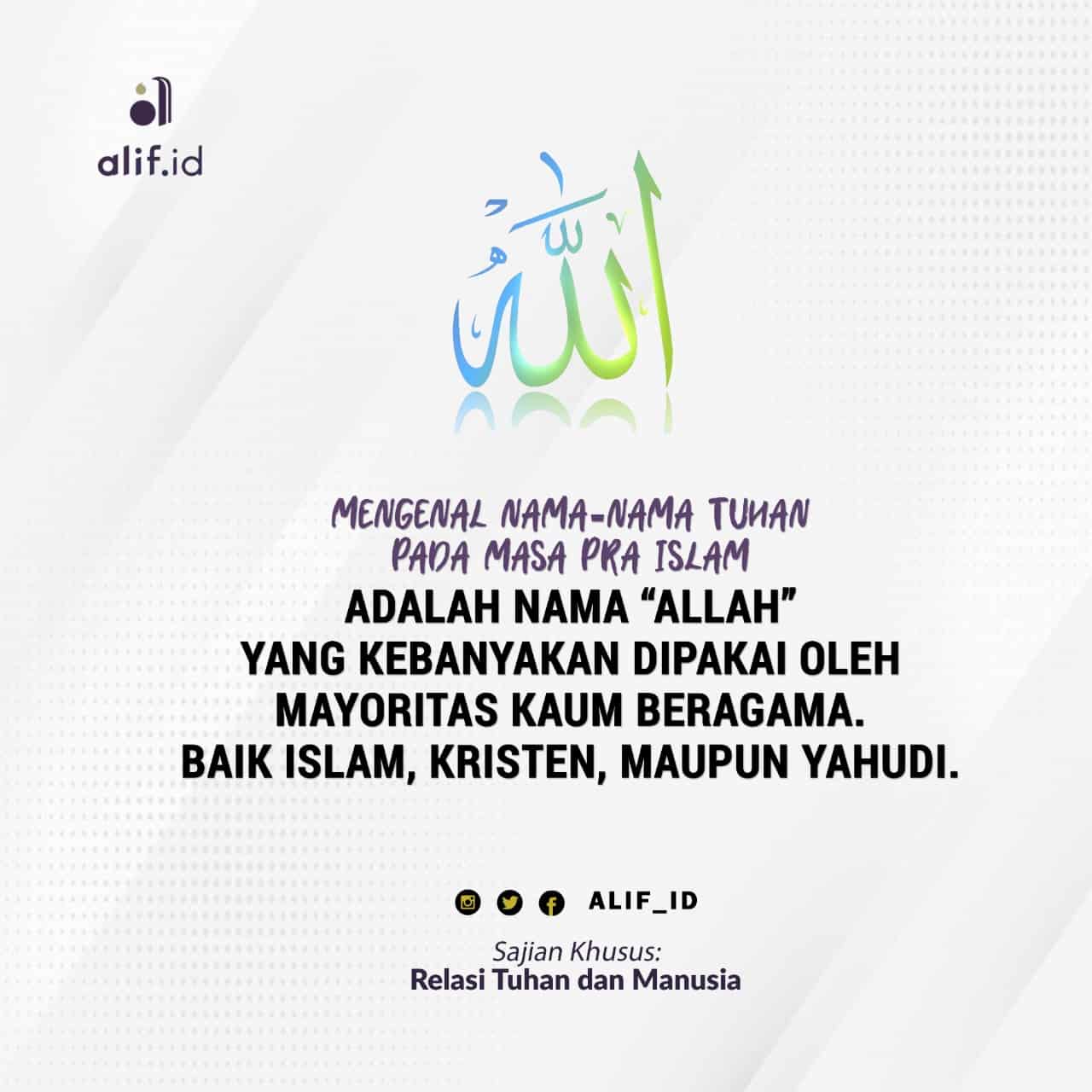Setiap agama atau keyakinan telah mempunyai cara pandang yang berbeda di dalam mengenal nama, sifat, dan bentuk Tuhan. Adalah nama “Allah”, yang kebanyakan dipakai oleh mayoritas kaum beragama. Baik Islam, Kristen, maupun Yahudi. Allah adalah nama Arab dari Tuhan Yang Esa. Semua agama menuju kepada-Nya. Nama itu menjadi perwakilan untuk menyebut Zat Yang Maha Kuasa. Namun, nama Allah acap kali menuai polemik oleh sebagian masyarakat tertentu.
Jika dicermati, nama “Allah” terbentuk dari kata sandang “al” (alif lam ma’rifah) dan kata “ilah” (tuhan ‘t’ kecil). Dalam ilmu linguistik, nama Allah yang demikian tersebut menurut mazhab minoritas. Karena kata ilah sendiri juga dipakai untuk penyebutan berhala, sehingga kata “tuhan” (ilah) adalah nama generik. Al-Qur’an menyebutkan, “Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia. Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu” ( Lihat, QS. Thaha (20): 98).
Sebab itu, dalam persaksian tentang keesaan Tuhan, kalimat tahlil—Laa ilaaha illallah—merupakan bagian integral dari nama ‘Allah’, yang hanya tertulis menggunakan empat huruf Arab yang terdapat nama ‘Allah’. Dengan demikian, nama ‘Allah’ memiliki karakter khas yang tidak dimiliki oleh nama-nama lain. Nama ini juga merupakan nama diri isim ‘alam, yang bentuknya tidak diturunkan dari akar kata apapun.
Adapun menurut Adian Husein (2010: hal. 108-109), nama Tuhan Allah adalah bersifat final.
“Nama Tuhan, yakni “Allah” adalah bersifat otentik dan final, karena menemukan sandaran yang kuat, dari sanad mutawatir yang sampai kepada Nabi Muhammad. Umat Islam tidak melakukan “spekulasi filosofis” untuk menyebut nama Allah, karena nama itu sudah dikenalkan langsung oleh Allah—melalui Al-Qur’an—dan diajarkan langsung cara melafalkan-nya oleh Nabi Muhammad”.
Pendapat Adian Husein di atas berbeda dengan Hesham A. Hassaballa dan Kabir Helminski (2013: hlm. 15). Menurut keduanya, kata Allah itu berasal dari akar kata yang sama dengan kata-kata yang digunakan untuk Tuhan dalam al-Kitab. Yakni; Elohim, ha Elohim, dan ha Eloh Allah, yang juga berasal dari akar kata yang sama untuk Tuhan dalam bahasa Aramaik/Syiria, bahasa yang digunakan oleh Yesus, yaitu Alaha. Kata Elohim sendiri berasal dari kata Ibrani eloh, yang berarti “tuhan”. Im yang ditambahkan pada akhir eloh adalah jamak abstraksi, yang digunakan sebagai tanda penghormatan. Sementara istilah Aramaik Alaha adalah bentuk empatik dari alah, yang dalam bahasa Aramaik berarti “tuhan”.
Di samping itu, bagi bangsa Israel, nama Allah Israel adalah “Yahweh”. Adapun menurut A. Hari Kustono (2008: hlm. 479), berhubung nama “Yahweh” adalah Kudus, suci, lalu bangsa Israel tidak berani mengucapkan nama-Nya secara langsung (menyebutnya dengan “Allah”), demi rasa ta’zim (hormat). Mereka lebih memilih membaca tulisan Yahweh dengan sebutan Adonay (Tuan atau Tuanku). Karena tulisan Adonay apabila dilihat dari bahasa Ibrani berarti Tuhanku, dan aynu berarti “milik kami”, dengan demikian Elohaynu dapat diterjemahkan sebagai “Eloh kami”, dan hal tersebut sama dengan “Allah kami”.
Ihwal tersebut menunjukkan bahwa Tuhan telah digambarkan sebagai sosok yang paling tinggi dan tidak ada yang mampu menandingi-Nya. Nama-nama Tuhan yang beranekaragam tersebut pula menjadikan sejarah Tuhan—yang telah dikenal oleh umat manusia hingga saat ini—kian menarik untuk ditelusuri. Penyebutan Tuhan yang Maha Esa bisa didekati dengan banyak nama, bentuk, sifat, dan istilah, namun secara substansial yang beragam tersebut menunjukkan kepada Zat yang sama, yaitu Tuhan semesta alam.
Kesadaran tentang Tuhan
Kesadaran akan konsepsi Tuhan di dalam sejarah umat manusia berbanding lurus dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dalam arti, awal kepercayaan manusia kepada Tuhan tersebut se-usia dengan usia manusia. Sebagaimana pernyataan Rodney Stark (1934 M), seorang filosof dan agamawan. Ia menyatakan bahwa lebih dari 3000 tahun yang lalu, terdapat sekelompok manusia yang telah memuja Tuhan Yang Maha Esa. (Waryono Abdul Ghafur: hal. 300)
Penulis sepakat dengan pernyataan Rodney Stark tersebut, mengingat banyaknya ritual-ritual keagamaan yang telah dilakukan oleh umat primitif sejak dahulu. Hal tersebut dikuatkan dengan tesis Abbas Mahmoud Al-‘Akkad (1981: hlm. 22), yang menyatakan bahwa ada tiga fase kepercayaan umat primitif pra-Islam di dalam mengenal Tuhan. Diantaranya adalah fase politeis (fase berbilang nya Tuhan), henoteis (fase seleksi), dan monoteis (fase keesaan atau ketauhidan).
Di dalam fase politeis, umat terdahulu mengenal banyak Tuhan dan beraneka ritual penyembahan. Bahkan, suku-suku pertama bisa mengangkat dewa-dewa (Tuhan-tuhan) dengan jumlah puluhan, hingga mencapai ratusan. Seperti orang-orang Yunani kuno yang menganggap bintang adalah tuhan (dewa), venus adalah (tuhan) dewa kecantikan, Mars adalah dewa peperangan, Minerva adalah dewa kerajaan, sedangkan Tuhan tertinggi adalah Apollo atau dewa matahari, dan lain-lain
Yang kedua, adalah fase henoteis. Fase di mana umat manusia masih mempercayai dewa-dewa banyak, akan tetapi mereka mengambil satu diantaranya yang menonjol dan memenangkan dari dewa-dewa yang lain. Ia mengakui Tuhan yang satu akan tetapi masih mempercayai potensi-potensi Tuhan yang lain. Fase henoteis ini sama persis dengan kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Walaupun jika masyarakat Arab ditanya tentang penguasa dan pencipta langit dan bumi mereka menjawab, “Allah”. Tetapi dalam saat yang sama, mereka menyembah juga berhala-berhala Al-Latta, Al-‘Uzza, dan Manata, tiga berhala terbesar mereka, di samping ratusan berhala lainnya.
Sementara fase terakhir adalah monoteis. Umat manusia pemuja berkumpul, bersatu melakukan satu ritual pemujaan, karena mereka mempunyai rujukan Tuhan yang tunggal, yang berbeda dengan fase sebelumnya. Namun, dalam perkembangannya nanti, sejauh pengetahuan penulis, konsep monoteis akan bergeser. Monoteis bukan lagi umat beragama yang berkumpul dari berbagai daerah lalu memilih sosok Tuhan yang kemudian dijadikan rujukan utama—sebagaimana yang dijelaskan oleh Abbas Mahmud—akan tetapi, monoteis adalah yang para anggotanya bukan para menyembah berhala (patung). Mereka ini yang kemudian menjadi cikal bakal para pengikut Nabi Ibrahim (Abrahimic Religions).
Abrahimic Religions ini termasuk diantaranya agama Nasrani (pengikut Isa) dan Yahudi (pengikut Musa), yang mempunyai akar ketuhanan pada Nabi Ibrahim. Telah dijelaskan Khalil Abdul Karim (2002: hlm. 125).
“Orang-orang Yahudi adalah ahli keilmuan, mereka memiliki kitab suci, beriman kepada ke-Esa-an Tuhan (monoteis) yang pada tingkat dogmatis-imaniah lebih maju dibanding dengan mereka yang menyembah berhala (pagan) dan bertuhan banyak (politeis) yang dianut oleh suku di jazirah Arab sebelum masing-masing individu nya bercampur dengan para penganut agama Tauhid.”
Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam sebuah proses fase keyakinan kepercayaan terhadap Tuhan, pada hakikatnya mengalami evolutif. Berawal dari politeis (umat bertuhan banyak), kemudian berkembang ke monoteis seperti keyakinan di dalam agama-agama semit; Yahudi, Kristen, dan Islam. Oleh sebab itu, apabila agama-agama semit itu memiliki persamaan di dalam keyakinannya, maka, tidak perlu kiranya mereka memperebutkan masa, bukan? Toh, sama-sama saling meyakini keberadaanNya. Wallahhu a’lam.