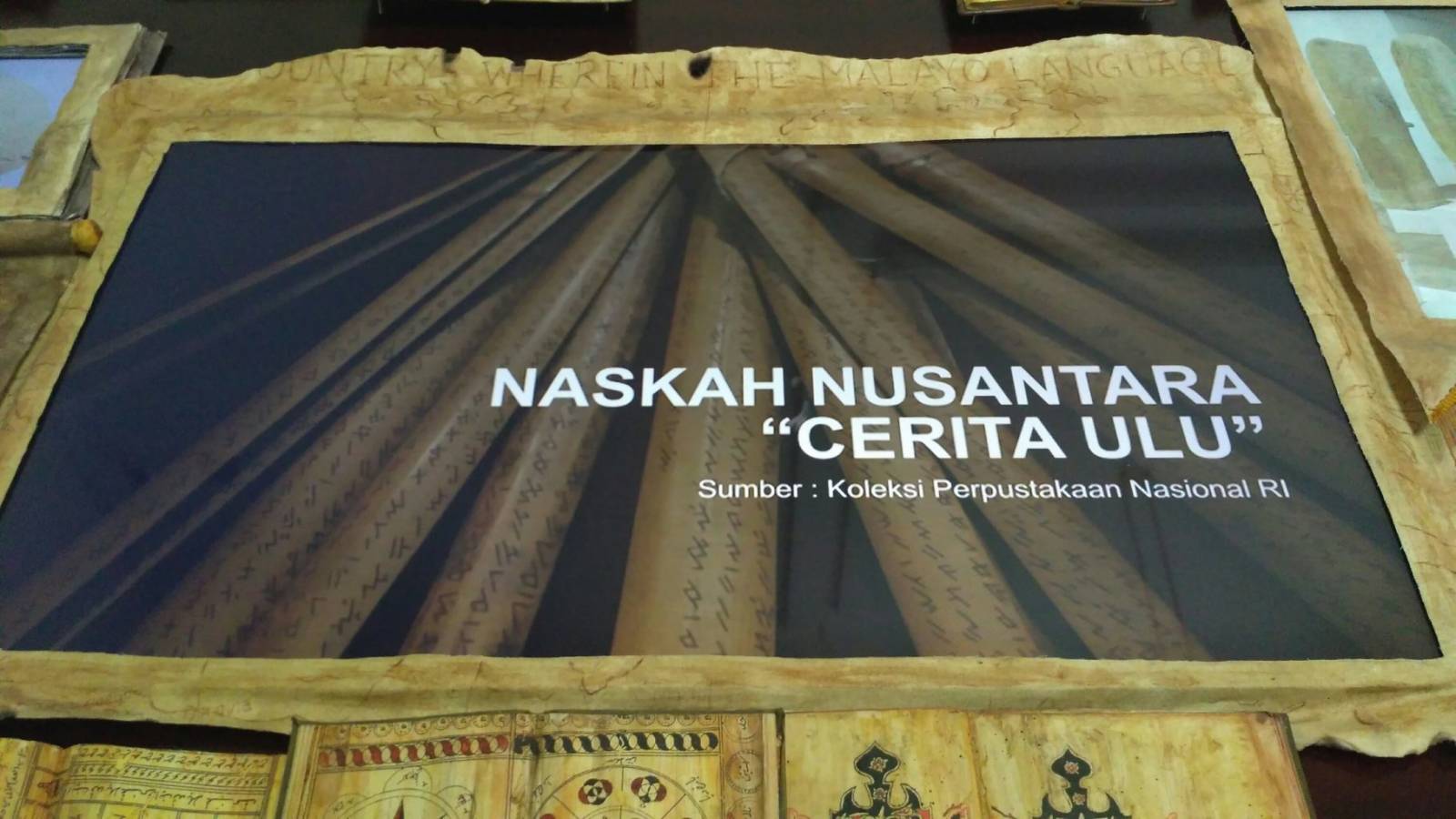
Lebih dari seabad yang lalu, Pigeaud membuat kesimpulan miring tentang aksara Pegon. Dalam katalog pentingnya yang memuat daftar manuskrip-manuskrip Jawa di perpustakaan Leiden dan beberapa perpustakaan lainnya di Belanda, sang filolog mengatakan bahwa penggunaan aksara Pegon telah mati pada akhir abad ke-19.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hal ini sejalan dengan berkembang pesatnya penggunaan kembali aksara Hanacaraka yang didukung oleh Keraton Surakarta (Pigeaud 1967, 27).
Kesimpulan Pigeaud di atas tentu saja keliru. Masyarakat santri di Jawa sejak masa Sultan Agung pada awal abad ke-17 hingga dewasa kini masih menggunakan aksara Pegon. Fungsi utamanya adalah sebagai wahana penulisan terjemahan antar baris dari teks-teks berbahasa arab klasik ke dalam bahasa Jawa. (Baca: Kapan Sumber Ortodoksi Islam Masuk di Jawa?)
Namun bagi penulis yang lebih menarik pada komentar Pigeaud di atas adalah narasi pertentangan antara aksara Pegon dan aksara Hanacaraka.
Dari komentarnya tersebut Pigeaud seakan menetapkan bahwa jika Hanacaraka hidup, maka Pegon harus mati, begitu pula sebaliknya. Cukup disayangkan bahwa kesimpulannya tidak didukung dengan fakta yang solid.
Tulisan berikut ini berusaha untuk memberikan bukti kuat mengenai hubungan antara kedua jenis aksara yang terus hidup di tanah Jawa ini. Tentu saja ini adalah tinjauan permulaan karena mengingat minimnya kajian mengenai Pegon.
Penulis berharap penelitian ke depan dapat memberikan cahaya terang menyangkut keduanya; apakah hubungan keduanya bersifat dominasi atau justru harmoni?
Kesimpulan permulaan menyangkut hal ini cukup mengejutkan. Bertentangan dengan wacana yang dibentuk oleh Pigeaud, terdapat bukti kuat menyangkut hubungan harmonis eksistensi kedua aksara ini di masyarakat santri Jawa.
Sebuah manuskrip berkode L. Or. 5592 mendukung kesimpulan ini. Manuskrip ini tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Bahan tulis yang digunakan adalah kertas daluwang dengan jumlah halaman mencapai 311.

Secara garis besar kandungannya adalah doa-doa, rajah-rajah, doktrin tasawuf, dan kamus Melayu-Jawa (Jan Just Witkam 2007, 6:160). Pada halaman pertama, pada baris keempat dan kelima, dalam manuskrip ini terdapat sebuah kolofon berbunyi:
Kawitane kawula anulis. Iya iku ing dina juma’ah. Ing sasih sa’ban kawite. Ing tanggal rolas iku. Ing tahun Be lan hijroh Nabi Muhammadinil Mustofa. Sewu lan rongatus. Wolongdasa wolong warsa.
Yang artinya: “Awalmula saya menulis adalah pada hari Jum’at 12 Sya’ban tahun Ba 1288 sesuai dengan hijrah Nabi Muhammad al-Mustofa.” Bila kita konversi ke dalam tahun masehi maka diperoleh angka sekitar tahun 1871 M.
Yang sangat menarik adalah aksara yang digunakan manuskrip ini ketika menuliskan teks tasawuf mazhab Ibnu Arabi berjudul Suluk Sujinah. Jika diperhatikan secara keseluruhan, aksara yang digunakan manuskrip ini adalah aksara Pegon kecuali pada teks Suluk Sujinah ini.
Pada halaman 132 sampai halaman 176 yang mengandung teks tersebut, penyalin manuskrip ini menggunakan dua aksara secara bergantian, yaitu aksara Pegon dan aksara Hanacaraka.
Kedua aksara itu ditulis dengan tinta yang sama. Tidak dilihat sama sekali petunjuk bahwa teks Hanacaraka itu ditambahkan sesudah aksara Pegonnya. Juga terlihat bahwa penyalinnya telah menyiapkan ruang jeda yang cukup baginya untuk menulis beberapa baris teks dalam aksara Pegon lalu diikuti dengan transliterasinya dalam aksara Hanacaraka. Terkadang dua atau tiga baris teks ditransliterasikan kedalam dua atau satu baris teks aksara Hanacaraka. Demikian seterusnya bergantian hingga akhir teks Suluk Sujinah.
Meskipun penulis belum bisa menemukan maksud dari penyalin, kita dapat cukup yakin dengan tulisannya. Bahwa tulisan kedua aksara itu dibuat oleh satu orang penyalin yang sama. Pada akhir abad ke-19, bertentangan dengan kesimpulan Pegeaud, justru terdapat para penulis yang mahir menulis dalam dua aksara tersebut.
Manuskrip lainnya dari Jepara lebih menegaskan kesimpulan bahwa kemampuan menulis dalam dua aksara adalah tradisi yang telah lama dikembangkan santri di Jawa; bukan perkembangan yang belakangan.
Manuskrip tersebut tersimpan di rumah Kiai Ubaidillah Nor Umar, Rais Syuriah PCNU Jepara yang mana pemilik dan penulis manuskrip ini adalah leluhurnya.

Pada halaman 161 terdapat keterangan silsilah pemilik manuskrip ini mulai dari Muhammad Arif hingga ke Abdullah al-‘Adniy dari Hadramaut. Terbaca di akhir baris pada halaman tersebut: 21 Dzul Qa’idah 1223 fil hijrah. Bila dikonversi ke tanggal Masehi menjadi Ahad, 8 Januari 1809 M.

Seperti penyalin dari manuskrip LoR. 5592, penulis manuskrip ini, Muhammad Arif, mampu menulis dengan baik dalam dua aksara: Pegon dan Hanacaraka. Hal ini cukup mengesankan mengingat bahwa Muhammad Arif merupakan keturunan Hadramaut yang mau belajar Islam bukan hanya melalui teks-teks Arab klasik, namun juga dari teks-teks lokal bahkan dalam aksara Hanacaraka.
Selain kajian keislaman konvensional, seperti tafsir Alquran (h. 162) dan Selawat Nabi (h. 119), dalam halaman 55 terdapat catatannya mengenai Kidung Rumekso ing Wengi. Hal yang demikian ini nampaknya akan sulit terjadi di masa kini. (Baca: Kidung Jawa: Catatan Santri Tahun 1809).
Di masa lalu seorang orientalis berusaha mempertentangkan antara penggunaan aksara Pegon dan Hanacaraka dengan kecenderungan jelas mendukung eksistensi aksara terakhir.
Sekarang, penulis melihat bahwa ada pandangan miring dari santri terhadap penggunaan aksara hanacaraka dan menekankan semata-mata aksara dan bahasa Arab untuk belajar Islam, meski bukan lagi dalam bentuk aksara Pegon.
Sikap keduanya tampaknya adalah ego kelompok yang sempit. Para penyalin ajaran agama di Jawa di masa lalu menunjukkan sikap bijaksana bahwa keduanya bisa berbagi eksistensi bukan?




















