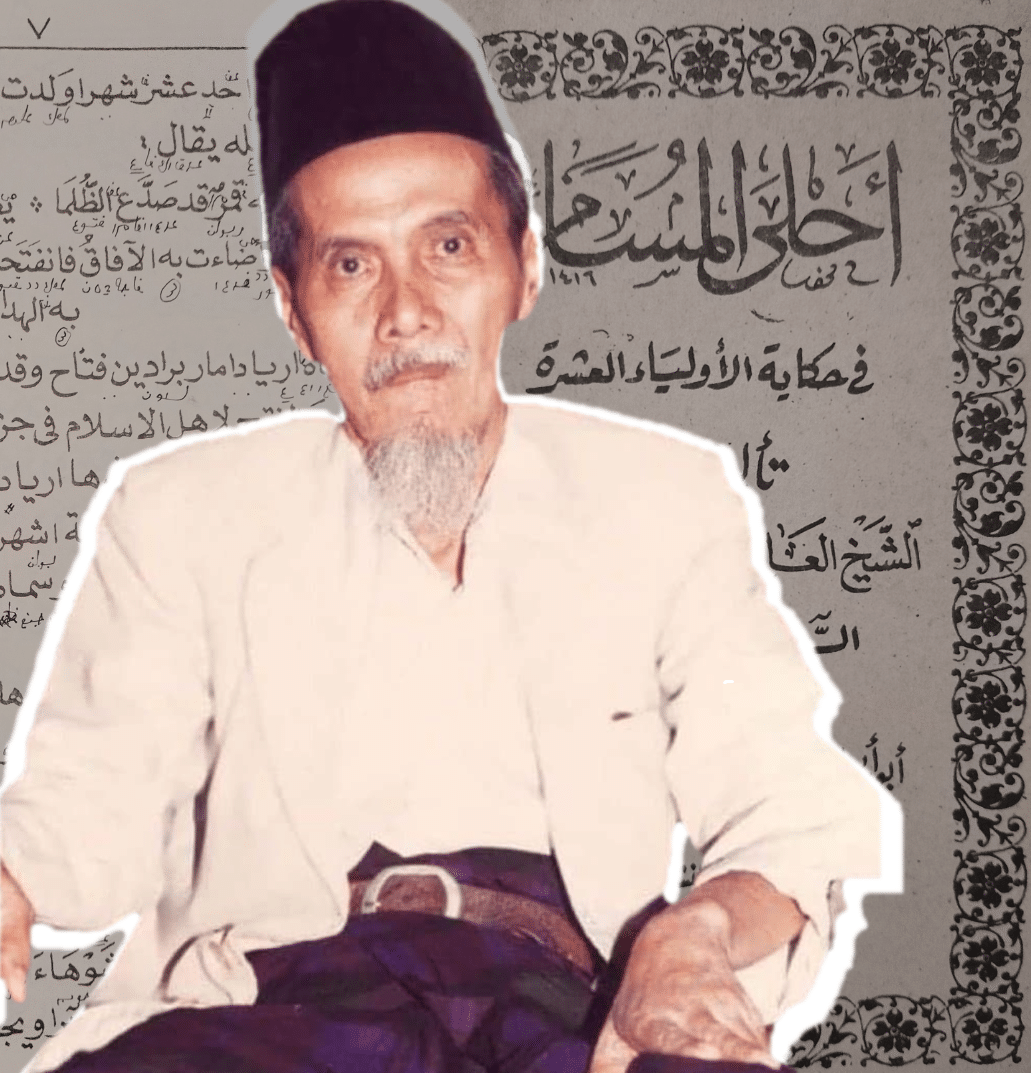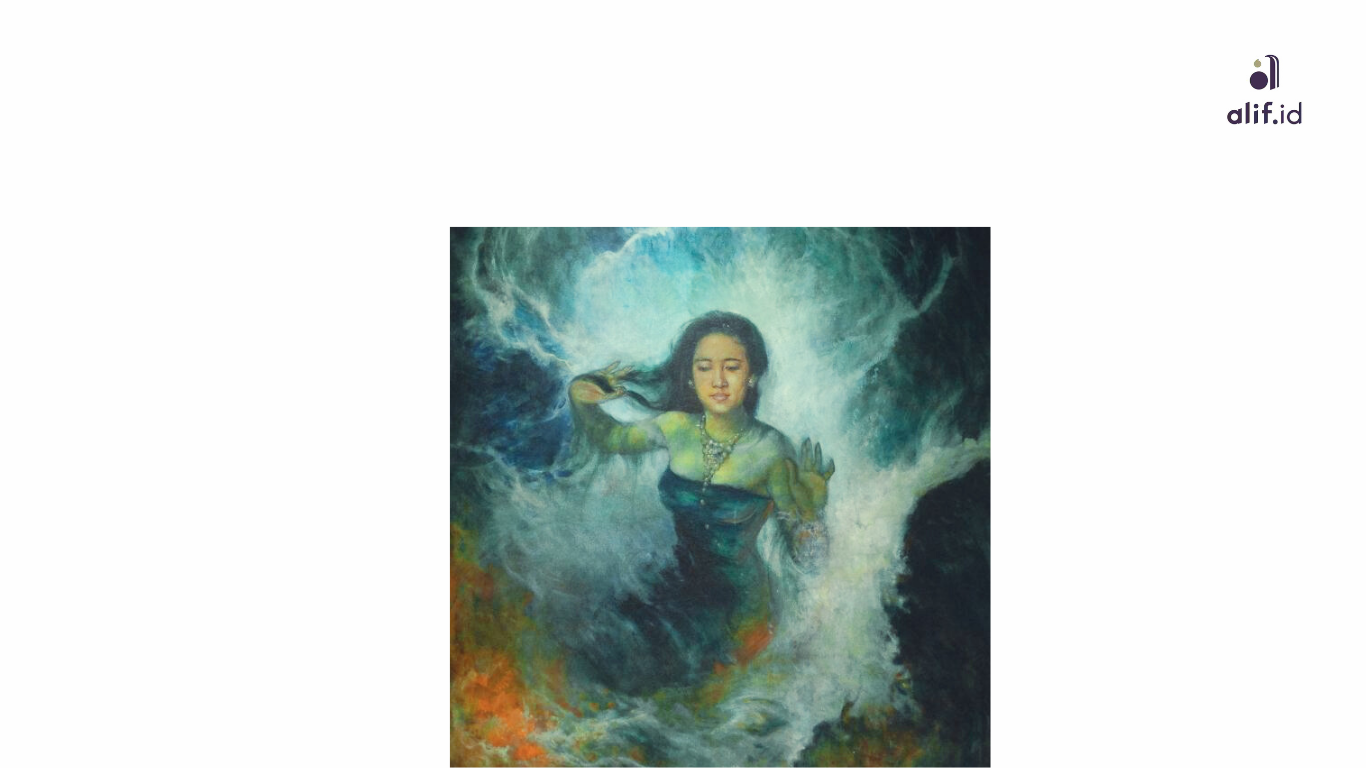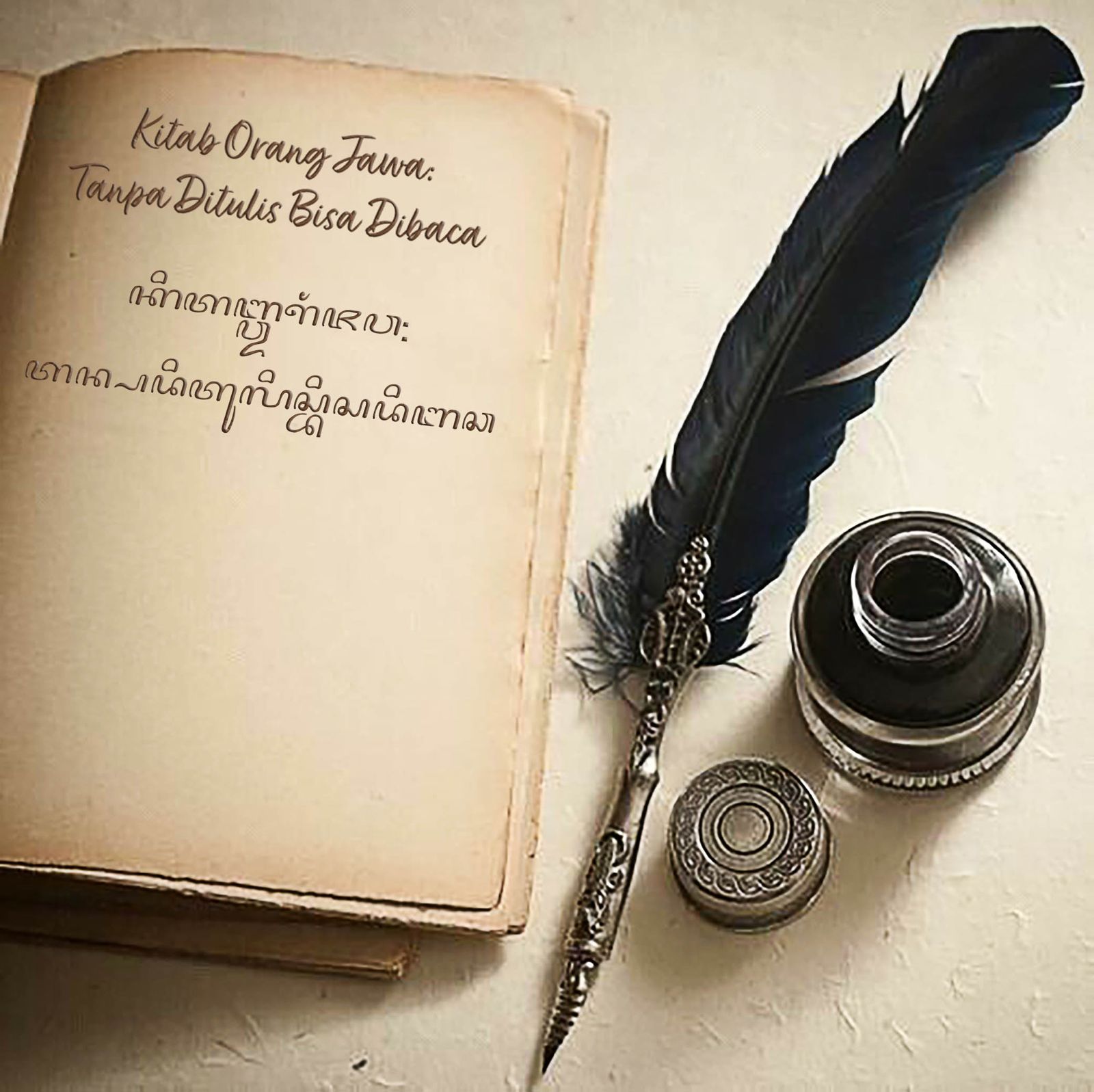
Apakah mungkin sebuah masyarakat memiliki kitab tanpa halaman, tanpa tinta, tetapi tetap bisa dibaca? Pertanyaan ini menyentuh jantung tradisi masyarakat Jawa yang memegang teguh sistem penyampaian pengetahuan yang tidak bergantung pada tulisan. Dalam dunia yang semakin didominasi oleh teknologi digital dan tulisan yang mendominasi hampir setiap aspek kehidupan, kita mungkin mulai lupa bahwa ada cara lain untuk menyampaikan pengetahuan dan kearifan yang tak kalah kuatnya. “Kitab tanpa tulisan” ini adalah warisan yang terus hidup dalam bentuk cerita, tembang, ritual, dan simbol yang diwariskan turun-temurun.
Tradisi lisan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai penghubung antara masa lalu dan masa depan. Dalam dunia modern yang semakin cepat dan serba instan, apakah kita benar-benar menyadari bahwa nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh orang Jawa, melalui cara-cara yang tidak pernah ditulis, masih relevan? Masyarakat Jawa, melalui tradisi ini, mengajarkan kita bahwa pengetahuan tidak harus terbatas pada tulisan untuk bertahan dan berkembang. Justru, dalam banyak hal, ia bisa lebih hidup dan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa perlu dipaparkan dalam bentuk teks.
Tradisi lisan di masyarakat Jawa bukanlah sesuatu yang baru, ia sudah ada sejak zaman kerajaan dan bahkan lebih jauh lagi. Sebagai contoh, dalam sistem pendidikan masyarakat Jawa kuno, pengetahuan tidak hanya diajarkan melalui buku atau tulisan, melainkan melalui percakapan dan pengajaran langsung dari sesepuh kepada generasi muda. Tertanam dalam masyarakat adalah pengajaran moral yang datang bukan dari huruf-huruf yang tercetak, tetapi dari cara-cara mereka berbicara, berperilaku, dan merayakan hidup. Bahkan, dalam syair-syair dan tembang yang sering dinyanyikan, terkandung ajaran hidup yang sangat dalam dan mengandung nilai-nilai kehidupan yang universal.
Tradisi lisan di Jawa bekerja dengan cara yang sangat simbolis dan kultural. Salah satu contoh yang sangat mendalam adalah tembang, yaitu bentuk puisi lisan yang sangat populer dalam budaya Jawa. Melalui tembang, banyak pesan moral dan nilai hidup yang disampaikan. Tembang tidak hanya sekadar lagu atau nyanyian, tetapi sebuah alat untuk mengajarkan etika, tata krama, bahkan filosofi hidup. Dalam tembang, seperti macapat atau gending, terkandung ajaran yang tidak hanya didengar, tetapi juga dirasakan oleh pendengarnya.
Selain tembang, ritual adat seperti selametan dan wayang kulit juga merupakan bagian dari tradisi lisan yang menyampaikan pengetahuan tanpa memerlukan tulisan. Sebagai contoh, wayang kulit yang sangat terkenal di Jawa adalah sebuah pertunjukan yang menyampaikan ajaran moral, sosial, dan agama melalui tokoh-tokoh yang dihidupkan dalam bentuk boneka. Walaupun cerita wayang sudah ada dalam naskah-naskah kuno, namun makna dari cerita tersebut tidak akan hidup sepenuhnya jika hanya dibaca di atas kertas. Wayang adalah perpaduan antara seni, moral, dan spiritual yang datang kepada masyarakat dalam bentuk visual dan lisan.
Sebagai contoh konkret, peran wayang kulit dalam menyampaikan nilai moral dan agama sangat krusial. Dalam setiap pertunjukan wayang, meskipun cerita yang dimainkan sudah lama ada dalam naskah kuno, namun cara penyampaiannya yang lisan dan visual memberikan dampak yang mendalam bagi penontonnya.
Dalam cerita Mahabharata atau Ramayana yang dimainkan melalui wayang, nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, kesetiaan, dan cinta terhadap tanah air diajarkan dengan cara yang bisa langsung dirasakan oleh penonton. Tidak perlu adanya buku atau teks yang menjelaskan secara rinci, karena melalui dialog antara tokoh wayang dan gambaran visual yang dibawakan oleh dalang, pesan moral tersebut menjadi hidup dan mudah dipahami. Wayang sebagai bentuk seni dan pendidikan, lebih dari sekadar hiburan. Ia mengandung pelajaran tentang kebijaksanaan hidup yang disampaikan secara oral dan visual, dan ini mengingatkan kita bahwa banyak hal dalam hidup yang lebih baik dipahami melalui pengalaman langsung daripada hanya membaca teori dari buku.
Filsuf Prancis, Maurice Merleau-Ponty, dalam pandangannya tentang fenomenologi, menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. Ia berargumen bahwa pengalaman kita terhadap dunia tidak hanya terbatas pada objek yang terpisah dari tubuh kita, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara langsung. Dalam konteks tradisi lisan Jawa, pengetahuan yang tidak ditulis namun diwariskan secara langsung melalui percakapan atau ritual, berfungsi sebagai bentuk pengalaman yang tidak terpisahkan dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Pengetahuan ini bukan hanya sebuah informasi yang bisa dipindahkan ke dalam bentuk teks, tetapi juga pengalaman yang lebih dalam yang diserap oleh pendengar atau peserta secara langsung.
Sejalan dengan itu, dalam karya The Myth of Sisyphus, Albert Camus berbicara tentang absurditas kehidupan dan cara manusia mencari makna dalam hidupnya. Ia menggambarkan bagaimana kita cenderung menolak dunia yang teralienasi, dan lebih memilih menemukan makna melalui interaksi yang lebih langsung dengan dunia. Tradisi lisan ini memungkinkan masyarakat Jawa untuk merasakan makna tersebut melalui setiap kata yang diucapkan, bukan sekadar membaca atau merenungkan teks. Hal ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang terkandung dalam tradisi lisan lebih banyak dirasakan melalui pengalaman hidup sehari-hari, ketimbang hanya dipahami lewat tulisan.
Pemikiran filsuf Muslim, seperti al-Ghazali, mengungkapkan bahwa pengetahuan sejati (ilmu) adalah pengetahuan yang muncul dari pengalaman langsung, intuisi, dan hikmah yang diterima melalui hati dan perilaku. Al-Ghazali, dalam karya Ihya’ Ulum al-Din, menekankan bahwa ilmu yang tidak diajarkan dengan cara yang bijaksana dan tidak dibawa dalam perilaku sehari-hari, hanya akan menjadi pengetahuan kosong. Dalam tradisi lisan Jawa, kita menemukan prinsip yang serupa. Sesepuh yang mengajarkan nilai-nilai moral kepada generasi muda bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan dan keteladanan. Pengetahuan yang disampaikan melalui cerita, tembang, dan ritual bukan hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga secara emosional dan spiritual.
Berangkat dari pendapat di atas, menurut penulis, kebudayaan lisan memiliki kemampuan luar biasa sebagai mercusuar pengingat kita sebagai generasi muda, akan nilai-nilai lama (sejarah) yang mungkin terlupakan di tengah arus deras dunia digital. Ia bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga jembatan yang menghubungkan kearifan nenek moyang dengan realitas modern. Sebagai contoh, dalam cerita wayang kulit, kita dapat menemukan nilai-nilai universal tentang kehidupan—keadilan, pengorbanan, dan kasih sayang—yang tetap relevan sepanjang zaman.
Setiap pertunjukan wayang bukan hanya menyampaikan cerita, tetapi juga menanamkan makna dan menghidupkan perasaan dalam hati para penonton. Seperti bayangan yang menari di atas kelir, nilai-nilai luhur itu terus bergerak mengikuti alur zaman, tetap berpendar meski malam semakin larut. Kebudayaan lisan adalah suara yang tak tertulis, namun selalu dapat dibaca oleh hati yang mau mendengar. Ia mengajarkan bahwa sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi cahaya yang menerangi langkah kita menuju masa depan. Selama ada yang mau bercerita dan ada yang bersedia mendengarkan, tradisi ini akan tetap hidup, meresap ke dalam jiwa, dan menjadi bagian dari identitas kita.
Namun, di tengah perkembangan teknologi yang pesat, tradisi lisan ini menghadapi tantangan besar. Teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi dan menyampaikan pengetahuan. Dengan kemudahan akses informasi, tulisan kini lebih mudah didapatkan dan dibagikan. Namun, apa yang kita dapatkan melalui tulisan atau teks, seringkali tidak sekomprehensif dan serasa ketika kita mendengarkan langsung dari mulut orang yang lebih berpengalaman. Teknologi telah memperkenalkan kita pada budaya instan, namun kita seringkali kehilangan kedalaman pemahaman yang dapat diberikan oleh tradisi lisan ini.
Di satu sisi, perkembangan ini membawa banyak kemajuan, tetapi di sisi lain, nilai-nilai luhur yang dahulu diajarkan secara langsung melalui percakapan, pengajaran, dan ritual-ritual adat mulai terlupakan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin menjauh dari cara-cara tradisional ini dan lebih memilih kenyamanan dalam menerima informasi secara instan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita untuk melestarikan tradisi ini di tengah arus modernisasi.
Sebagai generasi yang hidup di tengah modernitas, kita sering kali terjebak dalam kebiasaan menggunakan teknologi sebagai satu-satunya sumber informasi. Namun, ketika kita menengok kembali ke tradisi lisan yang kaya ini, kita dapat belajar banyak tentang pentingnya menghargai pengetahuan yang diwariskan secara lisan dan tidak selalu terbatas pada tulisan. Tradisi lisan mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai pengalaman, dan menghormati orang yang lebih tua yang memiliki wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan.
Apa yang bisa dipelajari generasi sekarang dari tradisi ini adalah bahwa tidak semua pengetahuan harus tercatat di atas kertas untuk dapat bertahan. Pengetahuan yang disampaikan dengan lisan, cerita, simbol, dan ritual dapat bertahan lebih lama dan lebih menyentuh hati. Nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam tradisi ini, seperti yang diajarkan melalui wayang atau tembang, masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern kita.
Mari kita melestarikan tradisi lisan ini, tidak hanya sebagai sebuah warisan budaya, tetapi juga sebagai bentuk cara pandang hidup yang lebih dalam dan penuh makna. Tanpa tinta dan kertas, kita masih bisa memahami inti dari sebuah kitab kehidupan yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Kitab itu, meskipun tidak tertulis, tetap bisa dibaca.
Lantas, di mana kitab tersebut saat ini dan di masa mendatang?
Dan bagaimana dengan tradisi tulisan?