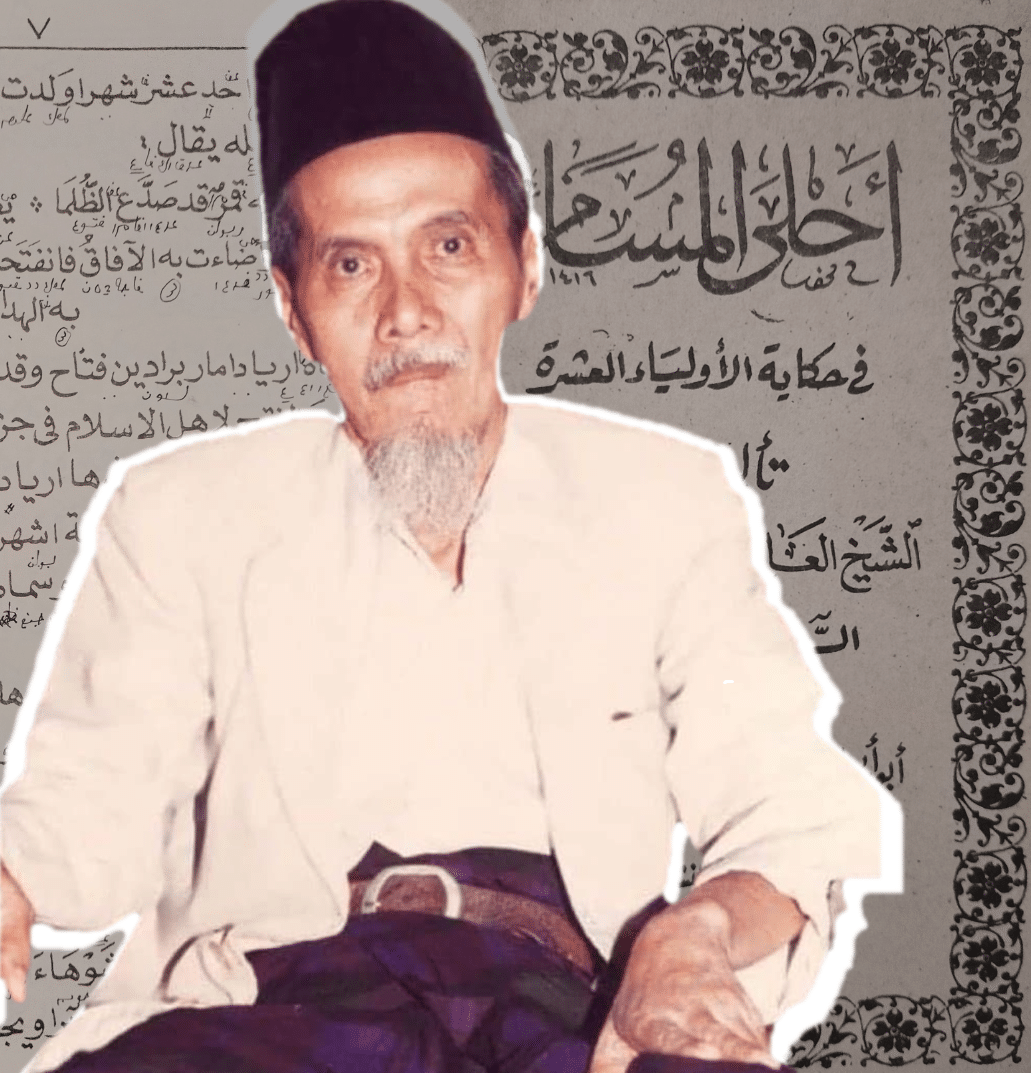Orang Jawa pada dasarnya tak pernah terpisah dengan Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan sebagai sesosok yang jauh dan sama sekali lepas dari kehidupan sehari-hari yang sekilas “rendah” dan “kotor.” Setidaknya, kesan inilah yang tampak dari berbagai kebudayaan Jawa masa silam yang masih dapat kita jumpai di hari ini.
Mulai dari istilah-istilah dan pola percakapan sehari-hari, cara menjalani kehidupan yang masih jamak kita jumpai pada kalangan yang masih lekat dengan pandangan hidup warisan masa silam, hingga berbagai kesenian tradisionalnya yang beberapa di antaranya telah mendapatkan pengakuan dunia dari UNESCO: wayang, keris, dan batik.
Bagi orang-orang Jawa seni tak sekedar dimaknai sebagai hiburan semata atau bersifat rekreatif. Memang terdengar klise untuk menyatakan bahwa segala bentuk kesenian tradisional Jawa, di samping memuat aspek tontonan, juga merupakan tuntunan. Tapi apa boleh buat, anjing boleh menggonggong kafilah tetap berlalu, kenyataannya UNESCO telah mengakui beberapa di antaranya sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Kenyataan ini tentu serius dan berdampak pada paradigma kesenian postmodern dimana perbedaan antara seni tinggi dan seni rendah sudah tak dianggap lagi karena jelas secara filosofis substansi bukanlah hal yang patut diperhatikan dalam paradigma postmodern
Kenyataan yang tak terbantahkan bahwa UNESCO telah mengakui beberapa karya seni tradisional nusantara sebagai warisan dunia tak ayal lagi meneguhkan idealitas lama tentang seni sebagai media atau sarana yang memuat pesan tertentu. Dari beberapa penelitian seumpamanya, saya menemukan bahwa kebanyakan kesenian tradisional Jawa merupakan sanepan atau perumpamaan yang mengandung data-data tertentu, baik data-data historis, antropologis, maupun spiritual (Ma-Hyang: Melibatkan yang Silam Pada yang Mendatang, Heru Harjo Hutomo, 2020).
Konsep Tuhan sebagai Sang Kayun atau Yang Maha Hidup seolah menjadikan Tuhan tak terpisahkan dari kehidupan. Pada Serat Centhini, terdapat pemahaman yang menggunakan simbolisasi huruf Alif yang tampak diyakini oleh mantan wartawan dari kulit berwarna yang pertama kali di dunia, R.M.P. Sosrokartono: “AIU,” “Aku Iki Urip” atau “Aku Iya Urip.” Kakak kandung Kartini ini menyebut kenyataan itu sebagai Sang Alif yang merupakan representasi dirinya sendiri yang telah memperoleh kesejatian, dimana aksara Alif ketika di-fathah akan terbaca “Aku,” ketika di-kasrah akan terbaca “Iki,” dan di-dhomah akan terbaca “Urip”—pada kasus Bima dalam kisah pewayangan adalah setelah ksatria Panengah Pandhawa itu “berkaca-tanpa-kaca” atau bersua dengan kehalusan dirinya yang dikenal sebagai Dewa Ruci atau Sang Marbudyengrat.
Setelah menyeksamai berbagai bentuk kesenian tradisional Jawa, saya berkesimpulan bahwa jantung kebudayaan Jawa tradisional secara keseluruhan memang terletak pada konsep besar sangkan-paraning dumadi. Inilah yang mendasari keseluruhan budaya Jawa tradisional. Seandainya dalam kajian metafisika, salah satu bidang dalam ilmu filsafat, dijelaskan soal prinsip pertama (the first principle) yang mendasari seluruh denyut epos zaman, maka konsep sangkan-paraning dumadi itulah prinsip pertama dalam kebudayaan Jawa tradisional. Dengan kata lain, apapun yang terkait dengan Jawa dan kejawaan hanyalah derivasi dari konsep besar sangkan-paraning dumadi. Dan hal ini tentu saja tak hanya berlaku pada Jawa dan kejawaan yang direpresentasikan oleh kebudayaan keraton, tapi juga oleh kebudayaan luar keraton atau non-keraton.
Kesenian secara luas memang telah lekat dengan cara hidup keseharian orang-orang Jawa di masa silam yang masih pula dapat disaksikan hingga kini. Orang-orang Jawa, dalam kerangka pikir ini, pada dasarnya tak pernah memilah antara seni, agama, politik, ilmu pengetahuan, dan etika sosial. Taruhlah konsep dan fungsi dalang yang sampai kini tak semata dipahami sebagai seorang seniman, tapi juga seorang pelaku spiritualitas atau bahkan pemangku ritual tertentu. Karena memang pada masa silam pagelaran wayang masih dianggap sebagai sebuah ritual sebagaimana yang tersirat dari istilah “wayangan” atau lebih tepatnya lagi “mahyangan.” Salah satu konsep dalang sebagai “ngudhal piwulang” menempatkan sesosok dalang sepadan dengan seorang pemuka agama yang tengah berdakwah, meskipun hikmah-hikmah dalam pagelaran wayang bersifat umum atau universal (Wayang dan Dakwah Substansial, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org). Di sinilah kemudian tipologi “dhalang wejang” mendapatkan konteksnya sebagaimana “dhalang sanggit,” “dhalang sabet,” “dhalang gecul,” dst. Hal ini mengindikasikan bahwa sampai kini paradigma bahwa kesenian, keagamaan, dan spiritualitas bukanlah bidang yang sama sekali lepas atau terpilah satu sama lain masih hidup dan dihidupi.
Perlu diketahui bahwa konsep waktu orang Jawa bersifat sirkular dan bukannya linear. Sebab, tanpa memahami konsep waktu orang Jawa ini konsep besar sangkan-paraning dumadi yang mendasari keseluruhan budaya Jawa tradisional tak akan terpahami. Konsep waktu yang sirkular terejawantah dalam berbagai bidang kehidupan. Taruhlah dalam konsep ritual yang masih dapat disaksikan dan dialami sampai hari ini: kenduri atau slametan. Sejak kehidupan dalam kandungan sang ibu, orang-orang Jawa sudah memperingatinya sebagai sebentuk waktu khusus yang patut untuk diistimewakan (Menyingkap Doktrin Martabat 7: Secarik Catatan Tentang Sangkan, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id). Hal ini juga berlaku sesudah manusia dikandung oleh rahim sang alam dimana bayi yang telah lahir diperingati pula dengan ritual tertentu yang biasanya sampai ia berusia 7 bulan sampai nanti di setiap hari kelahirannya. Demikian pula ketika kelak manusia meninggal dunia, ia pun akan pula diperingati dengan ritual slametan mulai dari surtanah atau geblak , 3 hari, 7 hari, hingga kelak 1000 hari dan akhirnya tersisa tinggal khol atau peling-nya.
Setidaknya, dari catatan di atas, manusia diyakini mengalami 3 fase kehidupan: kehidupan dalam rahim sang ibu, dalam rahim sang alam, dan dalam rahim Yang Maha Rahim. Bukankah dalam kerangka ini perjalanan seorang manusia berupa siklus?
Konsep waktu sirkular yang berhubungan dengan konsep besar sangkan-paraning dumadi ini sangat tampak dalam berbagai kesenian tradisional Jawa. Tulisan ini akan mengupas bentuk kesenian tradisional lainnya selain pagelaran wayang purwa yang telah banyak saya kaji. Tapi untuk mengawali pemahaman tentang konsep sangkan-paraning dumadi sekelumit catatan tentang pagelaran wayang dapat mengantarkan pada pemahaman tentang corak kesenian tradisional lainnya. Sebab, pagelaran wayang memang sebentuk kesenian yang paling lengkap yang mencakup kesenian-kesenian lainnya.