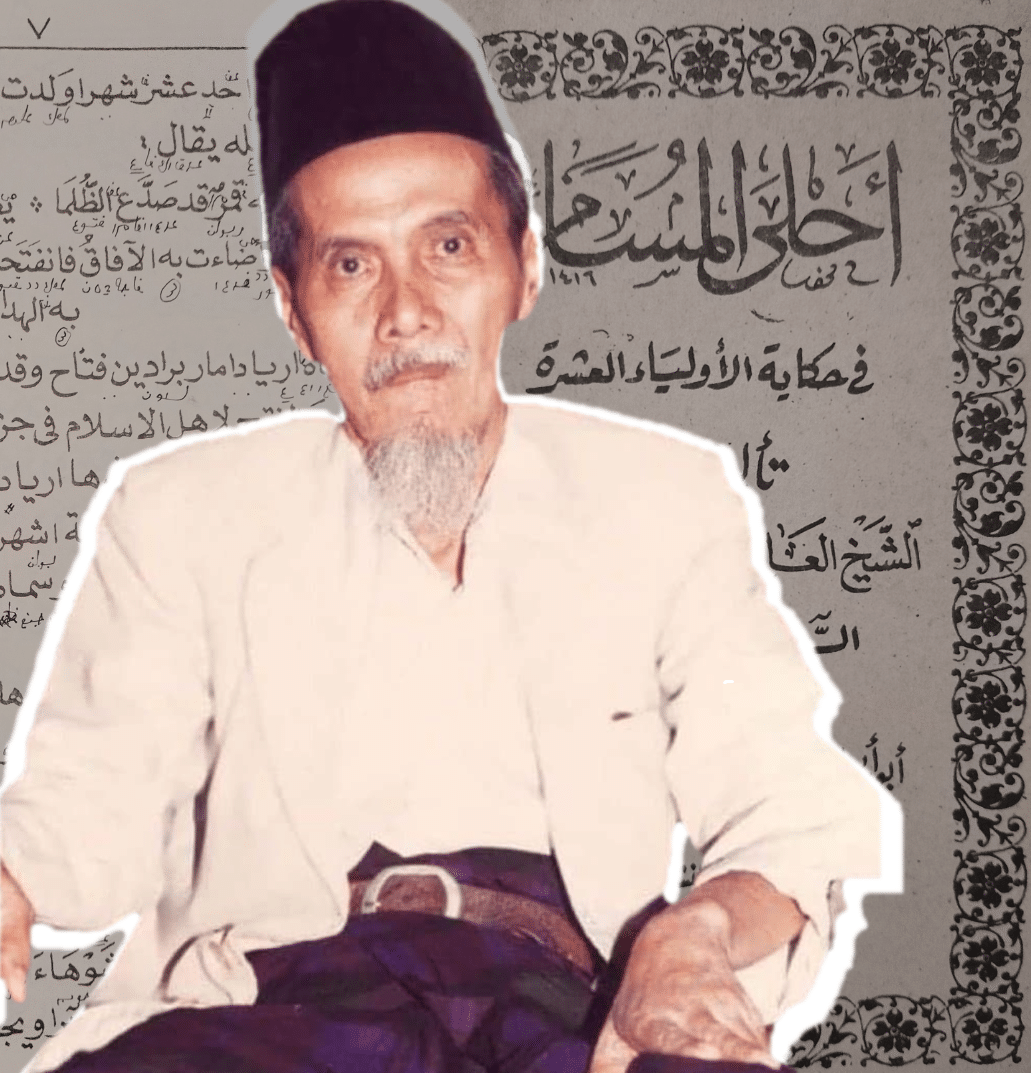Seni sebagaimana dipahami orang saat ini berkaitan dengan pengertian estetika, yang sering diartikan sebagai keindahan. Keindahan umumnya dipahami sebagai kualitas atau sifat tertentu yang terdapat dalam suatu bentuk (form), atau lebih tepatnya hubungan spasial dan temporal antar elemen penyusun suatu bentuk. Sifat atau kualitas semacam itu diungkap dalam istilah indah-jelek, serasi-janggal, baik-buruk, menarik-membosankan, merdu-sumbang, dan lain sebagainya.
Lono Simatupang (2006) menjelaskan bahwa istilah estetika (aesthetic) yang dipakai dalam dunia seni sebenarnya memiliki akar kata yang sama dengan anestesi di kalangan medis, yaitu kata aesthesis dalam bahasa Yunani yang berarti rasa, persepsi manusia atas pengalaman. Estetika tidak hanya mengandung persepsi manusia tentang keindahan, melainkan rasa dalam pengertian seluas-luasnya, termasuk rasa sakit, kemuakan, kegusaran, jijik, gairah, dan lain sebagainya. Segala macam rasa tersebut merupakan tanggapan manusia yang diperoleh lewat indera penglihat, peraba, pencium, pencecap, dan pendengarnya. Estetika, dengan demikian, merupakan tanggapan manusia atas pengalaman ketubuhannya.
Sebagai tanggapan manusia atas pengalaman ketubuhan, estetika tentu saja bersifat budayawi (kultural); dalam arti bahwa tanggapan atas pengalaman-pengalaman tadi diperolah manusia lewat proses pembudayaan diri – internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat melalui berbagai macam interaksi sosial. Tidak salah bila dikatakan bahwa seni merupakan sebuah sistem budaya (Geertz, 1983: 33). Artinya kesenian dalam masyarakat mempunyai posisi, fungsi, dan pemaknaan yang lekat dengan kebutuhan akan etika, estetika, spiritualitas, komunalitas dan identifikasi personal maupun komunal. Begitu juga dengan seni tari.
Meminjam analogi Shin Nakagawa (2000) eksistensi tari dapat dilihat dari kedudukannya sebagai teks dan konteks dalam masyarakat. Tari bukan hanya ekspresi gerak (teks) yang menghibur secara dangkal atau semata tontonan. Tari adalah ruang pembacaan yang lebih kritis tentang identitas, tradisi, modernitas, dan sejarah tari itu sendiri (konteks).
Sumandiyo Hadi (2005) menyebut bahwa ditinjau dari ilmu sosial, tari menghubungkan antara kesadaran kolektif, struktur sosial, individu, fungsi tari dalam struktur itu. Secara tekstual, tari dapat dipahami dari bentuk dan teknik yang berkaitan dengan komposisinya (analisis bentuk atau penataan koreografi) atau teknik penarinya (analisis cara melakukan atau ketrampilan). Sementara secara konsep yang berhubungan dengan sosiologi ataupun antropologi, tari adalah bagian integral dari dinamika sosio-kultural masyarakat. Keduanya diberlangsungkan melalui simbol-simbol yang ada dalam tariannya. Sistem simbol adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan secara konvensional digunakan bersama, teratur dan benar-benar dipelajari sehingga memberi pengertian hakekat ”manusia”, yaitu suatu kerangka yang penuh arti untuk mengorientasikan dirinya kepada yang lain, kepada lingkungannya dan pada dirinya sendiri, sekaligus sebagai produk dan ketergantungannya dalam interaksi sosial.
Jadi tari dipandang sebagai sistem simbol yang merupakan representasi mental dari subyek dan wahana konsepsi manusia tentang suatu pesan untuk diresapkan.
Walter Benjamin (dalam Fauzanafi, 2005) menyebut bahwa manusia mempunyai kapasitas tertinggi untuk memroduksi keserupaan (mimicking). Mimesis berasal dari tindakan fisik (gestural) dan tindakan itu selalu menunjuk pada sesuatu. Dengan kata lain, mimesis memertunjukkan bentuk atau citra-citra tertentu yang diindikasikannya.
Dalam tari tradisi Jawa, proses pembentukannya (termasuk tari bedhaya) juga diilhami oleh apa yang ada dalam lingkungan kehidupan manusia. Hal ini tampak pada pembentukan Bedhaya Ketawang yang diilhami suara-suara alam yang terdengar seakan-akan dari langit (pendekatan auditif) dan kemudian terwujud dalam pola garap gendhing kemanak.
Istilah yang digunakan untuk menyebut beberapa vokabuler tari seperti sekar suhun, mucang kanginan, lincak gagak, merak kasimpir, wedhi kengser, jala-jala, gajah-gajahan, dan lainnya, jelas menunjuk adanya pendekatan visual. Wujud vokabuler yang mengacu pada lingkungan alam seperti itu, digarap dalam bentuk tan wadhag (non-representatif, abstrak) (terutama dalam tari bedhaya). Stilasi (penggayaan) yang demikian tinggi menunjuk keluasan wawasan seniman tradisi, dan juga menunjuk bahwa seniman tari tradisi itu simpatea dengan kosmos (Prihatini dkk, 2008).
Seniman-seniman tradisi Jawa (Surakarta khususnya) juga telah mengimajinasi dan menginterpretasikan bentuk pola, kualitas dan karakter gerak tari tradisi dalam sepuluh sikap laku tari (patrap beksa). Yaitu merak ngigel (burung merak menari), digunakan untuk karakter tari alus luruh (tua), sata ngetap swiwi (ayam mengepakkan sayap), digunakan untuk karakter tari alus luruh (muda), kukila tumiling (burung menggelengkan kepala), untuk tari alus lanyap/mbranyak (lincah).
Karakter tari gagah tandang mempunyai patrap beksa branjangan ngumbara (burung branjangan terbang mengangkasa), anggiri gora (seperti gunung yang bergetar menakutkan/gemuruh menggemparkan) untuk tari gagah dugangan, mundhing mangundha (kerbau menanduk) untuk tari Bugis, wreksa sol (pohon tumbang tercabut akarnya) untuk tari raksasa.
Berikutnya pucang kanginan (nyiur tertiup angin) digunakan untuk tari putri (termasuk bedhaya-srimpi), sikatan met boga (burung sikatan mencari makan) untuk tari kera, ngangrang bineda (semut ngangrang diusik) untuk tari gagah sudira.
Patrap beksa yang terangkum dalam Serat Kridhwayangga (Sastrakartika, 1925) tersebut juga dilengkapi detail-detail gerak seluruh tubuh, menunjukkan pentingnya peranan tubuh sebagai alat ekspresi, yang mampu merefleksi berbagai persoalan hidup manusia, dengan intensitas, kualitas, dan virtuositas, serta koordinasi gerak yang total. Dengannya imajinasi kita seolah-olah dibawa pada bentuk/pola, kualitas gerak dan karakter gerak tertentu.
Manusia bukan hanya meniru suara (onomatopoeia) dan bunyi-bunyian di sekitarnya, tapi meniru melalui gerak. Artinya mimesis memiliki dimensi relasional, sebagai alat identifikasi, untuk menghubungkan dengan orang lain. Taussig (1993) menyebut mimesis adalah copy dan sekaligus contact.
Dalam konteks seni kerakyatan, sebagai contoh kesenian Topeng Dalang sebagai petunjukan teater tradisional dari Klaten. Pertunjukan yang hampir punah ini sajiannya sangat mirip dengan wayang orang, hanya saja pemainnya mengenakan topeng. Kisah yang ditampilkannya banyak mengangkat cerita Panji, seperti Ande-ande Lumut, Jaka Blowa, dan Rabine Gunungsari. Warna kebudayaan agraris-kerakyatan sangat kuat memengaruhi pertujukannya. Hal ini dapat ditunjukan melalui beberapa vokabuler tarinya, terutama sekaran (rangkaian gerak) bagi tokoh Klana.
Dalam buku Topeng Panji: Mengajak kepada Yang Tersembunyi (2014) saya pernah menuliskan bahwa vokabuler kiprahan Klana misalnya menggunakan sekaran-sekaran jogetan yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari orang Klaten seperti nutu (menumbuk padi), ngundhuh layangan (bermain laying-layang), trajon/traju (timbangan atau menimbang), main kertu (berjudi kartu), inter-inter(memutar padi dalam tampah), napeni (membersihkan kulit padi), nepleki, adus (mandi) dan umbul (tebak bumi). Semua itu merupakan gambaran kehidupan sosial-budaya masyarakat Klaten yang memang dekat dengan budaya pedesaan (kerakyatan) dan agraris.
Dari segi cerita, Ande-ande Lumut, salah satu bagian cerita Panji, memuat ide konservasi alam dan lingkungan, lewat tema pengairan, pertanian dan kehidupan fauna. Kisah Jaka Blowa juga memuat kajian nilai estetika ekspresi seni melalui kisah kehidupannya sebagai seorang seniman (tari, musik dan rupa). Bahkan cerita Timun Mas juga identik dengan konteks kekinian. Nurcahyo (2014) menyebut varian ini, dalam versi Jawa Tengah mengisahkan raksasa jahat yang berhasil ditenggelamkan dalam lautan lumpur hasil lemparan terasi (belacan) Timun Mas. Dongeng ini menjadi basis ide kreatif penciptaan karya seni rupa dan performance art dalam peringatan bencana lumpur Lapindo yang masih menjadi problem hingga kini. Timun Mas sebagai kisah maupun sebagai eksistensi “personal” menjadi dasar tema “Sudah saatnya menenggelamkan raksasa dalam kubangan lumpur Lapindo”.
Dengannya, tari sebagai sistem simbol menunjuk pada konsep, bukan pada bendanya. Seturut Soediro Satoto (2003) seni merupakan lembaga sosial, dokumentasi sosial, cermin sosial, moral sosial, eksperimen sosial, sistem sosial, sistem semiotik, baik semiotik sosial maupun semiotik budaya yang amat kaya akan nuansa makna yang terkandung dalam tanda-tanda yang terbangun oleh seni pertunjukan, baik tanda-tanda ikonik, indeksikal, maupun tanda-tanda simbolis.
Akhirnya, memahami kesenian memang tak sekedar mencicipi kuliner, atau mengabadikan alam dalam sebuah potret yang indah. Kesenian adalah bagian dari kebudayaan, berupa cita rasa, keanggunan memahami kehidupan dan logika kesejajaran antara manusia dengan lingkungannya, sebagai penanda kulminasi rasa juga pada Tuhannya. Hablu minallah, hablu minannas…