
Kemarin pagi, saya tertarik twit Scott Weinberg, salah satu akun twitter yang sejak lama saya ikuti karena dia penggemar berat film cult dan eksploitasi. Twit-twitnya sering lucu, dan yang kemarin saya tertarik, pun kocak. Rupanya, katanya, ada “daftar rahasia film-film suci di Twitter”. Maksudnya, ada film-film yang rupanya kalau dikritik, yang mengkritik bakal diserbu, bahkan dirundung.
Gara-gara itu, kemarin pagi saya ngetwit soal ada nggak ya “daftar film suci twitter” edisi film Indonesia? Saya sebut beberapa. Nah, siangnya, saya buka twitter, wah, film pendek Tilik karya Wahyu Agung Prasetyo, dari naskah Bagus Sumartono dan produksi Ravacana Films + Pemda DI Yogya–jadi trending topic. Saya sudah nonton sehari sebelumnya, dan saya kesal setengah mati selesai menonton.
Dalam 20 menitan pertama film berdurasi 32 menit itu, saya menikmati film itu, memujikan aspek teknis seperti sinematografi, seni pemeranan, dan merasa filmnya otentik betul. Jenaka, berbahasa Jawa yang terasa lentur, dan tokoh para ibu berjilbab ceriwis di truk itu cukup bernuansa lah. Tapi kemudian, saya mulai terganggu. Sosok Bu Tejo semakin dominan, dan oposisinya yang kuat; hanyalah Yu Ning.
Bu Tejo gencar mengumbar gosip tentang Dian: perempuan muda-cantik yang bekerja, lajang hingga usia yang dianggap ibu-ibu itu terlalu tua. O, ya, di akhir film, begitu Dian muncul, dia juga tak berjilbab. Segala gosip tipikal tentang sosok seperti Dian menguar dari mulut Bu Tejo. Sumbernya juga dari internet, juga amatan dengan prasangka (misalnya, Bu Tejo pernah lihat Dian muntah-muntah, dan mengisyaratkan secara tak halus bahwa bisa jadi Dian hamil di luar nikah).
Intinya, Bu Tejo menggalang anggapan ibu-ibu lain bahwa Dian adalah perempuan “nggak bener”. Gosipnya disanggah terus oleh Yu Ning. Ada text book argument lah di Yu Ning yang biasa kita terapkan untuk menyanggah hoax: jangan sembarangan menduga, cek sumbernya, jangan percaya begitu saja dong pada internet, dsb dsb. Jebule, Yu Ning masih saudara dengan Dian. Jadi, ibu-ibu lain tentu meragukan Yu Ning juga.
Para ibu-ibu tukang gosip demikian tentu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, dalam film, terutama ketika dikarikaturkan, unsur kenyataan pun bisa jadi sebuah stereotipe. Lagi pula, dalam keseharian pun bisa jadi kita punya prasangka dan stereotyping yang sudah terlalu tertanam, sehingga kita tak sadar bahwa stereotipe itu telah kita persepsi sebagai “kenyataan”. Misalnya, bahwa Ibu-ibu adalah tukang gosip, bawel, dan lelaki (dalam film ini, terlihat pada sosok sopir truk dan polisi lalulintas) selalu bingung dan kalah pada kecerewetan ibu-ibu. Tapi, sebatas itu, oke lah. Hanya terlalu berkepanjangan dan dieksploitasi saja, jadi saya yang tadinya merasa rumpi para ibu-ibu jilbab itu otentik, perlahan jadi merasa, ah, ini mah stereotipikal saja.
Sampai akhir film: dan saya tertohok. Saya mengerti siasat plot twist untuk menambah bobot hiburan sebuah film. Saya juga paham ada yang namanya ironi, atau sikap ironis terhadap sebuah subjek. Tapi, yang terjadi di akhir Tilik buat saya bukanlah ironi, tapi sebuah gagasan yang buruk tentang masalah hoax: film ini membuat Yu Ning jadi pihak yang bersalah karena justru dia yang tidak mengecek informasi, dengan demikian, menggugurkan omongan-omongannya soal keharusan mengecek sumber, dsb.
Lebih parah lagi, film ini menempatkan Dian (di adegan setelah ibu-ibu itu pergi dari rumah sakit) sebagai benar belaka sesuai gosip Bu Tejo: ia memang “perempuan nggak bener”. Ini seakan (1) mengukuhkan stereotipe perempuan lajang, bekerja, cantik, tak berjilbab sebagai bukan perempuan baik-baik; (2) bahwa segala kegiatan gosip dan menduga-duga dari Bu Tejo itu bisa jadi benar belaka, dan justru orang yang menganjur-anjurkan untuk cek dan ricek itulah yang tidak ricek. Apa artinya kesan yang terbangun ini bagi isu hoax di masyarakat kita?
Itulah sebab, saya ngomel dalam dua twit, tentang film ini. Dan lantas, cukup banyak lah komentar negatif melanda akun saya. Ada yang pasang profpic saya dan berkomentar: “your picture is just resemblence of your tweet. ‘Hmmm. Apa yang harus dikritik ya’….“. Ada yang nyuruh saya bikin film lebih baik dari Tilik. Cukup banyak yang bilang saya nggak ngerti filmnya, nggak ngerti satire, nggak ngerti realita. Beberapa rajin sekali bikin twit untuk membedah twit saya, sambil sibuk dengan bayangannya sendiri tentang apa yang saya pikirkan. Ada yang nyuruh saya nonton lagi film Funny Games-nya Hanneke dan “coba resapi” kenapa Hanneke bikin filmnya kayak gitu. Ada yang bilang saya sok edgy. Ada yang bilang saya mumet dan gak mampu menikmati sebuah film. Ada yang nyuruh saya gak usah nyap-nyap terus. Dan seterusnya. Sampai sekarang, tanggapan-tanggapan masih berdatangan.
Tentunya harus saya ungkap: tanggapan positif dan dialogis (termasuk yang tak setuju atas kritik saya, tapi tertarik berdialog) lebih banyak lagi. Wahyu, sutradara film ini yang saya anggap memang berbakat, dan Elena, produser keren dari film ini, beserta rumah produksi film ini menyambut hangat kritik saya dan berterimakasih. Elena bilang, dia paham, kadang dukungan pada film Indonesia bisa berbentuk kritik seperti yang saya lakukan.
Nah, yang saya heran, beberapa kalangan terdidik yang saya lihat rupanya menonton film ini, rupanya sama sekali tak keberatan atau tak melihat ada problem sama sekali mengenai stereotipe terhadap kaum Ibu rumpi dan sosok (semacam) Dian, serta sikap film ini terhadap isu hoax. Banyak yang hanyut merayakan nilai hiburan film ini. Banyak yang merayakan sosok Ibu Tejo yang kuat, justru karena segala “kejulidan” dia.
Seakan ada semacam blind spot terhadap film ini: nilai keterampilan pembuatan film ini dan nilai hiburannya, menutupi sama sekali nilai problematiknya.














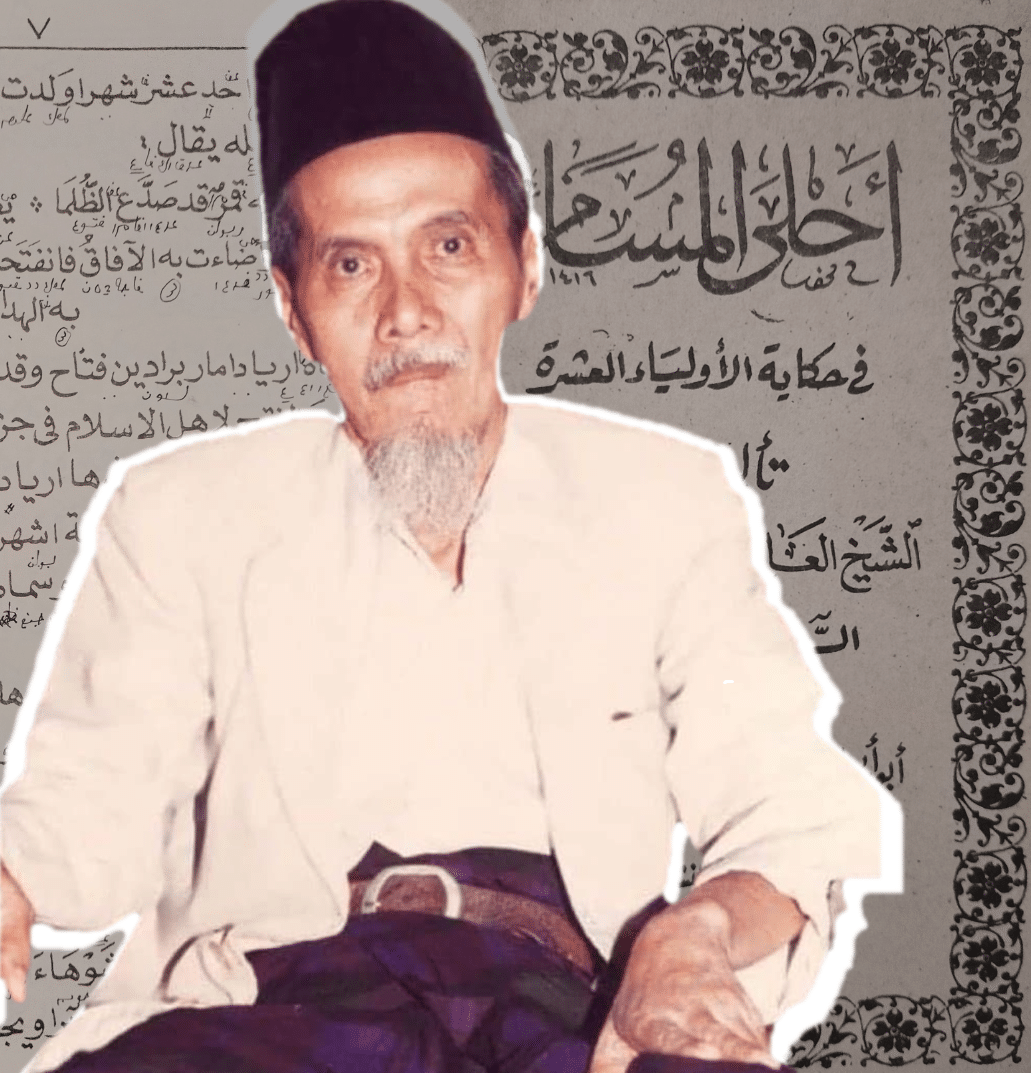

Saya bukan seorang kritikus film, cuma penikmat film. Cuma tertarik dengan pendapat Pak Hikmat. Mengapa Pak Hikmat berharap bahwa ini adalah film bernada nasihat anti hoax dan berharap pembuat film menyodorkan sisi sebaliknya dengan pesan moral, yang menurut saya menjadi klise. Sudah terlalu banyak film Indonesia atau sinetron yang bernada menasehati atau bahkan menggurui, yang membuat saya malah malas menonton, mungkin kare a saya tipe yang malas diberi tahu hal yang saya sudah tahu atau jelas-jelas terlihat. Menurut saya film ini hanya menunjukkan realitas sehari-hari yang begitu dekat dengan kita. Dan pada kenyataannya orang-orang seperti bu Tejo dan kawan-kawan memang banyak dan familiar, yang membuat film ini menarik. Justru meskipun endingnya dikatakan bahwa Yu Ning yang keliru, film ini tetap mengajak penonton untuk berhati-hati dalam mencari informasi, karena bahkan Yu Ning pun terjebak dalam emosi yang terburu-buru. Seperti kata bapake Fikri: “Tenang na pikirmu.” 🙂