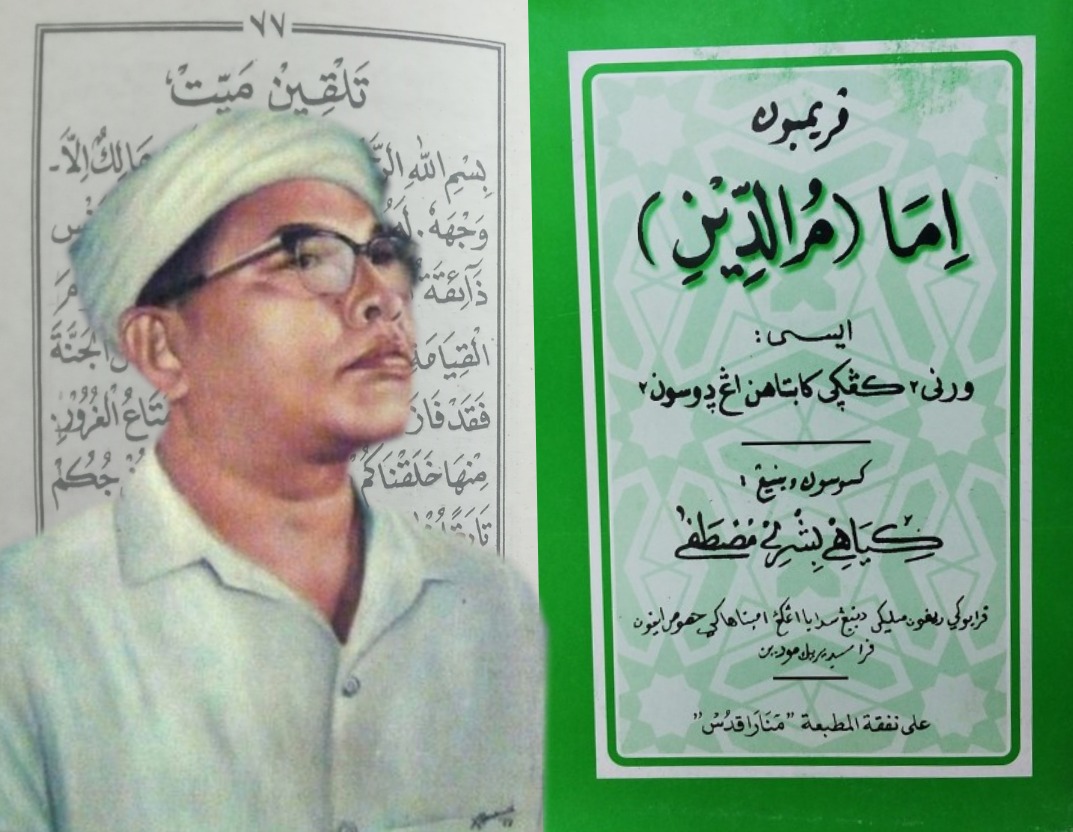Dalam opini yang menjelaskan karya-karya Abdulrazak Gurnah hingga berhasil meraih penghargaan nobel di bidang sastra (www.kompas.id, 24 Oktober 2021), saya menyampaikan secara eksplisit bahwa kemenangan Gurnah identik dengan karya besarnya yang berjudul “Paradise”. Novel itu diterbitkan sejak tahun 1994, dan diilhami dari perjalanan hidup Nabi Yusuf berikut nama-nama tokoh yang menyertainya. Gurnah membentangkan kisah tersebut dalam konteks kekinian, bahwa problema hidup yang dialami Nabi Yusuf puluhan abad lalu, masih tetap valid dan relevan hingga saat ini.
Ketika jauh dari keluarganya, Yusuf digadaikan sebagai budak kepada saudagar kaya-raya (Paman Aziz). Ia pun ikut mengembara dan berkelana bersama majikannya, mengikuti rombongan karavan untuk berdagang. Perjalanan melintasi Benua Afrika yang penuh keindahan surgawi justru membuat Yusuf terperangkap dalam ketertindasan dan perbudakan. Pergolakan dan perebutan kekuasaan yang terjadi membuat rombongan karavan Yusuf harus berhati-hati dan waspada selalu. Pengalaman hidup yang serba diselubungi intrik politik membuat kepribadian Yusuf semakin matang dan dewasa.
Selanjutnya mengenai kisah Nabi Yusuf, lebih mendetil dijabarkan oleh penulis Banten Hafis Azhari (www.alif.id) sekitar dua bulan sebelum Gurnah meraih nobel di bidang sastra. Sejak 3 Agustus 2021, Hafis telah menulis pada kolomnya dengan judul yang panjang, “Sebuah Kisah Qurani yang Berakhir dengan Happy Ending (Diadaptasi dari Surah Yusuf)”. Sangat interesan, karena kolom pada Alif tersebut seakan memprediksi tentang kemenangan Gurnah, yang sebenarnya bukanlah kandidat favorit. Ada nama-nama besar lainnya yang selama ini digadang-gadang, di antaranya Haruki Murakami (Jepang), Annie Ernaux (Perancis), dan Margaret Atwood (Kanada).
Sebagaimana penuturan dalam adegan film “Nomadland”, Gurnah juga sangat mahir mengeksplorasi pengalaman pengungsi dalam novelnya yang berjudul “Admiring Silence” (1996) dan “By the Sea” (2001), yang bertema tentang citra diri manusia, berikut identitas kehadirannya di permukaan bumi ini. Dua novel tersebut ditulis bagaikan sebuah otobiografi tentang perjalanan seorang pria dari Zanzibar (kini menjadi bagian dari Tanzania) yang melarikan diri ke Inggris dan berbohong tentang masa lalunya di Afrika guna melindungi dirinya dari rasisme dan sektarianisme kesukuan.
Novel terbaru Gurnah (2020) berjudul “Afterlives”, menggambarkan tokoh yang menyelematkan diri dari keganasan rasisme, mengingatkan kita pada tokoh Haris dalam novel Pikiran Orang Indonesia, yang kemudian menolak kultur peradaban yang dibangun rezim Orde Baru yang bersikukuh menegakkan sistem “right or wrong is my country”. Nalar dan akal sehat semakin mengetuk rasa kemanusiaan, hingga pada akhirnya setiap manusia beradab harus berani menegakkan prinsip “right or wrong is right or wrong”.
Dalam kisah “Paradise” ada relevansinya dengan perjalanan wabah yang menyerang penduduk Afrika Timur, identik dengan situasi pandemi Covid-19 yang melanda kehidupan manusia saat ini. Masing-masing suku membangun karakter dan aturannya sendiri. Bahkan, salah seorang tokoh dalam rombongan karavan memberikan kesaksian, “Di wilayah ini berlaku aturan baku, bahwa ketika seseorang akan berkuasa ia harus menjadi jawara penuh, dengan syarat berburu singa, membunuhnya kemudian menyantap kemaluannya. Ia hanya diperbolehkan menikahi perempuan setelah berhasil menyantap penis singa. Dan semakin banyak penis yang ia makan, semakin terpandanglah kedudukannya di mata masyarakat.”
Ketika Islam maupun Kristen disebarkan kepada komunitas suku tersebut, mereka menjadikan agama monotheis itu sebagai guyonan dan cemoohan. Bagi mereka, toh para pemeluk agama itu saling bertikai dan menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya. Abdulrazak Gurnah juga menggambarkan adanya tokoh perlawanan kepala suku yang mengobarkan kebencian terhadap ajaran monotheisme (keesaan Tuhan). Sikap resisten dari sebagian rombongan karavan terhadap adat dan tradisi mereka (yang dianggap kafir), tidak pernah menyelesaikan masalah. Ditambah dengan kehadiran kolonialisme Eropa yang terang-terangan mengobarkan perang terhadap mereka, telah menciptakan kengerian baru yang tak terbayangkan. Yusuf menyaksikan fenomena tersebut, hingga kemudian ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh, tampan dan perkasa. Banyak wanita yang jatuh cinta, bahkan tergila-gila kepadanya, termasuk Sang Nyonya, istri pertama Paman Aziz.
Novel “Paradise” yang membuat nama Gurnah dikenal secara internasional, dan digarap dalam konteks kekinian, seakan menggugat persoalan prinsipil dan abadi, mengapa kehidupan manusia – dari zaman ke zaman – selalu saja tergenangi oleh permasalahan tuan dan budak. Dan keberadaan Yusuf dan orang baik, seakan dipaksa hadir dan mengada dalam tugas membenahi kesemrawutan dan kesewenangan itu.
Di sisi lain, bicara tentang warna kulit atau ras suatu bangsa, erat kaitannya dengan tanah kelahiran atau kampung halaman seseorang (homeland). Permasalahan kampung halaman identik dengan persoalan perantauan atau pengungsian (displacement), bahwa seseorang yang dilahirkan di suatu tempat, belum tentu mempunyai sense of belonging terhadap tempat dan tanah kelahirannya. Dalam peradaban Islam, kita mengenal “hijrah”, ketika rasa nyaman yang diberikan Yatsrib (Madinah) memungkinkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya memandang tempat baru sebagai kampung halamannya.
Hal ini mengandung konsekuensi ketidakjelasan perihal identitas seseorang berdasarkan unsur geografisnya. Jadi, orang yang lahir di suatu tempat, belum tentu menunjukkan konsep identitas seseorang secara pasti. Dalam novel By the Sea (2002), Abdulrazak Gurnah dengan cermat menggambarkan identitas kebangsaan yang tak bisa dipisah-pisahkan berdasarkan warna kulit, apakah hitam, putih maupun cokelat dan sawo matang.
Sebenarnya, novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa (Pramoedya) sebenarnya lahir dari gagasan yang lebih jitu dan tajam, tetapi dalam By the Sea (Gurnah) lebih mendetil lagi dalam penampakan para tokoh secara eksplisit dan apa adanya. Permisalan yang disodorkan menyangkut keseharian orang-orang Afrika Timur yang (tanpa adanya paksaan) mengadopsi peradaban Barat, bahkan ada yang memilih nyaman dalam sistem peradaban yang dianutnya. Sebaliknya, orang-orang kulit putih (Inggris) banyak juga yang memilih menganut pola hidup ketimuran (Afrika), termasuk Islam sebagai agama monotheis yang dibawa penduduk Oman, kemudian dianut oleh mayoritas warga Zanzibar (Tanzania).
Hal ini mengingatkan kita pada karakteristik orang-orang Banten dalam novel Perasaan Orang Banten, yang meliputi orang-orang Jawa, Sunda, Cina dan Betawi, tetapi penulis menampilkan juga pendatang dari kepulauan lain seperti Padang dan Batak (Medan). Kemudian muncullah akulturasi budaya antara penganut Islam, Kristen dan Kong Hu Cu, yang berkecimpung dalam komunitas masyarakat plural yang dinamakan “wong Banten”. Jadi, persoalan kampung halaman (homeland) identik dengan soal kenyamanan, bukan hanya semata-mata soal ekonomi, keamanan dan stabilitas nasional.
Karena itu, betah atau tidak betah untuk tinggal atau “berpindah” kampung halaman, terkait dengan jaminan kenyamanan hidup atau (dalam istilah agama) jaminan keberkahan. Maka, di sinilah kita mengenal konsep “rizki” yang bukan semata-mata soal mewah maupun banyaknya uang, melainkan soal ketenangan jiwa, kelapangan hati dan kenyamanan hidup.
Pramoedya pernah menyatakan secara eksplisit perihal orang-orang Timor-Timur sebagai “anak angkat” dari bangsa indonesia. Mereka bukan bekas jajahan Hindia Belanda, meskipun secara geografis mendekati wilayah Indonesia namun secara historis berbeda. Karena itu, Bung Karno pernah menegaskan (1945), bahwa teritorial Indonesia tidak akan memasukkan suatu wilayah yang secara administratif bukan bekas Hindia Belanda. Jadi, secara implisit Soekarno sebenarnya sudah menyinggung soal wilayah Timor Timur, dan apa yang akan terjadi setelah 25 tahun pendudukan militerisme Orde Baru.
“Akan tetapi,” tegas Pramoedya, “kalau Indonesia mampu menjadi bapak angkat yang baik bagi Timor Timur, serta memberi kenyamanan hidup bagi penduduknya, siapa yang mau memisahkan diri dari orang tua yang bijak dan arif. Kalau militer Indonesia yang ditugaskan di sana, kerjaannya tidak membunuhi dan menembaki penduduk setempat, tentu saja tidak akan timbul sikap yang resisten dan antipati terhadap dunia militer di negeri ini.” (*)