
Pagi itu suasana kuliah umum di satu universitas ternama yang populer di kalangan orang Tionghoa, lumayan riuh. Saya bersama seorang Romo diminta berbicara mengenai Konsep ‘Tuhan’ Menurut Agama-Agama.
Tentu saja ini merupakan topik dan tema yang kompleks dan butuh diskusi panjang untuk menyepakati beberapa diskurus penting terkait isu-isu teologi dan filsafat agama. Istilah agama sendiri kalau meruntut peristiwa sejarah, sangat bernuansa politis. Namun saya sedang bermaksud fokus ke wilayah ini.
Betapa pun agama, sebagaimana dalam ilmu sejarah, memang merupakan suatu gejala yang sangat rumit dan unik.
Agama dan Kecemasan dalam Diri Manusia
Fenomena agama-agama di dunia acapkali membuktikan bahwa manusia di setiap zamannya selalu mengalami gejala “kecemasan”. Kalau meminjam teori psikoanalisis Frued, di dalam diri manusia terdapat perasaan terjepit dan terancam dalam bentuk serpihan-serpihan kecemasan (anxiety) yang tak kunjung usai.
Kecemasan yang paling mengerikan dihadapkan pada proses seleksi alam, hidup tidak banyak memberi penawaran yang bisa “memuaskan” harapan manusia. Saya mendapati beberapa catatan penting dari John F. Haught, Guru besar teologi dari Georgetown University, dalam tulisannya Science and Religion: From Conflict to Conversation (1995).
Yang menarik adalah ide tentang lanjutan pemikiran Darwin mengenai The origin of Species yang menyatakan bahwa “proses seleksi alam itu kejam; hanya organisme-organisme yang beradaptasi dengan baik saja yang dapat bertahan hidup. Pada dasarnya alam itu buta dan tidak peduli dengan kemanusiaan”.
Faktanya bahwa setiap anggota spesies harus berjuang bertahan hidup, dan banyak dari mereka menderita-hilang bahkan lenyap dalam perjuangan itu. Proses evolusi ini merefleksikan pada kenyataan betapa alam semesta ini selain tempat yang “asik” bagi mereka yang mampu bertahan, di sisi lain alam semesta pada dasarnya juga kejam khususnya terhadap yang lemah” (Haught, 1995).
Boleh jadi bermula dari kecemasan-kecemasan ini, manusia merasa perlu “bersandar” pada sebuah fetis untuk menjangkau “kekuatan” di luar dirinya. Maka, lahirnya sejarah-sejarah agama dan konsep tentang Tuhan yang berakar pada gejala kecemasan yang melekat dalam diri manusia akan ketidakpastian.
Ketidakpastian yang dimaksud di sini merupakan sebuah gerak perubahan peradaban dunia yang membuat umat manusia semakin merindukan ruang-ruang transendental dari zaman ke zaman. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya atas ketidakpastian itu?
Manusia semakin sibuk menghadirkan Tuhan dengan berbagai daya upaya, termasuk dengan cara menciptakan visualisasi, imajinasi, ritual, doa, hingga proses mempercayai, dan meyakininya. Meski bagi sebagian manusia fase iman saja ternyata juga tidak cukup, sebagian mereka masih rentan kehilangan arah untuk mencari jawaban atas kehadiran dan pertolongan-Nya.
Hadirnya kuil-kuil suci dan tempat ibadah sampai sekarang juga belum mampu secara optimal menjawab sekaligus menyelesaikan persoalan dunia dan manusia.
Di sisi lain, agama-agama dan imaji tentang Tuhan saling “mengutuk” satu sama lain. Gejala ini belakangan juga membuktikan bahwasanya selain mendorong umat manusia untuk menjadi lebih baik, di sisi lain agama dan imaji tentang Tuhan mendongkrak jumlah konflik sekaligus perang antar umat manusia. Fakta ini disinggung dengan jelas dan tegas oleh Charles Cimball dalam bukunya yang berjudul When Religion Becomes Evil (2008).
Tuhan-Tuhan yang Palsu
Kita, bagaimana pun juga, tidak mampu menghindar dari resonasi gelombang perubahan zaman dan peradaban yang tidak pernah berhenti menggoda sekaligus mencabik-cabik hasrat manusia untuk terus berevolusi. Modernisasi dan industrialisasi melibas segala angan-angan demi mewujudkan mazhab materialisme sebagai anak kandung ontologi monistik.
Apakah ketika manusia memiliki kepintaran, kekuasaan, kekayaan, popularitas, wajah yang rupawan dan semua yang material itu menjamin manusia merasa cukup atau puas atas hidupnya? Faktanya banyak referensi yang memberi jawaban tidak. Manusia masih terus menerus mencari lentera untuk menjawab kecemasannya melalui agama, entah seperti apa Tuhan yang diimajinasikan.
Mircea Eliade (1907-1986), filsuf asal Rumania, dalam “penziarahannya” yang cukup memilukan telah menemukan kategori manusia homo-religious di zaman archaic—yakni tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai spiritual yang dapat menikmati kesucian yang ada sekaligus tampak pada alam semesta, tumbuhan, hewan, dan manusia itu sendiri.
Manusia-manusia homo-religious adalah mereka yang menyadari kehadiran dirinya dengan alam dan menyatu dengan alam sebagai “bentuk spirit yang paling sakral”. Apa “yang tampak” menjadi tidak penting untuk “tampak”, dan apa “yang tidak tampak” menjadi penting untuk “tampak”—begitulah kira-kira salah satu tipe manusia homo-religious yang dimaksud Eliade.
Maka, zaman manusia homo-religious adalah sebuah zaman di mana menjadi spiritualis tidak perlu atribut “agama” sebagai identitas yang hanya bersifat profan saja. Sementara di zaman sekarang ini, atribut agama seolah-olah diposisikan menjadi penting hingga dipuja-puja dan “disembah” melampau “Tuhan” itu sendiri. “Agama” mulai diperdagangkan dan diperjualbelikan, termasuk jargon “Tuhan-Tuhan yang palsu”.
Pantas saja, Karen Amstrong dalam bukunya tentang Sejarah Tuhan (1993) menjelaskan bahwa ide tentang Tuhan dalam masyarakat tidak harus bersifat logis dan ilmiah, yang penting bisa diterima. Sementara teolog seperti Vine Deloria (1933-2005) mempunyai argumen yang tak kalah menarik yaitu bahwa “agama untuk orang-orang yang takut neraka sementara spiritualitas untuk orang-orang yang sudah sampai ke sana”.
Namun di atas segala denyut nadi perdebatan mengenai agama dan Tuhan, saya sependapat dengan antropolog J. Van Baal dalam tulisannya yang berjudul Apa Artinya Religi? (1987) mengingatkan kita semua bahwasanya—“Tuhan yang benar-benar Tuhan, melampaui segala bukti dan pengertian manusia”.
*Tulisan ini disampaikan dalam Kuliah Umum “Konsep Tuhan Menurut Agama-Agama” di Universitas Ciputra – Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2019.














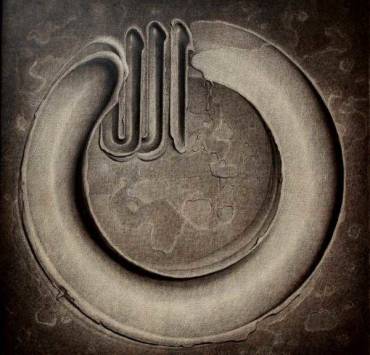






Lantas pendapat kakak tentang konsep Tuhan apa?