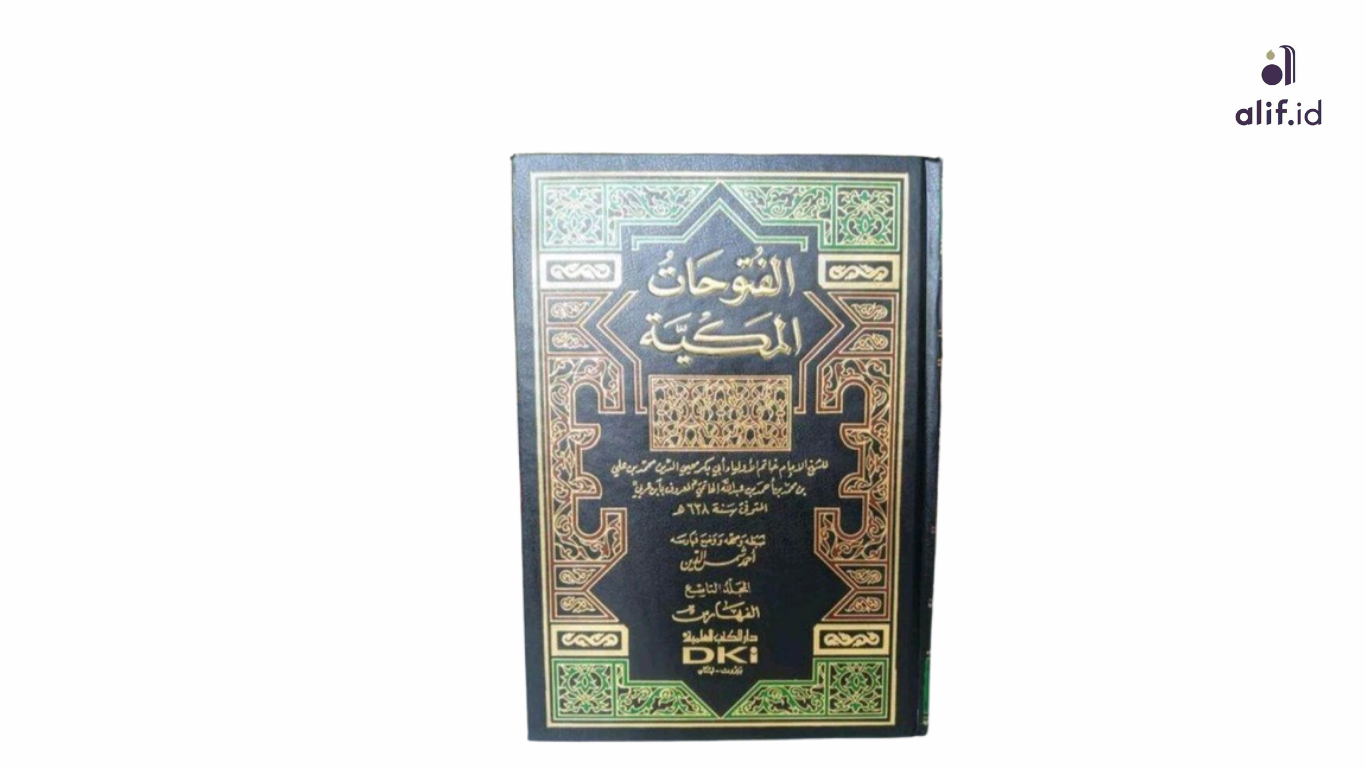Tiap manusia yang hidup, pasti menginginkan sesuatu, tetapi sejauh atau sebanyak apa yang telah direngkuhnya, tanpa rohani, ia tetaplah di antara miliaran manusia yang melewati sejarah, hidup hanya ‘terentang sepanjang bekas cakar kita pada pasir, dan segera lenyap. Demikian suatu kali dikatakan Annemarie Schimel dalam pengantar bukunya Mystical Dimension of Islam.
Bersamaan dengan itu, melalui buku Menjadi Manusia Rohani, setebal 284 halaman karya Kiai Ulil Abshar Abdalla ini terasa menghentak kesadaran kita. Mengapa kita harus berbuat baik dan memaknainya? Kenapa ada sesuatu yang ‘mandeg’, bahkan ‘hampa’, juga ‘pergi’ begitu saja dari ‘ruang’ hidup ini?
Pertanyaan-pertanyaan eksistensialis itu yang coba dijawab oleh syarah kitab al-Hikam 50 bait ini dengan bahasa yang renyah dan mudah dipahami.
Mungkin karena ditulis dengan refleksi bebas—tidak seperti biasanya sebuah buku syarah yang dogmatis—buku ini seperti benar-benar mengerti kegelisahan dan pergumulan kita dari ujung ke ujung. Semua aspek kehidupan dan misterinya dibahas dengan berbagai sudut pandang dan refrensial.
Bagi saya sendiri yang tiap malam Jumat mencoba istikamah membaca (belajar) kitab al-Hikam, baris demi baris kata dalam buku ini seperti memberi perspektif baru dan benar-benar mengena tepat di hati.
Bahkan, terkadang saya merasakan ada tamparan halus di pipi saya. Tak jarang pula, seperti ada secercah cahaya timbul dalam hati, juga sesekali saya pun tersenyum.
Bersamaan dengan itu, kata “rohani” membawa imaji melodramatik, pertentangan penuh gairah dan gundah, antara hidup yang pasrah di satu sisi, dan hidup yang penuh ambisi, disisi lain. Istilah yang sering disebut oleh spiritualis, saat kondisi terdesak atau sedang dalam posisi kesulitan merengkuh gemerlapnya dunia. Tak semuanya tertarik untuk membahas tema ini.
Namun demikian, tutur Schimel, seorang rohaniawan, acapkali punya sejenis ‘animisme’ dalam dirinya: mereka menemukan pemusnahan dari ketidak tahuan yang membuat misteri hidup terasa terkadang terungkap, terkadang terhijab, terkadang makna itu hilang, terkadang juga kembali. Tak ada yang sepenuhnya tersingkap, tetapi yang ada di sana adalah pengungkapan selubung-selubung ketidak tahuan.
Karena itu membaca buku ini, saya merasa tidak saja dibawa mengalir ke makna terdalam aforisma-aforisma Ibnu Athaillah, terutama ketika mengupas terminologi sulit seperti ‘makrifat’, ‘kasyaf’ dan ‘warid’, tetapi juga diseret ke puncak ‘arus iluminasi’ Imam Ghazali, terutama yang termaktub dalam Misykatul Anwar-nya.
Kuketuk pintu wujud itu berkali-kali. Kau mengizinkan, ini Aku, katamu, Aku izinkan kau memasuki. Tetapi tak ada yang ada dalam wujud kecuali Allah (fil hukmil Madun). (Misykat, 7).
Dengan ungkapan ini, al-Ghazali mengungkapkan terma al-Washilun yang sejajar dengan al-Marifah Ibnu Athaillah, untuk menunjuk personifikasi manusia rohani, yang sampai tingkat paripurna. Adalah orang-orang yang telah sampai dalam pengenalan dengan Tuhan melalui dzauq (intuisi) dan jiwa (nous).
Sehingga menempati maqam dengan mendapatkan pengetahuan, yang lebih dari indrawi dan akali, dengan merasakan segala sesuatu adalah keindahan, kesucian dan wujud dirinya sendiri. (Misykat, 48). Wallahu’alam.
Dalam Kereta Ranggajati.
Situbondo-Surabaya.
Jam 09; 07, 24 Februari 2019