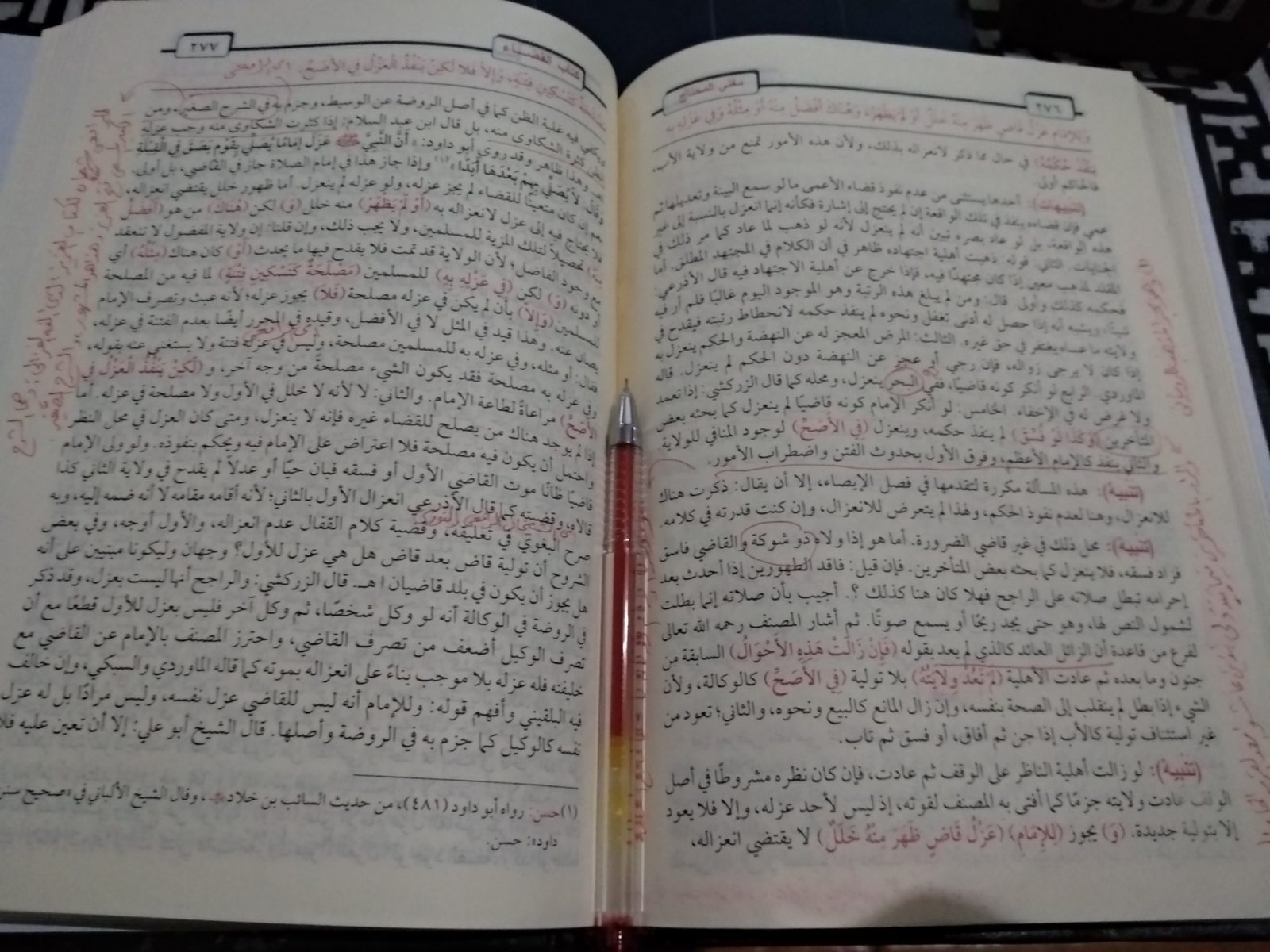
Tren kajian ilmu maqashid syari’ah semakin menanjak akhir-akhir ini. Meski secara konsep sudah ada sejak lama, perlu diakui bahwa sosok yang sangat berjasa dalam mempopulerkan kembali ilmu maqashid syari’ah adalah Ibnu Asyur dengan masterpiece-nya berupa kitab Maqashidusy Syari’ah al-Islamiyyah.
Peningkatan akan minat ilmu ini bisa dilihat pada berkembangnya wacana ilmu maqashid syari’ah, baik di ranah pesantren maupun perguruan tinggi Islam. Ilmu maqashid syari’ah pun merupakan konsentrasi dalam program studi Fiqih dan Ushul Fiqih di Ma’had Aly Krapyak, tempat saya menimba ilmu saat ini.
Wacana tentang ilmu maqashid syari’ah juga banyak dibicarakan dalam forum-forum Halaqah Fiqih Peradaban yang diadakan oleh PBNU di berbagai pesantren se-Indonesia. KH. Sahal Mahfudh, sebagai salah satu Rais ‘Aam PBNU, juga seringkali menyinggung tentang wacana ini dalam kompilasi tulisan buku Nuansa Fiqih Sosial-nya.
Meski ada beberapa kalangan yang masih menganggap ilmu maqashid syari’ah sebagai bagian dari ilmu ushul fiqih, namun dukungan atas ilmu ini berdiri sendiri dari ilmu ushul fiqih juga tidak kalah masif. Hal ini bisa dilihat terutama pada tradisi akademik kawasan Afrika Utara yang sangat mendukung berkembangnya ilmu ini.
Objek kajian dari ilmu maqashid syari’ah dengan ilmu ushul fiqih pun berbeda. Jika ilmu ushul fiqih fokus pada kajian nushush syari’ah (tekstualitas syariat), maka ilmu maqashid syari’ah berorientasi pada ma’ani syari’ah (makna dan hikmah syariat).
Perkembangan ilmu maqashid syari’ah ini pun memunculkan cabang-cabang ilmu lain yang berinduk pada ilmu maqashid syari’ah seperti ilmu ma’alatul af’al yang akan kita bahas kali ini beserta contoh-contohnya, mari kita simak bersama!
Pengertian dan Urgensi Ilmu Ma’alatul af’al
Dalam bukunya, Walid Ali al-Husain menjelaskan bahwa ilmu ini terdiri dari dua kata kunci, yaitu ma’al (مآل) dan af’al (أفعال). Kata pertama, yakni ma’al bermakna akibat, dampak, dan tempat kembali. Sementara kata af’al mempunyai makna semua perbuatan yang muncul dari orang yang mukallaf, baik dalam hati, ucapan, maupun perbuatan.
Ketika dua kata ini digabung akan memunculkan suatu istilah sendiri yang dipakai sebagai definisi dari ilmu ini, yakni merupakan ilmu yang membahas tentang pertimbangan atas dampak yang diakibatkan oleh hukum-hukum dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan maqashid syari’ah.
Ilmu ini mirip dengan ilmu kebijakan yang lebih dikenal secara umum. Keduanya sama-sama memperhatikan dampak dari keputusan yang akan diambil oleh si pemilik kewenangan. Bedanya, ilmu ma’alatul af’al berorientasi pada hukum-hukum fiqih yang akan difatwakan oleh para ahlinya.
Konsep dan teori dalam ilmu ma’alatul af’al mempunyai banyak keserupaan dengan konsep saddudz dzari’ah dan fathudz dzari’ah dalam ilmu ushul fiqih. Namun, tidak serta merta bisa disamakan, karena ilmu ini mempunyai ciri khas yang bisa membedakannya sendiri.
Saddudz dzari’ah merupakan keputusan untuk menutup atau melarang suatu tindakan yang sebenarnya tidak dilarang. Namun, perbuatan itu dilarang disebabkan oleh pertimbangan atas dampaknya yang membahayakan.
Sementara fathudz dzari’ah adalah konsep sebaliknya, yakni membuka atau membolehkan suatu tindakan yang pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang. Tindakan ini akhirnya dibolehkan atas pertimbangan dampaknya yang bisa menimbulkan kemaslahatan.
Selain itu, urgensi dari mempelajari ilmu ini adalah membantu kita dalam mengaplikasikan hukum dengan cara melihat dampak yang diakibatkan oleh perbuataan atas dasar hukum tadi, mengingat hukum syariat bisa berubah sesuai dengan akibat dan hasil dari tindakan suatu hukum.
Penerapan Ma’alatul af’al oleh Allah, Nabi, dan Para Sahabat
Sebagai salah satu cabang dari ilmu maqashid syari’ah, ilmu ma’alatul af’al juga merupakan hasil dari pengamatan atas kebijakan dan tuntunan oleh Allah melalui Al-Qur’an, Nabi Muhammad melalui haditsnya, serta para sahabat dalam berbagai riwayat-riwayatnya.
Contoh dalam Al-Qur’an berupa:
وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰۤأُوْلِي ٱلالْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 179)
“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal agar kalian bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)
Sisi ilmu ma’alatul af’al dalam ayat ini bisa dilihat dari pernyataan Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Qawaidul Ahkam-nya, bahwasanya membunuh seorang pelaku pembunuhan sebenarnya merupakan kerusakan karena bisa menghilangkan nyawa pembunuh, namun membunuh seorang pembunuh ini bisa dibolehkan dalam rangka menjaga kehidupan manusia secara umum.
Dari sini, bisa dipahami bahwa membunuh seorang sebenarnya termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Namun, penerapan ancaman hukuman mati bagi seorang pelaku kejahatan menjadi dibolehkan sebab melihat sisi dampaknya, yakni ketakutan calon pembunuh dan terselamatkannya jiwa manusia.
Contoh tindakan Nabi Muhammad dalam mengaplikasikan ilmu ma’alat af’al adalah ketika Nabi menerima seluruh sedekah Sahabat Abu Bakar dan menganjurkan Sahabat Ka’ab agar menyisakan sebagian hartanya dan tidak menyedekahkan seluruhnya.
Asy-Syaukani mengomentari riwayat ini dalam kitab Nailul Authar bahwasanya kebolehan sedekah dengan seluruh harta itu berbeda-beda, sesuai dengan kondisi pelaku.
Jika pelaku adalah orang yang kuat dan tahu bahwa dirinya adalah orang mampu sabar atas kondisinya, maka dia diperbolehkan untuk melakukannya, sebagaimana kondisi dari Sahabat Abu Bakar.
Namun, bagi orang lain, sebagaimana Sahabat Ka’ab, maka dia sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan dirinya karena dia masih berpotensi tidak bisa sabar dalam kondisi tidak mempunyai harta. Jika dia berpotensi bisa sabar, maka bisa dibolehkan.
Sekali lagi contoh penerapan ilmu ma’alatul af’al oleh para sahabat dilakukan oleh Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ia menyamakan hukuman cambuk peminum khamr dengan hukuman cambuk pelaku tuduhan zina (qadzaf).
Ketika Sahabat Ali bin Abi Thalib memutuskan kebijakan itu ia beralasan bahwa orang ketika mabuk, ia akan mengigau. Ketika ia mengigau, ia akan membuat tuduhan palsu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memberikannya hukuman cambuk penuduh zina.
Asy-Syathibi berpendapat bahwa para sahabat memandang minuman yang memabukkan adalah perantara dalam melakukan tuduhan palsu yang disebabkan oleh banyaknya mengigau, dan hal itu disebabkan kondisi mabuk.
Kebijakan yang dilakukan oleh Sahabat Ali tidak lain merupakan bentuk kecerdasan dan kebijakannya yang ia tiru dari Nabi. Bisa jadi, orang-orang pada masa itu menganggap Sahabat Ali melakukan suatu bid’ah, karena ia mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi.
Sebenarnya, ilmu ini secara konsep bukanlah suatu hal yang baru. Nabi, sahabat, dan para ulama sudah mengaplikasikan ilmu ini, meski tidak disusun secara formal dengan konsep teoritis tertentu.
Namun, penyusunan ilmu ini secara khusus memudahkan bagi kita dalam mengidentifikasi pertimbangan sisi dampak dalam pengambilan keputusan suatu hukum, terutama pada kasus-kasus baru yang tidak ditemukan di era sebelumnya.
Tentu saja, dengan mempelajari ilmu ini, bisa menjadikan kita bersikap lebih bijak dan visioner dalam menyikapi keputusan penting yang akan diambil. Gimana? Asyik kan!















