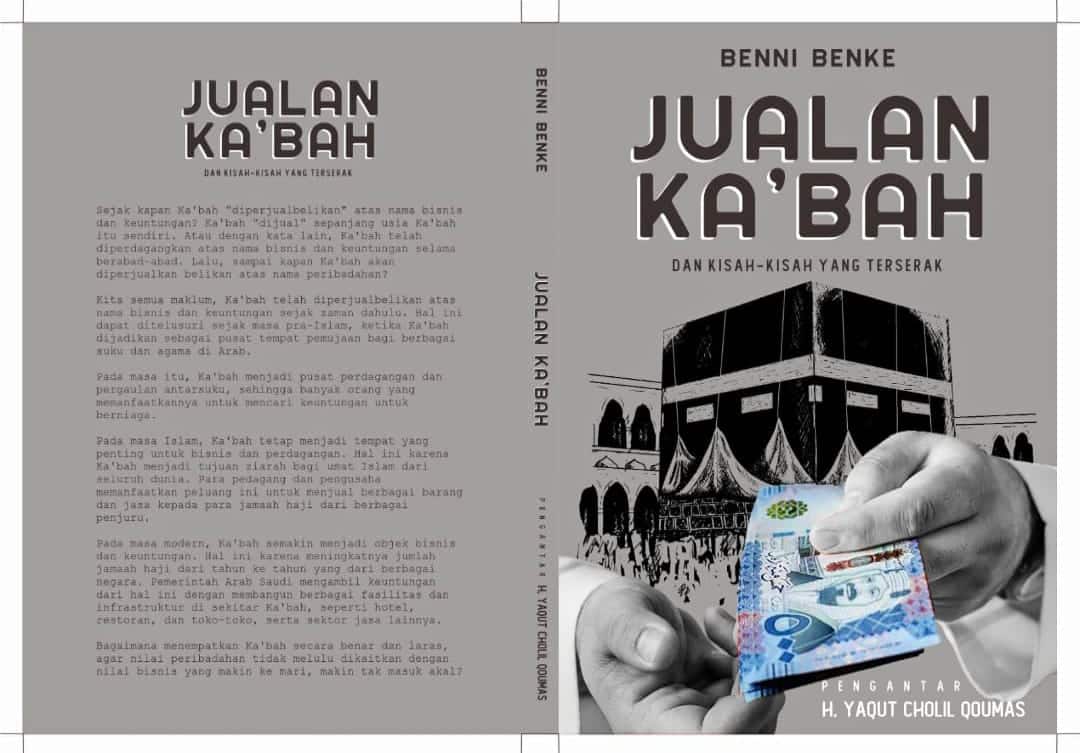Film Tauhid ini, jika diamati, merupakan tonggak penting dalam perfilman. Selain mengangkat film dengan tema haji pertama di Indonesia, ini juga bisa dikatakan sebagai tonggak film religi. Lebih-lebih para pelakunya berlatarbelakang Nahdlatul Ulama (NU), sebuah ormas keagamaan yang hampir tak memiliki perhatian dengan dunia perfilman.
Bahkan, memiliki resistensi yang cukup tinggi terhadap budaya-budaya baru yang menyerupai kebudayaan Barat. Terkadang perlu dilakukan serangkaian diskusi keagamaan (bahtsul masail) dalam forum Muktamar untuk menentukan boleh dan tidaknya.
Maka, sebelum film Tauhid beredar, Sang Produser Djamaluddin Malik, mengadakan preview khusus film tersebut. Sebagaimana dikenang Misbach, preview tersebut dihadiri para kiai dan tokoh NU. tujuannya untuk meminta koreksi sebelum nantinya dilempar ke publik dan menuai kecaman dari para kiai. Apalagi film itu bertema dakwah dan mengatasnamakan NU (Lesbumi). (Baca tulisan menarik: Film Pahlawan Islam…)
“Rasanya akan banyak kritik muncul, biar Asrul dihajar para kiai. Mana dia mampu melawan. Tapi ketika sebelum film diputar, Asrul tampil ke depan memberikan penjelasan yang sangat menarik. Dan setelah film usai dipertontonkan, tak ada kiai yang menghajar Asrul,” tulis Misbach (Asrul dalam Film).
Keberadaan Lesbumi – yang memproduksi film Tauhid – memang sempat memicu pro kontra di kalangan Nahdliyin. Choirotun Chisaan mencatat, keberadaan Lesbumi dianggap sebagai ‘penanda kemodernan penting’, sekaligus dianggap sebagai institusi yang ‘kurang menjaga martabat NU’. (Lesbumi: Strategi Politik Kebudayaan, LKiS: 2008).
Meski demikian, resistensi Nahdliyin terhadap hal yang baru, bukanlah berlaku rigid. Jika terdapat penjelasan yang tepat menurut syara’ dan logika, maka hal-hal baru dapat diakomodir. Seperti halnya dalam pembuatan film sebagai bahan dakwah itu sendiri. (Baca tulisan menarik: Banyak Jalan Menuju Dakwah)
Asrul Sani dalam prasarannya berjudul ‘Tantangan Zaman dan Kegiatan Kebudajaan Ummat Muslimin’ dalam Mubes I Lesbumi (1962) menyampaikan satu ‘provokasi’ kebudayaan yang cukup sensitif kala itu. Namun, rasionalitas yang ditawarkannya satu frekuensi pemikiran dengan para kiai dan tokoh NU. Sehingga resistensi yang ditimbulkan tidak terlalu besar dibandingkan pedasnya provokasi itu sendiri.
“….Tantangan tersebut [kebudayaan] dengan menatap ke depan ke suatu masa di mana gedung teater atau bioskop akan menggantikan atau mendampingi mimbar masjid atau gereja,” ungkap Asrul sebagaimana disalin ulang oleh Choirotun Chisaan.
Guna menghadapi tantangan tersebut, Asrul memberikan prasaran, “menjawab segala tantangan secara kreatif, secara mencipta, dan secara positif.”
Provokasi Asrul tersebut, tentu sempat menimbulkan pertentangan. Namun, apa yang disampaikannya tersebut, menjadi momok yang ditakuti kala itu. Tuntunan agama mulai tergeser oleh tontonan. Masyarakat lebih menggemari aneka kesenian dan pertunjukan. Lebih celaka lagi, saat itu, lawan-lawan politik dan ideologis NU, begitu gencar mempropagandakan kepentingannya melalui kebudayaan. Sebut saja PKI dengan Lekra-nya serta PNI dengan LKN-nya. (Baca tulisan menarik: Cara Gus Dur Memilih Media)
Kondisi demikian pun mau tak mau membuat NU harus beradaptasi. Medium yang sama pun harus dipergunakan, meskipun konten harus dijaga secara ketat. Sikap adaptif NU yang demikian, sebenarnya bukanlah barang yang baru. Prinsip NU yang ‘mempertahankan sesuatu yang lama yang masih baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik (almuhafadlatu alaa qadhimis sholih, wal akhdu alaa jadidil ashlah)’ menjadi legitimator akan hal itu.
Dari prinsip-prinsip demikian, Tauhid sebagai film yang diproduksi secara resmi oleh institusi NU (Lesbumi) dapat diterima oleh kalangan Nahdliyin. Meski pada perkembangannya, geliat perfilman di kalangan Nahdliyin tak banyak beranjak dari masa 60-an hingga kini. Padahal, meminjam bahasa Asrul, bioskop (baca: Youtube) kini telah mengungguli mimbar-mimbar masjid daya jangkaunya. (Baca Bagian pertama tulisan ini: Mengenang Tauhid, Film Haji yang Terlupakan)