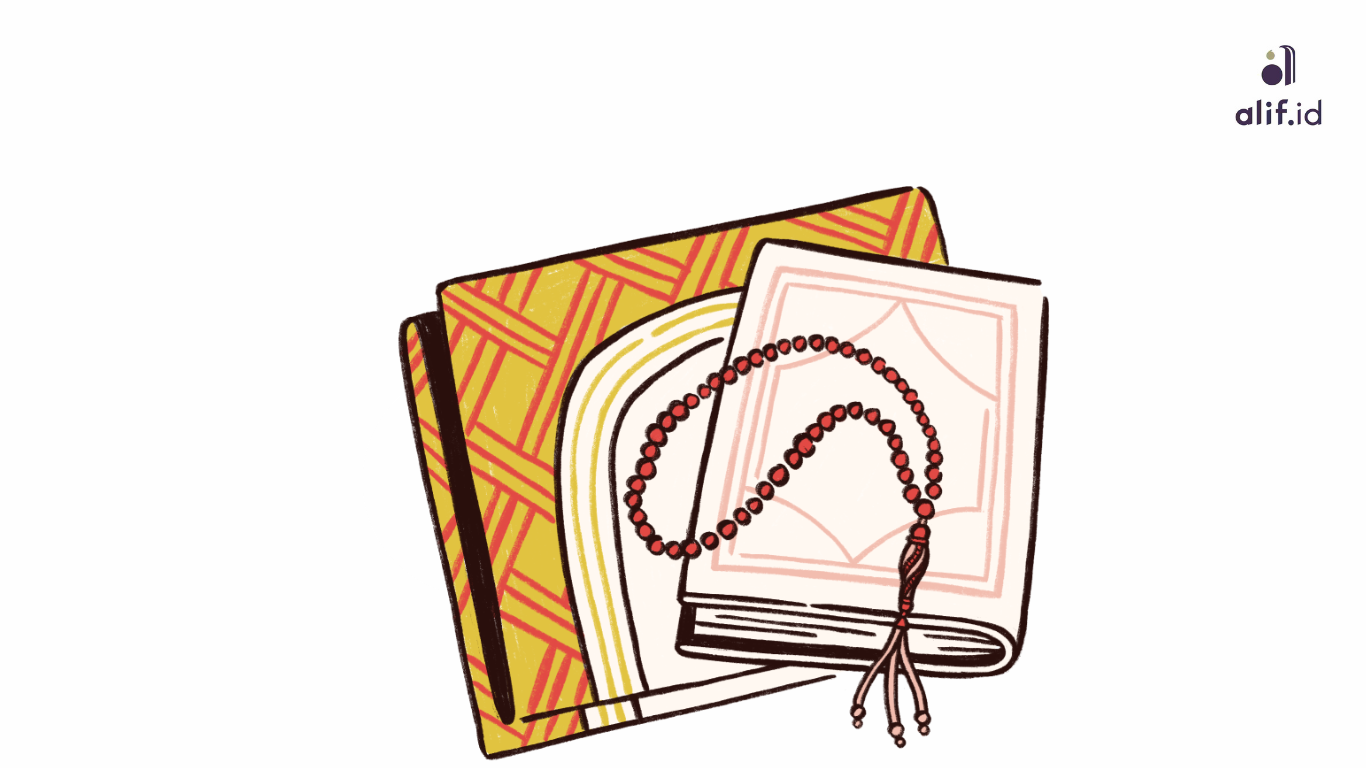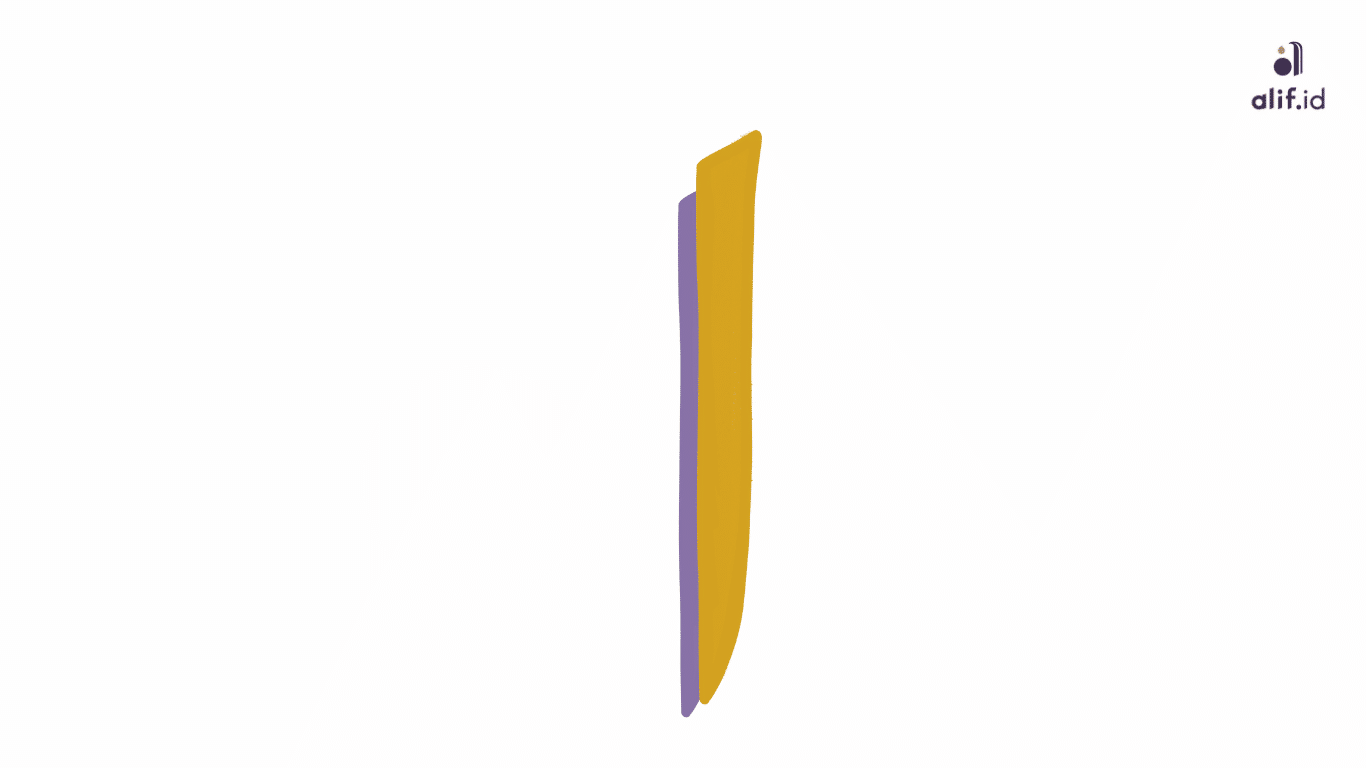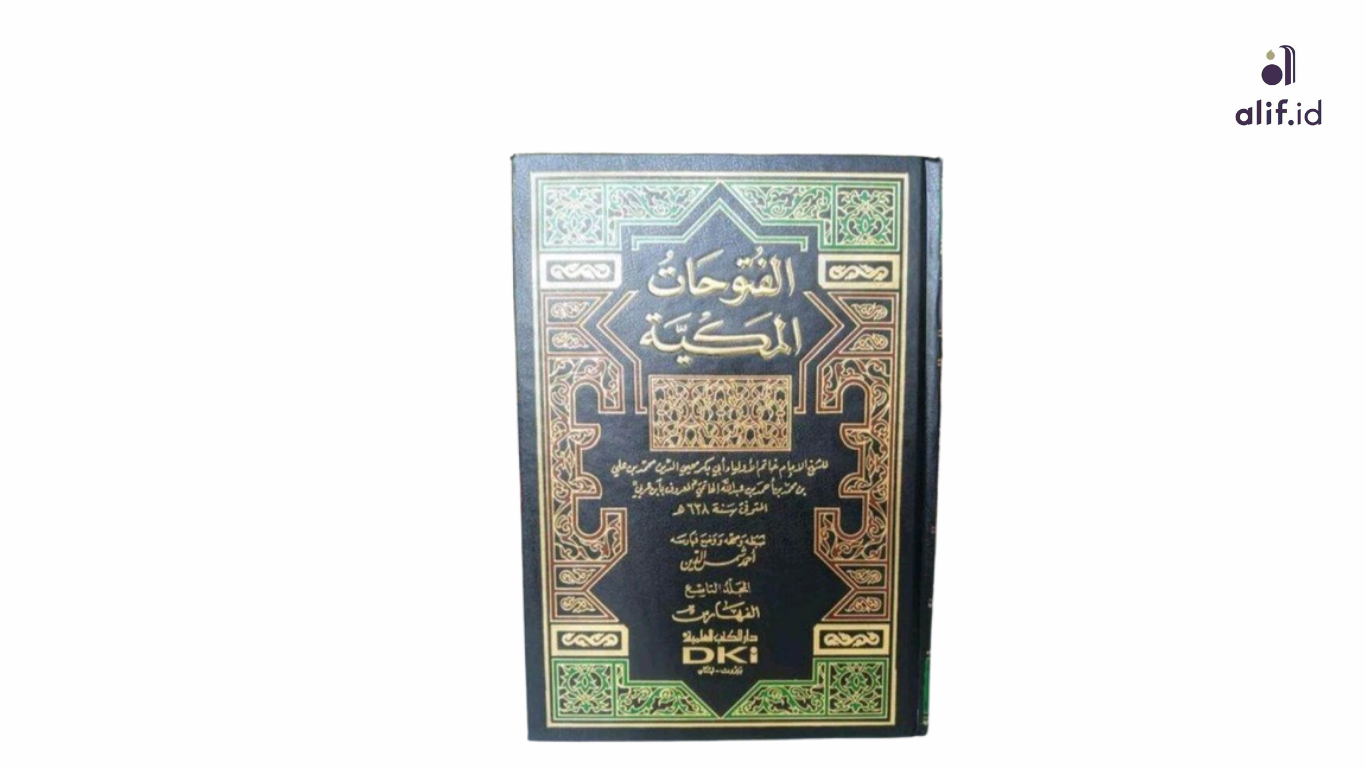
Karyanya yang paling bisa bertahan lama, Futuhat al-Makiyyah (Penyingkapan-penyingkapan Makkah) – dinamakan demikian karena dia berada di Makkah ketika malaikat pembawa ilham memerintahkan di memulainya – terdiri atas 565 pasal serta diterbitkan dalam 4 jilid besar. Selain memuat telaah-telaah seputar doktrin sentral Tasawuf dengan ilmu-ilmu kosmologis serta ilmu-ilmu lain yang seolah-olah terletak pada batas-batas Tasawuf, karya yang mirip sebuah bunga rampai ini pun banyak berkisah tentang kehidupan para mistikus sejawatnya, dan sekaligus merupakan salah satu sumber utama informasi mengenai kehidupannya sendiri.
Dari karya ini dan juga salah satu dari dua risalah yang lebih ringkas, kita memperoleh kesan mendalam yang tak terhapuskan dari seorang mistikus dalam arti yang sebenarnya, seorang manusia yang menempuh pengasingan spiritual dan tak pernah henti bermunajat, seorang yang diakui sebagai wali sepanjang hidupnya dan bahkan semasa mudanya, (dia dianggap sebagai) seorang penerima mimpi-mimpi ganjil yang hanya dilampaui oleh para Nabi saja. Lepas dari kehadiran spiritualnya yang begitu hebat, dia sangat dikasihi para sultan dan pangeran berkat nasihatnya yang blak-blakan serta dilontarkan tanpa kenal rasa takut. Lagi pula dia ditakdirkan untuk berkelana ke mana-mana dan kapan saja, dan tak pelak lagi dalam hal ihwal hubungan pribadi sebagaimana dalam tulisan-tulisannya, kalau tak dikatakan lebih, dia menjadikan dirinya dihormati selama hidupnya.
Ciri esensial periode yang kini kita tinjau menunjukkan pengakuan terhadap Tasawuf sebagai bagian untuh dari Islam sekaligus merupakan penembusan kembali Tasawuf atas umat, sejauh dimungkinkan dalam zaman yang demikian sarat dengan kristalisasi-kristalisasi eksoterik yang awalnya tidak ada. Formulasi berikut, yang diberikan oleh seorang yuris ulung abad ke-14, bisa dikatakan menggambarkan apa yang kini diterima secara luas: ilmu-ilmu agama itu meliputi tiga hal: yurisprudensi (fiqh), yang ditujukan kepada Hadis yang diriwayatkan ‘Abd Allah Ibn ‘Umar sebagai islam (penyerahan diri), asas-asas teologi (usul ad-Din), yang dirujukkan sebagai iman (kepercayaan), dan mistisisme (tasawwuf) yang merujuk kepada ihsan (kesempurnaan). Yang lain dari itu harus direduksi ke dalam salah satu di antara tiga sebutan ini, atau sebaliknya dia di luar agama.
Pengakuan diperlukan bagi pemulihan daya jangkau yang melibatkan organisasi, dan penyebaran serta keterbukaan yang semakin besar dari tarekat-tarekat, sehingga memungkinkan ‘darah hati’ mengalir lebih lancar ke seluruh ‘tubuh’ Islam sebagai keutuhan, dapat menjadi gangguan bagi kualitas mistisisme Islami ini. Karena pemahaman yang merupakan daya jangkaunya itu tidak pernah menyeluruh. Barangkali bukannya tanpa maksud di sini dinukilkan sebagian nasehat tentang Tasawuf yang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa Muslim oleh seorang rektor Universitas Al-Azhar Kairo, awal abad XIX, karena sebagai kiblatnya pusat pengkajian utama Islam, lembaga ini bisa dikatakan merupakan otoritas bagi seluruh dunia Islam:
“Ilmu tasawuf terbagi dalam dua kategori. Pertama, tentang pendisiplinan watak serta penanaman semua adab spiritual pada-Nya, dan termasuk ke dalam kategori ini kitab-kitab semacam karya al-Gazali, Ihya’… pengetahuan ini begitu terang bak siang hari, dan dapat dijangkau oleh setiap orang yang paling sedikit tekun mempelajarinya. Sedang kategori lainnya, para guru Tasawuf bersangkut-paut dengan misteri-misteri tak terhijab, dengan pencerapan-pencerapan spiritual yang langsung, dan dengan pengalaman-pengalaman mereka melalui berbagai manifestasi Ilahi, seperti yang termaktub dalam tulisan-tulisan Muhyi ad-Din Ibn ‘Arabi dan al-Jili, serta tulisan-tulisan lain yang menyangkut karamah mereka.
Pengetahuan ini terlampau musykil untuk dipahami seseorang yang belum merasakan pengalaman mereka hingga suatu tingkat tertentu. Tidak mustahil, cara pengungkapan mereka tidak memadai untuk menuangkan maksud mereka, dan bila dipahami secara harfiah bisa jadi bertentangan dengan semua bukti logis. Karenanya lebih baik untuk tidak mencoba-coba melibatkan diri ke dalamnya, dan biarkan para ahlinya menikmati sendiri kedudukan mulia mereka”.
Dalam tulisan ini memang tidak menyebut-nyebut al-Hallaj secara terperinci dengan namanya, namun hampir dapat dipastikan telah terlintas dalam benaknya ketika melontarkan ucapan terakhirnya. Sebab, jika bukan al-Hallaj yang menjadikan Tasawuf diakui perlu bagi Islam, tentunya tidak salah menyatakan bahwa, sementara sangat diakui, dia pun akan jauh lebih mampu meraih pengakuan haknya sebagai satu aspek eksklusivitas dan misteri. Sebab, jelas dan tak terelakkan lagi aspek itu terbukti memang ada dalam diri al-Hallaj, yang bukan lagi dipersonifikasikan semata oleh para pertapa yang secara relatif tersembunyi, melainkan oleh keterkenalan sepanjang masa, yang perihalnya dicoba kembali oleh setiap generasi yang memiliki kesadaran meningkat atas kesalahan bersama yang mesti ditebus.
Sebuah siklus juga berada dalam lingkaran merupakan kerangka yang dari segala sesuatu muncul, tidak ada mistisisme yang dapat mengelakkannya, dan semakin diakui serta semakin terorganisasi suatu mistisisme, kerangka itu semakin jelas. Di samping anggota-anggota yang paling sentral dan mereka yang ditahbiskan tetapi bukan sebagai penempuh jalan, pada pinggiran setiap tarekat Sufi yang masyhur, terdapat sejumlah besar pengikut – terkadang bahkan ribuan – pria dan wanita yang, tanpa secara formal ditahbiskan, mencari berkah serta tuntunan sang syekh mengenai pelaksanaan ibadah sunnah di samping yang fardhu.
Tuntunan semacam ini sering berupa pemberian puji-pujian untuk dibaca secara teratur. Dan melalui puji-pujiannya, Tasawuf menembus dunia luar Islam sehingga ke suatu tataran yang sebagian dapat diukur dari kenyataan bahwa Dala’il al-Khayrat, sebuah petunjuk mengenai shalawat kepada Nabi yang dirangkum oleh seorang syekh Tarekat Syazili dalam awal abad XV, boleh jadi merupakan kitab yang paling tersebar luas di dunia Islam setelah Al-Qur’an itu sendiri. Merujuk secara umum kepada meluapnya Tasawuf ini – pada fungsinya sebagai ‘hati’ agama, begitu kita menyebutnya – seorang cendekiawan Barat modern dalam pedoman-pedoman shalat Islam, menuliskan sebagai berikut:
“Dalam usaha mendapatkan kitab-kitab (tentang ibadah keagamaan), aku ingin menghindari karya-karya yang lebih esoterik bagi kehidupan batin tarekat-tarekat darwisy, dan penyelidikan dilakukan terhadap kitab-kitab yang dijual secara populer. Bagaimanapun juga, kebanyakan kitab-kitab itu ternyata dikaitkan dengan salah satu tarekat yang sangat berpengaruh, dan penghayatan resmi mereka pun dewasa ini masih berpengaruh, dalam kehidupan Islam. Memang tampaknya hampir mustahil seseorang mencari pedoman shalat, di luar petunjuk-petunjuk untuk shalat wajib sehari-hari, untuk menghindari karya-karya yang dikaitkan dengan salah satu tarekat itu. Karena tarekat-tarekat ini dilarang di Turki, maka terjadi kekosongan bahan kebaktian di Istanbul, yang suatu ketika merupakan pusat yang amat subur”.
Cara lain meluapnya Tasawuf ke luar dunia Islam adalah melalui kematiannya, dan boleh jadi ini mengungkapkan secara lebih jelas dibanding apa pun lainnya atas kedudukan sentral Tasawuf dalam agama Islam sebagai keseluruhan utuh. Seorang Wali yang masih hidup, pertama-tama adalah milik para pengikutnya dan diam-diam, melalui kehadirannya, kemudian menjadi milik seluruh masyarakat. Begitu meninggal, kehadirannya bukan lagi rahasia, dan nyaris tak pernah dijumpai satu pun kesultanan Islam yang tak memiliki seorang Sufi sebagai Wali Pelindungnya. Memang, tidak semua Sufi yang terkenal memperoleh penghargaan yang sama. Tetapi nisan-nisan sebagian besar mereka yang disebut-sebut, juga banyak dari mereka yang terlewati, menjadi tempat-tempat keramat perziarahan masyarakat sekitar maupun masyarakat dari kawasan yang jauh.
Kutipan terakhir tadi membawa kita ke abad yang sekarang lebih cepat daripada yang dibayangkan. Untuk sejenak kembali pada kurun yang segera disusul kristalisasi besar-besaran berbagai tarekat Sufi itu, perlu disinggung dua karya terpenting, karena termasuk karya-karya yang paling sering dirujuk, dikutip, dan direnungkan pada bagian-bagian inti Tasawuf. Yang pertama adalah al-Hikam (harfiah: “kearifan-kearifan”), sebuah kumpulan aforisme yang ditulis oleh Ibn ‘Ata’ Illah al-Iskandari di penghujung abad XIII. Nama belakang ini menunjukkan dia berasal dari Iskandariah (Aleksandria), yang merupakan satu pusat pertama Tarekat Syaziliyyah. Dewasa ini, monumen paling suci di kota ini adalah masjid yang mengabadikan nisan-nisan Abu al-‘Abbas al-Mursi, penerus dari pendiri tarekat tersebut. Ibn ‘Ata’ Illah adalah murid Abu al-‘Abbas, dan mungkin timbul sebersit kesangsian bahwa aforisme-aforisme ini, paling tidak secara tak langsung, merupakan bagian penting warisan yang kita terima dari Abu al-Hasan sendiri.
Teks kedua, yang termasuk dalam permulaan abad XV, yaitu teks yang telah tertuju pada al-Insan al-Kamil (Manusia Universal) karya ‘Abd al-Karim al-Jili – suatu pemaparan yang begitu gamblang, padat, serta mendalam tentang doktrin Sufi.
Hingga kini, hampir semua cendekiawan cenderung menganggap al-Jili sebagai mistikus besar terakhir Islam. Sedangkan rentang waktu antara dia dan kita, dianggap benar memiliki satu atau dua orang yang mendekati kebesarannya – misalnya Ahmad Zarruq, yang oleh kalangan mistikus sezamannya, khususnya di Libya tempat dia melewatkan bagian terakhir hidupnya, dianggap seperti al-Gazali pada zamannya. Telaah modern pun menaruh perhatian, namun jelas tanpa tindakan untuk membenarkannya, terhadap ‘Abd al-Gani an-Nabulusi yang, di samping sebagai pengarang berbagai ulasan mendalam atas Fushus al-Hikam Ibn ‘Arabi dan juga terhadap Khamriyyah (Syair Anggur) Ibn al-Farid, dia sendiri adalah seorang penyair sejati. Tetapi tokoh-tokoh seperti ini belum mampu menyelamatkan keseluruhan periode ini dari bencana kumulatif yang telah diungkapkan para cendekiawan Barat, yang saling bergema satu dan lainnya.
Dunia Barat telah demikian lama berada di bawah dominasi humanisme, sehingga para penulis tentang Tasawuf kadang-kadang tanpa disadari melancarkan tudingan terhadapnya menurut standar-standar humanistik dan karena itu bersifat anti-mistis. Kita digiring untuk percaya bahwa sejak kira-kira abad XVI dan selanjutnya, Timur mulai mandeg, sedangkan Barat berkembang serta maju. Namun praktis selamanya dilupakan bahwa apa pun makna yang mungkin terkandung dalam kata terakhir itu, ada satu hal yang tak pernah terlintas untuk memberi arti, bahkan oleh kalangan progresif paling fanatik sekalipun, bahwa ini merupakan ‘kemajuan dalam dunia ukhrawi’ – satu jenis kemajuan yang hanya dapat dikenal dalam mistisisme. Adapun tuduhan ‘kemandekan’, dalam kasus Tasawuf ini diartikan sebagai belum melahirkan ‘pemikir-pemikir orisinil’, yang mengingatkan kita pada awal tulisan ini. Apabila kata asli diketengahkan di sini dalam pengertian modernnya, maka kelemahan yang diasumsikan ini justru merupakan suatu kekuatan – keteguhan untuk tidak tergelincir ke dalam manifestasi-manifestasi individualisme, yang lebih mengutamakan hal-hal baru daripada kebenaran. Sedang keaslian dalam pengertian sebenarnya, artinya, kontak langsung dengan sumber asalnya, keabadiannya merupakan tema dari janji yang telah dikutip: “Bumi tidak akan kekurangan dari 40 orang yang hatinya seperti hati sang Kekasih dari Yang Maha Pemurah”, karena kata Arab khalil (kekasih) menunjukkan kontak mesra atau, lebih tepat lagi, kesalingtembusan. Kita juga dapat menukil Hadis ini: “Allah akan menurunkan kepada umat ini pada permulaan tiap seratus tahun, seseorang yang akan memperbarui agama umat ini”. Karena, mustahil ada pembaruan kembali daya dan kekuatan tanpa menoleh kembali kepada sumber inspirasinya.
Bagi kaum Sufi, janji-janji ini niscaya akan dipenuhi. Para cendekiawan Barat, sebaliknya, akan lebih tertarik pada apa yang mereka sebut bukti obyektif. Tetapi sanggupkah mereka menetapkannya? Bukankah bahwa mereka gagal memahami konsepsi tradisional tentang keaslian. Tokoh-tokoh seperti Nicholson, Massignon, dan Arberry, pastilah mengerti secara hakiki apa yang dimaksud di sini, dan meski pikiran mereka mungkin saja dirancukan oleh prasangka-prasangka tak disengaja dan boleh jadi kurang berakar menurut parodi modern, tak diragukan lagi keaslian sejati itulah yang mereka cari dari mereka apresiasikan dalam diri para Sufi besar. Walaupun mereka benar dalam mengandalkan keaslian itu sebagai hasil pasti dari ketinggian spiritual, dan karenanya menjadi kriteria tentangnya, hal yang tidak mereka pahami – atau yang kadang-kadang mereka lupakan – adalah bahwa manifestasi-manifestasi kontak langusng dengan sumber asal itu amat beraneka ragam. Dengan kata lain, konsepsi mereka tentang keaslian itu terlampau sempit, dan mereka juga tidak selamanya dapat diandalkan untuk mengakuinya dalam segala bentuknya.
Walaupun begitu, ini hanyalah penyebab kedua dari ketidakadilan intelektual yang kita tinjau ini. Tentang penyebab utama, telah diakui bahwa kesimpulan dari penelitian setengah resmi Orientalisme terhadap Tasawuf abad terakhir didasarkan terutama pada informasi yang tidak memadai. Tasawuf ada di balik rahasia hakikat-nya, dan tidak mustahil perlu waktu bagi kedalaman-kedalamannya untuk tampil, sementara buih serta-merta timbul ke permukaan. Arberry, misalnya, memaparkan tasawuf abad XVI pada saat-saat ‘sakaratul mautnya’, dan demi mempertahankan kesimpulannya dia menggeneralisir bahwa: “Kendati tarekat-tarekat Sufi masih tetap menguasai – dan di banyak negeri terus berlanjut – perhatian dan kesetiaan massa yang bodoh, tak seorang pun dari kalangan terdidik sudi menjadi pendukung mereka”. Tetapi ketika kemudian perhatiannya tertuju pada Syekh Ahmad al-‘Alawi yang wafat pada tahun 1934, dia serta-merta mengakui bahwa “tokoh ini kesuciannya mengingatkan kembali pada zaman keemasan ahli-ahli mistik Abad Pertengahan”. Para cendekiawan lain pun membuat pernyataan serupa tentang dia. Tanpa khawatir akan bertentangan, dapat ditandaskan bahwa telaahnya atas simbolisme huruf-huruf alfabet itu merupakan salah satu teks paling mendalam dari seluruh kepustakaan Sufi. Terlebih lagi – dan ini yang paling penting dalam konteks ini – risalah ringkasnya yang memukau tentang perjalanan spiritualnya sendiri, meyakinkan kita bahwa Syekhnya sendiri, Muhammad al-Buzidi, juga seorang penuntun rohani terkemuka seperti dirinya. Ini bukan soal kesalahan lantaran keturunan. Dengan pengertian yang begitu melimpah akan hak-hak atas kebenaran, terutama menyangkut masalah penting seperti kedudukan spiritual itu, Syekh al-‘Alawi terlampau obyektif untuk membiarkan sentimen mengeruhkan pertimbangannya. Dia pun tak sungguh-sungguh bermaksud menemui syekhnya. Dengan bersahaja dia sampaikan apa yang dikatakan serta dilakukan oleh sang Guru. Dan akibatnya, sejauh menyangkut diri kita, tidak hanya kesan semata tetapi juga keyakinan bahwa dia adalah seorang guru rohani sejati. Akan tetapi, Syekh al-Buzidi tidak meninggalkan satu pun tulisan dan tidak dikenal di kalangan cendekiawan Barat – begitulah hingga dewasa ini. Syekhnya sendiri, Muhammad Ibn Qaddur al-Wakili, yang nyata-nyata memiliki keluhuran spiritual, juga telah diabaikan. Syekh al-Buzidi biasa meriwayatkan kepada muridnya bagaimana dia menemukan gurunya ini melalui karamah penglihatan luar biasa di tempat Abu Madyan yang masyhur itu menampakkan diri kepadanya dan menyuruh dia berangkat dari Aljazair ke Maroko. Ini mengantar kita kembali, seluruh perihal kecuali satu mata rantai dalam silsilah, kepada pendiri adalah cucu spiritual dari Mulay al-‘Arabi ad-Darqawi, Syekh para Syekh kita demikian gelar yang diberikan kebanyakan Sufi di Afrika Barat Laut dan juga di tempat-tempat lainnya, bahkan hingga kini. Surat-surat guru Sufi ini telah dikutip dalam bab-bab sebelumnya, dan sebagaimana otobiografi ‘Alawi, surat-surat itu pun memberikan keyakinan kepada kita bahwa Syekh penulisnya, Mulay ‘Ali al-Jamal, juga seorang guru terkemuka. Jadi, tidaklah berlebihan bila kita katakan bahwa di sini dijumpai, dalam silsilah spiritual ini, dua pasang Syekh berturut-turut – ‘Ali al Jamal dan al-‘Arabi ad-Darqawi, dan kemudian setelah dua generasi, Muhammad al-Buzidi dan Ahmad al-‘Alawi – yang serupa dengan pendahulu abad IX mereka, Sarri dan al-Junayd. Dalam ketiga kasus ini, terbersit keraguan bahwa pasangan kedua, untuk abad itu, merupakan ‘pembaru’ yang dijanjikan Nabi. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan terletak pada para pembaru itu sendiri, tetapi pada lingkungan mereka masing-masing. Tidak bisa disangkal bahwa tataran umum spiritualitas jauh lebih tinggi dalam abad-abad pertama daripada abad-abad belakangan. Al-Junayd tak ubahnya sebuah puncak yang dikelilingi puncak-puncak lainnya dan lereng-lereng landai. Meski puncak-puncak Tasawuf tetap merupakan kebersinambungan, yang tak berkurang ketinggiannya, jumlah mereka semakin kecil, sementara lereng-lereng sekitarnya pun kian bertambah curam saja.
Bagaimanapun juga, Syekh ad-Darqawi memiliki banyak pengikut yang menonjol, beberapa di antara yang dia akui selama hidupnya merupakan Syekh-syekh yang berdiri sendiri. Namun, seperti yang mungkin diharapkan, surat-suratnya tidak banyak mengungkapkan penerusnya, begitu pula pendahulunya. Memang salah satu ciri terkuat mereka ialah mereka membuat kita sadar, dan tetap sadar, atas apa yang mungkin dinamakan getaran-getaran rantai spiritual pergantian berkat kutipan-kutipan yang banyak dan begitu indah, yang oleh sang pengarang disampaikan kepada kita dari para pendahulunya.
Banyak di antara para Syekh yang membentuk jalinan-jalinan dari salah satu rantai spiritual, yang terbentang dari abad XVIII hingga abad XIV dan sebelumnya, telah meninggalkan berbagai tulisan yang hanya terdapat dalam sejumlah kecil naskah dan sejauh ini tak dikenal para sarjana Barat. Namun, ada isyarat-isyarat bahwa kini berbagai upaya dilancarkan di Timur maupun di Barat untuk menggali kembali sebagian warisan ini. Kiranya tepatlah, walupun mungkin terlalu mendadak, kita tutup tuisan ini dengan nada-nada penuh harap itu. Namun, jangan sampai dilupakan bahwa tulisan-tulisan bukanlah gambaran asasi dari Tasawuf. Masalah utama yang harus dijawab sehubungan dengan alenia-alenia terakhir ini bukan ‘berapa banyak telaah Sufi bermutu yang telah ditulis selama beberapa abad belakangan ini?’, melainkan, ‘masih tetapkah Tasawuf merupakan satu cara operatif bagi manusia, untuk berpadu kembali dalam sumber asal samawinya?”. Dan selagi benar bahwa kian sedikit orang yang mampu mengambil manfaat dari semua yang harus disuguhkan oleh Tasawuf, maka tak ayal lagi jawaban bagi pertanyaan terakhir ini adalah “ya”.