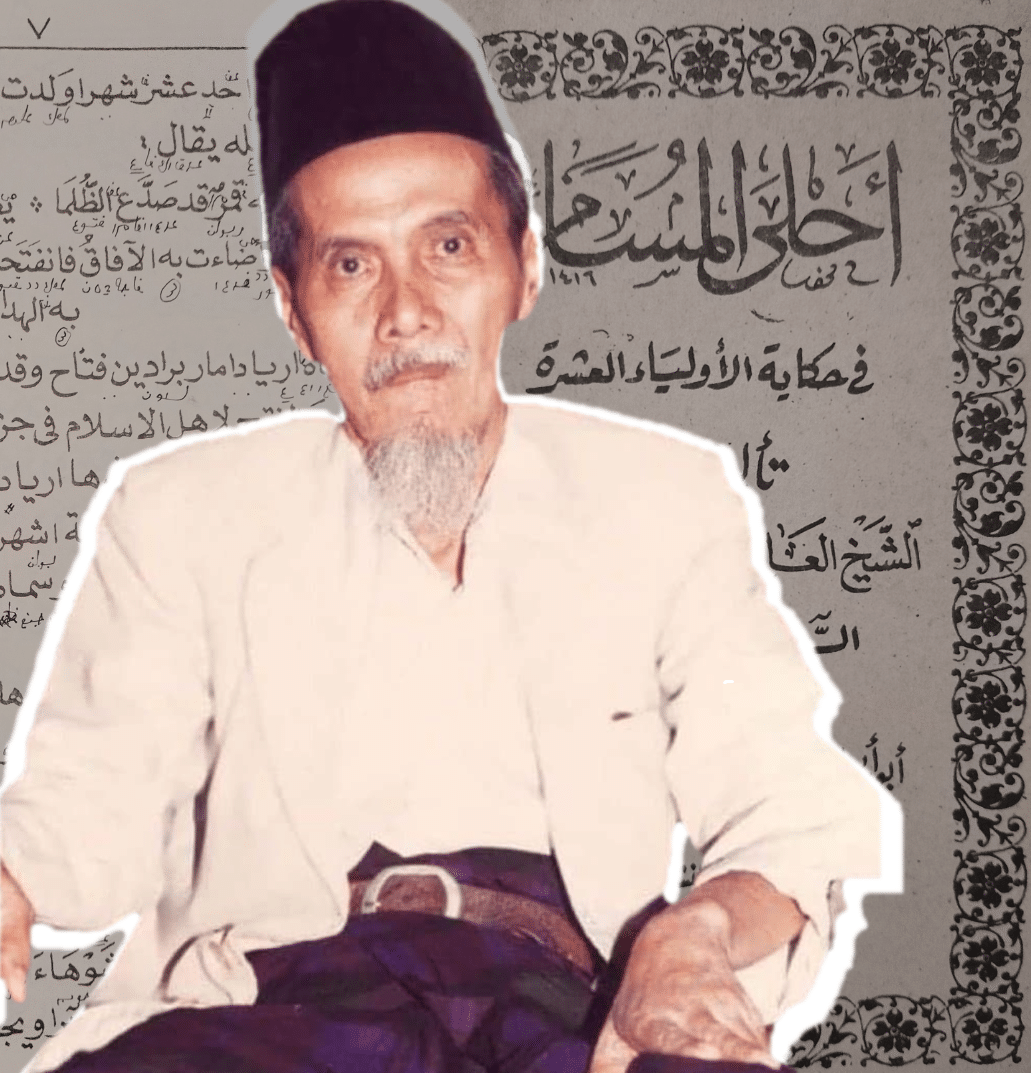Konon, Lailatul Qadar atawa Malam Kemuliaan atawa Malam yang Lebih Baik dari Seribu Bulan, jatuh pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan.
Malam yang teramat istimewa itu, saat-saat dimana Allah Swt menurunkan lembar-lembar wahyu suci-Nya dan menugaskan para malaikat termasuk malaikat Jibril untuk menebarkan keselamatan dan kesejahteraan bagi semesta, amat dirindukan oleh segenap kaum muslimin. Maka mereka pun menekuri malam-malam pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadaan itu untuk mencari atau menggapai Lailatul Qadar.
Pun aku. Dalam kesunyian aku ikut menekuri malam-malam panjang penuh kehidmatan itu. Malam ini aku berteman dengan Emha Ainun Nadjib, penyair dan budayawan yang lekat dengan pengembaraan spiritual dan pencarian kesejatian dalam kefanaan. Jangan salah paham; aku malam ini ditemani oleh Emha Ainun Najib, atau karib dipanggil Cak Nun, bukan secara fisik—namun secara batin. Aku ditemani oleh sebuah puisinya yang digubah dan dinyanyikan oleh sahabat lamanya, Ebiet G. Ade.
Lagu itu pertama kudengar pada penghujung tahun 1970an atau awal 1980an di kota kelahiranku, Pekalongan, dari sebuah kaset rekaman di sebuah studio kecil di kotaku. Pemilik studio rekaman kecil itu bernama Om Denan sudah berpulang beberapa tahun lalu. Sehingga aku belum berhasil melacak lagi jejak rekaman yang seingatku berisi sekitar 10 lagu, sebagian besar berasal dari puisi-puisi Emha yang dinyanyikan Ebiet. Lagu-lagu itu tidak pernah diproduksi secara komersial hingga kini. Termasuk lagu yang kunyanyikan ini.
Aku lupa judul persisnya, tapi seingatku bertajuk: “Dengan Musik yang Sederhana”. Aku pernah menemukan puisi itu di sebuah buku kumpulan puisi Emha. Sayangnya buku itu ketlingsut entah di mana.
Aku juga gagal menemukan lirik puisi itu di perpustakaan paman Google. Jadi aku sekadar mengandalkan ingatanku dan mencoba menyanyikannya sesuai nada-nada yang terekam di dalam otak sejak masa kecilku. Jadi, Cak Nun, mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan dalam mengingatnya.
Begini kira-kira lirik lagunya.
Dengan musik yang sederhana dari gitarmu
Aku merasa ditimang-timang
Oleh sebuah tangan gaib
Yang melemparkanku ke ruang hampa
Entahlah, itu urusanmu
Kata orang musik itu jalan menuju Tuhan
Dan mencari kekasih ialah mengundang kehadiran Tuhan
Kusendiri dalam hal apa
Kumenempuh lorong gelap
Berkali-kali memang ada yang menyapa
Tapi entah siapa
Engkau tidak berlagu untukku
Aku pun tahu
Sambil duduk di kursi kau memandang keluar jendela
Barangkali kepada angin dan bunga-bunga engkau bernyayi
Aku tak mau ditipu lagi segala suara yang hampa
Aku ingin langsung mendengar jawabmu
Di ujung lorong itu
Lagu itu, entah kenapa, terpatri kuat dalam ingatanku. Ikut menemani perjalanan masa remajaku—bahkan hingga kini: ketika warna rambutku mulai bersalin kelabu. Ia menjadi semacam sahabat dalam tualang spiritualku, berteman dengan musik sebagai “jalan menuju Tuhan”.
Terima kasih Cak Nun. Terima kasih untuk puisi-puisi indahmu yang menemaniku bertumbuh. Misalnya puisi ini yang berjudul: Seribu Masjid Satu Jumlahnya (https://www.caknun.com/2018/seribu-masjid-satu-jumlahnya-puisi-khilafah-1987/)
Puisi yang ditulis pada tahun 1987 ini teramat sangat pas dengan suasana Ramadhan di tengah pandemi corona saat ini, ketika kita diseru untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumuman, termasuk saat beribadah.
Satu
Masjid itu dua macamnya
Satu ruh, lainnya badan
Satu di atas tanah berdiri
Lainnya bersemayam di hati
Tak boleh hilang salah satunya
Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu
Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu
Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu
Dua
Masjid selalu dua macamnya
Satu terbuat dari bata dan logam
Lainnya tak terperi
Karena sejati
Tiga
Masjid batu bata
Berdiri di mana-mana
Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya
Timbul tenggelam antara ada dan tiada
Mungkin di hati kita
Di dalam jiwa, di pusat sukma
Membisikkan nama Allah ta’ala
Kita diajari mengenali-Nya
Di dalam masjid batu bata
Kita melangkah, kemudian bersujud
Perlahan-lahan memasuki masjid sunyi jiwa
Beriktikaf, di jagat tanpa bentuk tanpa warna
Tubuh kita bertakbir
Ruh mengagumi-Nya tanpa suara
Ruh bersembahyang tanpa gerak
Menjerit dengan mulut sunyi
Maka malam-malam seperti sekarang kita beriktikaf tidak di masjid batu bata, melainkan di masjid sunyi jiwa; “di jagat tanpa bentuk tanpa warna… Ruh bersembahyang tanpa gerak/Menjerit dengan mulut sunyi.”
Semoga penuh berkah. Semoga tergapai indah Lailatul Qadar. Amiin.
18 Mei 2020/24 Ramadhan 1441 H