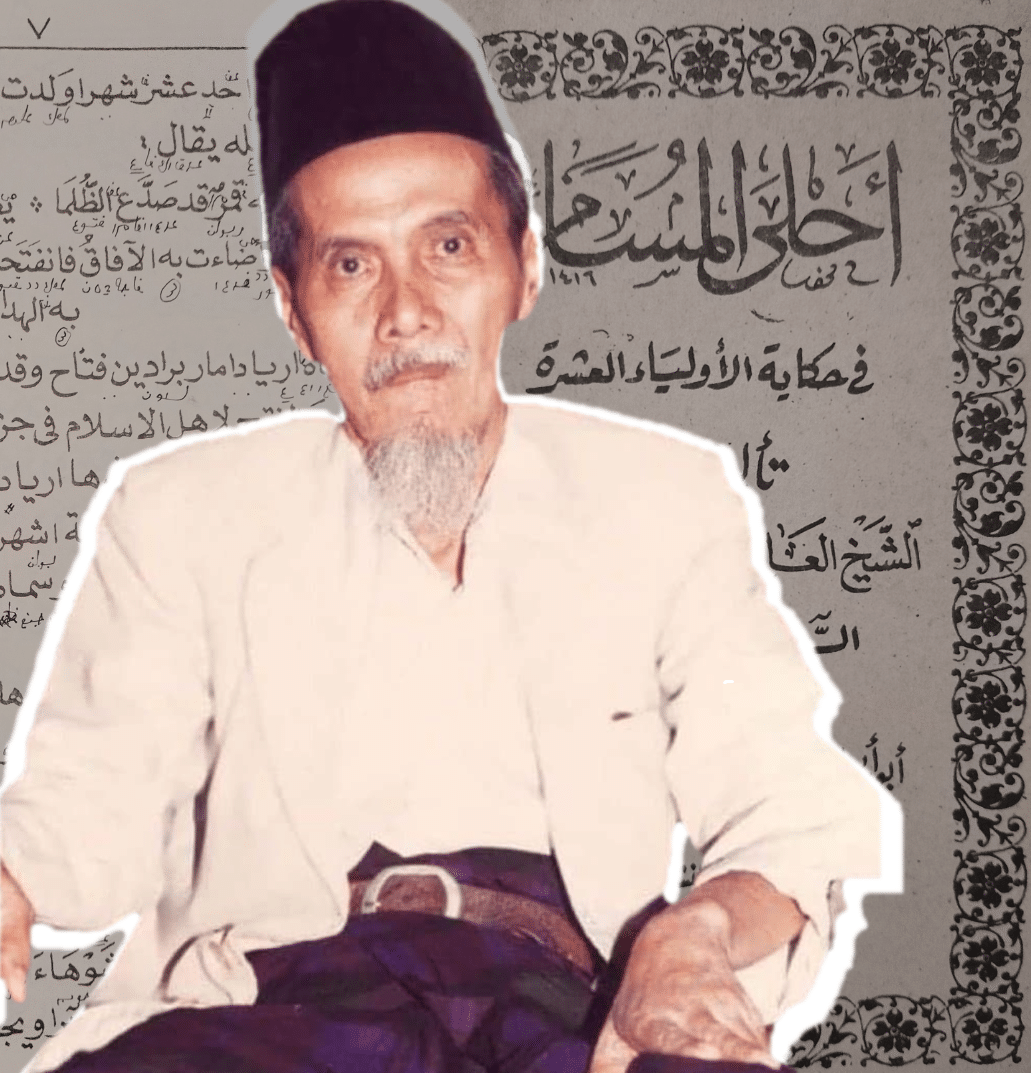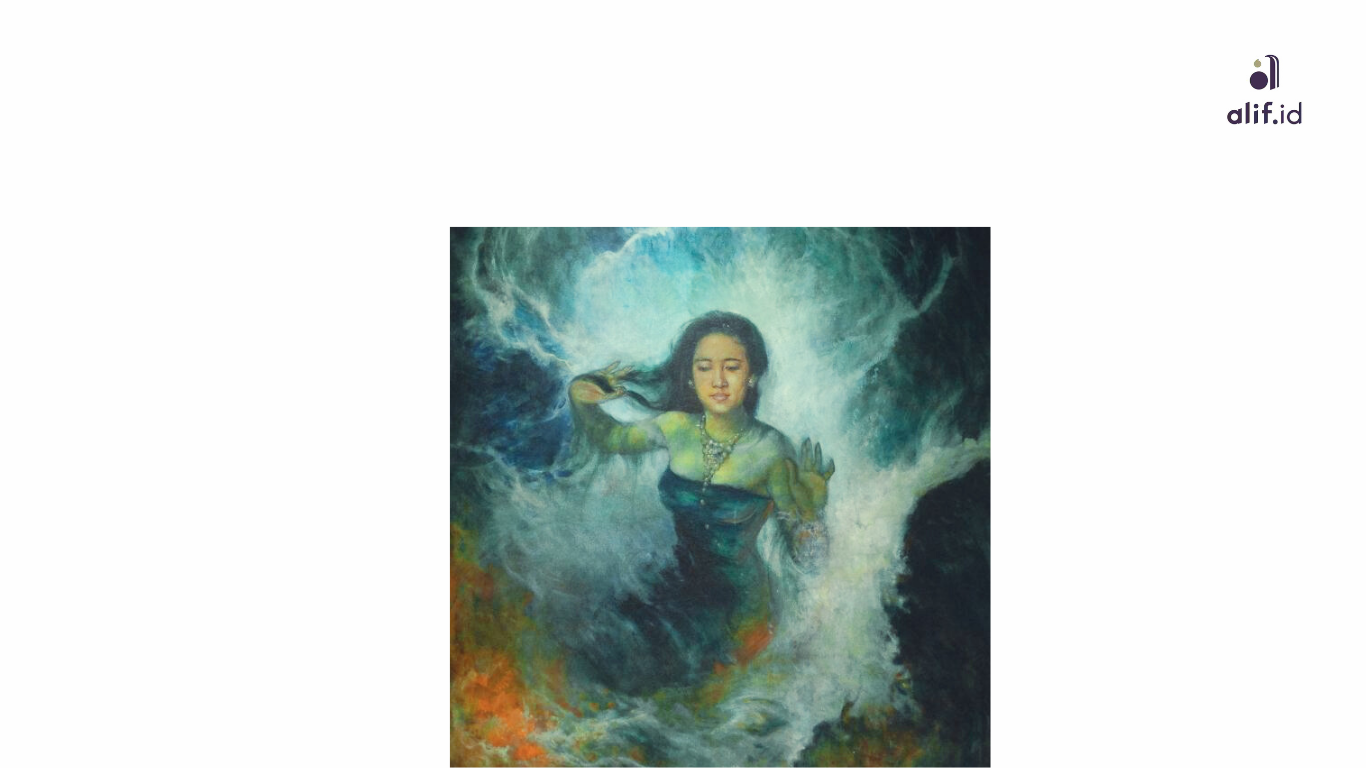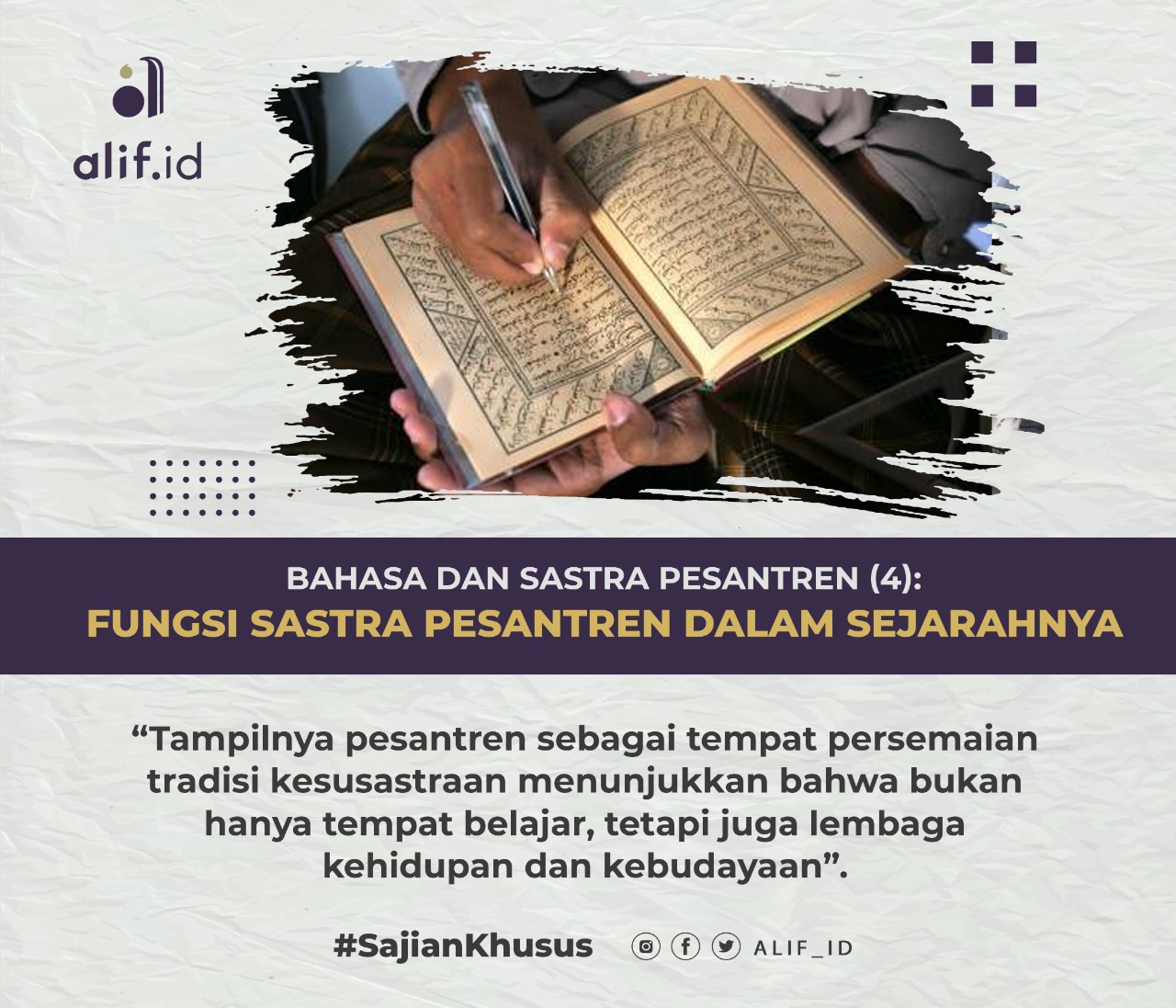
Tidak ada definisi yang pasti terhadap apa yang dimaksud dengan “sastra pesantren”. Walau demikian para ahli mencoba mendefinisikan hal tersebut. Sebagaimana yang ditulis oleh M. Irfan Hidayatullah dalam sebuah makalah dengan judul “Pergulatan dalam Sastra Pesantren”, ia menghimpun beberapa pendapat ihwal definisi sastra pesantren. Seperti Hidayatullah yang menjelaskan bahwa sastra pesantren merupakan sebuah konstruksi estetika kesastraan yang khas dan memiliki kekuatan roh transenden yang khas pula.
Sedangkan Abdurrahman sendiri memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sastra pesantren adalah karya-karya sastra yang mengeksplorasi kebiasaan-kebiasaan di pesantren dan memiliki corak psikologi pesantren dengan struktur agama yang kuat. Dari segala definisi yang diberikan, yang terpenting bahwa yang dimaksud dengan “sastra pesantren” adalah karya-karya sastra yang jelas dihasilkan oleh komunitas pesantren yang memiliki warna yang khas.
Dalam sejarahnya, pesantren pun memiliki banyak bentuk karya sastra yang telah dihasilkan di Nusantara, baik itu dalam bentuk hikayat, serat, kisah, cerita, puisi, roman, novel, syi’ir hingga nadzaman. Karya-karya tersebut pun tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga dalam bentuk lisan yang digubahkan di mana-mana pada masanya.
Karya-karya sastra dari dunia pesantren sendiri adalah karya-karya yang diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya sehingga dikatakan memiliki karakter komunal, sebab berpadu rapat dengan kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian menurut Ahmad Baso bahwa jika berbicara mengenai “sastra pesantren” maka bukan sekadar soal kehadiran suara komunitas pesantren dalam produksi sastra, tetapi juga melihatnya sebagai perbincangan atau diskursus tentang subyektifitas kreatif kalangan pesantren dan komunitas khalayaknya (mustami’/pendengar) dalam berkebudayaan.
Pada masa silam, karya-karya sastra komunitas pesantren ini banyak ditulis dalam huruf Arab Pegon dengan beragam bahasa di Nusantara. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari roman yang mengandung sejarah dan realitas sosial, hingga kisah-kisah yang dipenuhi dengan tema-tema moralitas dan kepahlawanan. Karya-karya sastra yang dihasilkan oleh pesantren ini walaupun bersifat fiktif, namun memiliki kesan realis yang melibatkan tingkah laku, norma atau nilai-nilai sosial kehidupan bermasyarakat dan berbudaya pada umumnya.
Pada abad ke-17 dan abad ke 18 dikatakan bahwa pesantren menjadi tempat para pujangga dan para sastrawan menghasilkan berbagai karya. Seperti pujangga kraton yakni Yosodipuro I, Yosodipuro II, dan Ranggawarsita yang merupakan santri-santri yang menghasilkan banyak karya, baik itu dalam bentuk kakawin, serat dan babad. Sumber dari karya-karya mereka pun dikatakan tidak hanya berasal dari kitab kuning, melainkan juga pengalaman sejarah bangsa mereka sendiri sebagaimana yang dialami kerajaan Hindu, Budha di zaman para Wali Songo. Selain mereka ada lebih banyak lagi karya sastra pesantren yang dihasilkan pada zamannya yang masih bisa ditemukan hingga kini.
Walaupun teramat banyak karya sastra pesantren pada zamannya, namun menarik untuk melihat berbagai karya yang memiliki dampak atau fungsi sosial yang nyata pada masyarakatnya. Misalnya seperti salah satu serat dari Jawa yang dikenal sebagai Serat Jatiswara khususnya versi yang beredar dari abad ke-18 di pesisir utara Jawa dan Lombok.
Para pemilik manuskrip kesastraan ini kebanyakan memiliki pendidikan pesantren dan mereka menegaskan kepemilikannya dengan menambahkan kolofon, catatan dan tanda tangan pada dua halaman terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial sastra pesantren ini ditunjukkan dari cara kaum santri melakukan penggubahan, tulis ulang, penambahan atau penyisipan, untuk disesuaikan dengan cita-cita sosial-keagamaan kaum pesantren.
Hal ini juga ditemukan misalnya dalam Hikayat Malem Diwa, suatu hikayat berbahasa Melayu dengan aksara Arab Pegon yang sepenuhnya diwarnai oleh kosmologi Hindu. Dalam naskah tersebut disisipkan satu predikat “guru ngaji di meunasah (semacam langgar di Aceh)” kepada tokoh protagonis. Walaupun sisipan ini minim, tetapi memiliki signifikansi yang cukup besar. Sebab keseluruhan cerita pun berubah total, di mana pesantren pun memiliki peran baru dalam memberikan spirit dan corak pada kesastraan lama, walaupun dalam karya tersebut tidak disebutkan bahwa sang tokoh protagonis tersebut memeluk Islam.
Selain karya di atas hal serupa juga ditemukan pada cerita epos I La Galigo, dengan tokoh protagonisnya, Sawerigading. Kisah Sawerigading ini pada dasarnya adalah kisah yang ada murni sebelum Islam masuk ke Nusantara, namun kemudian di dalamnya disisipkan satu versi cerita -baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan- di mana Sawerigading nyantri ke Mekkah, melaksanakan haji, bahkan bertemu dengan Nabi Muhammad saw, dan kemudian Sawerigading diceritakan kembali ke kampungnya mendirikan “masigi” (masjid sekaligus pondok). Cerita versi ini hingga ini masih terpelihara di beberapa pesantren Bugis-Makassar.
Selain berfungsi pedagogis yang artinya digunakan sebagai pengajaran etika atau akhlak, sastra pesantren juga mengintegrasikan tradisi kesyuyukhiya-an (jejer pandita) sebagai bagian penting dari lakon dalam karya-karya klasik. Misalnya seperti penulisan kembali Hikayat Iskandar Dzulqarnain dari Timur Tengah dalam berbagai versi bahasa Nusantara, dengan memasukkan figur Nabi Khaidir sebagai guru. Yang mana di dalamnya ia berperan sebagai sosok yang membimbing, mengarahkan, dan membawa kesuksesan bagi Iskandar yang juga digambarkan sebagai murid yang taat kepada gurunya tersebut. Berbagai versi hikayat seperti ini yang menunjukkan penekanan kepada relasi guru-santri juga muncul dalam karya lain, misalnya seperti dalam Sejarah Melayu, Hikayat Aceh, dan Tambo Minangkabau.
Kemudian lebih jauh lagi, sastra pesantren sebagai salah satu produk budaya juga menampilkan diri dalam karya-karya etnografis kesejarahan atau kisah-kisah perjalanan yang merekam tradisi-tradisi masyarakat setempat dalam bentuk sastra. Seperti dalam karya berjudul Poerwa Tjarita Bali yang ditulis pada abad 1875 dalam bahasa Jawa oleh seorang santri di Pondok Sepanjang, Malang, bernama Raden Sasrawijaya, asal Yogyakarta. Pengetahuan mengenai kota-kota, adat istiadat pembesar dan orang kebanyakan yang tinggal di desa-desa dituangkan dalam karya tersebut sebagai bagian dari kegiatan bersastra orang-orang pesantren.
Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa pesantren memiliki banyak karya sastra yang telah dihasilkan di masa silam. Tidak hanya sebatas sebuah karya yang dibaca begitu saja untuk menggugah perasaan, tetapi digunakan dalam misi pesantren untuk memberikan pengajaran baik itu untuk santrinya hingga masyarakat sosial. Lebih jauh lagi karya sastra pesantren bahkan menjadi sumber sejarah yang merekam kebudayaan serta tradisi yang ada di masa silam. Seperti yang dikatakan Ahmad Baso bahwa tampilnya pesantren sebagai tempat persemaian tradisi kesusastraan menunjukkan bahwa bukan hanya tempat belajar, tetapi juga lembaga kehidupan dan kebudayaan.