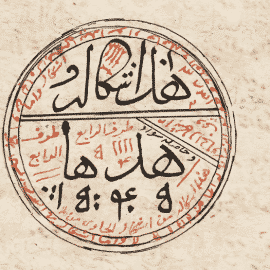Kata Jaya Suprana (Humorologi, 2013) tanpa humor sulit dibayangkan betapa keringnya hidup manusia di dunia ini. Di atas panggung para pelawak memainkan karakter manusia-manusia yang lain sehingga penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur cerita dari drama yang disajikan penuh kelucuan.
Dalam ilmu sosiologi, menurut cerdik cendikia, ada teori dramaturgi. Dramaturgi adalah teori yang menyatakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Menurut teori itu, seseorang mempunyai sifat yang berbeda antara di depan panggung dan di belakang panggung.
Itulah panggung kehidupan. Di atas panggung (front stage)—entah itu panggung lawak, ketoprak, lodruk, stand up, dagelan mataram, bahkan juga panggung politik, dan sebagainya—beda dengan yang di belakang panggung (back stage). Para pelawak, pemain ludruk, ketika di atas panggung bisa membuat para penonon tertawa terpingkal-pingkal, meski di belakang panggung hidupnya penuh derita.
Yang lucu di atas panggung, belum tentu lucu di belakang panggung. Apalagi, kata Jaya Suprana, para pelawak bersaing melawan kejenakaan yang ditampilkan—terutama kaum penguasa (sekarang ditambah mereka yang merasa berkuasa dan ingin berkuasa)—di panggung realitas kehidupan. Maka itu, tidak salah kalau dikatakan bahwa Indonesia kaya humor politik.
II

Sekarang ini, banyak “pelawak politik” yang mencari panggung. Mereka ingin menggantikan peran yang selama ini dilakoni oleh para komedian, para pelawak. Namun, mereka tidak memahami sesungguhnya apa fungsi komedi dalam kehidupan bermasyarakat.
Alan Dundes (1934-2005), profesor antropologi dan folklore dari Berkeley (California) mengatakan, komedi menjadi alat untuk melakukan kritik sosial; sebagai alat untuk melihat realita di masyarakat.
Dengan rumusan lain, komedi bisa menjadi media yang menjembatani antara kepentingan pemerintah dan rakyat, maupun antara rakyat dan pemerintah.
Lewat komedi, humor, lawakan, orang bisa menyampaikan protes tanpa harus menjadi gila atau nggak mutu atau kelihatan bodoh (atau sok pinter) karena protes tersebut. Maka itu, komedi bisa muncul di mana-mana, ada banyak panggung dalam kehidupan sehari-hari.
Semakin berkembang komedi dalam suatu masyarakat, maka semakin dewasa masyarakat tersebut.
Hal ini terkait dengan sikap suatu bangsa dalam menyikapi kritik, terutama kritik yang disampaikan melalui media komedi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.
Dengan kritik, orang memberikan pendapat beralasan atau analisis, pertimbangan nilai, interpretasi, atau pengamatan.
Kritik sejatinya disampaikan untuk memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang yakni bukan didasarkan atas kebencian terhadap orangnya. Kritik, dilakukan menggunakan pilihan kata yang tidak menyinggung perasaan, sopan dan bijaksana.
Di sinilah komedi berperan. Walau disampaikan dengan candaan, tetap tidak mengurangi ensensi kritiknya. Secara umum kritik menunjukan letak kesalahannya serta apa dan bagaimana solusinya.
Itulah sebabnya, kritik berbeda—bahkan sangat berbeda—dengan hujatan, fitnah, ujaran kebencian dan penghinaan. Karena hujatan, fitnah, ujaran kebencian, dan juga penghinaan tidak jarang disampaikan dengan narasi yang menyinggung perasaan, tanpa dasar.
Bahkan disampaikan secara tidak sopan dan tidak bijaksana serta, tidak bertujuan untuk memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang. Anak muda sekarang menyebutnya sekadar “nyinyir atau julid.”
Padahal, kritik merupakan sebuah upaya untuk menegasikan sesuatu, dan dengan demikian memelihara kebenaran yang terdapat dalam sesuatu. Tanpa adanya kritik, berarti tidak ada yang menjalankan fungsi kontrol terhadap sesuatu.
Sayangnya sekarang ada yang sok memainkan diri “menjalankan fungsi kontrol.”
III

Bagaimana menjalankan fungsi kontrol secara benar, tetap waktu, santun, efektif, dan berhasil-guna. Tentu, tidak asal berteriak. Tidak sekadar menyampaikan yang berbeda. Tidak sekadar menjelek-njelekkan. Tentu, harus ada dasar, ada alasan, ada bukti, dan bisa memberikan masukan untuk perbaikan bahkan jalan keluar.
Kemarin dulu, masyarakat tersenyum geli ketika Presiden Jokowi menanggapi kritik dari BEM UI, yang disampaikan saat masyarakat tengah berjuang keras antara hidup dan mati menghadapi pandemi Covid-19 yang semakin menggila ini. Mereka menyebut Jokowi sebagai “The King of Lip Service.”
Kata Jokowi, “Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer. Ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo. Kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter.
Kemudian, ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak bipang dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King of Lip Service.”
Nada bicara Jokowi datar, seperti biasa sambil senyum dan ketawa, ketika mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan soal.
Jawaban itu, membuat yang mendengarnya tak mampu menahan tawa; sekaligus prihatin karena kekurang-pekaan sejumlah mahasiswa terhadap kondisi negara.
Meskipun, Jokowi mengatakan, “Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi jadi kritik itu boleh-boleh saja, dan Universitas tidak apa, tidak perlu menghalangi mahasiwa untuk berkespresi.”
Tetapi, Jokowi menambahkan, “Kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan. Saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19.”
Mendengar kata Jokowi itu, tidak salah kalah berkesimpulan, ternyata, para pelawak Srimulat, dagelan mataram, ludruk, dan para seniman panggung lainnya lebih memiliki tata krama dan sopan santun saat menyampaikan kritik.
Belajarlah mengritik dari para komedian, para pelawak. Itu kata sahabat lama saya—satu SMP bahkan tiga tahun satu kelas—Gendut Janarto, penulis buku biografi Teguh Srimulat : Berpacu dalam Komedi dan Melodi (1990).
Sayangnya, panggung komedi tersebut mulai berkurang, meski muncul stand up comedy. Panggung Srimulat, ludruk, dagelan mataram, sudah jarang di tengah masyarakat, sehingga sarana kritik sosial yang lucu sebagaimana jati dirinya pun berkurang.
Yang ada hanyalah mereka yang mencari panggung untuk memanggungkan dirinya sendiri, tidak peduli terhadap pagebluk yang mendera negeri ini.
Untungnya, di Yogyakarta, ketoprak terus berusaha dihidup-hidupi, antara lain oleh Bondan Nusantara. (artikel juga diunggal di triaskun.id)