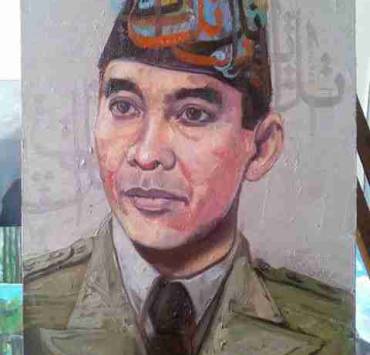Perjumpaan antara Islam dan budaya kerap mengundang perdebatan yang cukup panjang dan tetap menyisakan beberapa persoalan. Islam merupakan agama yang bersumber dari wahyu, di mana pasca Nabi wafat sudah tidak turun lagi. Sementara budaya sebagai hasil kreasi manusia, telah, terus dan akan terus berlangsung yang bisa saja berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya, meminjam istilah Gus Dur, merupakan sesuatu yang ambivalen [Wahid, 2001: 70].
Selama berabad-abad lamanya sebagian umat Islam di Indonesia terus mempertahankan dan mengembangkan tradisi-tradisi yang diturunkan oleh leluhurnya. Meskipun, sebagaimana diungkapkan dalam buku-buku sejarah para wali dan penyebar Islam di Indonesia, tradisi-tradisi tersebut telah di-Islamkan (mungkin lebih tepatnya diakomodir) tetap saja masih ada sebagian kaum muslim yang tidak setuju dan mengatakan bahwa tradisi-tradisi lokal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama.
Peleraian ketegangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal dijembatani oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka ruang untuk menjadi “alat” untuk melerai ketegangan. Sejumlah kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh seperti al-Adah muhakkamah, al-Urf yunzalu manzilat al-Syarth, Al-ashlu fil Asy’yai al-Ibahah dan lain sebagainya terbukti ampuh untuk “mendamaikan” pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal.
Abdurrahman Wahid, sebagai pencetus gagasan “pribumisasi Islam”, membuat contoh penerapan kaidah di atas. Salah satunya dalam menyelesaikan sebuah kasus pemberian waris antara suami-istri dimana terdapat adat atau tradisi gono-gini di daerah Yogya-Solo dan adat perpantangan di Banjarmasin.
Abdurrahman Wahid menilai bahwa respons masyarakat adat yang berada di luar lingkup pengaruh kiai terhadap ketentuan nash dengan pemahaman lama yang merupakan pegangan para kiai itu. Harta rumah tangga dianggap sebagai perolehan suami-istri secara bersama-sama, yang karenanya mesti dipisahkan terlebih dahulu sebelum diwariskan, ketika salah satu dari suami/istri meninggal. Setengah dari harta itulah yang kemudian dibagikan kepada ahli waris menurut hukum Islam, sedang setengah lainnya adalah milik suami/istri yang masih hidup [Wahid, 120].
Fakta tentang adanya usaha “Pribumisasi Islam” sebagaimana ditengarai oleh Abdurrahman Wahid di atas, menurut Agus Sunyoto, bisa dilihat dari jejak peninggalan dan warisan dakwah Walisongo masih terlihat sampai hari ini dalam bentuk penyesuaian ajaran Islam. Misalnya penggunaan bahasa lokal sebagai ganti dari bahasa Arab. Sejumlah bahasa lokal yang digunakan untuk menngantikan istilah berbahasa Arab, misalnya dalam penggunaan sebutan “Gusti Kang Murbeng Dumadi” sebagai ganti dari Allah Rabb al-‘Alamin. Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad saw. Susuhunan untuk menyebut Hadrat al-Shaikh. Puasa untuk mengganti istilah Shaum. Sembah Yang sebagai ganti salat. Dan masih banyak lainnya [Agus Sunyoto, 2012:120].
Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan kemudian dimasuki lagi oleh kali cabangan sehingga sungai itu semakin membesar [Wahid:120]. Artinya adalah bahwa pribumisasi adalah bagian dari proses pergulatan dengan kenyataan sejarah yang sama sekali tidak mengubah substansi Islam itu sendiri.
Islam Indonesia Islam Sinkretik?
Islam Indonesia yang penuh diwarnai dengan adat dan tradisi lokal ini selain unik juga mengundang banyak perdebatan. Baik perdebatan akademik maupun perdebatan yang tidak jelas: debat kusir.
Dalam ranah akademik, tesis Geertz dalam buku legendarisnya “Agama Jawa”, Nur Syam dengan “Islam Pesisir”nya, Mark Woodward dengan “Islam Jawa”nya, Muhaimin AG “Tradis Lokal”, Ahmad Muhtarom “Abangan”, hingga Agus Sunyoto dalam “Atlas Walisongo”nya, dan para akademisi lainnya merupakan sederet akademisi yang telah menuangkan hasil risetnya mengenai hubungan Islam dan Tradisi Jawa. Kita semua tentu berhak menilai, menerima bahkan menolak pendapat para peneliti di atas. Tentu dengan penilaian yang arif dan obyektif.
Sementara di akar rumput, sebagian umat Islam yang menolak tradisi-tradisi lokal ini tanpa alasan dan argumentasi yang jelas langsung menolaknya. Alih-alih berusaha memahami persoalan, yang ada justru langsung mencibir pelakunya.
Martin mengeritik sejumlah pengamat Islam Indonesia khususnya dalam persoalan tradisi Islam lokal. Menurutnya, mayoritas dari mereka tidak pernah tinggal di Negara muslim lain yang juga memiliki kekayaan tradisi. Pendapat Martin ini bertolak dari pengalamannya mengamati tradisi keberagamaan suku Kurdi di Irak. Pada titik ini, pendapat Martin selaras dengan ulasan Agus Sunyoto yang melihat adanya pengaruh Islam Champa dalam praktik keberislaman masyarakat Islam Nusantara.
Martin [2010, 59-60]mengatakan:
Banyak praktik dan kepercayaan lokal tampak sebagai bagian dari suatu kompleks budaya global yang nyaris hanya bisa disebut muslim atau “Islamicate”. Banyak muslim di Indonesia masa kini menolak mengakui semua itu sebagai Islami karena –menurutnya- bertentangan dengan konsepsi modern tentang Islam yang universal. Namun dalam banyak kasus, kepercayaan dan praktik tersebut datang ke Indonesia sebagai bagian dari peradaban Islam, meskipun tidak termasuk inti agama Islam. Kepercayaan dan praktik ini mewakili gelombang Islamisasi.
Selain faktor yang disebutkan oleh Martin di atas, salah satu hal yang diabaikan oleh banyak orang adalah melupakan pengaruh muballig Islam ke Indonesia itu sendiri. Sebab, sebagaimana digambarkan dalam berbagai buku sejarah bahwa penganjur, pembawa, dan penyebar Islam di Nusantara adalah para guru sufi, di mana mereka memiliki kearifan yang sangat tinggi dalam melakukan dakwah. Gubahan-gubahan syair, penggunaan wayang sebagai media dakwah, dan lain sebagainya merupakan bukti akurat yang menunjukkan kearifan para penyebar ajaran Islam di Nusantara dalam meresapi tradisi-tradisi lokal yang ada kemudian dimasukkan nilai-nilai keislaman.
Dari uraian dan penjelasan di atas, kiranya jelas bahwa dalam menilai tradisi lokal yang berkembang di Indonesia dan cukup kompleks ini perlu pemahaman yang holistik. Apalagi hanya berdasarkan ketidaksukaan terhadap kelompok lain atau sekadar mengikuti pendapat-pendapat yang beredar di dunia maya yang belum teruji keakuratannya, bukan?