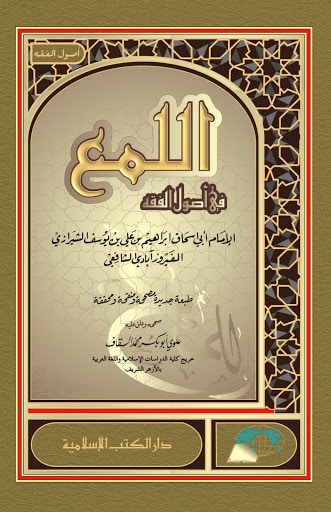“Aisyah: Sosok Perempuan yang Gagah.” Demikian salah satu judul artikel Kiai Husein yang terkumpul dalam buku, Spritualitas Kemanusiaan (2006), yang membuat saya terhentak.
Jujur, seluruh hasil bacaan saya selama itu, Aisyah putri jelita Abu Bakar, istri Rasulallah, ibu para mukmin itu amat sangat lembut dan feminim, apalagi kita mengenalnya dengan “si Pipi Merah” atau khumaira. Tetapi di tangan Kiai Husein, saya mendapatkan pemandangan lain. Tentu, selain ia perempuan yang tangkas dan cerdas, juga “tomboi”. Kata tomboi dalam bahasa Arab sering disebut rajulah, bukan mutarjilah.
Kata rajulah dan mutarjillah ini amat jauh berbeda maksud. Rajulah merujuk pada hal-hal maskulin secara mental, sementara mutarjillah merujuk pada sikap yang menyerupai, misal berdandan seperti laki-laki. Untuk mendapatkan kesan ini, Kai Husein bicara bukan tanpa data, melainkan dengan setumpuk literasi kitab turas.
“Sayangnya, orang asing menenggelamkan predikit ini dari sejarah,” keluh Kiai Husein dengan mengutip pendapat Abu Said al-Sairafi. Cerita mengenai ini bisa ditelusur lebih jauh dalam kitab Al-Imta’wa al-Muanasah, karya Abu Hayan at-Tauhidi, jilid III, hal. 199-200.
Selalu ada tiga hal yang identik dengan Kiai Husein yaitu perempuan (gender), kitab kuning, dan pesantren. Di hadapan literasi yang kuat, nalar yang hidup, dan tradisi pesantren yang mendarah-daging, Kiai Husein tumbuh terus dalam kreasi, mendobrak, dan membela pada kaum marginal, terutama pada kaum perempuan.
Tentu saja ini tidak mudah, sebuah liku-liku psikologi yang pelik dan pergulatan wacana yang pasang surut dalam proses transformasi dari yang ‘lama’ menjadi ‘baru.’
Memang, kreativitas diawali rasa gelisah mencari, kegalauan ingin menemukan, juga niat merombak dan Kai Husein tetap di jalan itu. Tetapi bagi yang tak mengerti alurnya, ia seperti Gus Dur, Habib Quraisy dan Gus Mus sering dianggap melampaui batas dan liberal. Sebuah resiko dari predikit kiai yang cerdas.
Menariknya, saat Kiai Husein bicara apa pun, sering dimulainya dari sudut pandang perempuan, sekalipun ketika yang dibahas budaya, ekonomi, sosial, negara, politik- kebangsaan, bahkan spiritualitas. Sesuatu yang nyaris tak ada duanya di negeri ini. Satu lagi yang amat membuat kita patut iri dan mendapatkan inspirasi.
Ia berkarya sejak masih muda-belia dan masih istikamah menulis hingga hari ini. Puluhan karya terjemahan Islam-kritisnya dan artikelnya sudah terbit sejak tahun 1980-an awal, sebagian terbit di P3M Jakarta. Menariknya, ia bicara fikih perempuan dan hal-hal seputar itu, bukan dari Barat, tetapi jalan lurus kitab-kitab turats dan al-Azhar.
Dengan latar belakang seperti itu, meksi banyak pemikir muda mencuat ke permukaana dengan diskursus yang sama, Kiai Husein tak pernah kehilangan posisi, terlebih ia meyakini, yaitu sebuah sebab yang lebih dalam: bahwa fokus di wacana gender adalah ibadah yang tulus, sekaligus tragis.
Melalui “gender” ia berusaha keras ”menangkap kehadiran Ilahi”, tapi sedikit yang berhasil memahami. Tapi ia ingin terus, meskipun cemoohan dan ocehan tak pernah berhenti.
Setidaknya semangat ini yang melatarbelakangi terbitnya dua buku yang fenomenal, Fiqih Perempuan (LKiS, 2001), dan Islam Agama Ramah Perempuan (LKiS, 2004). Dua buku yang lama menjadi menghuni deretan rak saya.
Ketika sensus menunjukkan grafik-jumlah perempuan cukup tinggi ketimbang laki-laki, disertai sebuah kenyataan, hidup di kota yang makin gelap dan pengap. Juga, belakangan telah menjamur para dai dan akitifis yang pro-poligami, dengan berbagai alasan, tetapi Kiai Husein seperti tak pernah peduli dengan data dan hal itu.
Mungkin, bahkan tak lagi sempat mempedulikan yang kosmis nun di atas. Sebab, baginya alam raya ini telah mengajari akan keseimbangan dan prinsip keadilan yang hakiki. Sepasang langit dan bumi, sepasang laut dan pantai, sepasang panas dan dingin dan seterusnya, sesuatu yang vertikal bertemu dengan yang horizontal. Manusia juga sama seperti itu. Lihatlah penggalan puisinya ini:
SATU SAJA
Tidak ada satu hati untuk dua cinta
Keinginanmu membaginya
untuk dua atau lebih secara sama
tidaklah mungkin..
Maka sudah seharusnya kita, para perempuan, terutama emak-emak yang harus berterimakasih kepada Kiai Husein, dan sehingga tak perlu menunggu ‘diingatkan’ oleh Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) yang memberinya anugerah Doktoris Honoris Causa, hari ini, 26 Maret 2019.
Dengan kata lain, tanpa Universitas itu memberi ‘ganjaran’ doktor honoris causa, semestinya kita, terutama para emak-emak sudah terlebih dulu menyematkan gelar itu, sebagai bentuk apresiasi dan dedikasi.
Sebab sikap dan keberpihakan Kiai Husein pada perempuan selama ini menunjukkan apa yang disebut sebagai civilitas. Dalam kata-kata sejarawan Belanda terkemuka, Huizinga, itulah perjuangan-sejati, kebaikan hati, dan sikap moderasi. Akhir kata, selamat buat Kiai Husein, salah satu kiai idola kaum muda yang mendapatkan gelar kehormatan ini. Wallahu’alam bishawab.
Yogyokarta, 19 Maret 2019