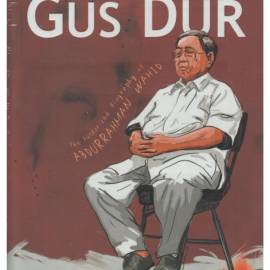“Barangkali misi dari mereka yang mencintai manusia adalah untuk membuat manusia tertawa pada kebenaran, untuk membuat kebenaran tertawa. Karena satu-satunya kebenaran, terletak dalam upaya belajar membebaskan diri kita dari La morbosa passione per la verità: gelora gila terhadap Kebenaran..” (Bruder William dari Bakersviile, The Name of the Rose, Umberto Eco, 1983).
Jaya Suprana, pianis, bos jamu Jago, yang juga pendiri MURI dan pionir “ilmu” Kelirumologi, suatu hari menuturkan ulang kisah yang diceritakan Gus Dur tentang acara debat politik antara KH. Agus Salim dan Musso.
Musso yang pertama naik podium, mengawali debat dengan bertanya kepada hadirin, “Saudara-saudara, orang yang berjanggut itu seperti apaaaaaaa?”
Hadirin, kaget bercampur geli, menjawab serentak, “Kambiing!”.
Musso lanjut bertanya lagi, “Lalu orang yang berkumis itu seperti apaaaa?”
Hadirin riuh rendah mulai tertawa-tawa bersama menjawab, “Kuciiiing!”.
K.H. Agus Salim yang memang berjenggot dan berkumis sadar bahwa dirinya menjadi sasaran cemooh Musso, tidak baper. Malah tetap ikut tertawa bersama hadirin.
Usai Musso, giliran K.H Agus Salim naik podium. Di atas mimbar, K.H. Agus Salim ikutan bertanya kepada hadirin. “Saudara-saudara, orang yang tidak berjenggot dan tidak berkumis itu seperti apaaaaaa?”
Ruang debat seketika sesak oleh gelak tawa hadirin, yang meledak riuh-rendah. Serentak hadirin dalam ruangan itu kompak berteriak menjawab, “Anjiiiiiing!”
Musso yang memang klimis tidak berjenggot dan tidak berkumis itu, ikut tertawa.
Ketika Humor Dianggap Racun
Ngakak itu enak, ngguyu itu bikin guyub. Kalau zaman sekarang kita susah cewawak’an, mari kita mulai dari cengengesan. Hasilnya, mata menyipit dan bibir melebar akibat pipi yang tertarik ke belakang, akan membuat wajah lebih manis. Ketimbang mata melotot, alis bertemu, otot pipi mengkerut dan rahang membentuk kotak kaku.
Ini bukan soal sport wajah, tapi soal ngakak itu enak, sehat, dan mencerdaskan. Ngaku sajalah, bukankah humor Gus Dur selalu membuat kita tertawa, dan bahagia? Bahkan keruwetan masalah menjadi sirna.
Gus Dur, berhasil membuktikan pada kita bahwa humor adalah bukti kecerdasan, peradaban, sekaligus strategi. Machiavelli, mengajak kita tertawa —meski kecut dan hanya dalam hati—melalui satirenya dalam Il Principe. Dan Umberto Eco, filsuf modern yang juga mengundang kita untuk melanggar larangan tertawa, melalui karya fenomenalnya: Il Nome Della Rosa (1983). Buku fenomenal yang beredar di Indonesia dengan judul The Name of the Rose itu, ditulis dengan semangat mempertanyakan: “Pernahkah Kristus tertawa?”
Ber-setting abad pertengahan (14 Masehi), di sebuah biara Benediktin bernama Melk. Terpencil, di Italia Utara. Saat itu teriakan bid’ah berujung hukum bakar, dan nalar masih perang melawan dogma kaku agama.
Il Nome Della Rosa dibuka dengan kisah kematian Adelmo, seorang biarawan muda (Bruder) akibat jatuh ke dasar jurang, suatu hari pada November 1327. Adelmo mati pada hari pertama ia datang sebagai mediator konflik tingkat dewa, yang akan berlangsung di biara itu, antara kubu Kerajaan (disokong ordo Fransiskan) dengan Paus (didukung Ordo Dominikan).
Lalu datanglah William dari Bakersville, seorang biarawan muda Fransiskan, mantan inquisitor, menyelidiki kasus kematian Bruder Adelmo. Ia bersama asistennya, frater Adso, belum rampung menyelidiki kasus Adelmo, ketika bruder dan frater lain susul menyusul menjadi korban pembunuhan, selama 6 hari berturut-turut.
Disebut ‘korban’, sebab kematian para Bruder: Adelmo, Venantius, Bareangar, Severinus, dan Maleakhi, memang tergolong tak wajar. Ada yang tenggelam dalam kuali penuh darah babi, ada yang mengapung di bak penampungan air, ada juga yang diketok kepalanya. Semua korban berciri sama: jari dan lidahnya menghitam.
Menjelang hari ke tujuh, Bruder William dan Adso menemukan kenyataan bahwa serangkaian kematian tak wajar itu terkait buku yang disimpan di Secretum Finis Africae, ruang paling rahasia dalam perpustakaan biara, di gedung Aedificium.
Perpustakaan biara pada abad pertengahan, berada di bawah otoritas Gereja Katolik, dan tak semua bruder-frater boleh memasukinya. Itu sebab, jabatan Pustakawan sungguh menjadi incaran dan dipenuhi intrik. Laiknya persaingan rebutan jabatan politik.
Gedung Aedificium yang ruangnya berkelok bagai labirin itu, memiliki perpustakaan berisi harta karun, berupa: naskah, buku, perkamen kuno dari Yunani, Andalusia, risalah kuno, buku-buku ilmu pengetahuan dari negeri ilmuwan Islam (yang saat itu disebut ‘kafir’), hingga lembar-lembar Injil paling awal.
Ada juga ruang rahasia, tempat menyimpan buku yang tergolong Un Strano Iibro, alias buku aneh. Antara lain, buku fabel dalam bahasa Arab yang mengajak orang menjadi bajik dan bijak, melalui humor yang mengundang tawa. Dan ada satu salinan buku, yang oleh Romo Jorge de Burgos yang buta, Kepala Perpustakaan Biara Melk, disimpan rapat di ruang tersebut.
Zaman itu, umumnya buku hanya salinannya, sebab semasa itu, buku ya hanya satu eksemplar, tak bisa dicetak banyak. Buku itu adalah kopi-an buku kedua Aristoteles, berjudul Poetics. Buku yang mengulas pentingnya kedudukan komedi, dan bahwa tawa adalah satu-satunya ‘tempat pengungsian’ dari doktrin kebenaran universal.
Jorge tak suka pada tawa. Menurutnya, tawa adalah bid’ah paling bejad. Jorge menyembunyikan jilid itu bagai aib paling busuk, selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan seumur hidupnya, Jorge menjaga kebenarannya sesuai pemahamannya yang kaku, dengan cara menjaga buku itu, agar pemahaman manusia atas semesta seiasinya, tak dijungkirbalikkan oleh pemikiran filsuf. Agama adalah soal serius, menurut Jorge. Itu sebab, Kristus tak pernah tertawa.
Maka, Jorge melumuri racun arsenik di sudut- sudut halaman Poetics yang memuat humor. Yang curi-curi membaca buku itu, akan mati keracunan arsenik, saat tertawa ngakak. Atau, saat lidah menjilat jari untuk membalik halaman buku.
Humor sebagai Kurikulum Wajib Ajar
Pada masa Yunani Kuna, filsuf Plato menilai humor sebagai sebuah emosi yang dapat menghilangkan pengendalian diri. Alias: tertawa bisa membuat manusia lupa daratan dan tak terkendali. Secara terang, Plato melarang aparatus negara untuk berdekatan dengan humor. “Seorang yang merepresentasikan manusia berharga (men of worth), terperdaya oleh gelak tawa, akan kami tolak keberadaannya,” kata dia.
Bahkan Stoics, aliran filsafat yang dinilai sangat kalem dan paling peduli dengan ketenangan pun turut menolak humor, persis seperti Plato yang mengatakan humor dapat menghilangkan pengendalian diri seseorang.
Penggunaan kata “humor” ini, semula tidak mewakili “kelucuan” hingga abad ke-18. Dalam tradisi lama, kita hanya mengenal tawa atau komedi. Filsuf sohor macam Plato, Hobbes, dan Kant tidak pernah membahas humor secara spesifik, dan hanya menyelipkannya dalam paragraf, itu pun saat mereka membahas topik lain.
Baru pada tahun 1900, Henri Bargon’s menulis buku berjudul Laughter, yang secara spesifik membahas soal humor. Kemuraman bangsa-bangsa di dunia pada abad-abad sebelumnya, akibat tertawa itu dilarang dan humor adalah racun, mulai pudar. Padahal, tawa mampu melepas energi jahat dalam diri kita dan bikin badan rileks. Itu Sigmund Freud yang ngomong, dalam relief theory.
Kata Freud, orang yang tertawa itu melepaskan ketegangan dan rasa lelah dalam dirinya. Dan sebuah studi ilmiah di India menyatakan bahwa: sepuluh menit tertawa, setara dengan manfaat tidur selama dua jam.
Mari kita cari bukti dan fakta, bahwa puncak dari kuil peradaban adalah humor. Mungkin, selama ini kita menyendirikan humor pada persoalan etik semata. Padahal, jika dilihat lebih jauh, humor ini melibatkan berbagai unsur disiplin ilmu. Mulai dari psikologi, sosiologi, biologi, neurosience, bahkan dalam ilmu politik.
Percayalah, memang tak mudah mencapai puncak suci itu. Kita harus serius belajar tertawa.
Untuk itu, marilah kita berjuang agar humor dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Jika perlu, sebagai disiplin ilmu wajib sejak SD. Syukur-syukur jika bisa mendapat dua SKS dalam kurikulum perguruan tinggi.
Padahal humor —terlebih jika humor itu keluar dari mulut Gus Dur—, jutaan nyawa bisa terselamatkan. Era 1980-an ilmuwan mulai serius melihat humor ini sebagai aset peradaban yang perlu dipelajari lebih serius lagi.
Bisakah kita meniru Gus Dur? Jika bisa, mengapa tidak segera dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah? Jika tidak, mungkin ada yang salah dengan peradaban kita yang memang malas belajar. Saking malasnya, belajar tertawa pun ogah.