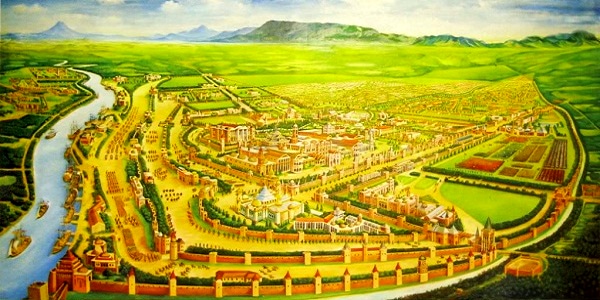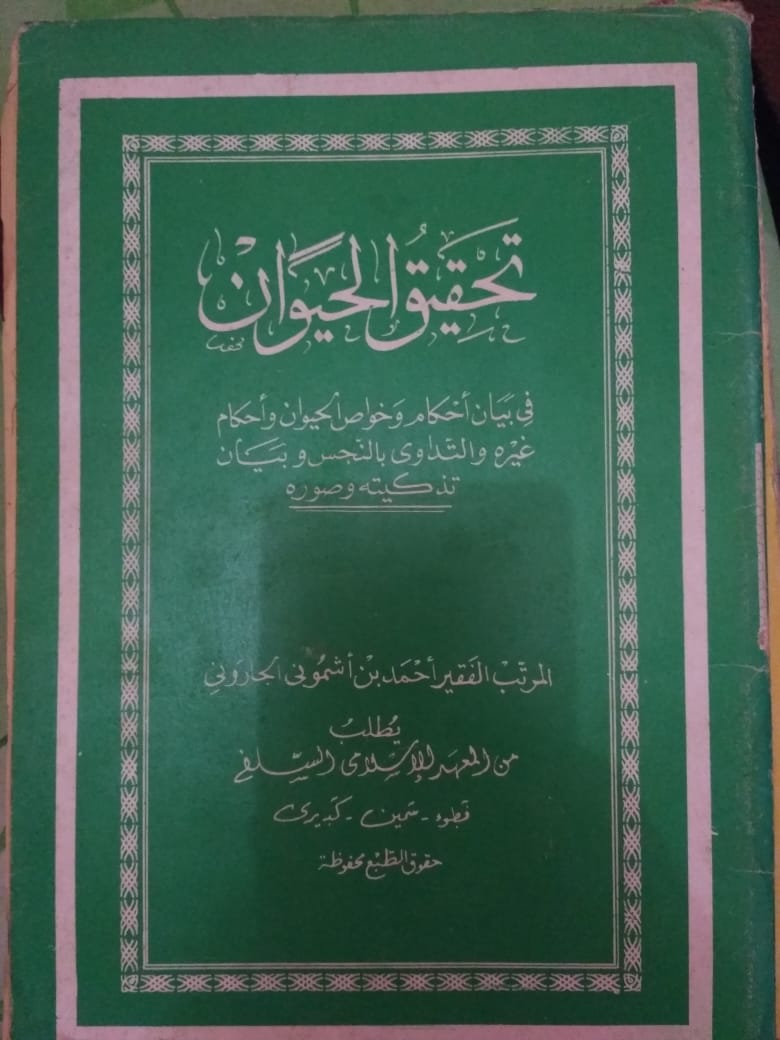Hari libur nasional akhir bulan Januari 2025 yang memperingati hari besar keagamaan (Isra' Mi'raj 27 Januari 2025 dan Tahun Baru Imlek 29 Januari 2025) lalu adalah momen yang dinantikan masyarakat. Banyak rencana jauh-jauh hari telah disusun untuk pergi ke luar kota, berwisata ke tempat-tempat hiburan dan memesan hotel, villa atau penginapan bersama keluarga. Pemerintah memfasilitasinya dengan menetapkan hari libur bersama untuk memperpanjang waktu vakansi. Niatnya untuk memberi ruang makin panjang bagi masyarakat untuk menikmati kebahagiaan liburan, yang pada saat yang sama, diharapkan juga berefek pada dinamika ekonomi.
Namun, di satu sisi, makna yang melekat pada hari-hari (yang diliburkan) itu sebenarnya mengalami perubahan makna yang signifikan. Apa yang semula dimaksudkan sebagai hari refleksi keagamaan atau penghormatan terhadap tradisi kini diidentikkan dengan kesenangan, gaya hidup, dan pergerakan ekonomi. Pergeseran ini membuka ruang refleksi kritis: apakah libur nasional masih berfungsi sebagaimana mestinya, atau telah menjadi bagian dari konsumsi modern yang mengikis nilai-nilai tradisional?
Tradisi Terkomodifikasi
Pada awalnya, asal-usul hari libur nyaris selalu berhubungan dengan agama. Hari libur diberikan sebagai izin bagi seseorang untuk menjalankan tugas agama pada hari-hari khusus yang disucikan. Itulah sebabnya sebagian bangsa Barat menyebut hari libur dengan "holiday" (holy + day) yang berarti hari suci. Liburan berisi pemujaan untuk merawat serta menyuburkan iman (Musyafak, 2014).
Konsep “hari suci” merujuk pada momen yang dimaksudkan untuk perenungan spiritual, penghormatan terhadap nilai-nilai agama atau tradisi, serta penguatan identitas kolektif. Isra' Mi'raj misalnya, mengandung nilai mendalam tentang perjalanan spiritual Nabi Muhammad dan esensi hubungan manusia dengan Tuhan. Begitu pula Imlek, yang membawa pesan harmoni, penghormatan kepada leluhur, dan harapan keberuntungan dalam kehidupan.
Namun, dalam kenyataan modern, hari libur semacam ini lebih sering dimanfaatkan sebagai "liburan" belaka. Orang berbondong-bondong ke destinasi wisata atau menghabiskan waktu di rumah tanpa ada aktivitas yang mencerminkan makna aslinya. Alhasil, nilai filosofis dan spiritual yang terkandung dalam hari-hari besar ini sering kali terdegradasi oleh kebiasaan konsumtif dan pola hidup modern.
Tahun Baru Imlek adalah salah satu contoh paling mencolok dari bagaimana tradisi telah berubah menjadi ajang komodifikasi. Di kota-kota besar, perayaan Imlek sering kali hadir dalam bentuk yang penuh warna: lampion, barongsai, dan dekorasi serba merah menghiasi ruang publik dan pusat dunia. Sementara itu, nilai filosofis Imlek tentang keharmonisan keluarga dan perenungan tentang kebersamaan jarang mendapat tempat.
Pendekatan serupa terlihat dalam peringatan hari besar lainnya. Ritual Isra' Mi'raj yang sering kali diisi dengan pengajian atau ceramah keagamaan di masjid kini tidak luput dari modernisasi. Acara-acara ini terkadang lebih fokus pada kemasan yang menarik perhatian massa daripada mendalami esensi nilai-nilai spiritual yang sebenarnya. Konteks hari keagamaan yang diperingati justru mencerminkan dilema religiusitas di era modern.
Seturut analisis Pierre Bourdieu tentang modal budaya, tradisi atau ritual yang semula memiliki nilai simbolis kini direduksi menjadi modal ekonomi yang dapat dimonetisasi. Dalam konteks ini, tradisi lebih dipandang sebagai aset untuk menarik wisatawan atau meningkatkan konsumsi, bukan sebagai warisan nilai yang dikontekstualisasi dan harus dijaga kelangsungannya.
Gaya Hidup Modern
Disisi lain, libur memberi keleluasaan waktu rekreasi bagi masyarakat untuk bersenang-senang. Terlebih pada perkembangannya, masyarakat modern memaknai hari libur sebagai masa rehat dan bersantai tak ubahnya akhir pekan. Setelah menjalani berbagai rutinitas sehari-hari, liburan menjadi cara untuk “melarikan diri” dari tekanan pekerjaan dan melepas penat. Liburan menempati jadwal tersendiri dalam agenda hidup.
Hari libur menjadi pengganti hari-hari biasa yang sudah dipenuhi oleh rutinitas dan tekanan kerja dan atau bersekolah. Di hari libur, tempat-tempat wisata, mal atau restoran dan rumah makan dibuka dan ramai dikunjungi masyarakat. Liburan menjadi kebiasaan atau bahkan menjadi target dan tujuan bekerja.
Pada saat yang sama, berlibur menjadi penanda kelas sosial di masyarakat. Bandung Mawardi (2011) menyebut liburan seorang buruh pabrik di Eropa yang bekerja selama 12 jam dalam sehari adalah bermalas-malasan di rumah. Gaya liburan tersebut menunjukkan status sosial buruh pabrik yang pada waktu itu (sekitar abad 18) adalah kaum proletariat yang ditindas oleh kaum filantropis dan moralis.
Disatu sisi, meski ada beberapa orang yang berlibur dengan cara ikut pengajian atau mudik ke kampung halaman, namun kelas sosial yang lebih tinggi memilih mencoba kafe baru, berburu diskon atau berlibur ke luar negeri. Hal ini tentu menghabiskan biaya yang tak sedikit. Ketimpangan ini menciptakan paradoks: libur yang seharusnya menjadi hak bersama, justru mempertegas perbedaan kelas sosial. Liburan menjadi kebutuhan yang sulit untuk didefinisikan.
Liburan menjadi penanda bahwa manusia masih hidup. Liburan adalah usaha untuk memuliakan hidup. Mumpung masih hidup, maka orang wajib liburan. Terlebih kini liburan menjadi lebih mudah dan terfasilitasi oleh berbagai perusahaan dan agensi perjalanan, fasilitas di gawai serta kebijakan pemerintah. Segala hal menjadi menyenangkan jika menyangkut liburan. Namun, ketika religiusitas dan tradisi sepenuhnya digantikan oleh gaya hidup konsumtif, muncul pertanyaan: apakah kita sedang kehilangan esensi hari libur sebagai momen kualitas nilai tradisi dan spiritualitas?
Refleksi Relevan
Hari libur panjang dapat menjadi peluang untuk memperkuat nilai tradisi dan spiritualitas, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menciptakan ruang refleksi yang relevan dengan konteks kekinian.
Misalnya, dalam peringatan Isra' Mi'raj, masjid atau komunitas keagamaan dapat menyelenggarakan kegiatan yang tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga aktifitas interaktif yang relevan dengan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan modern. Sementara itu, perayaan Imlek bisa diarahkan untuk menekankan filosofi harmoni dan penghormatan kepada leluhur, bukan sekadar festival warna-warni.
Narasi ini perlu diamplifikasi dalam kegiatan kontekstual yang dilakukan. Semua itu menjadi bentuk edukasi berbasis budaya dan spiritual yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum (sekolah dan) kehidupan. Dengan cara ini, masyarakat dapat memahami makna hari-hari besar keagamaan dan tradisi sebagai bagian dari identitas komunal yang plural.
Di era digital, pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi. Platform daring yang memberikan informasi mendalam tentang makna filosofis hari-hari besar dapat menjadi sumber refleksi bagi masyarakat modern yang akrab dengan teknologi.
Hari libur panjang, terutama untuk memperingati hari-hari besar seperti Isra' Mi'raj dan Imlek, tidak hanya urusan psikologi, mental komunal, dan pariwisata, tapi gaya hidup, identitas pencitraan hingga pamrih politis. Ia menyimpan kontradiksi dan kontestasi antara yang modern dan tradisional, yang sakral dan profan, yang elit dan ‘kebanyakan’, serta sederet kontradiksi lainnya yang berlangsung dalam benak masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita terus-menerus terkendalikan oleh hasrat liburan hingga akhirnya, kita semakin kehilangan (kesadaran dan) makna diri.