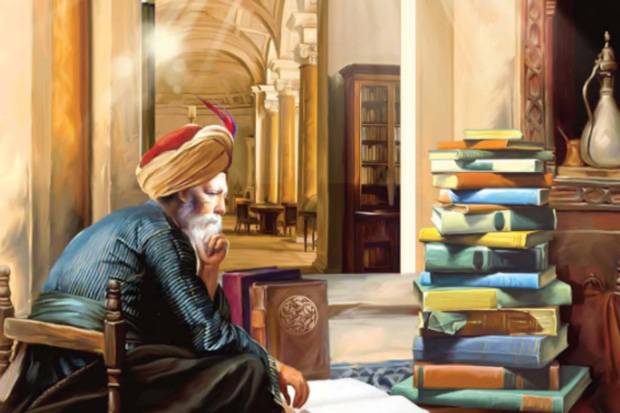“Rindu itu pilar utama kerajaan para pecinta. Di sana, singgasana pahitnya perpisahan tegak kokoh. Pedang getirnya kepergian terus terhunus. Kelopak bunga daffodil kebersamaan tergeletak di atas genggaman telapak tangan harapan. Di setiap waktu, sabetan pedang menebas ribuan leher. Kata mereka: tujuh ribu tahun telah berlalu, tetapi kelopak daffodil belumlah layu. Sejak saat itu pula, belum ada satu tangan pun datang menyentuh,” Abu Yazid Al-Busthomi.
Tidak mudah tetap tersenyum di kala kehilangan, apalagi kekasih tercinta. Entah itu keluarga, sahabat karib, lebih-lebih guru-guru terkasih. Kehilangan akibat perpisahan masih bisa terobati dengan perjumpaan. Tetapi berpisah karena kematian, apa yang tersisa selain kenangan?! Begitu kiranya gambaran sederhana perasaan umat muslim ditinggal pergi selamanya oleh orang-orang tersayang selama masa pandemi Covid-19.
Abu Yazid al-Busthomi (804-874 M.), sufi Persia itu, menggambarkan betapa pahit dan getirnya hati seseorang yang ditinggal pergi sang kekasih. Rasa sakitnya setara dengan dihunus pedang ribuan kali, sepanjang waktu tanpa henti. Rasa sakit dan perih yang lahir dari cinta, sayang, dan rindu mendalam. Namun, walau sudah mengerti rindu, cinta dan sayang membawa luka memeram, perasaan itu tidak mau hilang, sekalipun tujuh ribu tahun berlalu.
Sufi di Abad 3 Hijriyah ini, mengarahkan cinta dan rindunya pada Allah. Suatu hari ia berujar: “Idza ja-a hubbullah yahglib kulla syai. La halawata lid dunya, la halawata lil akhirah. Al-halawah halawatur Rahman”. Tatkala cinta itu mampir, ia melumat segalanya. Hampa dunia ini. Hampa akhirat itu. Rasa manis hanyalah Dia Yang Maha Kasih.” Ujaran ini indikasi dunia-akhirat menjadi hambar tatkala cinta Allah telah datang ke dalam hati manusia.
Abu Yazid, seorang sufi yang juga menekuni al-Quran-Hadits dan bermazhab Hanafi ini, salah satu level batin seorang manusia, yaitu, level ketidaktertarikan pada dan ketidakterikatan dengan kenikmatan dunia maupun akhirat. Sebuah gagasan yang lebih awal telah dilontarkan oleh sufi perempuan dari Basrah Irak, Rabi’ah al-Adawiyah (713-801 M.).
Abu Yazid dan Rabi’ah Adawiyah mengajarkan sebuah ajaran cinta, yang berpangkal pada sabda Rasulullah saw: “Tiga perkara yang bisa dimiliki seseorang maka ia akan mendapatkan manisnya iman: Allah dan rasul-Nya lebih ia cintai dari apapun, mencinta orang lain karena Allah, dan enggan mengulangi kekufuran sebagaimana enggan dilempar ke neraka,” (HR. Bukhari-Muslim).
Mencapai maqam cinta kelas para waliyullah ini sebuah anugerah besar dari Allah. Bahkan secara psikologis dan sosiologis, anugerah ini membawa efek manfaat dan asas maslahat. Abu Yazid mengisahkan pengalaman dirinya: “adzkhalani ma’ahu mudkhalan aranil khalqa kullahum bainal usbu’aini”. Allah pernah membawaku bersama-Nya pada satu tempat yang membuat aku melihat seluruh makhluk berada di antara dua jari ini.” Semua selain Allah menjadi kecil di mata Abu Yazid.
Secara psikologis, seseorang yang hatinya penuh dengan kebesaran Allah maka segala penderitaan di muka bumi menjadi kecil. Ia tidak pernah takut dengan kematian, kerugian, kekalahan, rasa sakit, duka, dan lara. Ketika pribadinya seorang diri telah sanggup menanggung beban, maka secara sosiologis ia sanggup menanggung beban derita orang lain.
“Ya Tuhanku, bila dalam pengetahuan-Mu sudah ditentukan Engkau akan menyiksa salah satu makhluk-Mu dengan api neraka-Mu, maka jadikan tubuhku ini memenuhi neraka hingga tak satu pun mendapatkan tempat selain aku,” begitu doa Abu Yazid.
Lapang jiwa dan empati merupakan spirit ajaran cinta Abu Yazid Busthami. Sanggup menanggung segala beban luka dan derita untuk dirinya sendiri. Namun, bersusah hati bila harus melihat orang-orang di sekitarnya yang menderita kesusahan. Artinya, egoisme lenyap tergantikan oleh kepedulian sosial. Mengedepankan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan diri sendiri.
Kata Abu Yazid, “in kunta tuhibb ananataka li, fa inni qad wahabtu ananati laka. Faf’al ma turid”. Jika engkau tulis menyerahkan dirimu untukku, maka sungguh aku menyerahkan diriku untukmu. Lakukan apa saja yang engkau mau.” Prinsip saling melengkapi satu sama lain. Tolong menolong dalam kebaikan. Tidak mendahulukan diri sendiri. Seperti firman Allah: “tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan,” (Qs. Al-Maidah: 2).
Di saat-saat genting seperti sekarang ini, di masa pagebluk dan pandemi, ajaran cinta kasih Abu Yazid al-Busthomi dibutuhkan. Walaupun tidak dapat dikatakan secara spesifik siapa yang harus memulai lebih dahulu; pemerintah yang harus memikirkan nasib rakyat, ataukah rakyat yang harus mendukung program pemerintah; tetapi tanggung jawab itu ada di pundak bersama, dengan melangkah bersama, harmonis-sinergis. Melempar egoisme jauh-jauh.
(bersambung).
Sumber: Qasim Muhammad Abbas, Abu Yazid al-Basthami, Damascus: l-Mada, 2004.