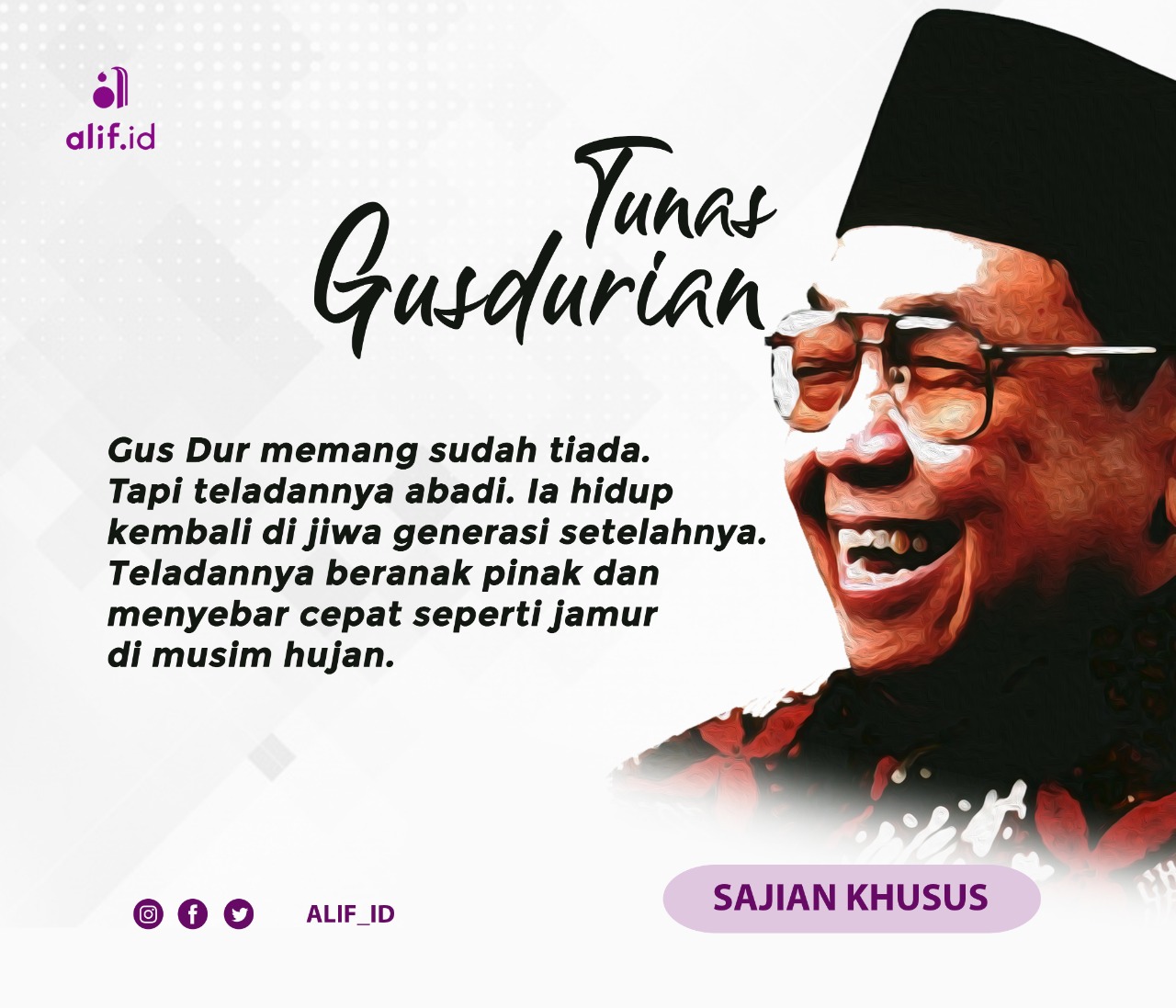
Saya punya keterikatan emosional dengan laku membantu. Sudah sejak lama sekali. Entah berasal dari mana. Itulah kenapa saya bisa menangis sampai sembap gara-gara menonton Seven Pounds (2008), ketimbang film-film paling sedih mana pun.
Selama pandemi, laku itu menemukan momentumnya. Saya mendapat kesempatan bergabung menjadi relawan GUSDURianPeduli untuk membantu para warga terdampak Covid-19. Meski sebelumnya sempat terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya, tapi bulan-bulan belakangan ini rasanya lebih intens.
Barangkali karena pandemi berlangsung lama, sehingga kerja-kerja filantropi juga mengekor mengikutinya. Atau barangkali kegiatan di posko memang tidak monoton, sehingga saya tidak merasa terjebak di dunia yang monokrom. Sebab, selain berjibaku dengan posko GUSDURian Peduli, beberapa kawan juga mengajak menggarap kebun kolektif di belakang posko persis.
Pada mulanya, sebelum pandemi, saya berkegiatan biasa di Komunitas Santri Gus Dur atau GUSDURian Jogja. Mendiskusikan artikel-artikel Gus Dur setiap Selasa, mengampanyekan nilai-nilai Gus Dur lewat media sosial komunitas, atau menyelenggarakan Kelas Pemikiran Gus Dur saban tahun. Tapi pandemi menghentikan semua pertemuan langsung secara mendadak.
Dari sanalah kegiatan saya banyak beralih ke GUSDURian Peduli, mengingat sayap kemanusiaan Jaringan GUSDURian itu mulai bergerak cepat menggalang dana dan membutuhkan banyak relawan untuk pengoperasian bantuan. Para relawan GUSDURian Peduli sebenarnya tak hanya berasal dari penggerak GUSDURian saja. Di posko Jogja ini, saya bekerja bersama beberapa mahasiswa, seniman, hingga tukang ojek daring.
GUSDURian Peduli sendiri mempunyai beberapa program penggalangan dana dan pendistribusian bantuan selama pandemi. Di antaranya seperti Gerakan #SalingJaga yang menyasar para pekerja informal yang kesulitan ekonomi sebab kehilangan pekerjaan; penggalangan gawai untuk disalurkan kepada anak-anak sekolah yang tak bisa belajar karena tak mempunyainya; atau sekadar mendistribusikan masker, APD, alat kebersihan, atau sembako dari organisasi, lembaga, atau perusahaan yang ingin berdonasi.
Di Gerakan #SalingJaga saja, katakanlah, donasi yang terkumpul mencapai 5,8 miliar rupiah. Gerakan yang diinisiasi oleh Alissa Wahid (GUSDURian Peduli) dan Haidar Bagir (Gerakan Islam Cinta) ini melibatkan 200 penggalang dana (fundraiser) dan 37.494 donatur di platform kitabisa.com.
Besarnya tanggung jawab penyaluran bantuan itulah yang membuat GUSDURian Peduli memerlukan banyak sekali relawan di berbagai kota. Posko Jogja hanyalah 1 dari 68 posko GUSDURian Peduli yang tersebar di berbagai kota. Sedangkan saya sendiri hanyalah 1 dari 900 lebih relawan yang berusaha menjadi bagian dari roda kebaikan ini.
Di posko, para relawan harus belanja sembako ke pasar grosir, membeli kardus, mengepak paket bantuan sesuai porsi, mendata warga penerima manfaat, mendokumentasikan kegiatan, hingga ikut mengantarkan bantuan sampai ke tujuannya. Selain menyasar pekerja informal dan anak-anak yang tak mempunyai gawai, sasaran manfaat juga ditujukan kepada panti asuhan, pesantren, rumah sakit, komunitas seniman, komunitas waria, dan mahasiswa indekos yang tak bisa pulang kampung.
Di posko yang kebetulan berada di ruang belakang Griya GUSDURian ini saya sering menghabiskan waktu dari pagi sampai malam. Setelah kegiatan posko berjalan lebih dari sebulan, kawan-kawan dari Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) mengajak saya untuk mengolah tanah kosong di belakang posko. Setelah mendapatkan izin, kami menggarapnya bersama.
SPJ adalah gerakan kolektif untuk menanggulangi krisis pangan selama pandemi, terutama di wilayah Jogja. SPJ memiliki sekitar 11 dapur umum yang beroperasi hampir setiap hari. Di dapur umum ini, ada banyak relawan yang memasak dan membagikan makanan siap saji untuk para pekerja informal dan warga kurang mampu di jalanan atau di kampung-kampung.
SPJ juga melakukan penggalangan dana sendiri agar dapur tetap mengepul. Sedangkan rencana untuk mengolah kebun ditujukan untuk menyuplai kebutuhan sayuran dan rempah sehat, supaya tak sepenuhnya mengandalkan hasil donasi.
Di kebun, kami mengolah tanah terbengkalai menjadi lahan produktif, mencari bibit dan benih, menyebar pupuk kandang, menyemai benih, menanam bibit, menyiramnya setiap hari, membuat pestisida organik dari rendaman tembakau, menyemprotnya berkala untuk mengusir hama, hingga memanen dan mengirimnya ke dapur umum.
Beruntung, semua kebutuhan kebun di awal penanaman dibantu oleh teman-teman WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Jogja. Sedangkan untuk perawatan rutin, kami semua turun tangan: kawan-kawan GUSDURian Jogja, WALHI Jogja, SPJ, Warga Berdaya, dan masih banyak lagi. Kami menanam sawi, terong, kangkung, bayam, cabai, tomat, kacang panjang, ubi, singkong, pisang, pepaya, dan seledri.
Para relawan kebun juga membuat serial diskusi daring bertajuk “Senja di Kebun” setiap Jumat sore. Diskusi ini bertujuan untuk mengajak lebih banyak orang agar terlibat dalam kegiatan berkebun selama pandemi dan bisa berdaulat atas kebutuhan pangan individu. Kami mengundang beberapa pemantik berlatar belakang pekebun, pengamat lingkungan dan pangan, hingga penggerak lembaga filantropi.
Kegiatan filantropi selama pandemi ini, saya kira tak hanya menjadi pengalaman sosial belaka, melainkan pengalaman spiritual berharga mahal. Setidaknya, lingkungan manusiawi inilah yang membuat saya merasa lebih hidup. Dari dua aktivitas laku membantu ini, saya merasa ada dua ruh perjuangan Gus Dur yang hidup kembali: keberpihakannya pada ‘yang dilemahkan’ dan kedermawanannya.
Saya banyak mendengar kisah-kisah keberpihakan dan kedermawanan Gus Dur selama berkomunitas. Soal keberpihakan, kita tak perlu meragukannya lagi. Gus Dur berdiri di sisi warga Kedungombo ketika ruang hidup mereka dirampas paksa oleh pemerintah Orde Baru. Gus Dur berdiri di sisi kelompok Ahmadiyah ketika mereka dituduh sesat dan dipersekusi oleh FPI dan sikap mayoritarianismenya. Bahkan, Gus Dur berdiri di sisi Inul ketika ia mendapat kecaman masif karena goyangannya yang dikutuk sekaligus dirayakan itu.
Soal kedermawanan, saya sering mendengar bahwa Gus Dur suka memberi amplop berisi uang kepada orang lain, tanpa menghitung nominal yang ada di dalamnya. Gus Dur memberi amplop kepada tukang duren di pinggir jalan yang membutuhkan uang untuk operasi anaknya, kepada orang-orang yang mendatangi di kantornya PBNU, kepada orang-orang terdekatnya yang membutuhkan, kepada siapa saja. Bahkan putrinya sering mengeluhkan bahwa bapaknya sering tidak punya uang meski memiliki jabatan tinggi.
Gus Dur memang sudah tiada. Tapi teladannya abadi. Ia hidup kembali di jiwa generasi setelahnya. Teladannya beranak pinak dan menyebar cepat seperti jamur di musim hujan. Semoga kita bisa terus meneladaninya. Semoga semua hal-hal baik panjang umur!















