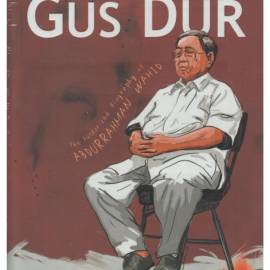Di dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ada etnisitas, ada kesukuan, ada golongan, ada mazhab keagamaan, ada pandangan politik, ada karakter, dan disiplin ilmu ulama yang berbeda-beda. Di dalam kedua organisasi itu, semuanya dirembug, dimusyawarahkan. Ada gesekan? Ya sudah pasti.
Tapi sudah jadi kepastian pula bahwa Indonesia yang berpulau-pulau dijahit di sana. Indonesia yang warna-warni dihargai di sana. Indonesia yang “sulit sekali” dimusyawarahkan di sana. Dengan apa mereka menjahit keindonesiaan? Dengan apa mereka menghargai keindonesiaan? Dengan apa mereka bermusyawarah tentang keindonesian yang sulit sekali itu?
Dengan agama, dengan ilmu keagamaan, karena Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan. Orang Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, Nusa Tenggara hingga Papua, berkumpul di oraganisasi keagamaan yang didirikan dua ulama seperguruan, Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Muhammad Hasyim Asy’ari.
Namun, mereka tidak egois. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, agama sendiri, kepentingan keaagamaannya masing-masing. Sebabnya jelas, di samping mereka orang Islam, orang NU atau Muhammadiyah, mereka juga orang Sumatra yang etnis, suku, dan karakter yang wajib diakui eksistensinya.
Orang NU dari Sumatra seperi Kiai Zainul Arifin tidak boleh menghormati Kiai Wahab dari sisi Islamnya saja atau NU-nya saja, tapi juga kejawaannya, dengan segala watak dan adatnya. Begitu juga Kiai Wahab yang dari Jawa, harus menghargai juniornya, bahwa Kiai Idham Chalid bukan saja dari NU atau Islamnya saja, tapi juga asal daerahnya, yakni menghargai segala aspek yang terkait Kalimantan.
Orang Muhammadiyah dari Jawa seperti Ki Bagus Hadi Kusumo tidak boleh menghargai Buya Hamka dari sisi keulamaan dan kepandaiannya saja, tapi juga kesumatraannya dengan segala adat dan sifatnya. Kiai Haji Mas Mansoer pun demikian, suka atau tidak suka harus menghormati aktivis Muhammadiyah yang latar sosio-kulturalnya yang berbeda-beda.
Keragaman dalam segala sudut pandang telah ada dalam satu wadah bernama NU dan Muhammadiyah. Dan itu terjadi sebelum Indonesia lahir, 17 Agustus 1945, sebelum ada sumpah pemuda, 28 Oktober 1928.
Itulah saya kira, modal mereka selanjutnya untuk bertemu, berkumpul bersama dengan sesepuh dan pendiri bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta dan lain sebagainya. Tidak terlalu sulit bagi Kiai Abd Wahid Hasyim dari NU dan Kiai Abdul Kahar Muzakkir (jangan keliru dengan Abdul Kahar Muzakkar dari Sulawesi Selatan yang DI/TII itu) dari Muhammadiyah memusyawarahkan hal yang memang dari sananya sudah berbeda.
Ya pasti dong, bisa kita memahami betul jika ada perbedaan, ada perseteruan, ada ego, tapi akhirnya mereka bersepakat menciptakan konsensus bersama dengan mengakui adanya semua perbedaan yang menempel lekat di tubuh masing-masing. Konsensus bersama itu bernama Pancasila.
Nah, bagi yang kemarin bingung kenapa demo anarkhis berhenti karena disebut NU, disebut Gus Dur, sekarang jangan bingung lagi. Sedikit narasi di atas semoga bisa dipahami. Di NU ada warga Papua, dulu Mbah Wahab cinta Papua, ada sejarahnya. Orang Papua yang di NU dan orang Jawa yang di NU bertemu, berbicara, berkomunikasi, saling memahami, saling mengerti, mendengar aspirasi dan seturusnya. Dari sinilah Gus Dur bersikap, dan turun pada gubernur Jawa Timur yang juga NU, Khofifah. Gus Dur dan Khofifah menjalankan amanat NU. NU menjalankan konsensus bersama, amanat bangsa. Jangan dikira berdiri sendiri.
Begitu pula saat orang Aceh yang dulu ingin merdeka. Muhammadiyah menjalin hubungan intensif dengan orang Aceh yang Muhammadiyah. Untuk informasi detailnya mungkin bisa didapat dari kawan-kawan Muhammadiyah. Muhammadiyah kuat di Aceh (Muktamar Muhammadiyah pernah di sana tahn 1995). Apa artinya? Muhammadiyah menjadi jangkar keindonesiaan di sana.
Nah, sekarang ada narasi begini, “Saya Islam saja, tidak Muhammadiyah, tidak NU. Islam itu satu jangan dipecah-pecah dengan kata sifat”. Sekelebat, narasi ini mulia, tapi sebetulnya dangkal, tidak lain bersumber pada ketidakmengertian.
“Ummatan wahidatan,” begitu tulisan dalam kaus oblong warna hitam, mengiringi telujuk jari yang berdiri. Ada yang salah?
Tidak ada yang salah, jika mereka tidak kampanye khilafah islamiyah. Tidak ada yang salah, jika mereka tidak mengibarkan bendera ISIS. Tidak ada yang salah jika mereka tidak berambisi menyeragamkan yang berbeda. Tidak ada yang salah, jika tidak bermimpi kebenaran milik sendiri. Tidak ada yang salah, jika mereka tidak menggap NU dan Muhammadiyah pengikut thogut. Tidak ada yang salah, jika mereka mengikuti konsensus bersama bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.