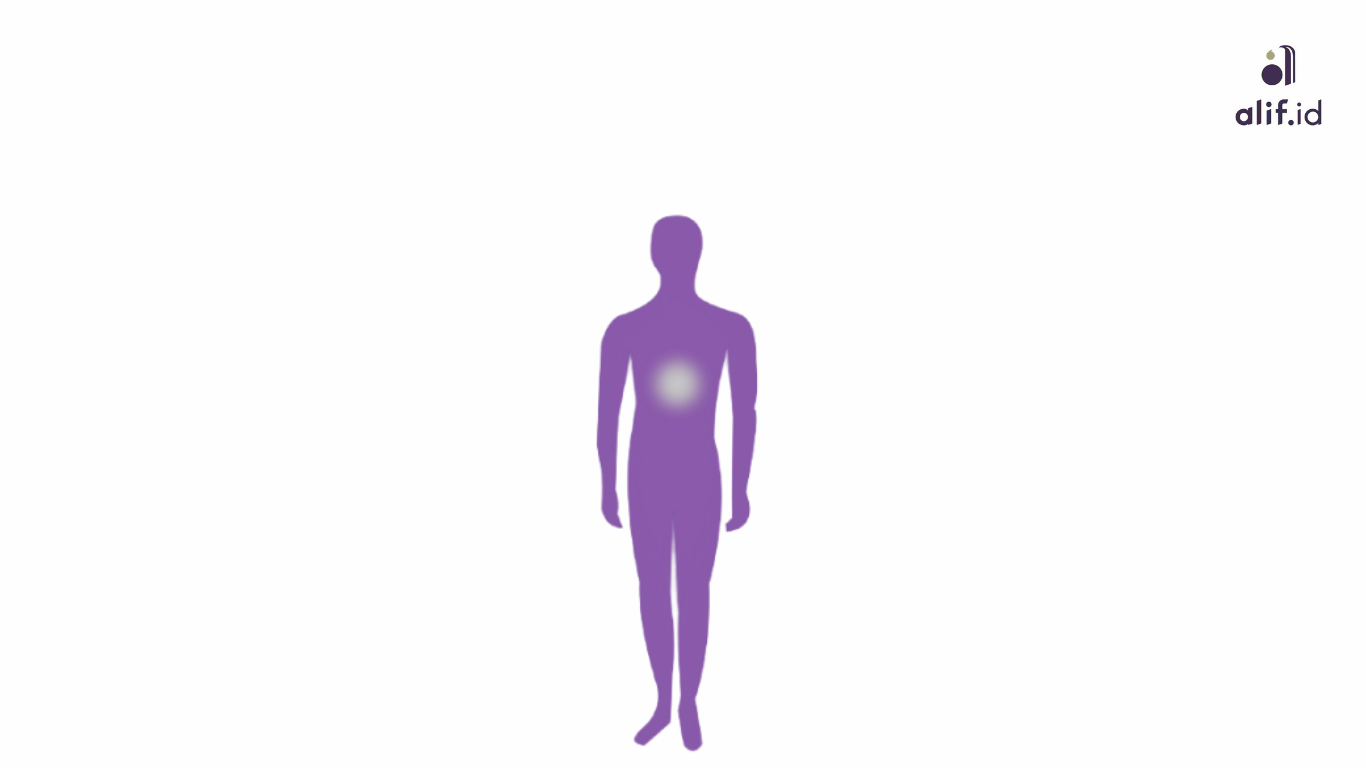
Diskursus tentang tubuh dalam sejarah filsafat kerap dikungkung oleh dikotomi metafisis: antara materi dan ruh, antara tubuh dan jiwa. Sejak Descartes, tradisi Barat mewariskan pandangan bahwa tubuh hanyalah objek diam yang dikendalikan oleh subyek berpikir. Dalam beberapa tradisi teologis, tubuh bahkan diposisikan sebagai rintangan menuju kesucian jiwa. Namun pemikiran dua filsuf besar—Mulla Sadra dari Islam dan Maurice Merleau-Ponty dari Barat—membalikkan asumsi tersebut. Keduanya menempatkan tubuh bukan sebagai penghalang, melainkan pusat pengalaman, kesadaran, bahkan spiritualitas itu sendiri.
Tubuh bukan sekadar pembungkus jiwa. Ia adalah jalan menuju pembentukan jiwa. Ia bukan fase awal yang harus ditinggalkan, melainkan metode eksistensial yang memungkinkan makna, memori, dan transformasi rohani terwujud. Sadra dan Merleau-Ponty sama-sama menolak reduksi tubuh sebagai benda; bagi mereka, tubuh adalah kondisi dari hadirnya dunia dan diri.
Mulla Sadra, melalui filsafat al-Hikmah al-Muta‘āliyah, menyatakan bahwa jiwa tidak mendahului tubuh. Jiwa lahir dari tubuh: an-nafs jismāniyyat al-ḥudūth wa rūḥāniyyat al-baqā’ — ia bersifat jasmani dalam kejadiannya dan ruhani dalam keberlangsungannya. Tubuh adalah titik tolak ontologis dari jiwa, bukan sekadar sarana, apalagi penjara. Dalam kerangka tashkīk al-wujūd (gradasi eksistensi), tubuh adalah panggung pertama tempat jiwa menginisiasi perjalanan menuju kesempurnaan spiritual. Artinya, kesempurnaan rohani tidak mungkin terjadi tanpa keberadaan tubuh.
Sementara itu, Maurice Merleau-Ponty, dalam Phenomenology of Perception, menyatakan bahwa tubuh bukanlah objek, melainkan subjek yang menghidupi dunia. Dengan konsep le corps propre—tubuh yang dihayati—ia menegaskan bahwa tubuh adalah titik orientasi kesadaran. “The body is not an object in the world, but our means of communication with it.” Tubuh bukan sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita ‘jadi’. Ia bukan alat, melainkan horizon: darinya dunia tampak, dan melaluinya makna dibentuk. Tubuh adalah logos praksis—penggerak yang mengartikulasikan dunia tanpa perlu selalu berpikir secara reflektif.
Sadra dan Merleau-Ponty sama-sama mengangkat tubuh dari status pasif menjadi agen eksistensial. Namun arah eksistensinya berbeda. Sadra melihat tubuh dalam garis waktu vertikal—dari materi menuju spiritualitas. Merleau-Ponty menempatkan tubuh dalam garis waktu horizontal—di sini dan kini. Sadra memandang tubuh sebagai awal yang akan ditransendensi, Merleau-Ponty menghayatinya sebagai kondisi permanen kesadaran.
Dalam struktur filsafat Sadra, tubuh adalah tempat jiwa berkembang secara bertahap: dari jiwa vegetatif, ke jiwa hewani, hingga jiwa insani. Melalui tubuh, pengalaman diindera, diolah, dan diinternalisasi menjadi pengetahuan. Akan tetapi, pada puncaknya, jiwa harus melepaskan keterikatannya pada tubuh—memasuki dimensi pengetahuan langsung (‘ilm ḥuḍūrī) yang tak lagi bersandar pada bentuk material. Di sinilah tubuh tetap penting, namun tidak final.
Berbeda dengan itu, Merleau-Ponty tidak pernah melepaskan tubuh dari struktur eksistensi. Baginya, tubuh bukan fase, tetapi fondasi. Konsep body schema menjelaskan bahwa tubuh memiliki kecerdasan pra-reflektif. Tubuh “tahu” bagaimana harus bergerak, bertindak, merespons. Seorang musisi tidak sekadar memainkan alat musik dengan pikirannya; tubuhnya menghidupi musik itu sendiri. Dalam dunia Merleau-Ponty, makna muncul dari gerak tubuh—dari kehadiran yang tak bisa direduksi pada pikiran semata.
Perbedaan mendasar muncul dalam pandangan tentang hubungan tubuh dan jiwa. Sadra menolak dualisme, tetapi tetap mempertahankan hierarki. Jiwa lahir dari tubuh, tumbuh bersamanya, namun akhirnya bisa eksis tanpanya—khususnya dalam realitas pasca-kematian. Di alam barzakh, jiwa mengalami eksistensi imaginal, dengan tubuh non-fisik yang terbentuk dari kesan-kesan batin. Di sini tubuh dan memori menyatu dalam lanskap spiritual.
Merleau-Ponty justru menghapus jarak antara tubuh dan jiwa. Ia menyatakan, “I am not in front of my body, I am in it—or rather I am it.” Jiwa bukan substansi yang mengamati tubuh, melainkan bentuk keberadaan yang meraga. Tubuh dan kesadaran adalah satu dan tak terpisahkan. Pikiran pun berakar dalam tubuh—dalam bahasa, gerak, dan arah pandang.
Memori menjadi titik penting dalam dialektika tubuh dan kesadaran. Bagi Sadra, memori bukan sekadar fungsi kognitif, melainkan bagian dari akumulasi spiritual. Memori menyimpan impresi fisik dan makna yang akan “diaktifkan” dalam kehidupan setelah kematian. Ingatan menjadi semacam blueprint eksistensial yang membentuk surga atau neraka batin.
Sementara itu, Merleau-Ponty memahami memori sebagai pengalaman yang hidup di tubuh. Ia membedakan antara habit memory dan recollective memory. Tubuh menyimpan kebiasaan secara non-verbal. Kita bisa mengendarai sepeda tanpa perlu mengingat langkah-langkahnya—karena tubuh “ingat”. Memori, bagi Merleau-Ponty, bukan gudang data, tetapi medan atmosferik yang menarik kita kembali ke horizon makna yang pernah kita alami.
Dalam konteks kekinian, perdebatan ini menjadi sangat relevan. Di era digital, tubuh kian terpisah dari kehadirannya. Sosial media mengubah tubuh menjadi citra yang dikurasi: bukan tubuh yang mengalami, tetapi tubuh yang dipertontonkan. Tubuh digital kita adalah topeng, bukan kesadaran. Baik Sadra maupun Merleau-Ponty akan mengkritik reduksi ini. Bagi Sadra, tubuh adalah arena spiritual yang sakral; bagi Merleau-Ponty, tubuh adalah jembatan menuju dunia. Ketika tubuh hanya menjadi avatar di dunia maya, yang hilang bukan hanya daging, tetapi juga makna eksistensial.
Begitu pula dalam bioetika modern: transplantasi, augmentasi tubuh, hingga integrasi dengan AI menantang batas pemahaman kita tentang tubuh. Sadra memberi peringatan: tubuh adalah jejak jiwa. Merleau-Ponty menambahkan: tubuh adalah cara kita berada di dunia. Perlakuan terhadap tubuh, karenanya, adalah perlakuan terhadap makna diri.
Pandemi COVID-19 memperjelas krisis ini. Kehadiran tubuh tergantikan oleh layar. Interaksi sosial, pendidikan, dan ibadah kehilangan kedalaman ragawi. Dalam perspektif Sadra, keterputusan tubuh dari komunitas adalah luka spiritual. Dalam pandangan Merleau-Ponty, kehadiran tanpa tubuh bukanlah kehadiran yang utuh. Tubuh bukan pelengkap, tetapi prasyarat makna.
Pada akhirnya, pembacaan terhadap Sadra dan Merleau-Ponty membawa kita pada satu kesadaran: tubuh adalah ruang tempat jiwa bertumbuh dan dunia terbentuk. Sadra melihat tubuh sebagai kawah penciptaan ruh; Merleau-Ponty sebagai horizon kesadaran. Sadra bergerak ke atas; Merleau-Ponty mengakar ke dalam. Tapi keduanya sepakat: tanpa tubuh, tidak ada kesadaran. Tanpa kebertubuhan, tidak ada makna.
Lalu, siapa aku? Apakah aku adalah tubuh ini?
Filsafat membawa kita pada ambang pertanyaan, tetapi tasawuf membawa kita melampauinya. Dalam tradisi sufi, diri sejati bukanlah tubuh, bukan pula pikiran yang berpikir tentang tubuh. Diri sejati adalah al-nafs al-muṭma’innah—jiwa yang tenang, yang telah melepaskan keterikatan dan kembali kepada Cahaya Ilahi. Imam al-Ghazali dalam Mishkat al-Anwar mengatakan bahwa hakikat manusia adalah ruh Ilahi, bagian dari cahaya yang ditiupkan Tuhan (QS. al-Hijr: 29). Dalam puncak eksistensial itu, tubuh bukan lagi batas, tetapi cermin. Cermin tempat Nama dan Sifat Allah terpantul.
“Yā ayyatuhā al-nafs al-muṭma’innah, irji‘ī ilā rabbiki rāḍiyatan marḍiyyah”
(QS. Al-Fajr: 27–28)















