
Di banyak belahan dunia Islam, kita akan disuguhi pemandangan yang berbeda-beda tentang –mari kita tulisan dengan sebutan yang sudah akrab– jilbab. Di Indonesia, Malaysia, Arab Suadi, Mesir, Sudan, Maroko, jilbab bukanlah sesuatu yang satu. Mungkin, Iran dan Afganistan, adalah kekecualian. Di dunia negara ini, jilbab tidak banyak “variasi”. Apa artinya?
Artinya, para yuris Islam, fukaha, berbeda pendapat tentang jilbab. Di Indonesia, jelas kita menyaksikan perbedaan pandangan, secara implisit, dengan banyaknya anak tokoh atau tokoh Islam tidak berjilbab, atau berjilbab dan “setengah-setengah”, juga banyak sekali perumpuan muslim yang begitu rapat berjilbab.
Secara eksplisit, shoreh, juga begitu: sebagian mewajibkan, sebagian tidak. Gus Baha kita tahu mewajibkan. Sementara Prof. Quraish Shihab, ulama senior dan salah satu ulama yang mempromosikan Gus Baha, tampaknya tidak mewajibkan. Kita bisa menyaksikan pendapat Pak Quraish, baik secara eksplisit atau implisit.
Ibu Nyai Abdurrahman Wahid atau Ibu Nyai Shinta Nuriyah, baru-baru ini mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. Bagi yang terbiasa dengan dunia fikih, tentu saja ini tidak mengagetkan. Namun, bagi Felix Siauw, pernyataan Ibu Nuriah sudah cukup untuk “digoreng” sampai gosong.
Nah, pada kesempatan yang pendek ini, saya sedikit nimbrung, dengan menyampaikan pendapat seorang ulama kontemporer asal Tunisia. Mari pelan-pelan kita bahas.
Makna jilbab dan kerudung sendiri saya artikan secara bahasa Indonesia, yakni kain penutup rambut kepala dan leher.
Beberapa kalangan meyakini jilbab tidak wajib. Dalam arti mereka meyakini bahwa rambut kepala tidaklah wajib ditutupi. Dalam khazanah fikih klasik ditemukan bahwa menutup kepala adalah kewajiban bagi wanita muslim yang merdeka berdasarkan beberapa ayat Al-Quran.
Namun ada beberapa sudut pandang dan perspektif dari para ulama kontemporer yang yu’taddu biqaulihim, alias ucapannya bisa dijadikan pegangan. Di antaranya adalah Ibnu Asyur.
Selintas tentang Ibnu Asyur. Beliau adalah seorang ulama bermazhab Maliki, lahir di Tunis. Beliau juga keturunan klan Adarisah yang secara otomatis membuat beliau tergolong sebagai “sayyid “, alias keturunan Nabi saw. Selain diakui di dunia keilmuan Islam sebagai pakar “Maqasid Syariah”, beliau adalah seorang mufasir. Tafsirnya berjudul Tahrir wa Tanwir terdiri dari 30 jilid. Jumlah yang mengagumkan. Beliau menjamin bahwa tafsir itu adalah tafsir orisinil yang tidak memperbanyak menukil ulama-ulama sebelumnya. Beliau meninggal pada tahun 1393 H.
Ulama hebat ini punya pandangan menarik soal menutup aurat. Dia menulis dalam bukunya Maqashid Syariah Islamiyah bahwa syariat Islam itu universal. Karena universal, tidak mungkin syariat memaksakan nilai satu bangsa tertentu kepada bangsa yang lain. Karena pemaksaan nilai kaum tertentu bertentangan dengan kodrat bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Jika budaya satu kaum adalah syariat, tentu Islam tidak bisa universal kepada seluruh alam, kira-kira begitu.
Selain universal, syariat Islam adalah ajaran yang selalu berorientasi maslahat dan menolak mafsadat. Ibn Asyur memandang hal ini sebagai keniscayaan.
“Maka memaksakan budaya suatu bangsa untuk menjadi syariat adalah kemusykilan yang besar,” tulis Ibnu Asyur. Beliau memberi contoh larangan menyambung rambut dalam hadis Ibnu Mas’ud yang masyhur: “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut .. dst.”
Larangan ini menurut beliau “sulit dicerna akal”, karena tidak ada mafsadat sama sekali dalam menyambung rambut. Jika larangan ini adalah syariat, maka di mana posisi syariat sebagai aturan yang anti-mafsadat?
Beliau menulis tentang larangan menyambung rambut:
ووجهه عندي الذي لم أر من أفصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أماراتٍ على ضعف حصانة المرأة ، فالنهي عنها نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك العرض بسببها
“Hal ini menurut saya—pendapat ini tampaknya belum ada yang mengungkapkan sebelumnya—bahwa hal-hal itu di masa Jahiliyah dulu adalah tanda-tanda wanita tidak terjaga. Maka larangan melakukan hal itu adalah wujud melarang melakukan hal yang bisa membangkitkan adat Jahiliyah atau larangan untuk menghilangkan wibawa sebab melakukannya.”
Nah, bagaimana soal jilbāb? Ibn Asyur mengatakan bahwa jilbab adalah adat Arab. Maka, sebagaimana sudah beliau jelaskan sebelumnya, tidak mungkin Syariat Islam menjadikan adat suatu kaum sebagai syariat karena syariat itu universal, tidak untuk kaum-kaum tertentu. Beliau menulis mengomentari Al-Ahzab ayat 59:
فهذا شرع روعيت فيه عادة العرب ، فالأقوام الذين لا يتخذون الجلابيب لا ينالهم من هذا التشريع نصيب
“Ini (jilbab) adalah adat orang Arab. (Jika memang wajib), maka bangsa yang tidak biasa menggunakan jilbab tidak mendapat bagian-bagian apa dari syariat.”
Tentu menjadikan jilbab sebagai syariat adalah wujud memaksakan adat. Hal ini bertentangan dengan syariat itu sendiri. Karena, sebagaimana beliau ulang-ulang, syariat itu universal. Tidak mungkin menjadikan jilbab yang notabene adat orang Arab sebagai syariat yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia. Tentu ada nilai (bahasa beliau: hikam wa ma’ani) di balik ayat jilbab itu.. Nilai ini adalah nilai yang bermacam bentuknya tergantung suku-bangsa namun tunggal maksudnya. Beliau menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini:
فتعين أن تكون معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون أحكامها كليات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح ، صالحة لأن تتفرع منها أحكام مختلفة الصور متحدة المعنى
“Maka tentulah yang dimaksud bahwa syariat Islam itu kompatibel di tiap masa adalah hukum-hukumnya harus universal dan memliki alasan yang mengandung hikmah dan maslahat, serta pantas untuk menelurkan aturan-aturan yang berbagai macam bentuk namun tetap satu tujuan.”
Begitu juga soal jilbab. Tentu ada satu tujuan di balik syariat ini. Barangkali tujuannya adalah: “yang penting berpakaian sopan”. Wallahu a’lam.












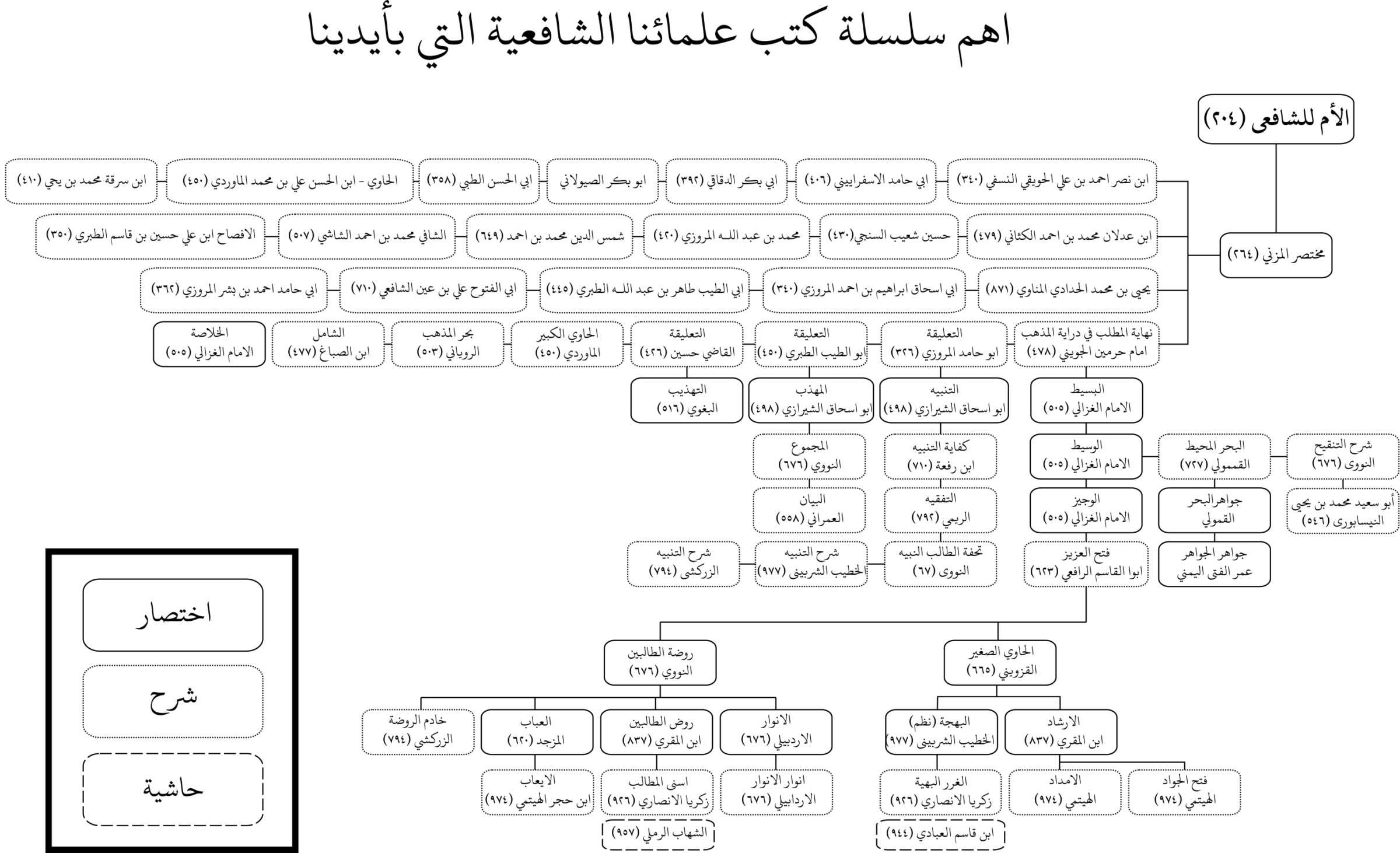








Woww perspektif yang berbeda, cukup mengejutkan. Saya mau bagi bagi wawasan pula https://jejakislam.net/perjuangan-panjang-jilbab-diindonesia/ monggo bisa dibaca dengan perspektif yang berbeda pula. Semakin banyak referensi yang kita ketahui semakin bijak lah kita dalam memutuskan. Terima kasih gus, keren tulisanya