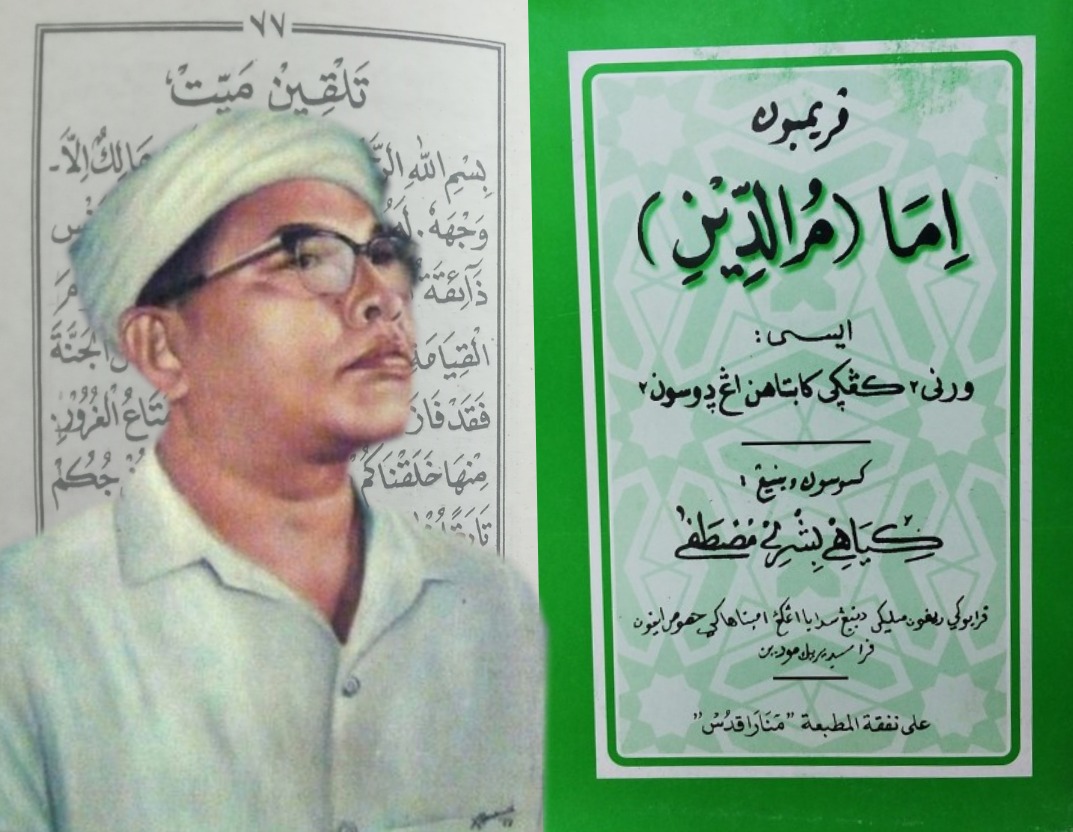Prof. Nurcholis Madjid atau akrab disapa Cak Nur merupakan sosok cendekiawan muslim Indonesia yang sangat arif dan bersahaja namun katalog pemikiran dan praksisnya begitu sangat komplit. Jika meminjam istilah dari kiai Ulil Abshar Abdalla atau akrab disapa Pak Lurah Pondok, Cak Nur merupakan sosok “manusia hibrid” karena beliau terlahir dari kalangan keluarga Nahdlatul Ulama –buah pasangan dari KH. Abdul Madjid dan Ibu Fatonah– namun corak pendidikan dan pemikirannya –serta corak politiknya– begitu sangat modernis.
Hal ini ditandai dengan benih-benih pendidikan yang pernah beliau semai, mulai dari nyantri di Pesantren Darul Ulum Rejoso – Jombang pada tahun 1955, kemudian pada tahun 1960 jenjang pendidikannya dilanjutkan di Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo yang merupakan embrio dari lahirnya berbagai jenis pesantren modern di Indonesia, hingga menuntaskan pendidikan doktoralnya di University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1984.
Maka menjadi wajar jika Cak Nur begitu sangat progresif dalam membangun berbagai “piramida” wacana dan gagasan yang kemudian menuai berbagai respons –baik pro maupun kontra– dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia, utamanya gagasan “piramida” pembaharuan Islam dan sekulerisasinya yang sempat viral dan menghebohkan publik Indonesia pada dekade 70an.
Pada medio 1980an atau tepatnya pada tahun 1985, Cak Nur yang genap berusia 46 tahun kembali ke tanah air setelah enam setengah tahun lamanya dirinya “boyong” ke negeri “Mbah Sam” untuk menuntaskan pendidikan doktoralnya di University of Chicago, Amerika Serikat dalam bidang Ilmu Kalam atau Filsafat Islam dengan disertasinya tentang filsafat dan kalam Ibnu Taimiyah (1984). Enam setengah tahun absen dari gelanggang pemikiran di Indonesia membuat Prof. Azyumardi Azra yang kala itu masih tercatat sebagai redaktur pelaksana Panjimas berkeinginan untuk mewawancarai sosok mercusuar pembaharuan Indonesia tersebut.
Pekan pertama Desember 1985 Prof. Azyumardi Azra pun bertandang ke kediaman Cak Nur di bilangan Tanah Kusir, Jakarta Selatan dan kedatangannya pun disambut dengan hangat oleh Cak Nur serta Ibu Omi Komariah Madjid yang kala itu masih tercatat sebagai Mahasiswi di IKIP Muhammadiyah Jakarta, serta dua orang anaknya yaitu Nadia Madjid yang baru genap berusia 15 tahun, serta Ahmad Mikail yang kala itu masih berusia 11 tahun.
Setelah enam setengah tahun absen dari gelanggang pemikiran di Indonesia, kira-kira apakah Cak Nur masih konsisten dalam membuat “piramida” wacana dan gagasan seperti halnya gagasan “piramida” pembaharuan Islam serta sekulerisasinya yang pernah beliau bangun sebelum dirinya ngangsu kaweruh di kawah candradimuka University of Chicago? Lalu bagaimana pandangan Cak Nur tentang Asas Tunggal dalam UU Keormasan yang telah disahkan dan diundangkan per tanggal 31 Mei 1985? Bagaimana juga tanggapan beliau tentang gagasan pembaharuannya, apakah masih sama atau sudah berubah? Serta bagaimana pula tanggapan mantan Ketua Umum PB HMI dua periode tersebut (1966-1969 dan 1969-1971) tentang sekulerisasi utamanya dalam tubuh umat Islam?
Berikut saya tuliskan kembali hasil wawancara dari Prof. Azyumardi Azra yang pernah dimuat oleh Panjimas No.488 – Tahun XXVII 28 Rabiul Awal 1406 H atau 11 Desember 1985, dan berikut petikan wawancaranya:
Telah tiga dasawarsa bangsa kita membangun, tetapi masih banyak masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Cak Nur, masalah-masalah besar apa saja yang dihadapi bangsa kita dewasa ini?
Pertama kali, saya kira secara sportif apapun segi kekurangannya, apapun segi kelemahannya, tetapi kehidupan rakyat setelah pembangunan harus dilihat dulu agar bisa membuat proyeksi yang obyektif. Pembangunan selain menigkatkan taraf hidup, jelas sekarang orang lebih mudah mendapatkan sandang, pangan dan papan walaupun yang terahir ini masih luks. Nah, maksud saya, masalah kepincangan anatara si kaya dan si miskin; dulu ada, tetapi memang karena miskin, kesenjangan itu tak kentara. Namun sekarang karena lebih kaya, maka kesenjangan itu masih terasa, dan itu kelemahan yang sangat menyolok, dari pembangunan kita. Secara menyeluruh masyarakat telah merasakan hasil-hasil pembangunan. Kalau saya pulang kampung ke Jombang; semua rakyat punya nada bersyukur, walaupun berbarengan dengan itu mereka juga mengeluh, misalnya tentang padi yang masih suit dijual dan sebagainya.
Tetapi lebih penting lagi, pembangunan selain meningkatkan taraf hidup rakyat secara meteril, juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, sehingga terjadi peningkatan pendidikan yang menyeluruh. Sekarang jika sebuah desa punya mahasiswa, bukan hal yang aneh. Dan, yang bisa mengirimkan anak-anaknya ke universitas tidak lagi terbatas seperti zaman-zaman dulu. Dengan kata lain, pembangunan ini telah membawa kepada peningkatan-peningkatan level kecerdasan umum. Jadi terang rakyat Indonesia yang makin cerdas meskipun dengan sedih kita misalnya membaca bahwa sumbangan ilmiah Indonesia kepada dunia masih rendah sekali, hingga sampai kalah dari Ethiopia. Betapapun, kecerdasan rakyat kita makin tinggi.
Meningkatkan kecerdasan rakyat yang diiringi dengan kenaikan pendapatan ekonomi akan melahirkan berbagai implikasi, antara lain, tuntutan politik yang lebih tinggi. Jadi, peningkatan kecerdasan itu akan membawa pula pada peningkatan kesadaran politik. Dan peningkatan kesadaran politik itu juga mengakibatkan tuntutan politik atau poitical demand. Misal, rakyat Indonesia secara keseluruhan telah mulai berbicara demokrasi, tentang keadilan sosial. Untungnya gitu, tapi sekaligus juga celakanya, itu semua termuat dalam Pancasila. Celakanya, itu berarti Pancasila belum terlaksana.
Dengan kata lain, saya kira persoalan kita sekarang adalah pelaksanaan Pancasila itu sendiri; mana perikemanusiannya, mana kerakyatannya, mana keadilan sosialnya. Kalau sila yang dua, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Persatuan Indonesia sudah mendapat pendukung yang paling militan. Ketuhanan oleh kaum beragama, dan persatuan oleh ABRI dengan penggunaan istilah-istilah security, kesatuan bangsa dan sebagainya. Jadi, kedua sila ini telah terlaksana dengan baik, walaupun masih perlu ditingkatkan. Misal soal ketuhanan, tentu saja orang bisa berbeda-beda. Ada orang berpendapat, bahwa ketuhanan telah kuat jika masjid telah banyak. Walaupun bukan itu persoalan yang sebenarnya, namun sekurang-kurangnya, sila pertama itu telah menemukan momentumnya, inner dinamic-nya, dinamika intinya.
Demikian juga Persatuan Indonesia. Tetapi sila peri kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, masih perlu pendukung-pendukung, dan kita tahu pendukung-pendukung itu muncul dari rakyat, karena rakyat semakin mampu.
Mobilitas horizontal rakyat kelihatan sekali. Kendaraan apa saja ke kota penuh sesak oleh orang-orang. Untuk saya, yang absen selama enam setengah tahun, perkembangan itu sangat menyolok. Di dalam mobilitas horizontal ini implisit mobilitas vertikal, sebab misalnya orang pedalaman di Cianjur kini dapat pergi ke Bogor atau Jakarta karena kemampuan ekonomi. Perjalanan seperti ini, selain dianjurkan oleh al-Quran, jelas meningkatkan kualitas manusia. Jadi implisit di sini kemampuan atau kualitas. Itu juga akan meningkatkan taraf tuntutan politik.
Gampangnya begini; orang pedalaman Cianjur tadi ketika mulai perjalanan tidak mempunyai tuntutan apa-apa, tetapi begitu melihat apa-apa di perjalanan, maka ia akan mempunyai gambaran apa-apa yang ideal baginya. Jelas pada mulanya material, kemudian konsumerisme. Ini sebuah proses.