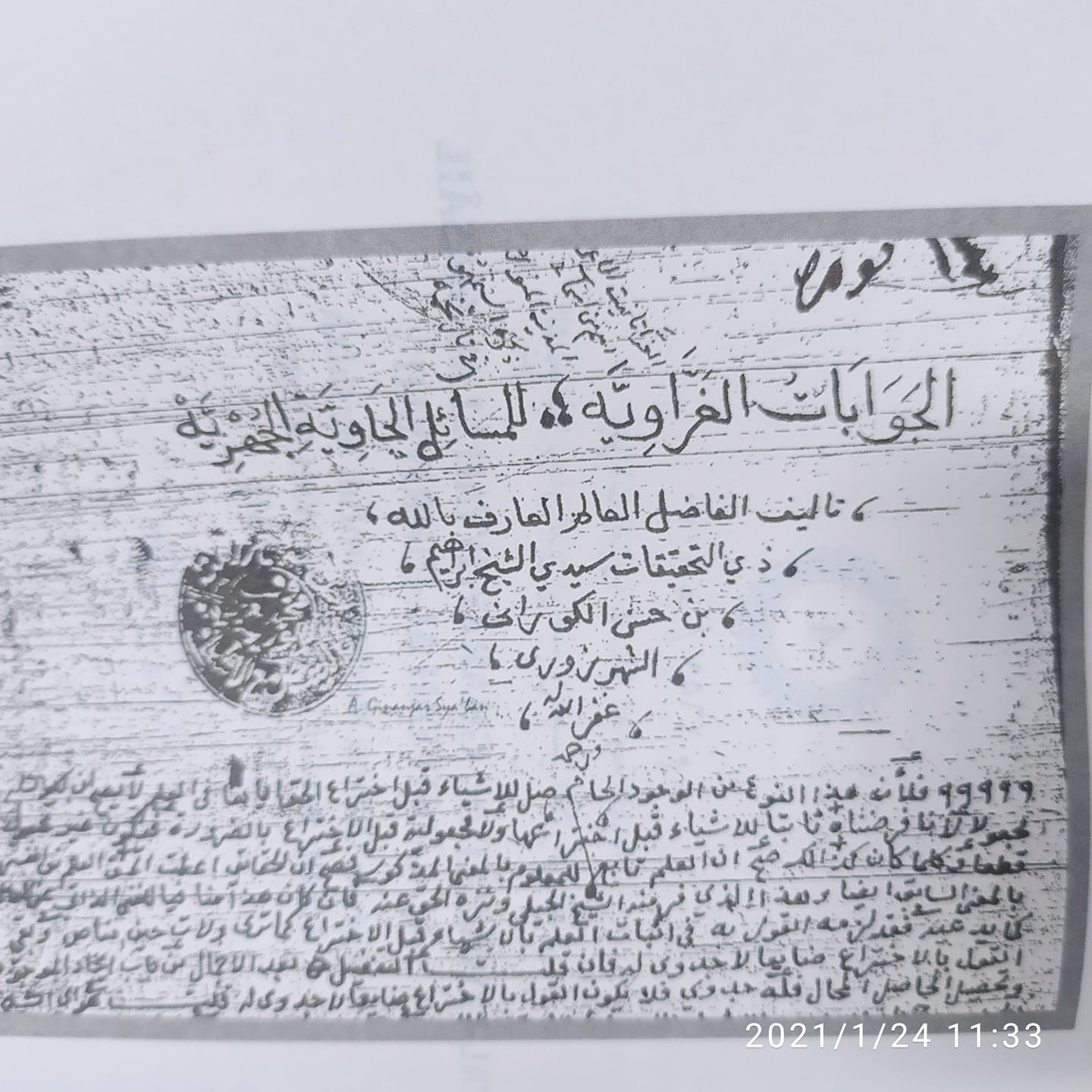
Sejak dekade awal abad ke-19 lalu, orang Nusantara mengenal Serat Centhini, suatu dokumen gaib yang dinilai sebagai karya sastra adihulung dari Keraton Surakarta (Solo). Buku itu menjadi pegangan wajib bagi para muslim Jawa, yang kemudian dianggap keramat, bahkan lebih nyaring suaranya ketimbang Alquran dan hadis-hadis Nabi. Saat itu, cetakan Alquran memang masih sangat terbatas, ditambah peran politik kolonialisme Belanda (Eropa), yang membuat kitab suci belum menjangkau relung-relung rumah-tangga masyarakat Jawa.
Tertulis dalam kitab Centhini perihal hukum-hukum menikah, memperlakukan jenazah, membangun rumah, cara menebang pohon jati, hingga tata-cara membuat dan merawat keris. Segala hal yang menyangkut kebiasaan sehari-hari orang Jawa terhimpun dalam kitab itu. Bahkan, pada hal-hal yang bersifat mitos dan takhayul sekalipun. Karena itu, tidak jarang kiai atau ulama yang menilai kitab tersebut tak termasuk dalam kategori sunnah, meskipun di dalamnya banyak kutipan hadis Nabi, fiqih, tasawuf, yang disesuaikan dengan kultur Jawa pada masa itu.
Pada akhir abad ke-19 muncullah tarekat “Haddadiyah” yang mengacu dari ajaran Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad. Ia mengklaim bahwa Serat Centhini tak bisa dikatakan sunnah, karena tidak mengacu dari hadis-hadis shahih Bukhari sebagai kutub sittah, yang dinilai sebagai kitab paling utama. Gerakan reformis dari tarekat itu berusaha membangun suatu misi tentang kemurnian ajaran Islam, hingga mengklaim tradisi lokal sebagai bukan bagian dari Islam yang sejati.
Muncullah pemisahan antara ajaran Islam dengan ajaran kebatinan Jawa. Meskipun, kebatinan Jawa yang berasas “Islam Keraton” itu masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai sunnah yang merupakan hasil perkawinan dengan kearifan lokal (partikular). Wacana terus menggelinding dan bermuara pada “Islam Nusantara” yang sangat terpaku pada tradisi pesantren, tradisi habaib, khususnya dari tarekat Haddadiyah. Terkait dengan ini, kompleksitas kultur Jawa dan Bugis tentu berbeda dengan pesisir pantai utara Jawa Barat, Cirebon, Cilegon dan Banten, yang mudah mengadopsi budaya dan peradaban Islam yang dibawa para pedagang Arab (baca: Perasaan Orang Banten).
Kemudian, datanglah generasi Habib Luthfi bin Yahya yang mencoba membangun kultur jamaah, dengan menggabungkan tradisi Islam Jawa, baik tarekat Haddadiyah, Naqsyabandiyah, termasuk tradisi Keraton Jawa. Sampai kemudian, terbentuk komunitas baru yang bisa diterima oleh mayoritas muslim Jawa dan Indonesia. Namun menurutnya, perjuangan ini tidak mudah, dan tak mungkin bisa diterima semua pihak. Proses membangun komunitas (jamaah) bukanlah pekerjaan instan dan sesaat. “Yang penting, kita menawarkan konsep pemikiran agar masyarakat ber-Islam dengan baik, dan upaya ini harus betul-betul ditekuni dan diperjuangkan terus-menerus,” tegas Habib Luthfi.
Menurut beliau, sunnah itu tidak mesti dipelajari dari buku dan kitab-kitab, tapi juga bisa dari kehidupan nyata sehari-hari yang kita jalani. Itulah yang disebut sunnah kontekstual, yang hidup dan mewujud, bukan semata-mata sunnah tekstual dan lateral.
Praktek sunnah untuk membangun otoritas religius semacam itu, seringkali didapatkan dari komunitas para sufi. Bagi mereka, sunnah dapat hidup dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kultur jamaahnya. Setiap figur mursyid bisa mengajarkan sunnah partikular yang dibutuhkan setiap muridnya. Kita bisa memberi satu murid preskripsi yang berbeda dengan murid lainnya. Bahkan, itulah yang dicontohkan Rasulullah yang juga mengajarkan hal-hal berbeda sesuai dengan kualitas kecerdasan masyarakatnya.
Tradisi pesantren
Karena Islam bersifat khas dan partikular tadi, maka bentuk-bentuk otoritas religius juga berbeda-beda. Ada seorang ahli fiqih, ada figur muhaddist, mursyid hingga wali, dan lain-lain. Mereka bertugas menghubungkan kita dengan masa lalu kerasulan. Semua yang kita sebut sebagai otoritas religius adalah konektor, orang-orang yang melakukan pekerjaan mengoneksikan masyarakat dengan masa lalu kenabian.
Jadi, tidak relevan lagi menuduh “ortodoks” kepada komunitas lain, karena setiap jamaah akan menganggap dirinya yang paling benar, dan paling sesuai dengan sunnah Rasul. Mereka saling berkompetisi dengan komunitas lain yang juga menganggap dirinya paling ahlussunnah waljama’ah.
Inilah yang dilakukan K.H. Eeng Nurhaeni (Kiai Eeng) dalam buku “Revolusi Pesantren di Banten”. Kiai Eeng adalah murid dari K.H. Rifai Arief, pendiri pondok pesantren Daarul Qolam (Rumah Pena) di daerah Tangerang, Banten. “Bagi saya, perbedaan pendapat itu terjadi sejak awal mula kelahiran Islam. Hal itu bukanlah sesuatu yang perlu kita risaukan. Justru menurut saya, dengan adanya perbedaan itu akan muncul semangat kompetisi antar jamaah yang menjadikan Islam terus berkembang pesat. Untuk itu, kita perlu membabat alas di tempat lain, membangun pesantren di tempat-tempat lain, sehingga akan terus bermunculan komunitas Islam di mana-mana,” tandas Kiai Eeng.
Konsep pemikiran itulah yang menggerakkan K.H. Eeng Nurhaeni mendirikan pesantren Al-Bayan (Rangkasbitung), Al-Fatihah (Pandeglang), Daar El-Kalam (Lebak), An-Nida (Bogor), Alfiya (Tangerang), Lan Tabur (Serang) hingga Al-Karomah Aidarusi (Riau). Dengan lahirnya pesantren dan komunitas-komunitas itu, maka perkembangan pendidikan Islam menjadi dinamis, hingga memunculkan dinamika perdebatan, argumentasi, yang memekarkan rahmat ilahiah di mana-mana.
Orang tua yang merasa kurang cocok untuk menyekolahkan anaknya ke suatu pesantren tertentu, ia bisa memilih pesantren lain sesuai dengan karakterisktik pengasuh maupun kiainya. Setiap komunitas pesantren memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan itu hal yang lumrah dalam setiap lembaga pendidikan Islam. Adakalanya pemimpin pesantren memiliki kredibilitas intelektual, baik secara tradisional maupun modern. Tapi tidak jarang, kiai atau ustad yang tak memiliki kapasitas keilmuwan namun sanggup membangun pesantren basar dan mengasuh ribuan santri.
Jadi, seseorang mungkin saja mengikuti seorang guru karena melihat kemampuan ilmunya yang tinggi, tapi kadang sang kiai hanya punya kemampuan berkisah dan bercerita dalam sistem pengajarannya, yang dinilai cukup memikat di hati publik.
Warna-warni tarekat
Apabila dilihat dari sisi sosiologis, terkadang informasi tentang masa lalu kerasulan yang disampaikan oleh mereka yang ahli bercerita mudah terealisasi ketimbang hadis-hadis yang dibawakan oleh para ahli hadits. Salah satu contohnya, tarekat Baktesyiah yang didirikan oleh Baktesy Wali. Dia sebenarnya tak memliki kapasitas sebagai tokoh agama yang mumpuni, dan otoritas keilmuwannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, dia tak bisa baca-tulis Alquran. Tapi, sampai berabad-abad kemudian pengaruhnya masih tetap ada, dan tarekatnya kebanyakan diikuti para petani di wilayah Anatolia.
Baktesy Wali menggabungkan ajaran Islam, Kristen dan berbagai-macam kultur lokal. Tarekat ini pernah mengalami kejayaannya di masa kekhalifahan Utsmaniyah, sampai akhirnya dinyatakan terlarang. Namun kemudian, para penganutnya terus berkembang dan menyebar ke wilayah Albania.
Banyak jamaah tarekat yang tak memiliki legitimasi dan didirikan oleh “tokoh agama” selevel Baktesy Wali ini. Bahkan, tidak sedikit yang kemudian mengidentifikasi sebagai bukan muslim maupun kristen lagi, misalnya kaum Yazidi di Kurdistan. Mereka membentuk aliran dan sekte tersendiri, sebagaimana Lia Aminudin (Lia Eden) di Jakarta, yang pengikutnya banyak dari kalangan aktivis kemanusiaan, seniman, akademisi hingga doktor dan profesor sekalipun.
Ini menunjukkan, bahwa setiap jamaah mempunyai standarnya sendiri-sendiri. Tidak sedikit jamaah yang standarnya bukan verifikasi keilmuan lagi, melainkan kedigdayaan, seperti ilmu kebal, kedut, debus atau ilmu kanuragan lainnya.
Jadi, otoritas keagamaan tidak mesti bersandar pada kemampuan intelektual, tapi soal keuletan dan ketekunan dalam membangun dan merawat jamaahnya. Banyak pengasuh pesantren, kiai dan para habaib, yang kebanyakan figur-figur yang ulet membangun komunitas dengan cara mengajar ngaji, menghimpun dana, membangun majlis ta’lim, mengadakan kajian-kajian ilmiah tentang keislaman dan seterusnya.
Pada prinsipnya, seorang pembangun otoritas keagamaan mau berkecimpung, membantu, melayani dan mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Mereka bermaslahat di tengah mereka, serta berupaya memberi solusi atas kesulitan yang mereka hadapi. Para pemuka agama maupun pemimpin pesantren yang memiliki jamaah besar, itu bukan hal yang tiba-tiba jadi, tapi betul-betul didirikan, dipelihara, dan dirawat dengan baik dari waktu ke waktu.
Seseorang bisa saja menjadi alim sebagai ahli ibadah, dan memiliki kapasitas inteketual memadai. Tapi, bila tak sanggup merawat jamaahnya dengan tekun, lalu tak ada murid dan anak-anak yang serius menjalankan tugasnya setelah beliau wafat, tidak menutup kemungkinan jamaah itu akan habis dan menghilang dengan sendirinya. (*)















