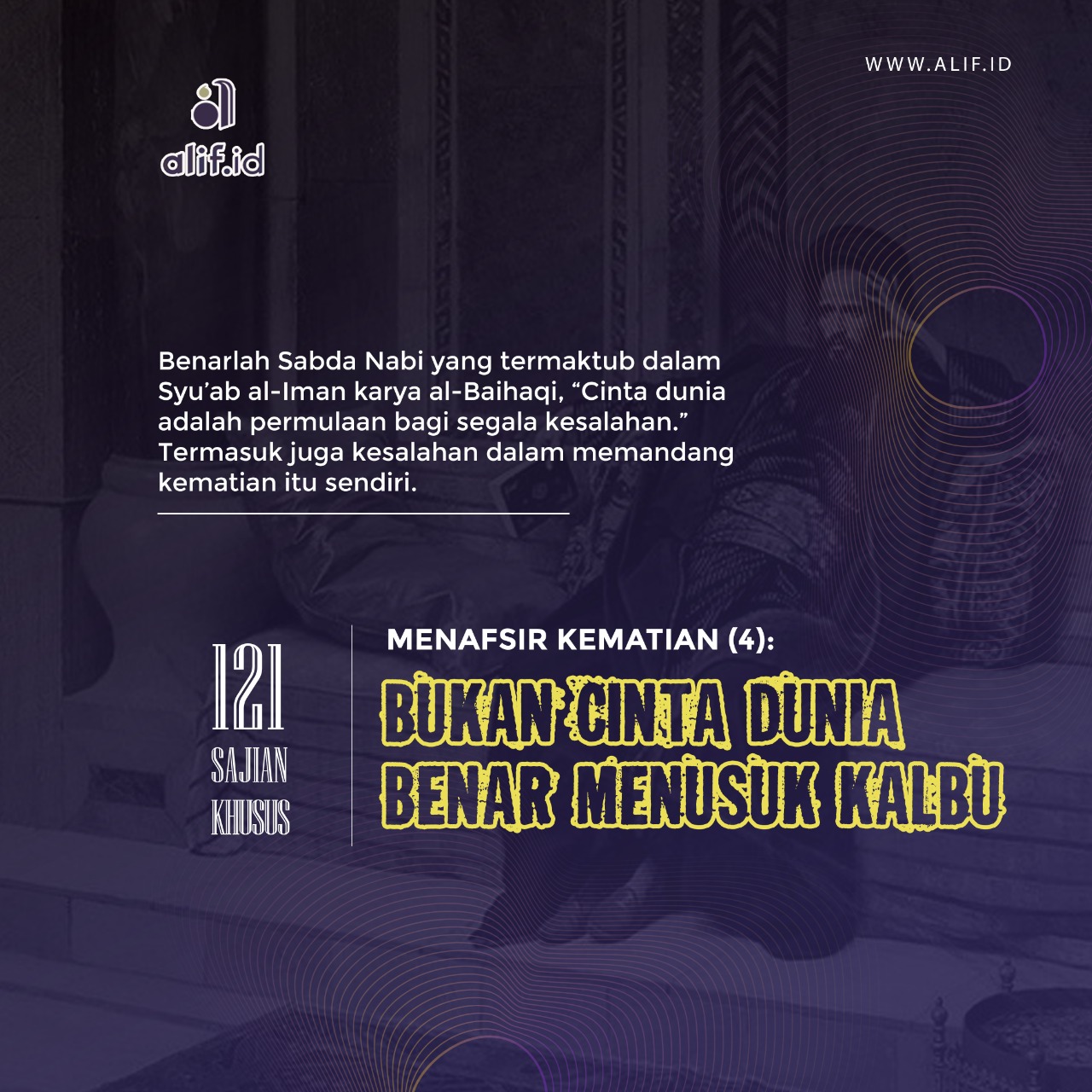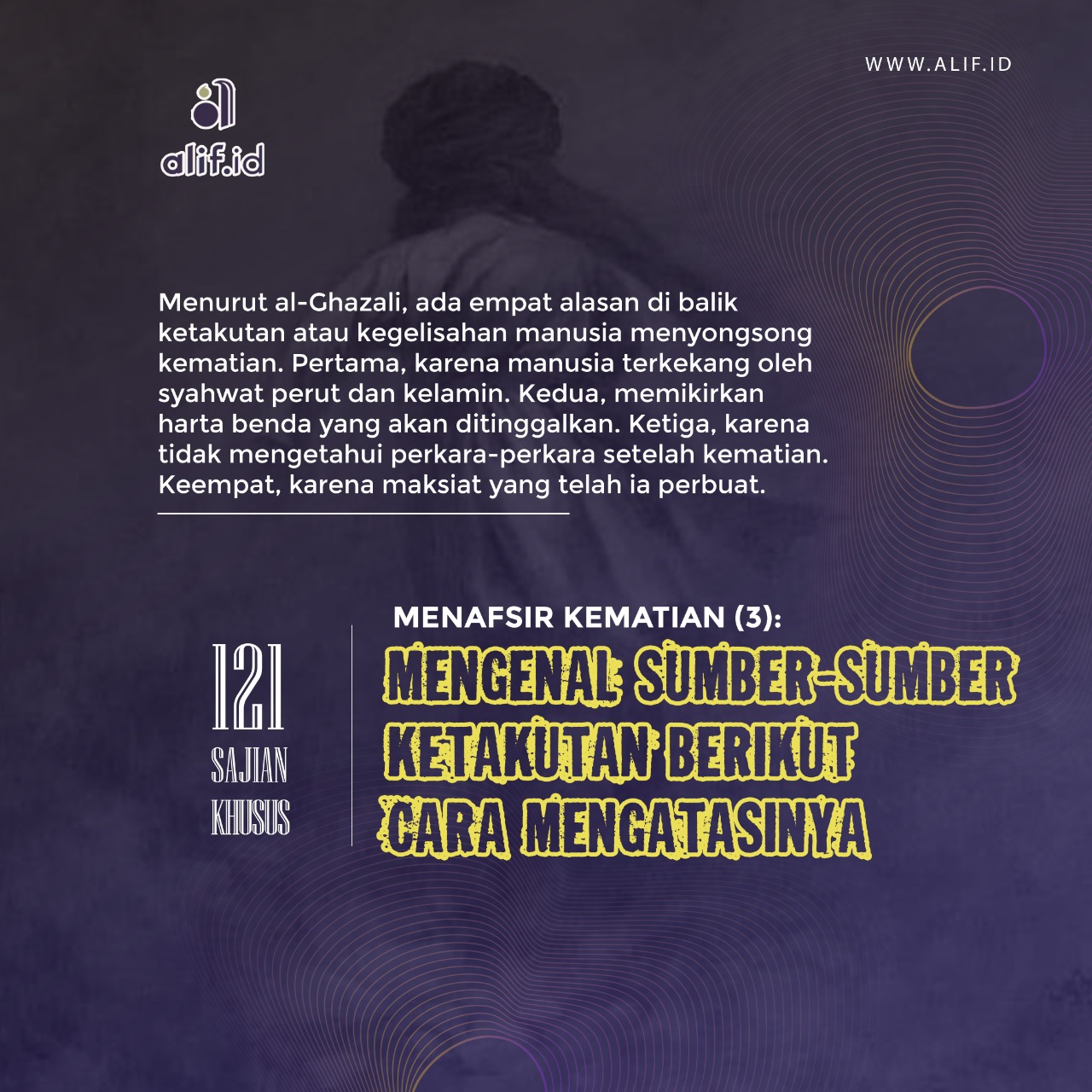W. Santrock dalam Life Span Development, menyatakan bahwa kini tiga puluh enam negara dan District of Colombia telah mengadopsi undang-undang yang melegitimasi berhentinya fungsi otak sebagai standar penentu kematian. Menurut standar ini, orang yang otaknya sudah tak berfungsi, kendati mungkin masih bisa bernafas atau bergerak, telah absah disebut almarhum.
Barangkali pandangan ini agak mengagetkan memang. Tetapi, mendahului informasi tadi, tradisi pesantren telah mengintroduksi santri dengan pandangan yang mirip dengan pandangan medis tersebut. Ketika masih nyantri di Pondok Pesatren Al-Amien Prenduan, misalnya, guru-guru kami punya cara unik untuk memantik semangat belajar para santri. Ketika melihat kami malas-malasan, seringkali di antara mereka menyindir kami dengan senandung syair Diwan al-Syafi’i yang fenomenal itu. “Siapa yang melewatkan kesempatan belajar di masa mudanya, angkatlah empat takbir atas kematiannya.” Menurut syair ini, pemuda yang malas belajar sudah saatnya ‘diwisuda’, kemudian diberi titel almarhum.
Mengapa kematian identik dengan aktivitas otak yang sebagian di antaranya berdimensi intelektual?
Saya ingin masuk dari konsep kalbu manusia. Al-Ghazali dalam Ihya ‘Ulum al-Din, menyebut atau lebih tepatnya mengibaratkan kalbu ini sebagai raja. Yakni otoritas tertinggi dalam tubuh manusia yang diumpamakan sebagai kerajaan. Laiknya raja betulan, kalbu pun memiliki serdadu, yaitu anggota badan kita yang tampak ini. Pun laiknya serdadu, ia harus tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap rajanya. “Semua anggota tubuh –terang al-Ghazali–“memang didesain untuk tunduk dan patuh terhadap kehendak kalbu, sang raja.”.
Dengan demikian, tak ada satupun anggota tubuh yang sanggup menyimpang atau keluar dari kehendak kalbu. Ketika kalbu memerintahkan mata membuka, mata akan terbuka. Ketika memerintahkan kaki bergerak, kaki pun bergerak. Begitu seterusnya. Tak berlebihan, berdasarkan pandangan al-Ghazali ini, kalbu kita sebut pusat segala tindakan manusia. Peran kalbu di sini mirip dengan otak yang disebut sebagai sistem saraf pusat dalam kajian kedokteran modern.
Hubungannya dengan pengetahuan, kalbu adalah singgasana ilmu atau pengetahuan. Dalam ilustrasi al-Ghazali, kalbu seumpama cermin di hadapan suatu objek atau realitas. Ketika kalbu berhasil memantulkan realitas yang ada di hadapannya, ia disebut berpengetahuan (al-‘alim). Ihwal terpantulnya realitas pada cermin, itulah yang disebut ilmu.
Dalam bagian yang lain, al-Ghazali mengutip Fath al-Mushili yang menyatakan bahwa ilmu dan hikmah disebut nutrisi kalbu. Ilmu dan hikmah bagi kalbu tak ubahnya makanan dan minuman yang menjadi nutrisi bagi tubuh. Tanpa keduanya, hati akan sakit, lalu mati. Persis seperti tubuh yang tak diberi asupan makan dan minuman sama sekali. “Barang siapa yang luput dari ilmu, kalbunya akan sakit, kematiannya pun menjadi niscaya.”, tegas al-Ghazali.
Untuk mendiagnosis kematian sang raja, kita bisa merujuk antara lain Minhaj al-‘Arifin yang juga merupakan karya al-Ghazali. Pada bagian “I’rab al-Qalb”, “Fluktuasi Kalbu”, tersebut beberapa indikator matinya kalbu. Hilangnya rasa manis dalam ketaatan, tiadanya rasa pahit dalam kemaksiatan, dan ketidakjelasan kehalalan adalah tiga indikator matinya kalbu. Tetapi penting dicatat bahwa indikator ini hanya dapat terbaca oleh mereka yang masih memiliki kepekaan. Sedang bagi yang tak peka, mereka akan senantiasa merasa kalbu mereka baik-baik saja.
Masih menurut al-Ghazali, sebab utama hilangnya kepekaan spiritual dari diri seseorang adalah cinta dunia. “Cinta dan sibuk dengan dunia menghilangkan kepekaan, sebagaimana rasa takut yang mendominasi seringkali menghilang perihnya luka seketika.”, tulisnya. Kecintaan terhadap dunia ini selanjutnya melontarkan kebanggaan duniawi ke dalam hati. Ia menjadi “Racun mematikan yang mengalir di peredaran darah”, dalam bahasa al-Ghazali. “Kemudian mengeluarkan rasa takut, sedih, sadar kematian, dan ketakutan akan kiamat dari hati.” Ketika itu, sang raja betul-betul sudah meninggal.
Sebagaimana telah tersebut terdahulu bahwa cinta dunia merupakan awal mula tindakan-tindakan destruktif. Ia yang banyak menggiring manusia keluar dari rambu-rambu kehidupan, dari batasan-batasan yang telah digariskan. Pelanggaran-pelanggaran ini pada akhrinya juga melemahkan fungsi kabu, bahkan mengantarkannya pada kematian. Tak salah jika dalam banyak keterangan termaktub bahwa dosa dapat mengakibatkan kematian kalbu.
Secara lebih jelas, kita bisa belajar dari pengalaman al-Syafi’i dengan gurunya, Waki’ bin Jarrah. Suatu ketika, al-Syafi’i mengadu kepada gurunya itu perihal kemampuan hafalannya yang sedang memburuk. Nasihat yang ia terima dari gurunya adalah agar ia meninggalkan maksiat. Sebab kata sang guru, “Ilmu adalah cahaya, sementara cahaya [ilmu] Allah tak mungkin dicurahkan bagi pendosa.” Bagaimana mungkin mencerap pengetahuan sedangkan peranti utama untuk menangkapnya, yakni kalbu itu telah mati akibat dosa-dosa?
Sampai di sini kita mulai menjumpai titik terang. Kalbu adalah entitas vital dalam diri manusia. Di sanalah segala tindakan bermula. Dan untuk terus hidup, kalbu membutuhkan nutrisi yakni ilmu dan hikmah. Ketika suplai ilmu dan hikmah tiada, kalbu melemah, sehingga lambat laun akan mati. Dengan demikian, barangkali kita bisa memaklumi pandangan Ibn Taimiyah, salah satu guru dari mufasir kawakan Ibn Katsir, yang barangkali cukup ekstrem. Dalam Syarh al-Washiyah al-Kubra, ia dengan tegas menulis, “Tak soal manusia mati (karena tak makan dan tak minum) asalkan tetap istikamah di atas jalan dan agama Allah. Namun jika seseorang tak dapat hidayah, kalbu dan jiwanya akan mati, jadilah ia ke neraka.”