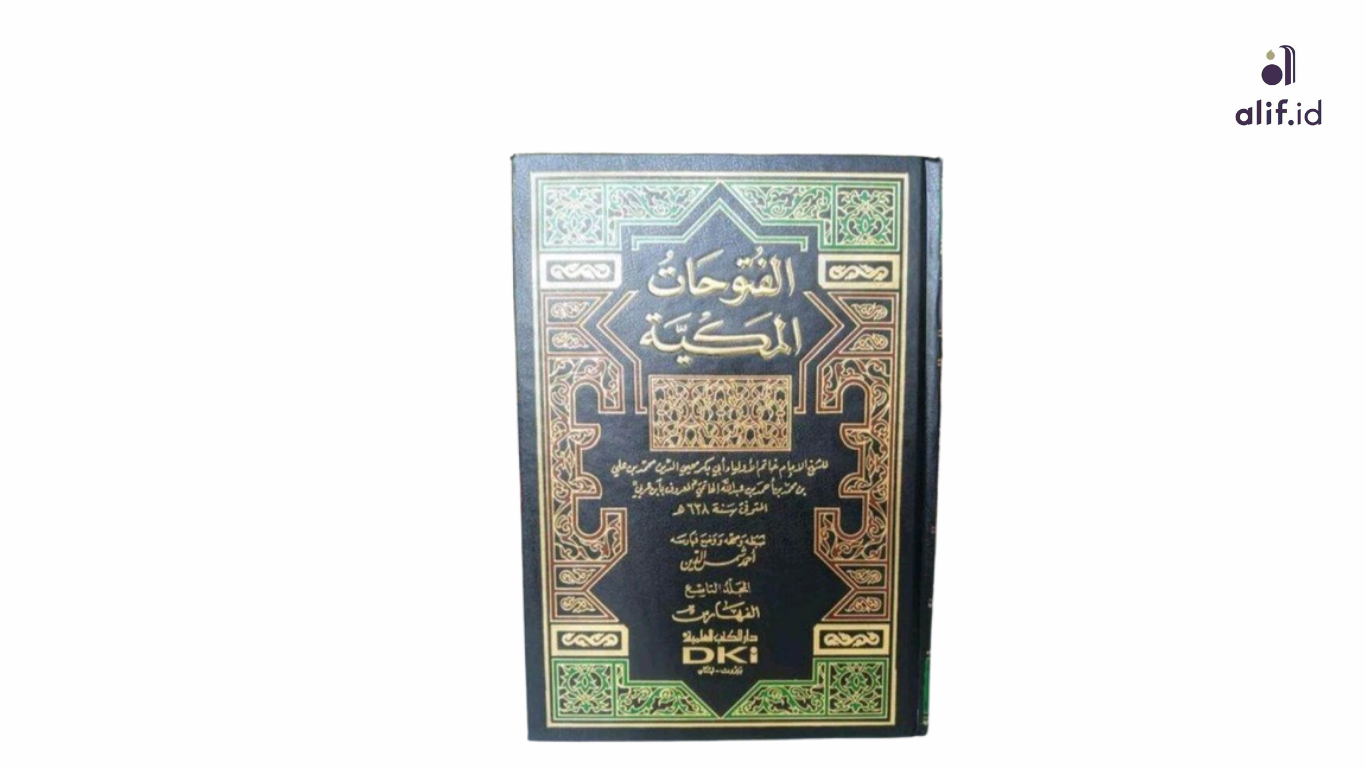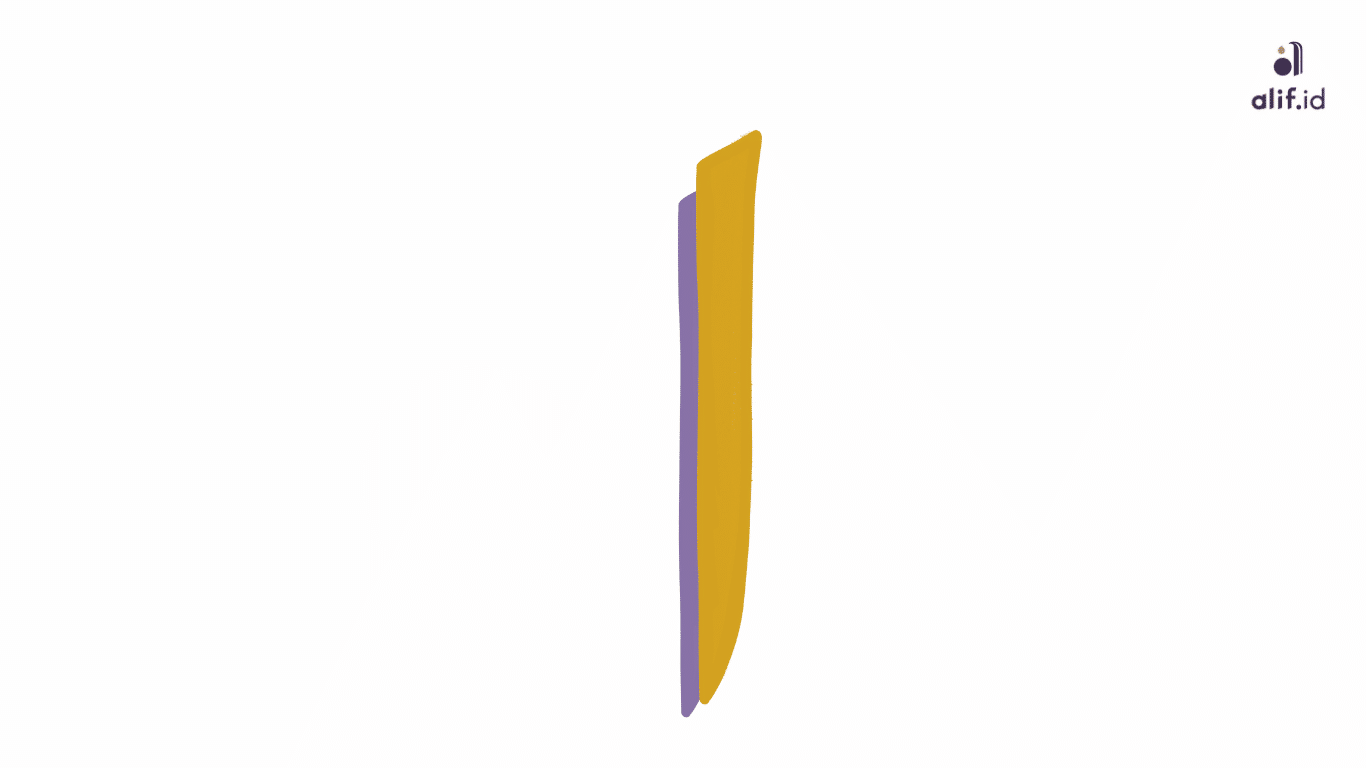Sukar rasanya mencari tahu sebab musabab mengapa beberapa kelompok masyarakat kerap kali merazia buku. Hingga saat ini, peristiwa razia atau boikot buku telah melebihi hitungan jari. Beberapa isu yang mencuat misalnya terkait dengan substansi buku yang bertema komunisme. Sejak Orde Baru, komunisme memang menjadi musuh utama sebagian besar masyarakat Indonesia.
Menariknya, razia buku ini bukan hanya terjadi di zaman modern, namun juga terjadi pada zaman kesultanan Islam di Indonesia. Contohnya, karya-karya sufi nusantara yang masyhur seperti puisi dan pemikiran Hamzah Fansuri di abad keenam belas.
Memang sudah banyak peneliti yang menulis tentang ini, salah satunya karya Dr. Abdul Hadi, Tasawuf yang Tertindas (2001) yang menjadi rujukan penulis kali ini. Kini yang menjadi pertanyaan kita adalah: apakah razia karya ini disebabkan hanya perbedaan pemikiran? Ataukah ada motif lain, misalnya politik?
Menilik Ulang Hamzah Fansuri
Berbicara tentang puisi atau syair Indonesia klasik, Hamzah Fansuri bukanlah nama asing lagi. Ia adalah seorang ulama dan sufi sekaligus seorang penyair. Beberapa ahli menyebutkan bahwa Ia merupakan ulama yang berasal dari Barus. Abdul Hadi, mengutip dari Valentjin, menyebutkan bahwa Fansuri berasal dari Barus.
Namun, Syed Naquib Al-Attas berpendapat lain. Ia meyakini bahwa Fansuri berasal dari sebuah daerah yang disebut Shahr Nawi (atau Shahr-e naw dalam pelanulisan Persia), ibu kota Campa. Fansuri misalnya menulis:
Hamzah nin asalnya Fansuri,
Mendapat wujud di tanah Shahr Nawi
Al-Attas meyakini bahwa Barus adalah asal dari ibunda Hamzah Fansuri. Adapun orientalis Belanda, Drewes, meyakini bahwa kata wujud di atas bukan bermakna kelahirannya, akan tetapi bermakna tempat di mana ia menjadi ma’rifat (Hadi, 2001). Drewes juga menganggap bahwa Barus memiliki nama lain, yang biasa disebut juga oleh masyarakat timur tengah, yaitu Fansur. Adapun Hasan Muarif menganggap bahwa Shahr Nawi adalah nama lain yang diberikan oleh Hamzah Fansuri untuk daerah Peurlak.
Bahkan, perdebatan ini juga merambat pada waktu kelahiran penyair masyhur ini. Beberapa ahli menyebut bahwa Ia lahir di abad ke-16, akan tetapi ada pula yang meyakini bahwa Ia lahir di abad ke-17. Al-Attas (1970) yang didukung oleh Braginsky dan Brakel (1986) meyakini bahwa Hamzah Fansuri hidup pada zaman kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Syah (1588—1604) dan awal masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda hingga 1636.
Karya-karya Hamzah Fansuri sebagaimana Al Attas (1970), baik yang tertulis dalam risalah tasawufnya maupun dalam syairnya, menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan sufi ternama lainnya, yaitu Ibn Arabi dan ‘Abdul Karim al-Jilli. Selain itu pula terdapat beberapa tokoh sufi ternama lainnya seperti Al Bagdadi, Al-Hallaj, dan Al-Ghazali.
Berdasarkan beberapa syairnya pula, Hamzah Fansuri diduga kuat sebagai ulama pertama di Nusantara yang mengenalkan ajaran tasawuf dan tarikat, khususnya Qadiriyyah. Alasan tersebut diyakini kuat karena hingga saat ini belum ada pembuktian ilmiah yang menyatakan bahwa ada ulama tarikat tersebut yang hidup sebelum zaman Hamzah Fansuri di Nusantara.
Adapun dalam falsafah pemikiran tasawuf Hamzah Fansuri, semuanya terpusat dalam ajaran Wujudiyyah. Beberapa ahli lainnya menyebutnya dengan istilah Wahdat al-Wujud. Pemikirannya dalam hal ini cenderung terinspirasi oleh Ibn Arabi, yang dianggap sebagai pelopor pemikiran ini. Ringkasnya, Wujudiyyah berarti kebersatuan wujud antara wujud manusia dengan wujud Sang Khalik yang mutlak. Hamzah Fansuri pun mengaminkan bahwa wujud yang nyata itu hanyalah satu yaitu Allah SWT. Adapun lainnya, yaitu segala ciptaannya, adalah bayangan atau manifestasi dari wujud yang nyata itu sendiri. Begitu pula tentang konsep penciptaan alam, bahwasanya alam diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada di mana alam bersifat qadim (lampau, tua, sejak dahulu kala) yang tercipta melalui proses tajalli (menampakkan diri), yaitu perwujudan diri yang abadi.
Pada sekitar abad yang sama, terdapat ulama lain yang bernama Nuruddin ar-Raniri. Ia merupakan ulama besar kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah. Ia berasal dari daerah Gujarat, India, dan diperkirakan lahir di akhir abad ke-16. Selain belajar Islam di kota kelahirannya, yaitu Ranir (Rander), Ia juga sempat belajar di Tamir (daerah selatan semenanjung Arab) dan juga di tanah suci Mekah dan Madinah. Ia merupakan bagian dari tarekat Rifa’iyah di bawah seorang guru bernama Abu Hafs Umar bin Abdullah Ba-Syaiban dari Tarim, Yaman.
Selepas pulang dari perjalanan keilmuannya, Raniri mulai berpindah lagi ke pesisir Aceh. Namun saat itu Kesultanan Aceh berada di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dan memiliki ulama pentingnya yang tidak lain adalah murid Hamzah Fansuri itu sendiri, yaitu Syamsuddin as-Sumatrani. Oleh sebab Ia tidak mendapatkan posisi penting dalam kesultanan, maka Raniri sempat bermukim di daerah Pahang (kini berada di negara Malaysia).
Setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636 dan kemudian digantikan dengan Sultan Iskandar Tsani, ia mendapatkan posisi penting dalam kesultanan yaitu sebagai mufti dan penasihat di kesultanan. Selain itu pula, Syamsuddin as-Samatrani pun telah wafat enam tahun sebelumnya (1630). Mulai kepemimpinan Iskandar Tsani inilah, razia buku atau karya tulis yang membahas paham Wujudiyyah dimulai dan bahkan para pengikutnya pun dikejar dan dibunuh karena dianggap menyebarkan ajaran sesat.
Ar-Raniri melancarkan kritik terhadap paham Wujudiyyah, salah satunya adalah argumen bahwa apabila yang wujud nyata hanyalah Allah, maka apa yang manusia makan pun adalah Allah. Bahkan pula hal ini sampai ke segala perbuatan manusia, yang mungkin pula terdapat perbuatan tercela di dalamnya, adalah tidak lain dari perbuatan Allah. Selain itu, masih terdapat beberapa poin lainnya yang dikritik keras oleh Nuruddin Ar Raniri.
Lebih lanjut, Abdul Hadi menjelaskan bahwa tidak semua karya Hamzah Fansuri yang terselamatkan. Hanya terdapat 3 risalah tasawuf dan 33 ikatan syair. Hilangnya karya agung ini diyakini kuat berkaitan pada pembakaran karya-karya yang menjelaskan tentang paham Wujudiyyah. Pembakaran ini terjadi pada tahun 1637 M, di depan Masjid Raya Kutaraja, di mana wilayah itu diduduki oleh Kesultanan Aceh. Padahal, sebagian besar karya yang membahas Wujudiyyah ini merupakan permintaan Sultan Iskandar Tsani dan juga di antaranya terdapat karya Syeikh Nuruddin ArRaniri.
Selain itu, nama Hamzah Fansuri tidak masuk ke dalam tulisan karya ar-Raniri yang berjudul Bustan as Shalatin. Meminjam argumen Hadi (2001), agaknya Ar Raniri berfikir apabila menulis nama Hamzah Fansuri dalam karyanya akan berdampak negatif pada nama Kesultanan Aceh dan sejarahnya. Padahal, Ar-Raniri sendiri mengetahui siapa itu Hamzah Fansuri. Namun ia menanggap bahwa ajaran yang dibawakan oleh Hamzah Fansuri adalah ajaran Wujudiyyah ad-Dhalalah atau Wujudiyyah yang Sesat.
Ar-Raniri yang saat itu juga memiliki posisi penting dalam istana Kesultanan Aceh menganggap bahwa ajaran yang dibawa Hamzah Fansuri dapat mengarahkan para kaum muslimin awam kepada kesesatan. Faktanya, pertentangan Ar-Raniri terhadap Hamzah Fansuri tidak menyeluruh. Sebagaimana yang ditulis pada paragraf sebelumnya, bahwa Ar Raniri pun menerima ajaran Wujudiyyah akan tetapi Ia bagi ajaran tersebut menjadi dua yaitu yang benar dan yang sesat.
Asumsi lainnya adalah akibat adanya kritik-kritik tegas dari Hamzah Fansuri pada kepemimpinan Kesultanan Aceh ini. Dalam beberapa syairnya, Hamzah Fansuri menentang kebijakan kesultanan yang suka menghabisi para lawan politiknya. Sebagaimana Hadi (2001), kritiknya tampak pada beberapa bait syair berikut.
Aho segala yang menjadi faqir
jangan bersuhbat dengan raja dan amir
karena rasul Allah bashir dan nadhir
melarang kita saghir dan kabir
Atau pada bait lainnya, Ia menulis:
Aho segala kamu anak ‘alim
jangan bersahabat dengan orang zhalim
karena rasul Allah sempurna hakim
melarang kita sekalian khadim
Rasul Allah itu nabi yang sahih
membawa firman dengan lisannya fasih
menyuruh kita meninggalkan qabih
supaya datang ke hadirat Allah malih
Dalam karya tersebut, dapat ditelaah bahwa pemimpin zalim yang dimaksud adalah para keluarga kesultanan, dan khususnya sultan itu sendiri. Inilah juga yang tidak dapat kita nafikan, tentu, menjadi alasan pengkafiran paham wujudiyyah yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri.
Selain itu pula, terdapat penentangan lainnya dari Hamzah Fansuri terhadap istana. Sebagaimana Al-Attas, Ia menamakannya dengan istilah demokratisasi ajaran tasawuf yang keliru dalam penamaan tempat-tempat di lingkungan istana yang diambil dari istilah-istilah sufi, seperti Dar Ad Dunya (Kediaman Dunia) pada nama istana, Teluk Isyqidar (Teluk Berahi) pada sebuah pantai, dan Dar al Isyq (Kediaman Cinta) pada nama sungai di dekat istana.
Beberapa penelitian lainnya menyatakan bahwa adanya kekhawatiran akan perebutan kekuasaan di kesultanan. Hal inilah yang membuat Sultan Iskandar Tsani menyetujuinya untuk melakukan tindakan pembakaran buku, pengejaran, dan bahkan pembunuhan para penganut paham Wujudiyyah ajaran Hamzah Fansuri.
Upaya-upaya membangkitkan karya Hamzah Fansuri hingga saat ini masih terus berlangsung. Beberapa contoh nyata yaitu penelitian mengenai karya itu sendiri. Para akademisi hadir ke bumi Aceh atau pun daerah sekitarnya untuk terus menelusuri jejak manuskrip-manuskrip yang kemungkinan besar adalah karya ulama agung tersebut.
Beberapa di antaranya yang mudah kita jumpai adalah buku karya Abdul Hadi yang berjudul Tasawuf yang tertindas atau karangan lainnya seperti tulisan Azyumardi Azra dan Oman Fathurrahman. Atau, beberapa karya lain yang ditulis oleh Syed Naquib Al Attas. Karya-karya ilmiah tersebut membahas pemikiran serta mengulik tulisan Hamzah Fansuri secara komprehensif, rinci, dan mendalam sehingga memberikan jawaban yang akurat.
Penelitian dan penulisan inilah yang diharapkan agar karya-karya penting Hamzah Fansuri ini, berikut pula karya muridnya, dapat hidup kembali. Karena karya beliau sangat kaya akan manfaat dalam ilmu pengetahuan. Secara umum, syair-syair Hamzah Fansuri secara permukaan dapat dipelajari kembali untuk para siswa jenjang sekolah menengah perihal struktur dan ciri-ciri syair lampau. Lebih mendalam, hal ini akan membantu para sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi dalam menelaah lebih mendalam terhadap susastra, linguistik, filsafat, studi Islam, dan sejarah.
Kejadian-kejadian tadi jelas menunjukkan adanya andil besar pemangku tahta dalam pelenyapan karya-karya penting nan masyhur itu. Dalam hal ini, saya melihat bahwa adanya kecenderungan perbedaan dalam hal pemikiran sedikit saja telah menyebabkan pihak kesultanan menyetujui adanya pembakaran kitab-kitab yang berisi tentang paham Wujudiyyah itu.
Entah apa pun tujuannya, belum tentu sebuah buku atau karya literatur lainnya dapat secara spontan menyebabkan pembaca mengikuti atau menjadi pengikut setia sebuah jalan. Masih banyak kalangan yang sebenarnya membutuhkan buku itu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dan bukan untuk ditelan mentah-mentah.