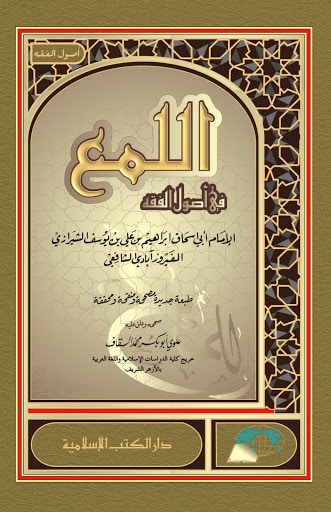Pilihan belajar Filsafat di Institut Agam Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada tahun 1992 mungkin didorong keinginan konyol. Andaian pada waktu itu adalah penguasaan
terhadap induk pengetahuan akan memudahkan jalan memahami disiplin-disiplin lain.
“Kalau mendapatkan ibunya, saya mudah meraih anak-anaknya,” kira-kira begitu pikiranku waktu memilih filsafat.
Tentu saja, jiwa remaja yang menggelegak acap menyeret pada ide dan sikap yang tak sejalan dengan pandangan khalayak luas. Meskipun kehendak pemberontakan meluap, namun sebagai santri, saya masih ragu untuk melangkah lebih jauh.
As-Suyuthi, penulis kitab Annuqayah, yang menjadi ilham nama pondok saya belajar mengharamkan filsafat. Informasi ini saya dapatkan dari Kiai Mahfudh, pengasuh pondok Sabajarin.
Memang, aroma anti-kemapanan telah menyerbu masuk sejak awal saya menginjakkan kaki di kampus. Sebagai mahasiswa Aqidah dan Filsafat (AF), kami merasa tidak sama
dengan mahasiswa Tafsir Hadits (TH) dan Perbandingan Agama (PA), yang sama-sama berada di atap yang sama, Fakultas Ushuluddin. Itu juga disadari oleh dosen kami,
sehingga Pak Romdlon, yang kebetulan penasehat akademik saya, meminta mahasiswa tidak terlalu melibat belajar ilmu yang berasal dari negeri para dewa ini.
Kata dosen tersebut, ada seorang kakak kelas yang mengalami masalah mental, dengan hanya
memakai celana pendek ke kampus. Aha! Ini seakan-akan peringatan awal agar kami tak menerabas rambu-rambu.
Namun, sejatinya sebagian besar mahasiswa masih berpenampilan “normal”. Malah, hampir semua mahasiswi memakai jilbab syar’i, tak ada yang pelik. Hanya sebagian kecil yang memakai celana bolong, berambut gondrong dan bersandal jepit, yang sebenarnya tidak hanya dimonopoli oleh pelajar filsafat, tetapi juga teman-teman pergerakan banyak berpenampilan seenaknya, malah kadang tampak tak terurus.
Dari segi ide, kami pun masih suka mengutip potongan-potongan pemikir, filsuf dan sarjana.
Namun, pertanyaan-pertanyaan aneh di kelas jelas menghentak nalar kami. Juhdi, asal Jepara, sempat bertanya pada Pak Affandi, dosen Ilmu Kalam, apakah malaikat Jibril
pensiun setelah akhir kenabian Muhammad?
Sepertinya kami mengalami euforia, semua mesti disoal agar hidup tak sial.
Betapapun asupan kami belum penuh dengan bacaan Filsafat, namun keliaran berpikir
membuat kami tak bersemangat mengikuti pelajaran-pelajaran normatif, seperti Fikih, hadis, dan bahkan Alquran. Maklum, para dosen kebanyakan mengulang kembali pelajaran kami di pondok, bukan karena IAIAN penganut liberal seperti dikatakan para mubalig.
Fikih, misalnya, masih berkisar pada bab-bab bersuci, sembahyang, zakat, puasa, dan haji. Namun mengingat subjek tersebut harus lulus sebagai prasyarat untuk subjek yang sama pada semester berikutnya, tidak boleh tidak kami mempelajarinya kembali. Bayangkan, kami harus
mengambil mata kuliah Tafsir I-IV, demikian pula, bahasa Arab dan hadis.
2
Beruntung, kami sedikit terhibur ketika mengambil Filsafat Islam, yang diampu oleh Pak Musa Asy’ari. Haji tidak dilihat semata-mata kewajiban dari Tuhan. Tapi, seluruh
rangkaian ibadah ini secara simbolik mengandaikan pesan kemanusiaan yang dalam.
Dengan menyodorkan karya Ali Syari’ati berjudul Haji, mantan rektor Universitas Islam Negeri
ini memupuk pikiran kami agar subur untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, kami mendapatkan banyak sudut pandang untuk mencerna kembali prasangka yang sempat menggelayuti benak. Untuk apa jauh-jauh pergi ke Mekkah, jika
Tuhan lebih dekat dari urat nadi.
Tak hanya itu, pengalaman belajar Filsafat Nilai dari Achmad Charris Zubair juga menyodorkan warna baru. Sebagai dosen filsafat Universitas Gajah Mada, ia tidak hanya melihat filsafat sebagai diskursus dan spekulasi, tetapi juga cara melihat kenyataan. Tak
terelakkan, di akhir mata kuliah, lelaki yang berambut sebahu ini mengajarkan mahasiswa untuk meneliti perilaku etik warga Desa Bekonang, Sukoharjo, tempat
penghasil ciu, arak lokal.
Ketika filsafat cenderung dipahami secara abstrak, atau kami menyebutnya mengawang, dosen tersebut mengajak mahasiswa untuk mengamati realitas konkret. Betapa sebuah pengalaman yang mengilhamkan!
Untuk pertama kalinya, saya mengenal Lawrence Kohlbeg, filsuf moral. Aneka ragam pengalaman di atas makin membuat ingin tahu membuncah karena kami
sadar bahwa pilihan jurusan ini didorong untuk melihat pengalaman masa lalu kami secara kritis. Seperti diungkap oleh Basir Soulissa, dosen Filsafat Umum, bahwa belajar
ilmu ini sejatinya mensyaratkan kedalaman (radix) berpikir dan kebebasan.
Namun, seperti masuk hutan, kita bisa bertindak “semau gue”, namun ada binatang buas siap
menerkam, yang justru membatasi gerak kita. Dengan filsafat, mahasiswa bukan menafikan ritualitas, tetapi memberikan makna lebih luas terhadap kewajiban agama.
Sepanjang ingatan saya, ada seorang teman kelas yang sama sekali meninggalkan salat. Teman lain dengan santai menunaikan sembahyang seraya memakai helm dan menyanding tas di bahu tanpa berwudhu’. Bayangkan, kalau masa itu ada media sosial, seperti Facebook dan Twitter, lalu gambar yang bersangkutan diunggah! Kehebohan akan mudah menyebar.
Menariknya, ada teman kelas yang tidak betah duduk berlama-lama belajar di AF dan pindah ke Tafsir Hadis. Andaiannya, yang bersangkutan tidak tahan dengan kebablasan berpikir yang menyebabkan dirinya gundah-gulana. Sebaliknya, ada mahasiswa TH yang meninggalkan kelasnya untuk belajar Filsafat, karena ingin menemukan suasana baru.
Pendek kata, pada masa itu, setiap orang sedang mencari jati-diri yang otentik. Tentu saja, selain belajar di kelas, pengalaman yang mewarnai perjalanan intelektual
kami adalah kelompok diskusi.
Atas inisiatif bersama, seperti Kuswaidi Syafi’ie, Muhammad Husnan, Faruk, Fadlillah, dan Faridl Ma’ruf kami menggelar diskusi rutin tentang topik-topik bebas di kamar kost Zainal, asal Ponorogo, mengingat kamarnya paling luas.
Menariknya, sebagian makalah ditulis dengan tangan. Kelompok diskusi sekelas yang dimotori oleh Ismail, mahasiswa pindahan dari Fakultas Tarbiyah, adalah pengalaman lain yang sangat berkesan. Atas inisiatif senior ini, kami tak bergantung pada kelas, tapi kehendak bebas, menyusuri belantara isu dan pendekatan. Saya masih ingat betul bahwa sudah saatnya kita membaca buku-buku utama, bukan dari tangan kedua.
3
Jika hendak memahami Ibnu Taimiyyah, misalnya, bukan dari Nurcholish Majid, tetapi langsung mendaras karya-karya tokoh yang menjadi mentor pemikir Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Tentu saja, buku Ahmad Wahib adalah sedikit buku yang mengisi gelegak kami untuk menemukan jati-diri. Keinginan untuk berbeda dengan kebanyakan acap menghantui kami untuk mencari pijakan.
Tak hanya itu, di tengah keterbatasan uang, kami tidak hanya meneroka pengetahuan di
kampus sendiri, tetapi juga universitas lain, seperti Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) dan Universitas Gajah Mada. Minat kami tidak dikerangkeng dengan pesona jurusan sendiri.
Di IKIP, kami mengikuti kursus jurnalistik. Sekali waktu, kami mengikuti seminar di Fakultas Hukum UGM, yang pada waktu itu sedang menggelar pidato politik Amien Rais. Ketika kembali ke kostan di Gowok, kami terpaksa berjalan kaki karena angkutan umum sudah pulang ke kandang.
Selagi ada waktu, kami selalu mengikuti seminar yang menghadirkan para pemikir, baik
dalam kampus maupun luar. Salah satu dari sarjana itu adalah Mohammed Arkoun. Betapapun dikenal sebagai sarjana terkemuka, penulis Nalar Islami dan Nalar Modern, ini melayani pertanyaan mahasiswa S1 dengan riang.
Harus diakui betapapun kami mengambil jurusan Aqidah dan Filsafat, namun mata
kuliah kami juga merangkumi disiplin lain, seperti Psikologi, Antropologi, dan Sosiologi.
Tak pelak, buku-buku kami yang dibeli dengan susah payah meliputi banyak subjek. Sepertinya, filsafat harus bersaing dengan begitu banyak mata kuliah yang lain,
sehingga kami tidak sepenuhnya memusatkan perhatian pada teori dan tokoh pemikir sejak zaman klasik hingga pasca modern dari pemikiran yang bermula di Yunani.
Tak dapat dielakkan, kami kerap tergoda dengan potongan-potongan ide yang memantik kontroversi, seperti Tuhan telah Matinya Nietzsche dan mencetuskan kedalaman berpikir, seperti Cogito Ergo Sumnya Réné Descartes, meskipun belum mengkhatamkan keseluruhan karya-karya mereka. Apalagi pada tahun 1992, belum banyak buku-buku babon filsuf diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Kegilaan membeli buku di tengah kantong tipis hampir-hampir menjadi kebiasaan mahasiswa IAIN pada waktu itu. Sepertinya, kami hanya perlu memenuhi rak dengan buku, dan bisa membacanya kemudian. Selain membeli di pusat buku di Shopping Center , kami lebih suka memburunya di pameran buku, yang berharga miring. Dua buku yang memengaruhi saya adalah E.F. Schumarcher, Keluar dari Kemelut: Peta Pemikiran
Baru, dan Johan Huizinga, Homo Ludens. Karena teman baik saya menyukai buku yang terakhir, saya melepasnya dengan harga beberapa lembar ribuan. Menariknya, buku
tersebut pindah ke tangan kawan lain. Saya mengetahui perpindahan ini dalam sebuah percakapan di grup WhatsApp angkatan 92 AF, setelah 24 Tahun berlalu.
Selain itu, didorong mesti bersikap aneh, saya sering menemukan kelucuan di kelas.
Sekali waktu, dosen Sejarah Kebudayaan Islam sempat meluapkan amarah karena
teman-teman yang duduk di belakang bising. Tak hanya itu, ia menantang berkelahi seraya menyebut dirinya Angkatan 66.
Di lain waktu, teman yang sering usil mencabuti janggut di kelas. Dosen yang mengajar menghampiri dan memintanya berhenti. Namun
karena berdegil, pengajar tersebut, memberi pilihan, siapa yang harus keluar dari kelas.
Kawan tersebut diam dan bergeming. Tak lama kemudian, dengan wajah bersungut
dosen itu keluar dari ruangan. Setelah agak jauh, teman-teman menyatakan terima kasih karena kelas kosong. Tak hanya itu, orang yang sama sempat menantang dosen
4
Tasawuf untuk beradu kepandaian membaca kitab kuning. Lagi-lagi dosen ini hanya tersenyum.
Namun, keusilan teman-teman tak berhenti di situ. Ketika seorang dosen menerangkan gramatika bahasa Arab, salah seorang dari kami mengangkat tangan dan bertanya, apa perbedaan filosofis antara raghiba ‘an (رغب عن ) yang berarti benci dan raghiba fi (رغب في) yang bermakna rindu. Pengajar bahasa rumpun Semitik ini terdiam karena tak menyangka pertanyaan yang mungkin tak sempat terpikirkan.
Apa lacur, penanya malah maju ke depan dan menjawab soal yang diajukan. Perbedaan terletak pada ta’liq ‘an yang menunjukkan dari (jauh) dan fi yang menunjukkan berada (dekat). Kebencian menyebabkan menjauh, dan kerinduan menyebabkan mendekat, terangnya.
Hebatnya, yang bersangkutan tetap mendapatkan nilai A. maklum sebagai santri, ia bisa menjawab dengan mudah soal bahasa Arab. Lebih hebat lagi, dosen yang mengajar kami memang dikenal objektif, baik dan murah senyum.
Tak hanya bersikap aneh, kawan sekelas juga percaya diri. Ketika dosen Tafsir meminta
teman-teman menulis makalah, seorang teman malah mengajukan “Tafsiruna”, ketika kawan lain mengurai kandungan kitab Jalalalain, al-Qurthubi, dll.
Tafsiruna berarti ijtihad dia sendiri. Kemampuannya membaca kitab kuning tentu menjadi modal yang
bersangkutan untuk bersuara vokal. Tak hanya itu, dalam sesi soal-jawab, dengan berkelakar ia juga pernah menyergah bahwa pemakalah menjawab pertanyaan seperti
Kobutri (angkutan umum butut dan berasa yang lewat kampus) berputar-putar tak karuan. Tak pelak, semua yang hadir pada waktu itu melepaskan tawa. Sebenarnya, saya tak hanya belajar dari dosen, tetapi juga dari teman-teman sendiri.
Mereka tak hanya mengajarkan bagaimana berasyik-masyuk dengan pengetahuan, tetapi juga pengalaman hidup. Salah satu teman sering terlambat masuk ke kelas, karena pagi-pagi harus berjualan ikan di pasar.
Sepanjang pengetahuan saya, kawan-kawan menikmati kelas Amin Abdullah. Ketika itu, lulusan Ankara Turki tersebut telah dikenal sebagai intelektual terkemuka. Kesediannya
mengajar kami tentu merupakan anugerah.
Hal serupa juga kami dapatkan dari
Nuruzzzaman Ash-Shiddiqi. Ia membuka jalan pengetahuan kami lebih luas. Dari mantan rektor ini, kami diajak untuk menelusuri pemikiran para filsuf muslim. Di
tengah kegairahan menekuri filsafat Barat, perkenalan dengan al-Farabi, misalnya, menjadi penyeimbang untuk mendekatkan Filsafat pada wacana keagamaan.
Dosen lain yang menarik adalah pengajar Adabul Bahtsi wal Munazarah (etika diskusi dan berdebat), karena yang bersangkutan
senantiasa menghembuskan rokok di kelas, tapi tak lupa membawa asbak berupa bekas wadah Pastilles, permen penyegar mulut. Subjek ini penting karena sebuah diskusi
mensyaratkan etika. Seorang dosen lain sempat lupa memasukkan bolpoin ke saku baju,
padahal pakainnya tak bersaku. Serta-merta, setelah mengambilnya di lantai ia berujar,
maaf, baju ini saya beli di Belanda.
Terus terang, pengalaman belajar Filsafat tidak sepenuhnya diraih karena subjek ini bersifat umum, seperti Filsafat Umum, Filsafat Aliran, dan Filsafat Modern. Tak ada mata kuliah yang mendorong mahasiswa untuk betul-betul memahami philosophia secara lebih terperinci, misalnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai subjek khusus, sehingga ada kedalaman dan kesungguhan untuk menuntaskan istilah-istilah kunci. Belum lagi, disiplin lain yang tak terkait langsung dengan filsafat telah menyita waktu mahasiswa. Tambahan lagi, subjek Aqidah sengaja dipasangkan agar Filsafat tak menyebabkan mahasiswa kehilangan arah dan akarnya.
Bayangkan subjek Aqidah masih diperinci ke Ilmu Tawhid, Ilmu Kalam, dan Teologi. Tambahan lagi, kami juga awal-awal telah mengambi Dirasah Islamiyyah I-III.
Akhirnya, puncak dari perjalanan ini adalah karya akhir. Saya menulis skripsi terkait dengan konsep keadilan Tuhan menurut pandangan Ibnu ‘Arabi. Di bawah bimbing Pak
Romdlon, saya menyelesaikan tugas ini sebanyak 80 halaman. Betapapun pemikir tersebut banyak menangguk ide dari filsuf Barat, namun tautannya dengan Alquran
seakan-akan memberi garis panduan pada saya untuk menjaga keseimbangan antara otoritas akal dan kuasa wahyu.
Jadi, bagi saya, filsafat menyediakan ruang untuk mengerti dengan baik ajaran agama, bukan menyangkalnya.
Betapapun keseimbangan tiap dari kami tidak sama persis, namun penghayatan kami tak jauh berbeda.
Sejauh ini, teman-teman seangkatan masih memegang teguh
agamanya. Filsafat tidak dengan sendirinya membuat kami menjadi orang yang asing dari masyarakat yang dulu dianggap sebagai kerumunan. Mungkin pemaknaan terhadap amalan agama bertambah kaya dan bernuansa, yang tidak semestinya diumbar pada khalayak karena tingkat pemikiran abstraktif mereka terbatas. Ide phronimos Aristoteles mengajar kami bahwa tindakan dan pikiran seseorang harus hadir dalam ruang, waktu, dan khalayak secara tepat. Inilah sejatinya kearifan itu.
Semoga.