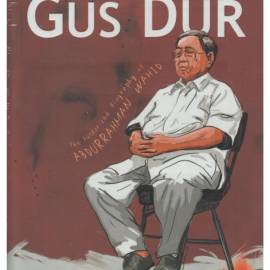Masalah privilese itu nyata, bukan fiksi. Gus Dur mungkin satu dari banyak tokoh yang tumbuh karena adanya privilese. Dan ia mengakui adanya privilese tersebut. Kita tahu, ia adalah anak (mantan) menteri, cucu pendiri NU dan Pesantren Tebuireng. Ia adalah seorang yang berdarah biru.
Dalam suatu wawancara dengan sebuah majalah di tahun 1996, ia pernah menyatakan seperti ini:
“…kebetulan saya ini cucu pendiri (NU). Jadi, saya mendapat comparative advantages: pernah pesantren, pernah ke Timur Tengah, dan mendapat privilese untuk belajar sana-sini. Tapi advantage apapun, kalau tidak bisa kita manfaatkan, tidak akan ada hasilnya.”
Jelas, Gus Dur tak mengelak dan mendustakan betapa pentingnya privilese tersebut. Seorang yang menjalani hidup dan meniti karier dengan privilese-privilese yang sudah tersedia, jelas berbeda ‘cara’ maupun ‘hasil’nya dengan seorang yang tanpa privilese apapun, meski ikhtiar yang dikerahkan sama besarnya. Seorang yang punya privilese, anak seorang kaya misalnya, seperti seorang sudah berada di depan garis ‘finish’ dibanding seorang yang bukan siapa-siapa yang harus mulai dari garis ‘start’.
Gus Dur membagi dua istilah: advantages dan privilese. Keduanya istilah dari bahasa Inggris. Yang pertama bermakna ‘keuntungan’, sedangkan yang kedua ‘hak istimewa’. Apa perbedaannya? Yang pertama bisa jadi bersifat material, dukungan materi dan keuangan yang cukup kuat.
Pada masa kecil misal diceritakan Gus Dur rajin membaca dan belajar bahasa Inggris langsung dengan seorang native. Tahun 1950an, buku-buku masih langka dan mahal. Belajar bahasa Inggris juga sangat istimewa. Jelas hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Barangkali inilah contoh advantages itu, yang benar-benar dimanfaatkan Gus Dur dengan maksimal.
Gus Dur belajar ke Kairo, kemudian lanjut ke Bagdad, dan seterusnya di Leiden, Belanda, hampir setahun. Ia memang memperoleh beasiswa ketika di Kairo, tetapi tampaknya tidak di Bagdad dan Leiden. Kalau tidak Ada dukungan financial yang kuat tampaknya sulit dilakukan. Inilah advantages itu.
Sementara privilesse adalah hak istimewa yang melekat karena dia seorang “gus”. Ketika belajar di Pesantren Krapyak dan Tegalrejo, Gus Dur tidur di nDalem kiai, dan yang menarik, ia bisa dan dibolehkan baca buku apa saja. Jelas ini privilesse karena dia seorang “gus”. Tapi sekali lagi Gus Dur bisa memanfaatkan privillese itu dengan sebaik-baiknya.
Ada suatu cerita menarik berkaitan dengan privilese Gus Dur ini dan perbandingannya dengan Cak Nur (Nurcholish Madjid). Berbeda dengan Gus Dur, Cak Nur berasal dari keluarga biasa saja. Karena usaha keras dan aktivitasnya, ia bisa menduduki dua kali kursi Ketua PB. HMI dan meraih gelar doktor di Amerika. Cak Nur pun menjelma menjadi seorang intelektual muslim Indonesia terkemuka. Tapi ia tak memiliki privilese sebagaimana Gus Dur.
Orang-orang yang hidup di tahun 1990an tahu dan mungkin masih ingat bahwa setiap kali menulis makalah seminar, Cak Nur selalu membubuhkan kalimat ‘Bismillahirrahmanirrahim’ dalam aksara Arab Kufi. Berbeda dengan itu, Gus Dur sama sekali tak pernah menuliskan kalimat tersebut di pembuka makalahnya.
Suatu kali ada yang menanyakan ke Cak Nur, mengapa ia selalu membubuhkan kata ‘Bismillah…’ di setiap pembuka makalahnya? Kok beda dengan Gus Dur?
Cak Nur menjawab, Gus Dur itu cucu pendiri NU dan pesantren Tebuireng. Tanpa pakai bismillah… atau simbol formal apapun, dia sudah jelas dipandang sebagai (representasi) muslim. Saya tidak memiliki kelebihan seperti itu. Memulai dengan ‘bismillah…’ saja masih banyak yang menganggap saya tidak mewakili Islam…
Yang dikemukakan Cak Nur jelas adalah sebuah privilese. Privilese yang dimiliki Gus Dur, dan tidak dimilikinya. Meski privilese di sini bukan suatu yang bersifat material, lebih kultural, tapi bisa jauh lebih bernilai karena berfungsi sebagai ‘modal sosial’ yang besar.
Sebagai anak tokoh, Gus Dur jelas memiliki privilese, dan itu sekali lagi, diakuinya. Kendati demikian, ada dua hal yang bisa dicatat dari pengakuan Gus Dur ini. Pertama, kenyataan menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang memiliki privilese-privilese –karena kaya atau telah menjadi anak tokoh sejak nongol di muka bumi– otomatis bisa besar, hebat dan kaya juga. Kedua, tetap saja harus ada ikhtiar dan usaha yang keras untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita.
Orang tentu tak bisa menolak takdir terlahir sebagai anak orang kaya atau putera seorang tokoh. Karena itu, mungkin bukan privilese-privilese itu benar yang penting, tapi sejauh apa privilese-privilese itu dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan banyak orang, kemaslahatan kemanusiaan, kemajuan peradaban, dan lain-lain. Sejarah mencatat, ada banyak figur yang rela mengorbankan dan meninggalkan privilese yang dimiliki, atau memanfaatkan privilese yang diipunyai, untuk hal-hal yang besar, lebih dari sekadar kepentingan pribadi dan keluarga.
Dalam hal inilah, sosok seperti Gus Dur, dan sosok sejenis yang juga banyak memperoleh privilese, menjadi penting dan menarik. Ia menggunakan privilese-privilesenya untuk memajukan demokrasi, membela kaum marjinal, membela minoritas, menegakkan HAM, mengembangkan peradaban dan lain-lain.
Itulah juga harapan saya, dan mungkin banyak orang, terhadap mereka, siapa pun yang memiliki privilese-privilese karena ditakdirkan lahir sebagai anak orang kaya atau anak tokoh.