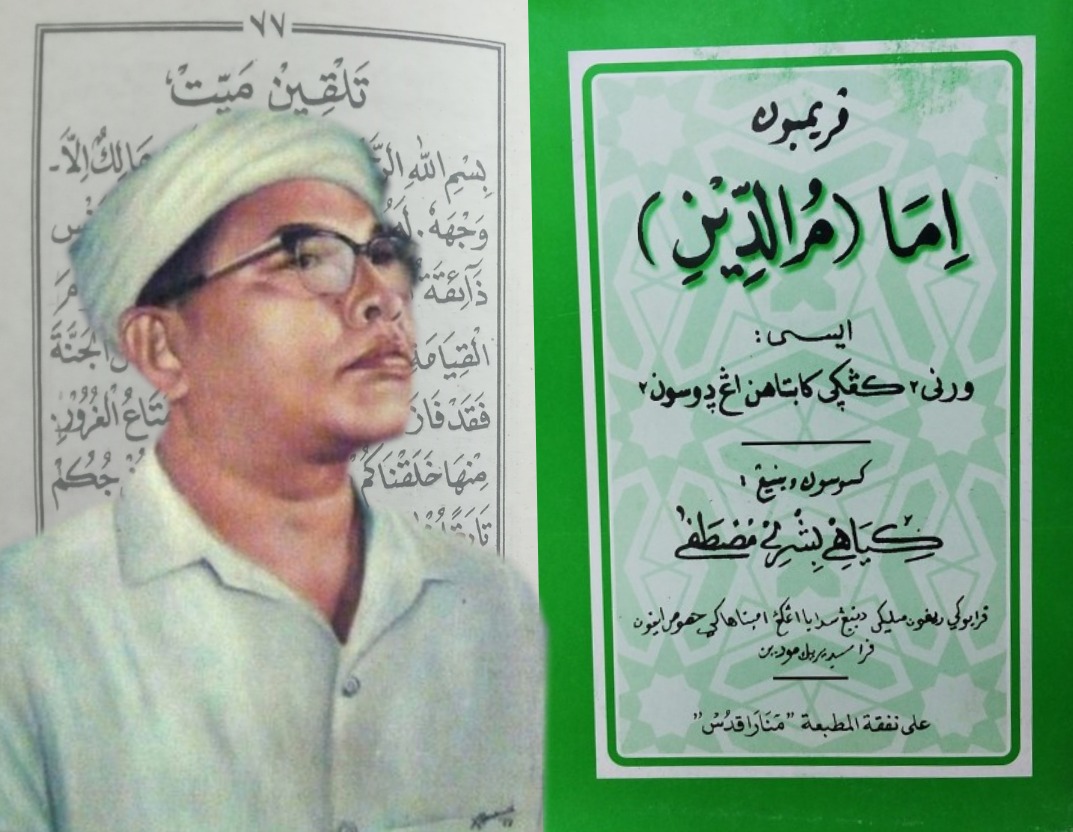Aktif di media massa di lingkungan NU, saya merasakan betapa perihnya saat Gus Dur dilengserkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI selaku lembaga tertinggi negara, melalui Sidang Istimewa. Gus Dur baru menjabat sebagai presiden selama 21 bulan, terhitung sejak 20 Oktober 1999. Sebagai warga Nahdliyin, saya merasakan perihnya sekuel sejarah perjalanan NU dan kehidupan bangsa kita. Detik-detik pelengseran Gus Dur terasa mencekam. Rakyat yang mendukung presiden keempat RI itu menyemut di Istana Kepresidenan Jakarta, berhadapan dengan militer yang berseliweran di sekitarnya. Nuansa haru pun mewarnai momen tersebut tatkala Gus Dur tak kuasa menahan air matanya.
Berbeda dengan waktu sebelumnya. Sebagai Nahdliyin, seperti santri yang lain, saya merasa bahagia ketika menyaksikan di Ruang Sidang MPR riuh di penghujung rapat paripurna 20 Oktober 1999. Tak terbayangkan oleh siapa pun Gus Dur terpilih menjadi presiden. Beberapa hari sebelum sidang paripurna digelar, MPR dipimpin Amien Rais menolak laporan pertanggungjawaban Presiden ketiga RI, B.J. Habibie. Dan Habibie dikenal sebagai “seorang berotak cerdas di Indonesia”, mengundurkan diri dari arena pencalonan presiden. Gelanggang pemilihan presiden pun menjadi milik berdua: Gus Dur mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Megawati Soekarnoputri, memimpin PDI Perjuangan.
Ketegangan terjadi, banyak pihak mengira pertarungan akan dimenangkan Megawati. Selain suara PDI-P lebih besar dari PKB pada Pemilu, kondisi fisik Gus Dur ketika itu sudah payah. Namun, seperti keyakinan Gus Dur, dalam pandangan KH Abdul Muchith Muzadi (almaghfurlah) sebagai “Jimat NU”, kelak akan tampil duduk di kursi presiden. Gus Dur berhasil unggul dengan mengantongi 373 suara, 60 suara lebih banyak dari Megawati.
Sebagai penyaksi zaman, kita tahu, beberapa hari sebelum pemilihan presiden digelar, Gus Dur seakan mendapat dukungan penuh dari Amien Rais — saat itu tokoh Muhammadiyah itu baru terpilih menjadi Ketua MPR. Amien Rais bahkan bilang bahwa Gus Dur menjadi satu-satunya harapan untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Amien Rais memberikan pengakuan pada Greg Barton: “Greg, Gus Dur-lah satu-satunya yang dapat mempersatukan muslim, non-Muslim, dan yang lainnya. Segalanya tergantung kepadanya. Dia adalah harapan kita satu-satunya”. (Greg Barton, penulis Biografi Gus Dur). Memang, benar. Selang beberapa hari setelah itu, Gus Dur betul-betul menjadi presiden. Sementara, Megawati yang terpilih jadi wakilnya.
Gus Dur baru menginjak bulan ke-21 saat riak-riak politik menggoyangkan kursi kekuasaannya. Gus Dur diterpa sejumlah isu kontroversial. Salah satu yang paling kencang ialah tudingan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atas dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar 4 juta dolar AS. Kita tahu, dugaan itu tak pernah terbukti di Pengadilan hingga kini.
Situasi politik makin memanas hingga akhirnya MPR mengagendakan Sidang Istimewa pada 23 Juli 2001. Mendengar kabar ini, menjelang tengah malam tanggal 22 Juli 2001, Gus Dur mengadakan pertemuan dengan salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlawi dan tujuh ulama sepuh di Istana Negara. Dalam pertemuan itu berlangsung khidmat dan penuh haru. Gus Dur tak kuasa kuasa menahan air matanya. Cucu Hadlatussyaikh Muhammad Hasyim Asy’ari ini, berkali-kali meminta maaf karena merasa tak berterus terang kepada para ulama mengenai situasi politik yang dihadapinya. Tangis Gus Dur pecah. Bukan karena lemah menghadapi situasi politik saat itu. Namun, dia memikirkan para ulama dan pendukungnya yang berkomitmen kuat untuknya.
Atas dorongan para ulama dan pengurus pondok pesantren, lewat tengah malam memasuki tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden – dibacakan Yahya Cholil Staquf, didampingi Abdul Mudjib Manan, sekretaris presiden dan kawan Gus Dur sejak belajar di Kairo, Mesir. Maklumat itu memuat 3 poin utama: pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan pembekuan Golkar. Langkah Gus Dur ini justru membuat Parlemen kian meradang. Dekrit itu tak memperoleh dukungan. Akhirnya, melalui Sidang Istimewa MPR dipimpin Amien Rais pada 23 Juli 2001, Gus Dur resmi dimakzulkan. MPR menarik mandat yang diberikan kepada Gus Dur dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai pengganti presiden.
Menjelang pelengserannya, Gus Dur dibanjiri simpati para pendukung. Di sejumlah daerah, simpatisan Gus Dur bahkan membentuk pasukan berani mati jika presiden keempat itu diturunkan. Sedikitnya, ada 300.000 relawan berani mati yang siap berangkat ke Jakarta untuk membela Bapak Pluralisme tersebut. Namun, kala itu Gus Dur menahan massanya. Gus Dur tak mau ada kerusuhan, apalagi pertumpahan darah sesama anak bangsa.
Pada episode ini, Cak Anam menulis buku Seandainya Aku Jadi Matori, menggambarkan bagian ‘Politik Hati Nurani’ dan ‘Berani Menanggung Risiko’. Ketika era Reformasi, orang-orang menyambut dengna suka cita, termasuk warga Nahdliyin. Merespon arus bawah, PBNU memfasilitasi berdirinya PKB. Saat Pemilihan Umum digelar pada 1999, hasil kerja keras NU menampakkan penghargaan dengan tampilnya Gus Dur di puncak kursi pemerintahan dan pemimpin negara yang tengah mengalami porak-poranda oleh badai krisis multidimensi — dari krisis moneter, hingga krisis moral dan perosok jebakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Toh, penghargaan pada NU hanya bersifat sementara, pada akhirnya Gus Dur pun dilengserkan.
Dilengserkannya Gus Dur tak hanya menyisakan kekecewaan warga Nahdliyin terhadap anggota DPR RI di gedung parlemen di Senayan, Jakarta, terlebih terhadap mereka yang dianggap mengkhianati janjinya akan “menjamin keamanan” posisi Gus Dur hingga akhir jabatannya. Saya teringat betul ketika Amien Rais di tengah-tengah para Kiai Sepuh, khususnya yang beberapa kali bertemu dalam Forum Langitan, menyampaikan janjinya itu. Para kiai, di antaranya, K.H. Abdullah Abbas (Cirebon), dan K.H. Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), sempat khawatir akan terjadinya pengkhianatan itu dan pada akhirnya memanglah terbukti kebenarannya.
Ternyata, pengkhianatan itu pun bukan hanya dari komplotan Amien Rais dan Megawati, melainkan juga terjadi dalam tubuh PKB. Sangat ironi. Pada rapat akbar PKB di Surabaya — menyusul deklarasi PKB di Ciganjur, Jakarta pada 23 Juli 1998 — Matori Abdul Djalil, menangis di pangkuan Gus Dur. Ketika itu, Gus Dur — deklarator PKB bersama KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH Ahmad Mustofa Bisri dan KH Abdul Muchith Muzadi – sedang menyampaikan pidato di depan warga Nahdliyin yang hadir. (Catatan: Foto adegan ini menjadi campul depan buku Choirul Anam, Seandainya Aku Jadi Matori).
Matori Abdul Djalil, memang sempat diragukan oleh sejumlah Kiai Sepuh saat awal pembentukan PKB sebagai ketua umum. Namun, Gus Dur membela mati-matian dan meyakinkan kemampuan dan kecerdikannya sebagai politikus. Pada saat Gus Dur dilengserkan, sangat disayangkan, Matori Abdul Djalil justru mengambil jalan di persimpangan. Tokoh asal Salatiga ini tak menaati keputusan DPP PKB di bawah kepemimpinan Dewan Syuro, KH Abdurrahman Wahid, terkait keabsahan Sidang Istimewa MPR. Sebagai hadiah atas perbedaan dengan Gus Dur, Matori Abdul Djalil menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri.
PKB pun terbelah: Matori Abdul Djalil membawa gerbong PKB (Batutulis), sedang PKB dipimpin Gus Dur disebut PKB (Kuningan), dengan Ketua Umum Alwi Shihab. Di pengadilan PKB Matori dinyatakan tidak sah. Matori bersama Abdul Khaliq Ahmad, kemudian membentuk Partai Kejayaan Demokrasi (PKD) pada 2001. Saya menyaksikan, pada 2003 saat digelar Istighotsah Kubro di Surabaya, Gus Dur dan Matori, bersama Alwi Shihab, Ketua Umum PBNU K.H. A. Hasyim Muzadi, K.H. Abdullah Faqih Langitan, K.H. A. Mustofa Bisri, sempat berjabatan tangan (islah bil-haq) di depan mata lebih dari setengah juta warga Nahdliyin.
Untunglah, kendati diterpa badai perpecahan yang berlarut-larut, PKB masih mampu berbicara banyak pada Pemilu 2004 dipimpin Alwi Shihab (ketua umum) dan Muhaimin Iskandar (sekjen), dengan mempertahankan posisi ke-3 dengan hasil suara 10,57% (11.989.564) dan memperoleh 52 kursi di DPR. Perolehan suara PKB merosot pada Pemilu 2009, hanya mendapat 27 kursi di DPR. Saat itu, Muhaimin Iskandar mengikuti jejak Matori Abdul Djalil, mengambil jalan di persimpangan dari Gus Dur. Pemilu 2014, suara partai meningkat dua kali lipat dengan mendapatkan 47 kursi di DPR.
Sementara itu, perjalanan Duta Masyarakat selalu beriringan dengan kegiatan NU dan PKB. Saat Istighotsah Kubro digelar di Surabaya pada awal Maret 2003, Duta Masyarakat merayakan Hari Lahir (Harlah) dalam rangkaian Pekan Muharram 1424 H: ada pameran lukisan, pembacaan puisi bersama para penyair, dan seminar. Setelah membacakan “Doa Akasah” pada Istighotsah Kubro, K.H. A. Mustofa Bisri menghebohkan lewat karya lukisan yang dipamerkan salah satu sisi gedung Masjid Al-Akbar Surabaya. Karya itu berjudul “Berdzikir Bersama Inul”. Lukisan kontroversi memperlihatkan perempuan sedang berjoget di tengah para kiai bersurban, sempat dihargai Rp75.000.000,-. Pada malam harinya, ada Pembacaan Puisi Muharram bersama para penyair, seperti D. Zawawi Imron, Sutardji Calzoum Bachri, Acep Zamzam Noor, dan, tentu saja Gus Mus juga. Dalam Doa Akasah, Gus Mus bermohon:
Ya Allah, Wahai Tuhanku;
bila ujub, takabur, riya, nafsu kemasyhuran
dan kekukarangan merasuki amalku untukMu
tanpa kusadari atau kusadari
aku bertobat darinya dan berserah diri
seraya mengucap Laa ilaaha illaLlah Muhammadur RasuuluLlah
shallaLlahu ‘alaihi wasallam
Ya Allah, Wahai Tuhanku;
bila kebohongan, gunjingan, adu-domba, dan kepalsuan
meluncur dari lisanku tanpa kusadari atau kusadari
aku bertobat darinya dan berserah diri
seraya mengucap Laa ilaaha illaLlah Muhammadur RasuuluLlah
shallaLlahu ‘alaihi wasallam
Ketika Gus Dur lengser dari kursi presiden, perih di hati warga Nahdliyin tak mudah dihapus.Pun semakin menambah kecintaan umat Islam di Indonesia, khususnya warga Nahdliyin, terhadap Gus Dur. Ada kata-kata Gus Dur, kemudian populer, ketika ditanya siapa orang yang paling bertanggung jawab dalam pelengseran itu: “Amin Rais dan Megawati”.
Tapi mengapa soal itu tetap menjadi perhatian Gus Dur? Bukankah agama mengajarkan untuk saling memaafkan? “Maafkan, ya. Tapi lupa, tidak”.
Dalam takshow di televisi dipandun Andi F. Noya, pernah ditanyakan pula siapa orang yang paling menjadi musuh Gus Dur?
Gus Dur menjawab, “Pak Harto”.
Tapi begitu pun setelah Soeharto dilengserkan dalam Gerakan Reformasi pada Mei 1998, toh Gus Dur tetap hadir menemuinya. Apa artinya bagi Gus Dur?
“Artinya, saya tidak punya musuh dong!”
Begitulah! Gus Dur dengan mudah memaafkan dan berkeyakinan, kelak ada suatu penelitian sejarah yang akan membuktikan kebenaran, terhadap tindakan dan kebijakan yang dilakukan bagi negeri ini.
Selepas dari kursi kekuasaan, Gus Dur kembali di tengah masyarakat, berdekat-dekat dengan nasib rakyat. Kembali menjadi penulis, selain melakukan perjalanan di basis-basis NU dan mengisi berceramah dalam pengajian dan seminar. Saya merasa bersyukur, ketika belum marak internet, dan masih berfungsi optimal penggunaan faksimili. Setiap sepekan sekali Gus Dur mengirim tulisan melalui faks ke Duta Masyarakat. Gus Dur dibantu Gamal Ferdhi dalam proses pengiriman faksimilinya. Dari faksimili, kerap tintanya kurang jelas, saya bertugas untuk menulis ulang di komputer sebelum akhirnya bisa di-lay-out pada posisi menarik di halaman pertama.
Salah satu artikel Gus Dur berjudul “Islam: Kajian Klasik ataukah Wilayah?”, ditulis di Paso, 27 Mei 2002, begitu mengesankan. Ya, tercantum Paso (bukan Poso, Sulawesi Tengah). El Paso, sebuah kota di barat Texas, Amerika Serikat. Kota ini terletak di perbatasan Meksiko, di sebelah utara dari Rio Grande. Gus Dur berkisah terkait undangan Soedjatmoko, saat menjabat Rektor Universitas PBB di Tokyo. Suatu kesempatan baik, menyampaikan pandangan tertulis di Jepang mengenai kajian Islam. Undangan itu membawa Gus Dur pada pengembaraan menarik: bertemu Hassan Hanafi, yang intelektual Muslim yang tinggal di Prancis. Gus Dur pun bersama Soedjatmoko menonton film Ghandhi di suatu gedung bioskop di Tokyo. Gus Dur merasa mendapat gambaran sangat hidup tentang diri tokoh pejuang anti-kekerasan, yang sebelumnya hanya dikenal melalui buku-buku.
Gus Dur menyampaikan bahwa “kajian Islam tak dapat hanya bersifat tunggal”. Kajian tunggal itu, sebagaimana dijalankan beberapa perguruan Islam sendiri, hanya akan melahirkan kajian klasik tentang ajaran Islam. Bila itu terjadi, maka hanya ada satu warna kajian Islam, yang sebenarnya menjadi inti formalisme agama dengan ujung Negara Islam. Nah, untuk menghindari hal itu, menurut Gus Dur, harus dibuat lembaga yang melakukan kajian kawasan (area studies) bagi bangsa-bangsa Muslim. Di samping persamaan-persamaan ajaran yang dimiliki Kaum Muslimin sedunia, seperti peribadatan dalam Rukun Islam, yang menunjukkan persamaan penerapan ibadat itu sendiri oleh masyarakat, sekaligus pengetahuan akan perbedaan dalam cara beribadat itu.
Gus Dur menegaskan, dengan mengetahui persamaan dan perbedaan yang dimiliki sebuah kawasan Muslim dengan/dari kawasan-kawasan lain akan memperkaya pandangan tentang bagaimana Islam dijalankan oleh masyarakat-masyarakat Muslim yang saling berbeda itu. Hanya dengan pengetahuan seperti itulah Kaum Muslimin mengenal diri mereka dengan lebih baik. Kajian kawasan diusulkan Gus Dur: Islam di kawasan Afrika Hitam, kawasan Afrika Utara dan negeri-negeri Arab, Islam di kawasan peradaban Turki-Persia-Afghan, kawasan Asia Selatan, kawasan Asia Tenggara dan kaum minoritas Muslim di negeri-negeri berteknologi maju (advanced countries). Digabungkan dengan sebuah pusat kajian klasik, dapatlah diharapkan kita memiliki pusat-pusat kajian (study centers) yang akan memperkaya rangkaian tindakan-tindakan untuk memajukan agama tersebut.
Saya bersyukur, sekaligus beruntung dengan mengetik ulang tulisan Gus Dur yang dikirim melalui faksimili itu. Dengan mudah pula memahami percik-percik pemikiran tokoh yang saya kenal tulisannya sejak remaja itu. Semasa ngaji dari guru-guru kami, KH Syihabul Irfan Arief dan KH Zainul Arifin Arief, keduanya putra KH M. Arief Hasan (almaghfurlahum), pendiri Pondok Pesantren Raudlatun Nasyi’in, Desa Beratkulon, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto. Nama Gus Dur begitu menghunjam di hati. Ada pula nama Mahbub Djunaidi yang jenaka mencerdaskan, dan K.H. Saifuddin Zuhri, yang menghidupkan suasana teduh dan mengesankan dunia pesantren.
Selain menulis di Duta Masyarakat, Gus Dur menulis untuk Harian Memorandum (Surabaya) dan Pikiran Rakyat (Yogyakarta). Terkait dengan Memorandum, Gus Dur mempunyai kedekatan dengan H. Agil H. Ali, bos koran yang lebih banyak di kalangan rakyat bawah itu. Saya sempat tergabung di Memorandum, dan beberapa kali mengundang Gus Dur. Baik untuk seminar maupun ceramah. Yang mengesankan, saat Gus Dur berceramah pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad s.a.w. di depan kantor di Jalan Pahlawan Surabaya pada pertengahan 1996.
Gus Dur tak membeda-bedakan pemuatan pikiran antara media besar, seperti Kompas dan Tempo, melainkan juga media-media yang dibaca kalangan bawah di masyarakat. Disadari betapa orang-orang NU perlu menikmati tulisan bagus, pemikiran mencerahkan, termasuk dari Gus Dur.
Bagi santri dengan latar tradisi agraris, pemikiran Gus Dur memang terkadang menjulang ketika dibaca di Prisma dan Kompas. Namun, dengan bahasa bergaya renyah, dengan mudah dipahami pada kolom-kolomnya di Tempo dan suratkabar Harian Pelita. Begitu “gila” pada Gus Dur, saya alami. Jauh sebelum menerjuni profesi jurnalistik saya sempat mengalami kecelakaan, patah tulang di pangkal baha sebelah kiri. Untuk memulihkannya, harus dioperasi dan dipasang pen dengan jahitan 16 titik. Pada saat dioperasi di satu Rumah Sakit di Mojokerto, bagian luka dibius terlebih dahulu. Saat tak sadarkan itulah, saya merasa sedang melakukan wawancara Gus Dur. Saat tersadar dan mulai terasa panasnya bagian tubuh yang tersayat alat operasi itu, saya baru tahu: ternyata hanya mimpi bertemu Gus Dur dan wawancara itu merupakan pengalaman bawah sadar.
Meski tak terhitung berapa kali melakukan liputan pada kegiatan Gus Dur di Surabaya selama menjadi Ketua Umum PBNU, hanya beberapa kali berkesempatan melakukan wawancara khusus. Lebih banyak bareng-bareng. Karena itu, ketika menggarap produksi video klip guna mendukung peresmian Museum NU, pada pertengahan 2004 saya harus wawancara Gus Dur. Tetap dengan semangat dan ceria, meski pada waktu itu bertepatan hari Idul Fitri. Saya harus meninggalkan keluarga dan orangtua demi mendapat gambar dan penjelasan dari Gus Dur. Untuk produksi video klip Museum NU, kami juga melakukan serangkaian wawancara dengan K.H. M. Yusuf Hasyim, KH Amanullah di Tambakberas, KH Aziz Masyhuri di Denanyar, Jombang. Juga dengan Cak Anam, sebagai penulis sejarah NU dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama. Berperan dalam pengambilan gambar untuk video adalah Aam Amrullah, yang saat itu sebagai penata desain koran Duta Masyarakat. Narasi untuk video klips itu, saya susun sendiri sekaligus sebagai sutradara, dengan produser Mokh. Kaiyis.