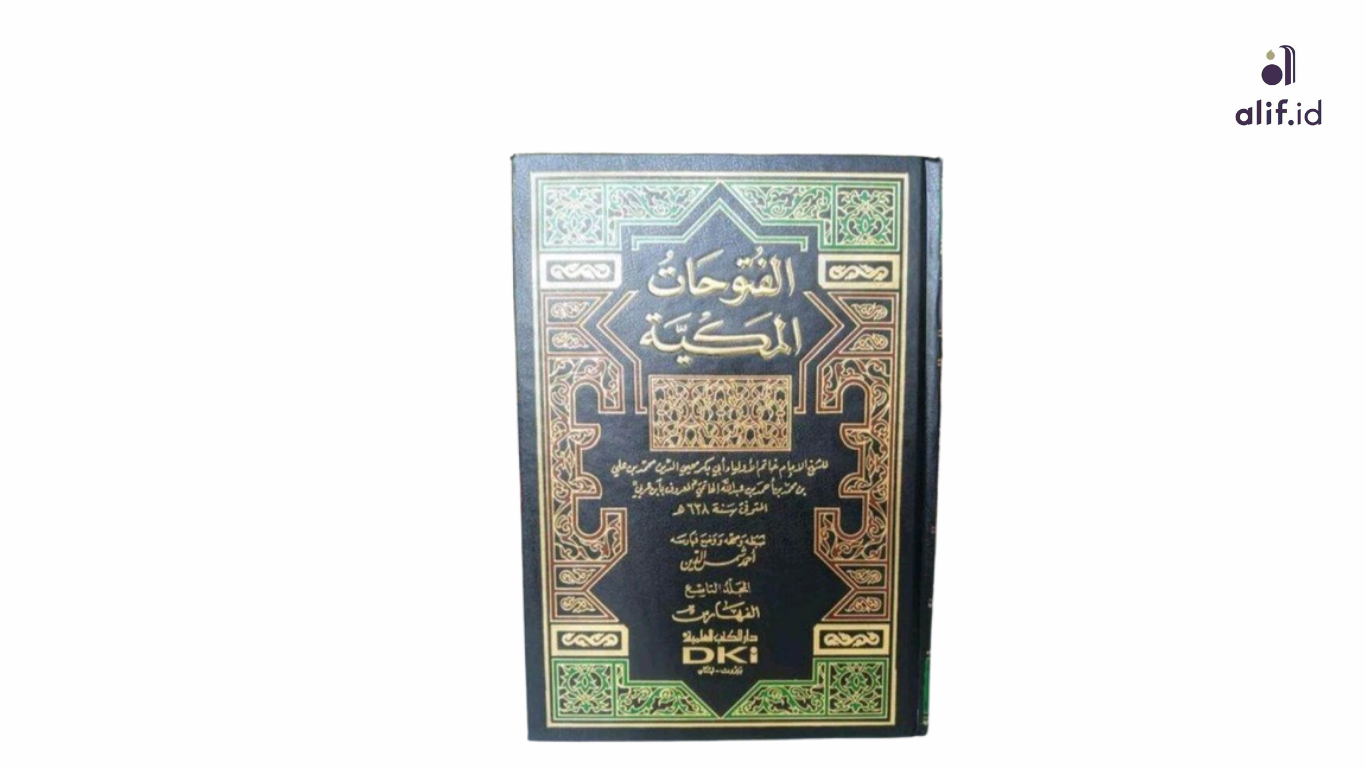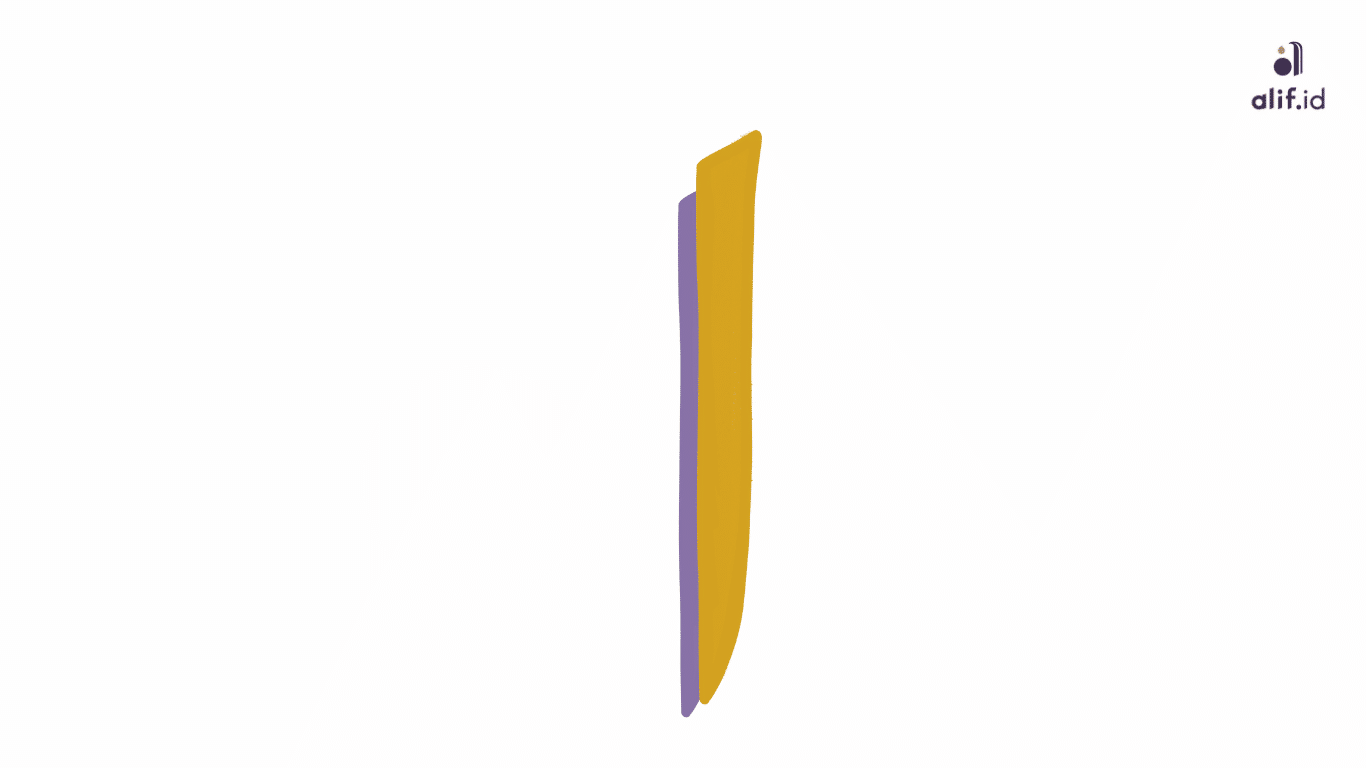Dalam sejarah perkembangan Tasawuf, minim sekali munculnya sosok sufi-sufi wanita. Seolah-olah keheningan dzikir hanya dimiliki oleh kaum lelaki. Mungkin, hanya Rabi’ah Al-Adawiyah―satu-satunya sufi perempuan yang paling dikenal serta diingat banyak orang. Padahal, tidak sedikit sufi-sufi wanita yang memberi warna dalam ajaran-ajaran Tasawuf. Syaikh Abu Abdurrahman as-Sulami (w 412) dalam Dzkr an-Niswah al-Muata’abbidat ash-Shufiyat mencatat―setidaknya terdapat 82 sufi wanita terkenal yang berhasil ia kumpulkan.
Karunia Allah, terutama berkaitan dengan maqamat Tasawuf, tidak pernah mengenal waktu, tempat, usia, maupun gender. Siapa pun―tua atau muda, Arab atau Ajam, pria atau wanita mempunyai potensi yang sama dalam menggapai berbagai maqomat. Dengan catatan, harus bersungguh-sungguh dalam mujahadah di jalan Allah. Karena itu, Abdurrahman Jami (w 899) ketika mengawali risalahnya―Nafahat al-Uns―telah mengutip syair Al-Mutanabbi (w 354),
“Seandainya semua wanita seperti yang telah kami sebutkan,
Niscaya kaum wanita akan lebih diutamakan atas pria
Feminitas kata matahari bukanlah celaan
Dan maskulinitas bukanlah kehormatan bagi bulan” (Rkia A. Cornel; 2004)
Dalam banyak sisi, kaum hawa mempunyai nilai plus dibanding pria. Mereka lebih halus―lebih peka dalam urusan perasaan. Dan ini memudahkannya untuk menerima doktrin-doktrin Tasawuf. Karena, seperti dikatakan oleh banyak ulama―dunia olah rasa (dzauqiyah)―merupakan dimensi penting dalam Tasawuf. Dengan modal kehalusan rasa disertai kesungguhan tekad, tidak sedikit perempuan yang dapat meraih maqam tinggi. Bahkan dalam banyak kasus, maqam yang mereka raih melebihi sufi pria.
Jika ditelaah lebih jauh, corak Tasawuf kaum hawa bermuara pada dua jenis maqam; Cinta (Hubb) dan Rindu (Isyq). Dua hal yang tidak jauh dari naluri dasar mereka sebagai seorang wanita.
Maqam Cinta (Hubb)
Cinta yang dimaksud tentu adalah cinta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kecintaan hamba kepada Allah tidak memiliki kecenderungan apapun, selain ingin berdekatan dengan-Nya. Itu disebabkan Allah merupakan realitas tertinggi, sempurna, kekal, dan satu-satunya. Selain Allah―pasti bergantung dengan keberadaan-Nya. Hamba yang mencintai Allah akan tenggelam―luruh dalam samudera-Nya. Setidaknya selalu mempunyai orientasi untuk selalu mendekat kepada Allah.
Maqam Cinta dalam banyak literatur, sangat mendominasi corak sufisme wanita. Rabiah Al-Adawiyah (w 185) sufi dari Bashrah dengan hasrat cinta kepada-Nya yang meluap-luap, menjadi rujukan utama dalam maqam ini. Dalam sebuah kesempatan, Rabi’ah pernah bersenandung ketika ditanya tentang hakikat keimanannya oleh Sofyan At-Tsauri,
“Aku mencintai-Mu dengan dua cinta
Cinta yang tumbuh karena nikmat
Dan cinta karena engkau adalah yang berhak untuk dicinta
Aku tidak menyembah-Mu karena takut neraka atau ingin surga
Tapi karena aku mencintai-Mu.”
Pada kenyataannya, cinta memang tidak pernah berdiri sendiri, selalu ada sebab-sebab yang turut membingkainya. Sebuah ungkapan populer mengatakan, ‘tak kenal maka tak sayang’. Manusia tidak akan mencintai kecuali terhadap apa yang telah diketahuinya. Syaikhah Lubabah Al-Abidah, seorang sufi wanita dari Syiria―pernah mengatakan sebab-sebab hamba tenggelam dalam samudera cinta-Nya,
“Pengetahuan tentang Tuhan melahirkan cinta kepada-Nya; cinta kepada-Nya melahirkan kerinduan kepada-Nya; kerinduan kepada-Nya melahirkan keakraban kepada-Nya; keakraban dengan-Nya melahirkan keteguhan dalam mengabdi kepada-Nya dan menaati hukum-Nya.” (As-Sulami: 2004)
Senada dengan Lubabah, Ubaydah binti Kilab juga menegaskan hal yang sama. Namun, yang sedikit berbeda, ia menekankan totalitas dalam pengamalan yang disertai dengan pengetahuan. Sufi wanita dari desa ath-Thufawah―sebuah desa badui dekat kota Basrah―itu berkata,
“Apabila orang telah sempurna taqwanya dan pengetahuannya tentang Allah, maka tak akan ada sesuatu pun yang lebih dicintainya selain berjumpa dengan Tuhannya dan berdekatan dengan-Nya”
Maqam Rindu (Isyq)
Setelah cinta bersemayam, bahkan menguasai kesadaran manusia. Maka kerinduan terhadap yang dicintai akan mengalir deras dari relung rasa. Karena cinta tak ubahnya api yang membakar dan rindu adalah asapnya.
Dus, maqam rindu bukan sekadar fase psikologis dalam perjalanan sufi. Rindu adalah kegoncangan hati untuk menemui yang dicintai. Kerinduan tergantung akan dalamnya cinta, demikian kata Imam Al-Qusyairi. Kerinduan itu baru bisa reda dengan bertemu dan melihat yang dicintai. Rindu yang membara tidak mungkin bisa timbul tanpa penglihatan yang nyata―dan penglihatan menuntut adanya sebuah pertemuan.
Dalam konteks rindu kepada Allah, nikmat yang utama adalah perjumpaan dengan-Nya, tidak ada yang lain―bahkan surga sekalipun. Rindu menjadi manifestasi kuasa paling murni; penolakan segala bentuk kekuasaan selain kekasih itu sendiri. Rayhanah Al-Walihah, seorang wanita yang ahli ibadah dari Bashrah pernah bersenandung,
“Tuhan. Begitu lama aku merindukan-Mu. Hatiku tak mau mencintai apapun selain-Mu. Wahai kekasihku, cita-cita dan sasaran kebahagianku. Rinduku tak ada akhirnya, kapan akan bertemu dengan-Mu? Sama sekali aku tak memohon nikmat surga. Aku hanya ingin bersua dengan-Mu.”
Bahkan seringkali kerinduan mengakibatkan tumpahnya air mata. Tetesan air mata yang keluar dari hati yang terdalam (fuad). Karena dalam rindu, selalu ada jarak. Keterpisahan dari Allah―meskipun sesaat―bagi para sufi merupakan musibah, dan perlu ditangisi. Tangisan mereka bukan kelemahan―melainkan rahasia rindu kepada Maha Cinta, tak kuat menahan bara rindu yang tak kunjung padam. Ghufayrah Al-Abidah, seorang wanita ahli ibadah dari Bashrah adalah contoh nyata tentang hal ini. Ia selalu menangis hingga menyebabkan kebutaan terhadap kedua matanya. Seorang laki-laki pernah mencela Ghufayrah,“Alangkah sengsaranya kebutaan!”. Sementara ia dengan tenang menjawab, “Terhijab dari Allah adalah lebih buruk. Dan kebutaan hati dari memahami maksud perintah-perintah Allah adalah lebih buruk lagi”.
Seperti halnya Ghufayrah, ada Sya’wanah al-Ubullah wanita yang tiap hari menangis, bahkan tangisannya mampu menggiring orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sufi yang mempunyai suara nan indah dan merdu ini pernah berkata, “Dapatkah mata tak dipisahkan dari kekasihnya dan rindu untuk bersatu dengan-Nya tanpa menangis? Itu tidak akan bisa terjadi”.
Alhasil, wanita mempunyai bahasa spiritualnya sendiri. Mereka tidak melulu memekikkan doktrin, tetapi mengaktualisasikan dalam perilaku keseharian. Sufisme perempuan bukan tentang ingin disetarakan, apalagi dibedakan. Tidak. Tetapi mengingatkan bahwa dalam menuju Tuhan (suluk) tidak pernah mengenal jenis kelamin. Yang ada hanya keikhlasan dalam bentuk cinta dan kerinduan. Dan seringkali, keikhlasan dalam bentuk ini, justru paling jernih ditemukan dalam hati seorang wanita yang diam-diam mencintai-Nya. Wallahu a’lam.
Bahan Bacaan
Abu Abdurrahman As-Sulami, 2004, Sufi-Sufi Wanita: Tradisi yang Tercadari, Bandung: Pustaka Hidayah.
Abul Qasim Al-Qusyairi An-Naisaburi, 2013, Risalah Qusyairiyah, Jakarta: Pustaka Amani.
Al-Hujwiri, 2015, Kasyful Mahjub; Buku Daras Tasawuf Tertua, Bandung: Mizan.
Imam Al-Ghazali, 2009, Ihya’ Ulumiddin vol 8, Semarang : CV As-Syifa’.