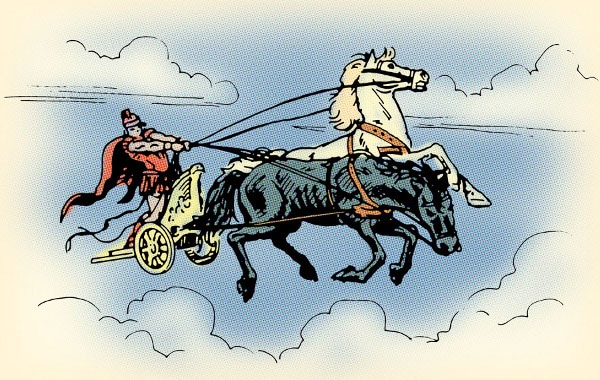
Februari 1989. Ketika itu Amerika Serikat beranjak dari musim dingin ke musim semi, menandakan hari akan lebih cerah dan berwarna. Francis Fukuyama yang masih berusia 36 tahun, menyampaikan kuliah umum di Universitas Chicago. Tidak banyak yang hadir, serta tidak ada tanggapan yang betul-betul serius atas ceramahnya.
Kecuali seorang editor majalah kecil di Washington bernama The National Interest. Owen Harries, editor itu, menerbitkannya dengan judul “The End of History?” Cuaca benar-benar cerah.
Tepat dua bulan sebelumnya, pada 7 Desember 1988 Mikhail Gorbachev berpidato di sidang PBB, bahwa Uni Soviet tidak akan campur tangan lagi pada negara-negara di Eropa Timur. Mereka dibebaskan untuk menjalankan pemerintahan secara demokratis. Pidato ini menjadi penanda awal dari akhir Perang Dingin.
Argumen, atau sejenis ramalan, Fukuyama sejatinya sederhana. Kejatuhan Uni Soviet menandakan pilihan ideologi selain liberalisme telah hilang. Fasisme berserakan bersama puing-puing Perang Dunia II. Di negara seperti China yang menyebut diri berideologi komunis, reformasi ekonomi dan politik justru mengarah pada tatanan liberal.
Jika melihat lambang-lambang strategis liberalisme didirikan—keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan, pasar bebas, budaya konsumerisme—bisa dikatakan sejarah telah mencapai titik puncaknya. Beberapa peristiwa mungkin menyimpang, tapi itu kebanyakan terjadi di negara-negara kecil yang tidak memiliki kuasa pada dunia, bahkan diri sendiri.
Tulisan Fukuyama tetap saja belum mendapatkan pembaca yang banyak dan signifikan. The National Interest hanya majalah kecil yang tidak dibaca oleh ilmuwan dan politikus. Majalah tersebut, pertama kali terbit pada tahun 1985 oleh Irving Kristol, seorang tokoh terkemuka ideologi neokonservatisme. Pada tahun 1989 sirkulasinya hanya enam ribu. Fukuyama sendiri hampir tidak dikenal, kecuali oleh kalangan terbatas pemerhati Uni Soviet.
Tetapi klaim “akhir sejarah” diangkat dalam media arus besar, profil Fukuyama secara khusus diterbitkan di New York Times Magazine. Artikelnya diperdebatkan di Inggris dan Prancis, serta diterjemahkan ke banyak bahasa, dari Jepang ke Islandia, bahkan juga Indonesia. Argumennya dibangun dari tesis yang penuh perdebatan, dan masih banyak yang memandang skeptis pada ramalannya.
Namun entah mengapa, momentum sejarah mendukung Fukuyama. Artikelnya terbit sebelum Revolusi Velvet di Cekoslowakia, dan sebelum keruntuhan Tembok Berlin pada November 1989.
Beberapa peristiwa masih simpang siur ketika itu, antara kebijakan dalam negeri Gorbachov dengan kekeliruan-kekeliruan strategi luar negeri Amerika. Namun ramalan Fukuyama benar-benar terjadi. Majelis Agung Uni Soviet membubarkan diri pada 26 Desember 1991.
Ramalan Fukuyama benar, tetapi justru di titik itulah ia melupakan, atau bisa jadi mengesampingkan, beberapa peristiwa lainnya. Di dalam The End of History, Fukuyama sama sekali tidak menyinggung tentang Tragedi Tiananmen di China. Mungkin karena rentang waktu tragedi itu dengan penulisan Fukuyama sangat dekat. Tetapi bahkan diskusi-diskusi lanjutan tidak pernah melihat China dalam posisi strategis. Meski banyak yang mulai menganggap China, bukan Rusia, sebagai kekuatan yang perlu diperhitungkan di masa depan.
Kesalahan utama Fukuyama adalah pandangannya yang Eropasentris. Begitu juga politik luar negeri Amerika yang dalam beberapa hal berangkat dari artikel Fukuyama. Bagaimana, misalnya, negara itu menginterpensi negara-negara di Dunia Ketiga dengan cara yang sama: aksi demonstrasi mahasiswa. Hampir keseluruhan berhasil, salah satunya di Indonesia. Tetapi bagi negara yang lebih kuat, justru menjadi serangan balik bagi Amerika.
Bukti Eropasentris Fukuyama yang lain adalah kebangkitan Islam, demikian tulis Hasyim Wahid dalam buku tipis Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia (LKiS, 1999), buku yang ditulis setelah aksi reformasi mahasiswa. Dalam buku itu, Hasyim Wahid menjelaskan kemungkinan Islam sebagai ideologi ketiga, setelah liberalisme Amerika dan komunisme China, menjadi salah satu kekuatan besar dunia di masa mendatang.
Hal ini ada benarnya. Tetapi Amerika lebih bisa mengendalikan penyebarannya dengan mengacaukan politik di negara yang berpotensi menjadi kebangkitan Islam. Terakhir gerakan massa pada tahun 2016 lalu, merupakan salah satu bentuk pelemahan kekuatan Islam di Indonesia, dengan membangkitkan masyarakat menengah urban yang tidak memiliki fondasi agama kuat untuk mengambil alih bendera agama.
Dua puluh sembilan tahun setelah ceramah Fukuyama di Universitas Chicago, tampaknya sejarah tidak menghendaki perubahan yang terstruktur. Justru realisasi liberalisme belum ke mana-mana. Demokrasi liberal dan perdagangan bebas masih sangat rapuh, kecuali budaya konsumerisme yang memang telah mewabah ke seluruh dunia. Terdapat hal-hal prinsipil yang tidak sesuai dengan liberalisme.
Fukuyama berasumsi telah mengetahui gejala kontemporer, yang jawabannya dituliskan di dalam buku Identitiy: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment (Farrar, Straus &Giroux, September 2018). Tuntutan martabat, atau politik identitas, menurut Fukuyama, adalah sebab utama ketidakpuasan global pada kapitalisme liberal: Vladimir Putin, Osama bin Laden, Xi Jinping, live matter, gerakan #MeToo, pernikahan gay, ISIS, Brexit, kebangkitan nasionalisme Eropa, gerakan politik anti-imigrasi, politik kampus, dan pemilihan Donald Trump.
Fukuyama menariknya sampai masa Reformasi Protestan, revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Komunisme China, gerakan feminisme, multikulturalisme, pemikiran Luther, Rosseau, Kant, Nietzsche, Fredu, dan Simone de Beauvior. Hanya dalam buku yang tidak lebih dari dua ratus halaman. Semuanya diulas menggunakan teori Plato dalam Republic.
Gejala kontemporer itu bernama “Thumos”. Dalam teori Plato, manusia bisa hidup bahagia jika tiga unsur terpenuhi: ephitumia, thumos dan logistikon. Ephitumia adalah hasrat naluriah manusia yang harus terpenuhi seketika itu juga. Ephitumia di badan bagian bawah, seperti makan, minum, seks, dan uang.
Sedangkah thumos adalah hasrat manusia untuk dilihat, dihargai dan dipuji. Thumos berada antara leher dan dada. Sedangkan logistikon adalah rasionalitas manusia, sais yang seharusnya bisa mengatur laju ephitumia dan thumos.
Fukuyama beranjak dari Hegel menuju Plato. Dia menyadari, sejatinya logistikon bisa menjabarkan antara thumos dan ephitumia. Namun dalam beberapa hal manusia lebih membutuhkan pengakuan ketimbang ekonomi. Hal ini membuat hipotesa Fukuyama tidak lagi pada liberalisme klasik, beranjak dari ephitumia menuju thumos. Tesis ini seakan mengindikasikan bahwa apa yang sedang dikerjakan Vladimir Putin atau Xi Jinping misalnya, sama saja dengan perasaan seorang perempuan yang mengeluh karena potensinya dibatasi oleh diskriminasi gender.
Sejarah tak pernah henar-benar berakhir, dan terus bejalan bersisian dengan hasrat, keinginan dan kepentingan manusia yang diinstitusikan, diperdagangkan, dibenturkan dengan hasrat yang sama-sama kuat. Akan selalu ada yang menguasai dan dikuasai.














