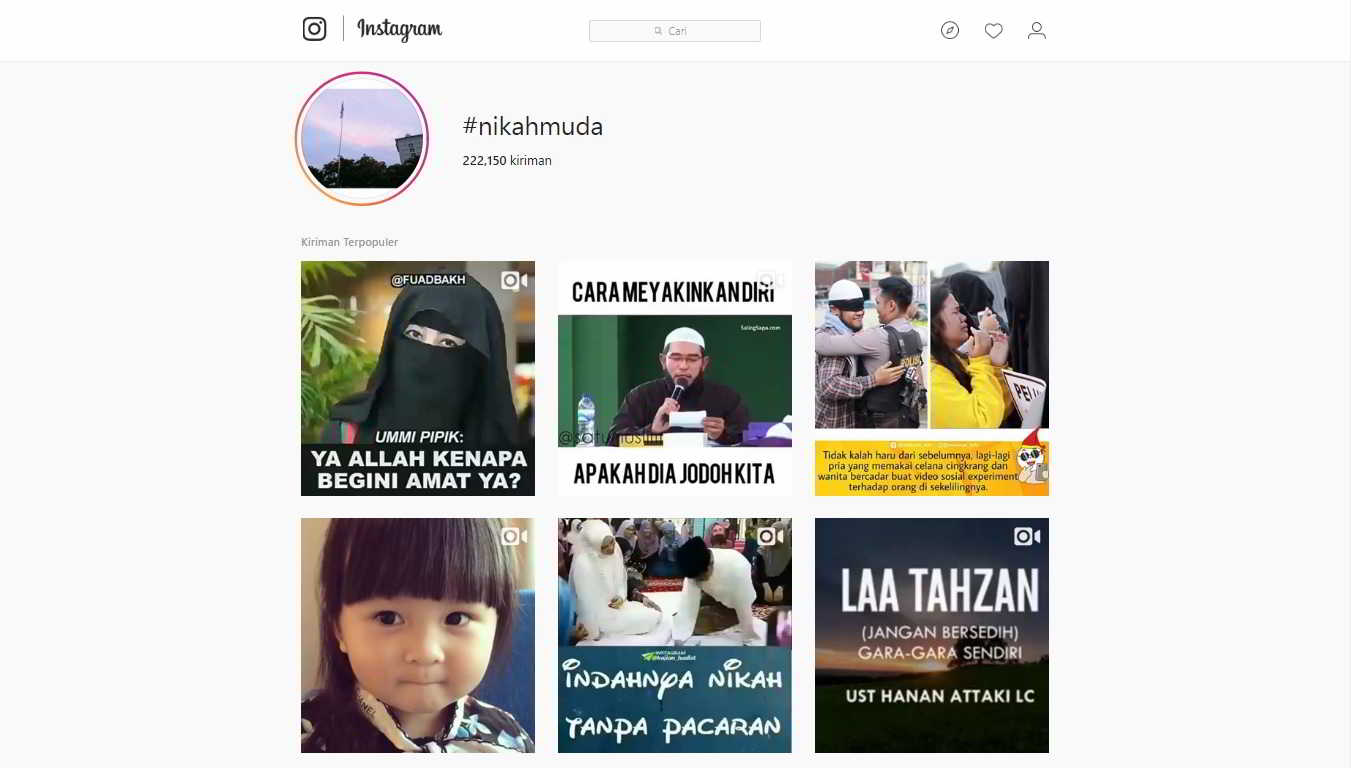Minggu pagi, 23 Desember 1928. Hujan lebat disertai angin ribut mengguyur Kota Yogyakarta. Jalan-jalan lengang. Suasana kontras terjadi di pendopo milik Raden Tumenggung Joyodipoera. Sejak pukul 8.30 pendopo luas yang biasanya untuk pertunjukkan seni maupun pertemuan partai politik itu ramai didatangi perempuan.
Rangkajo Chairoel Samsir Datoek Toemenggoeng, utusan Ch. O. Van der Plas (pejabat penasihat urusan pribumi), melaporkan ada sekira seribu perempuan berkumpul di sana. Kedatangan mereka seperti aliran sungai.
"Begitu banyaknya, kursi-kursi tak kelihatan lagi, yang terlihat hanya tubuh manusia. Sungguh, hujan yang turun di pagi itu menunjukkan bahwa sebetulnya kaum perempuan Indonesia juga sudah cinta pergerakan," tulisnya.
Setengah jam kemudian, hujan berhenti dan langit cerah. Pendopo gelap berubah terang. R.A. Soekonto, sang ketua, mengetuk meja tanda kongres hari kedua siap dimulai.
Kongres mendadak gaduh ketika pembicara kedua, Sitti Moendjijah, menyinggung hukum perkawinan Islam. Mubhalighah kondang utusan Aisyiyah sekaligus wakil ketua kongres itu diserang. Ia dianggap sebagai pembela standar ganda untuk laki-laki dan perempuan (Susan Blackburn, 2007: xxxviii).
Perdebatan sengit—dan terulang dalam kongres selanjutnya—itu meninggalkan kesan bahwa organisasi perempuan Islam seolah kurang progresif. Padahal, jika kita jeli membaca rekomendasi kongres, terlihat bahwa Aisyiyah aktif mengusulkan persatuan melalui pembentukan suatu badan perhimpunan perempuan se-Hindia Timur.
Selain itu, kader Aisyiyah yang mendominasi kongres juga tampak berusaha keras berbahasa persatuan; bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan "bahasa baru". Bahasa ini diambil dari bahasa Melayu yang kala itu menjadi lingua franca (bahasa pergaulan). Kongres Pemuda II 27-28 Oktober 1928 menetapkannya sebagai bahasa persatuan.
(Ber)Bahasa Persatuan
Sitti Badilah Zuber dalam sebuah bunga rampai yang disusun Lasmidah Hardi (1984: 100) menuturkan bahwa kesadaran akan bahasa persatuan sudah disadari Aisyiyah sebelum Kongres Perempuan I maupun Kongres Pemuda II.
"Gerakan Aisyah [sic] pun meluas ke Jawa Barat yang berbahasa Sunda dan ke Jawa Timur yang berbahasa Madura. Dirasa perlu adanya bahasa persatuan untuk memudahkan komunikasi dan bahan-bahan ceramah yang diberikan mudah dipahami."
Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu. Sehubungan dengan hal ini, Soeara Aisjijah yang berbahasa Jawa mulai tampil dengan dwibahasa (Jawa dan Melayu) per 1927. Sementara kongres kedua di tahun yang sama mendorong pelaksanaan kursus bahasa di setiap cabang dan ranting.
Aisyiyah juga terbilang giat menjalin kerja sama dengan organisasi perempuan lainnya. Salah satunya ialah Wanita Taman Siswa. Keduanya bahu membahu meningkatkan pengetahuan perempuan serta pemberantasan buta huruf di Yogyakarta.
Kegiatan kursus bahasa dan pemberantasan buta huruf yang dilakukan Aisyiyah itu sangat berarti. Pertama, belum banyak orang yang bisa berbahasa Indonesia. Laporan rahasia penasihat urusan pribumi tanggal 3 November 1928, misalnya, menyebutkan bahwa Kongres Pemuda II sepi dan tanpa tawa karena nyaris semua peserta belum bisa berbahasa bahasa persatuan. Sementara tak sedikit pembicara Kongres Perempuan Indonesia pertama yang membayar jasa pelatih bahasa. Kedua, keberaksaraan adalah kunci untuk memahami (ke)Indonesia(an).
Di masa penjajahan Jepang, kegiatan Aisyiyah dibatasi. Dakwah-dakwah tentang kedudukan perempuan dalam keluarga, agama, maupun negara dilarang.
Tak hanya itu, segala usaha sosial dipaksa berhenti. Naskah ceramah harus melewati pemeriksaan kempetei (polisi Jepang). Adapun kegiatan Aisyiyah sebatas membagi-bagikan beras dan pakaian. Amal yang masih disyukuri. Terlebih di tengah kemerosotan ekonomi karena peperangan.
Aktivitas Aisyiyah pulih seiring gema proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ekspresi manusia merdeka mereka wujudkan dengan menghias baju dengan peniti merah putih serta aktif mendatangi berbagai pertemuan untuk mengisi kemerdekaan.
“Begitu terdengar proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 dikumandangkan, Aisyah [sic] sudah siap melakukan tugas yang searah dengan jalannya Revolusi. Aku mengajak anggota lainnya menghias baju mereka dengan peniti merah putih. Mendatangi pertemuan mendengarkan pidato Pak Sayuti Melik mengenai Indonesia Merdeka dan persiapan membentuk barisannya di kalangan pria dan wanita, sipil dan militer,” demikian kenang Sitti Badilah Zuber (Hardi, 1984: 107).
Pada akhirnya, Aisyiyah pun menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya memberi mereka identitas baru sebagai manusia Indonesia. Lebih dari itu, identitas itu mereka buktikan dan hidupi dalam laku.