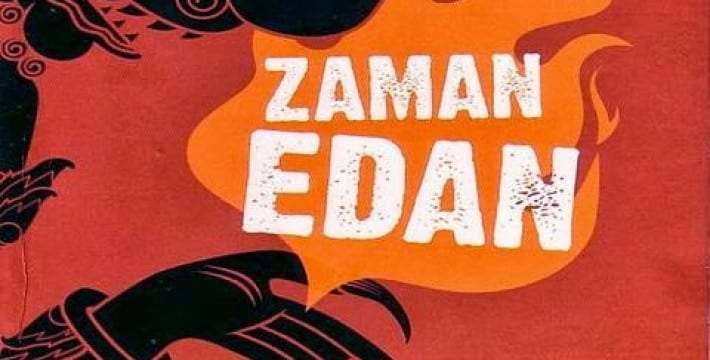
ADA segolongan manusia di dunia kita ini yang dikaruniai Pusaka Airmata oleh Tuhan Semesta Alam. Empat di antara segelintir mereka kita sebut saja Teresa, Gandhi, Dalai Lama, dan Gus Dur.
Airmata para manusia ajaib itu, bagai pusaka bagi usianya. Airmata bagi mereka, seolah tak pernah berhenti mengalir dan terus menjebol relung jiwa umat manusia hingga berbuah kebaikan, kedamaian, ketulusan, tenggang rasa, kasih-sayang, juga cinta.
Hanya dengan diam dan sorot mata yang teduh, Gandhi membungkam kebanalan 300-an juta penduduk India yang saling bertikai atas nama Hindu, Sikh, Jain, dan Islam. Ia tak lelah mengajar(k) rakyatnya menyelam lebih dalam ke diri sendiri. Melakukan penemuan sejati tentang hakikat hidup ini. Pertikaian, kendati dilambari menang-kalah & salah-benar, tetap saja bernama pertikaian. Sebuah upaya serius mengotori kesucian hati dengan merasa benar sendiri.
Memang tak semua manusia beroleh rahmat khusus dari tuhan sebagaimana empat manusia istimewa itu. Namun setidaknya era kita ini pernah melahirkan-menghidupi mereka. Kita wajib belajar dari keteladanannya. Airmata mereka tak tumpah siasia. Mereka tak sekadar menangis. Tak cuma bersedih. Tapi memberi sumbangsih besar pada peradaban kita dengan kucuran airmata yang membasahi ketidakadilan, hingga merembes sempurna jadi nilai luhur kehidupan–yang bagi kebanyakan manusia, dianggap rongsokan sejarah.
Kita beralih ke riwayat keanehan yang lain. Semasa remaja dulu, kami sering terpesona dengan sebuah serial televisi berjudul Highlander. Film yang dirilis pada 7 Maret 1986 dan disutradarai oleh Russell Mulcahy ini, menceritakan kisah perjalanan Connor MacLeod (diperankan Cristopher Lambert).
Ia merupakah salah seorang anggota Kaum Highlander dari Skotlandia. Kaum Pemukim Ketinggian ini tidak akan mati kecuali bila kepalanya dipisahkan dari tubuh. Di negeri kita lazim disebut rawa rontek.
Sejarah tentang mereka, kemungkinan bertautan dengan para Qalandar dari Dunia Islam–yang saat itu sedang berada di puncak kemahsyuran. Sebagian besar qalandar berasal dari kalangan sufi yang jadi Waliyullah. Mereka hidup melintasi zaman. Mengendarai ruang-waktu. Para penyintas ini dipimpin Manusia Hijau yang paling misterius di jagat dunia: Nabi Khidr as.
Berpuluh tahun kemudian sejak menyaksikan film Highlander, ternyata perjalanan hidup membawa kami pada pertemuan menakjubkan dengan golongan qalandar di negeri ini. Setidaknya kami telah menjumpai empat orang dari mereka. Seorang di perbukitan Kebumen, tiga lainnya di wilayah Banten.
Sosok terakhir yang kami temui di Tanara, berasal dari era yang sama dengan Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi’i (l. 1058 – w. 1111). Ia masih lelananging jagad bersama tigabelas orang yang lain. Perawakannya tinggi kekar. Tulang pembentuk tubuhnya, besar dan panjang.
Sosok manusia zaman lalu yang ia sembunyikan dalam dirinya, tersimpan pada sorot mata yang tajam & nada bicaranya yang bak samudera. Padahal usianya tampak seperti masih empatpuluhan. Kendati berhadapan dengan tamu yang jauh lebih tua, ia seketika terlihat pinisepuh–dan begitu santai menyebut diri sendiri dengan panggilan abah. Dalam pandang matanya, tergambar lautan waktu yang meruang seketika dalam satu saat.
Lantas apa tautan kisah para Qalandar di atas dengan mereka pemilik Pusaka Airmata itu? Jawabannya; kejanggalan, keganjilan, dan keanehan hidup yang sudah sedemikian misterius ini.
Mereka teguh menjalani hidup yang tak lazim–meski itulah yang sejatinya daim. Kata kuncinya; dari sekian banyak hal yang logis dan masuk akal, masih lebih banyak soal yang sulit dimengerti dan takkan bisa dipecahkan nalar.
Dalam kitab Syajaratul Kaun (Pohon Kejadian) karya Syeikh al Akbar Muhyidin Ibn ‘Arabi, tertera penjelasan berikut ini, “Allah menciptakan para pendosa, kesalahan yang mereka perbuat, dan taubat mereka, hingga dengan demikian terejawantahlah sifat-Nya yang Mahapengampun. Dia menciptakan kebaikan dan amalan mereka, kemudian menebarkan Rahmat-Nya atas mereka. Dia menciptakan para hamba-Nya yang taat dan melimpahkan Rahmat-Nya pada mereka. Dia mengejawantahkan keadilan-Nya kepada para pembangkang dan kemurkaan-Nya atas orang² tak beriman.”
Jadi, apakah Anda sudah menyadari betapa kehadiran kita di dunia ini adalah sebuah hadiah dari ketiadaan semata? Sudah tiada tapi malah mengada-ngada. Hahahaha… Maaf jika makin membingungkan. Bocoran dari Ibn ‘Arabi tersebut, kiranya bisa jadi petunjuk bagi kita betapa segala yang dianggap rasionalitas hidup, sejatinya merupakan irasionalitas yang sarat kegilaan. Ya, dunia fana ini hanya bisa dimengerti oleh mereka yang standar gilanya menyerempet kejeniusan. Mereka yang masuk kategori jenius, tapi dianggap gila oleh para pemangku kepandiran.
Mereka belajar sebagai murid, dari guru yang adalah diri pribadi. Mereka menjadi Guru, dari murid yang diri pribadi. Tempat belajarnya (pelajaran mereka), penderitaan makhluk. Ganjarannya, kebaikan dan keharuman nama sesama.
Seorang gila yang dicatat Abul Qasim an Naisaburi dalam magnum opusnya, ‘Uqalaul Majanin–dari masa seribuan tahun silam, Aban ibn Sayar ar Raqi, pernah berkata, “Demi Tuhan manusia. Ada yang lebih gila dariku, yakni: yang membeli dunia dengan agama.” Ujaran itu malah seperti memeras pesan dari sebuah ayat al Quran di bawah ini:
كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
“Demikianlah, tidak seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, “‘Ia adalah penyihir atau seorang gila.”‘ (QS az Zaariyat [51]: 52)
Akhir kalam, siapkah kita menjadi orang gila di tengah zaman edan, atau menjadi waras di dalam ketidakwarasan peradaban manusia? Silakan memilih. Kami mau ngopi dulu. []














