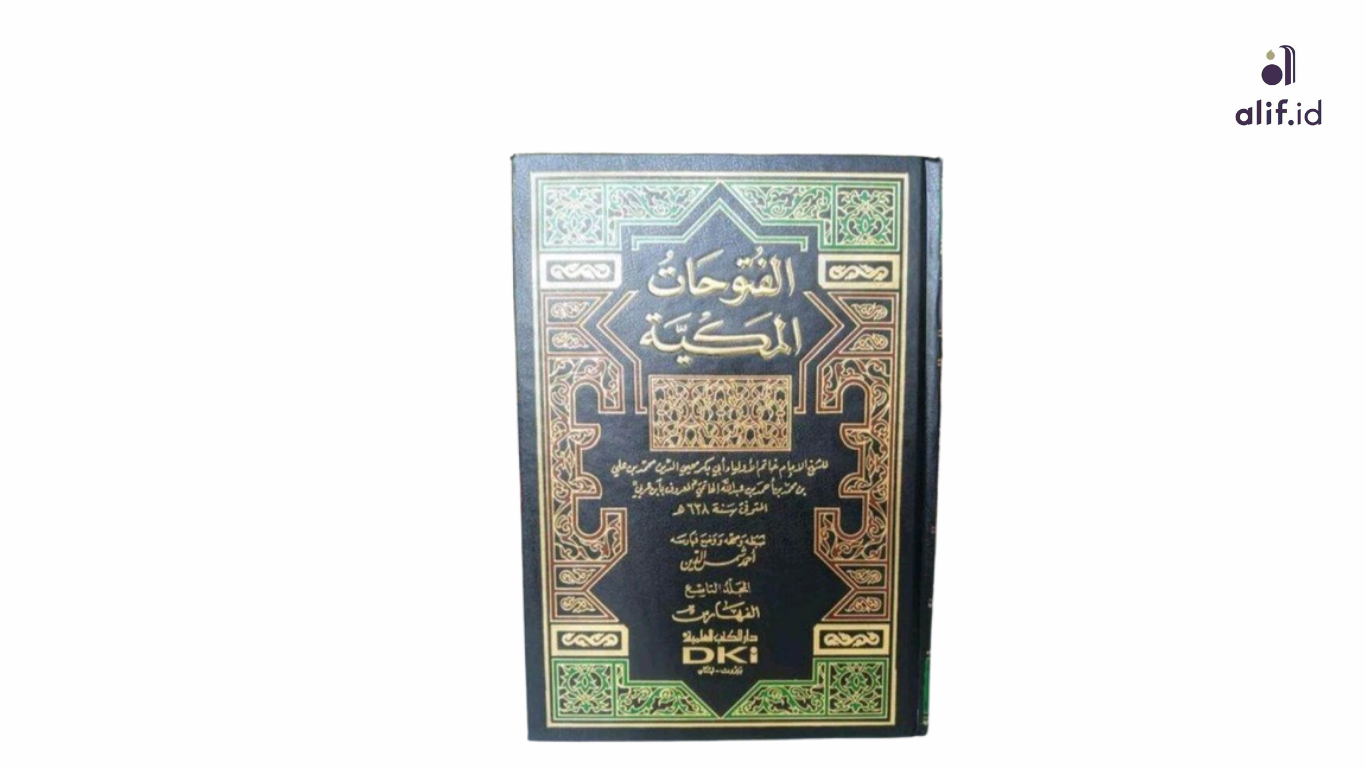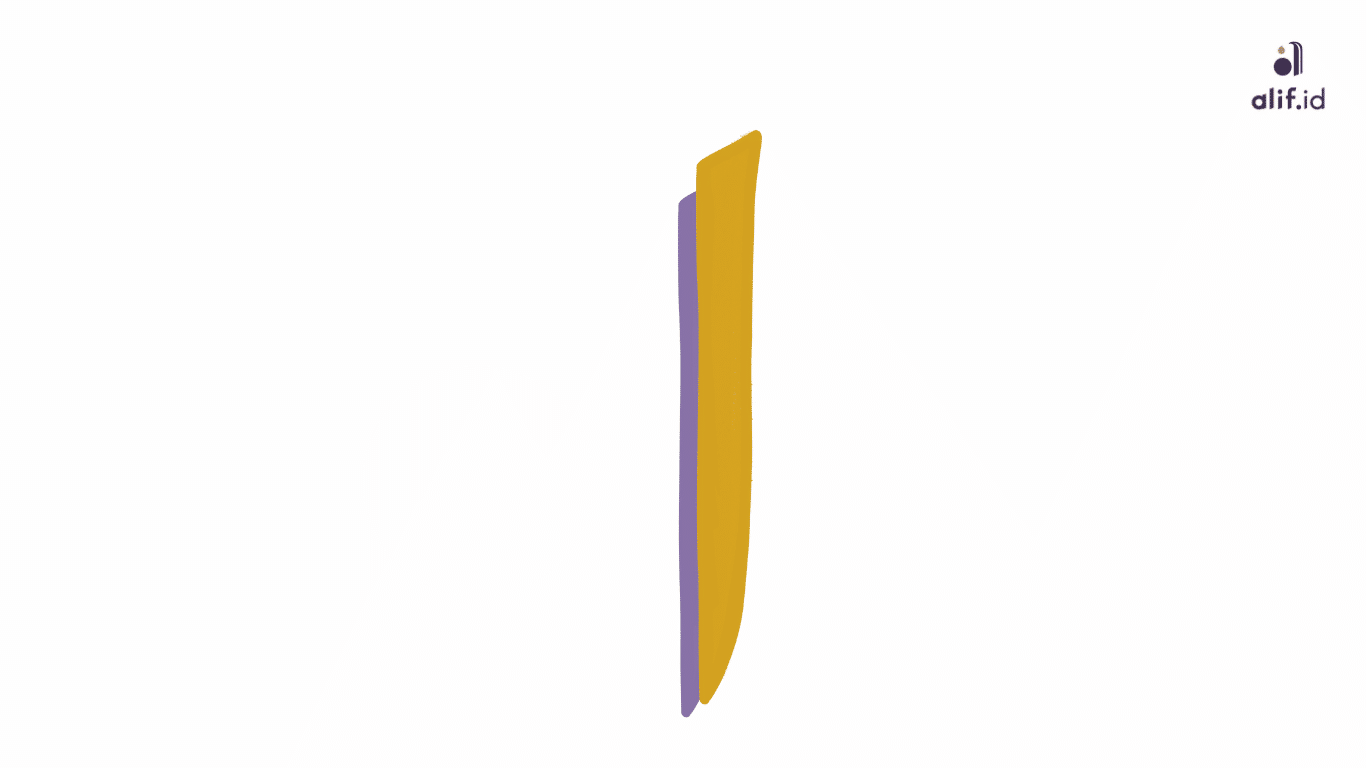Banyak kisah para bangsawan yang akhirnya, setelah berbagai kontribusinya terhadap raja dan keraton, memilih menyisih, menjadi sufi, dan membabarkan agama Islam. Kita mengenal Pangeran Benawa, putra sultan Pajang, Hadiwijaya. Juga ada Kanjeng Kyai Kasan Besari di Ponorogo. Pangeran Singasari pun melakukan hal yang sama.
Setelah membantu Pangeran Mangkubumi dalam usahanya mendirikan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Pangeran Singasari menyingkir ke Muntilan, Magelang, menjadi pembabar agama Islam dan akhirnya bermakam di Gunungpring. Ia terkenal dengan gelar Raden Santri.
Adakah istilah “santri” diderivasikan dari gelar yang disandangnya tersebut, tak ada keterangan yang pasti. Yang jelas, dalam catatan Bruinessen, data-data sejarah yang dapat diverifikasi tentang eksistensi beserta kurikulum pesantren pertama kali ditemukan pada pesantren Gebang Tinatar di Tegalsasri, Ponorogo, pada abad ke-18.

Saya mendekati situs Gunungpring melalui dua jalur: jalur keraton Yogyakarta dan jalur “sarkub” (baca: sarjana kuburan). Melalui jalur pertama ditemukan sejumlah nama yang masih memiliki galur Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang paling tenar adalah Raden Santri, Kyai Krapyak III, Kyai Harun dan Kyai Gus Jogorekso yang bernama lengkap Kyai Basah Damas Telung. Yang terakhir ini dikenal sebagai majdzub di mana dahulu pernah menjadi magnet di Gunungpring (Menyingkap Jadzab, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id/read/hs/menyingkap-jadzab-b222976p/)
Sementara dari jalur “sarkub” dikenallah seorang kiai mursyid sekaligus penghafal al-Qur’an, KH. Nahrowi Dalhar yang nasabnya bersambung ke Kyai Abdurrauf, salah seorang senapati perang Dipanegara di wilayah eks karesidenan Kedu, dan Kyai Hasan Tuqo, seorang keturunan Sunan Amangkurat Mas yang bernama asli Raden Bagus Kemuning. Merebak sebuah keyakinan di kalangan “sarkub” tentang situs Gunungpring yang memang lekat dengan pemberontakan Dipanegara.
Pada situs Gunungpring inilah salah satu aforisme al-Hikam mendapatkan manifestasinya. Kyai Dalhar sebagai seorang mursyid tarekat yang melewati segala jenjang maqamat dan ahwal-nya dan Mbah Jogo sebagai sang majdzub. Saya pun pernah terhenti pada tangga-tangga untuk menanjak dan menurun dari situs Gunungpring. Adakah mereka pernah bertemu, pada saat sang salik menanjak (taraqi) dan sang majdzub turun (tanazzul) sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Athaillah?

Dalam kitab yang dipandang kitab kasepuhan kalangan pesantren itu, ‘Athaillah, selain mengakui dan menjelaskan eksistensi para majdzub, tapi juga mengatakan bahwa karena para majdzub dalam wushul-nya pada Allah tak melalui jenjang maqamat dan ahwal selaiknya para salik, maka secara formal mereka tak dapat dijadikan mursyid.
Seperti halnya pendidikan yang butuh sistematika ataupun silabus, pendidikan tasawuf pun juga butuh hal itu. Dan tentu saja para majdzub tak dapat melakukan hal itu secara normal dan gamblang. Analoginya seperti seorang musikolog dan pemusik. Yang pertama jelas menguasai teori ataupun wacana musik, teknik beserta pedagogi para murid—meskipun tak selamanya ia jago bermain musik dan mampu menelurkan karya-karya yang bersifat masterpiece.
Tapi yang kedua, kadang saking jeniusnya, sampai tak mampu menjelaskan karya-karyanya sendiri, ia seakan hidup dalam dunianya sendiri yang tak dapat dengan mudah dimasuki oleh orang lainnya—seperti tiba-tiba bernyanyi dan menggenjreng gitar tanpa tahu apa nama chord dan genre-nya.

Pada titik ini orang sampai pada pembicaraan perihal piranti epistemologis manusia, tentang akal dan intuisi. Seiring perjalanan sejarahnya terdapat satu penilaian bahwa tasawuf adalah suatu bidang yang secara khusus menggeluti akhlaq. Banyak kitab tasawuf, dari Kasf al-Mahjub (al-Hujwiri), Awarif al-Ma’arif (al-Suhrawardi), Ihya’ ‘Ulumuddin (al-Ghazali), Tanwir al-Qulub (Amin al-Kurdi), semuanya mewedarkan perihal adab: adab murid ke mursyid, adab seorang mursyid sendiri, adab ber-suluk dan adab seorang hamba pada Tuhannya sebagaimana yang dibabarkan ‘Athaillah dalam al-Hikam.
Semuanya ini kemudian merujuk pada tasawuf yang bercorak ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah atau yang karib dikenal sebagai kalangan sunni. Secara umum tarekat-tarekat yang bercorak sunni memang menitikberatkan pada masalah akhlaq yang kemudian dikategorikan sebagai tarekat akhlaqi.
Tasawuf akhlaqi selalu saja mengidealkan hati sebagai piranti epistemologis manusia yang paling utama. Rumusannya sangat sederhana: ketika hatinya bersih idealnya bersih pula keseluruhan diri manusia. Karena itulah al-Ghazali pernah menganalogikan hati sebagai sebuah cermin: ketika cermin itu bersih, maka jelas pula segala sesuatu yang memantul darinya.
Ada dua karya sastra Jawa klasik yang terpengaruh—karena ditulis abad-abad sesudah al-Ghazali—filosofi cermin dari al-Ghazali, di mana hal ini menunjukkan bukti bahwa tak selamanya tasawuf nusantara bercorak filsafati, yang di samping menggunakan hati juga nalar, dan tak selamanya pula bahwa kapitayan itu identik dengan segala hal yang menyimpang dari nilai-nilai yang dibawa nabi Muhammad dan para penerusnya.
Hanya orang-orang picik yang menilai bahwa karena diungkapkan dengan bahasa Jawa, maka kapitayan dan ekspresi-ekspresi spiritualitas nusantara tak memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai keislaman yang diwedarkan oleh nabi Muhammad dan para sufi.
Mangkunagara IV, dalam Serat Wedhatama, pernah melukiskan peran dan fungsi hati secara indah: “Kedhap kilap liniling ing kalbu/ Kang minangka colok celaking Hyang Widhi.” Bahwa ketika hati itu sudah bening, maka dapat menjadi obor dalam mendekati Tuhan.
Adapun seorang murid dari Ki Kusumawicitra, pendiri Harda Pusara (Temali Sang Mahayogi, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id), pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Serat Kacawirangi. Kacawirangi yang dalam doktrin martabat 7 dikenal sebagai mir’at al-haya’i (cermin kemaluan), adalah sebuah kondisi yang pernah saya catat dalam Jalan Jalang Ketuhanan: Gatholoco dan Dekonstruksi Santri Brai (2011): “budinya sudah tak terhijab (kalingan) angan yang bertingkah (obahing angen-angen) dan rasa-nya sudah tak beriak (rasa wis ora kalimput kedhering rasa).”
Dengan demikian, tak selamanya karya-karya sastra Jawa klasik yang bersinggungan dengan masalah kasepuhan atau kasampurnan (baca: ketuhanan) bercorak filsafati yang condong ke paham wihdatul wujud. Hanya orang-orang yang tak paham, sekali lagi, yang mengartikan istilah sepuh ataupun sampurna berkaitan dengan sebentuk ambisi untuk menjadi manusia sempurna laiknya proyeknya Hitler dan Nazi.
Konsep insan kamil Abdul Karim al-Jili pun, yang terpengaruh Ibn ‘Arabi, tak mengartikan hal itu sebagai sebentuk upaya penciptaan ras yang murni dan tangguh. Sungguh sederhana sekali, di rahim sang ibu, manusia berproses melewati berbagai tahapan hingga tahap ke-7 di mana sang janin telah lengkap menjadi sesosok manusia dengan segala pirantinya—belum lagi tahapan-tahapan di rahim sang alam.
Ketika yang terkenal sebagai pujangga terbesar dan terakhir Jawa adalah Ronggawarsita banyak orang yang secara picik kemudian menghakimi spiritualitas yang berbasis budaya Jawa semuanya bercorak wujudiyah. Padahal, Ronggawarsita sendiri tak secara mutlak berpaham wujudiyah.
Sebagaimana pamannya, pengarang Suluk Acih (baca: Aceh) bernama Ronggasasmita, Ronggawarsita (dengan nama muda Bagus Burham) adalah juga penganut tarekat Syatthariyah yang di Aceh dibabarkan oleh Syekh Abdurrauf al-Singkeli dan di Jawa di wakili oleh Syekh Abdul Muhyi, Pamijahan, Tasikmalaya. Tarekat Syattariyah secara filosofis terpengaruh pemikiran Ibn ‘Arabi, Abdul Karim al-Jili, dan Syekh Burhanpuri, yang sama-sama mengetengahkan doktrin wihdatul wujud beserta martabat 7-nya. Tapi, secara formal, mereka tetap memiliki sanad keilmuan hingga Sayyidina ‘Ali.
Hal itu membuktikan bahwa di Jawa sejak abad ke-17, ketika Syattariyah hadir untuk pertama kalinya, paham wujudiyah dan ahlus sunnah sama-sama dapat hidup berdampingan secara leluasa sebagaimana Ronggawarsita, Mangkunagara IV, atau Paku Buwana IV, pengarang Serat Wulangreh yang sangat tampak berpaham ahlus sunnah. Konflik antara paham wujudiyah dan ahlus sunnah memang pernah terjadi di awal kesultanan Demak, antara Syekh Siti Jenar dan sebagian walisanga sebagaimana di Aceh yang sampai berujung pembakaran kitab dan pembantaian.
Dapat disimpulkan bahwa justru Syattariyah-lah yang mampu mengakomodasi kedua corak tasawuf itu sebagaimana Abdurrauf al-Singkeli yang tak berkubu sekaligus berkonflik baik dengan Hamzah Fansuri (ekspresi tasawuf wujudiyah) maupun Nuruddin al-Raniri (ekspresi neo-sufisme yang cenderung revivalistis dan puritan).
Di sinilah kemudian peran dari seorang Kalijaga (Kalijaga: Wulung yang Agung, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id) yang bernama lain Raden Margono tak dapat dianggap kecil. Ia adalah salah satu wali yang paling njawani sebagaimana tarekat Syattariyah yang dinilai Martin Van Bruinessen sebagai tarekat yang paling mempribumi (Kitab Kuning, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, 1995).
Peran Syattariyah pada perang Jawa (1825-1830) tak dapat pula dianggap remeh. Ia merupakan salah satu jejaring laskar Dipanegara di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia juga menjadi doktrin dasar dalam pemaduan berbagai tarekat.
Akmaliyah adalah salah satu tarekat yang memadukan dua tarekat yang berbeda, Syattariyah dan Naqsyabandiyah, yang dianut sebagian besar pelarian laskar Dipanegara. Di Muntilan, Magelang, Kyai Abdurrauf adalah salah satu senapati perang Dipanegara, meskipun cucunya sendiri, KH. Nahrowi Dalhar, menjadi mursyid dan pembabar tarekat Syadziliyah di Magelang.
Adapun jejaring di Jawa Timur merentang dari Pacitan (Syekh Yahuda), sampai di Malang (Eyang Jimat Suryangalam Tambaksegara) dan Banyuwangi (Ki Ageng Djoyopoernomo). Kedua nama terakhir mentransformasikan Akmaliyah menjadi paguyuban PDKK dan PAMU (Kawruh, Matahari dan Rembulan Kemanusiaan, Heru Harjo Hutomo, https://www.idenera.com).
Abdurrahman Wahid pernah mengabadikan pertemuan sekaligus perpisahannya dengan salah seorang sesepuh PAMU di Banyuwangi dalam secarik esainya, Kematian Seorang Pangeran, yang ia berani mengakui dan menjaminnya sebagai “saudara.” (SI)