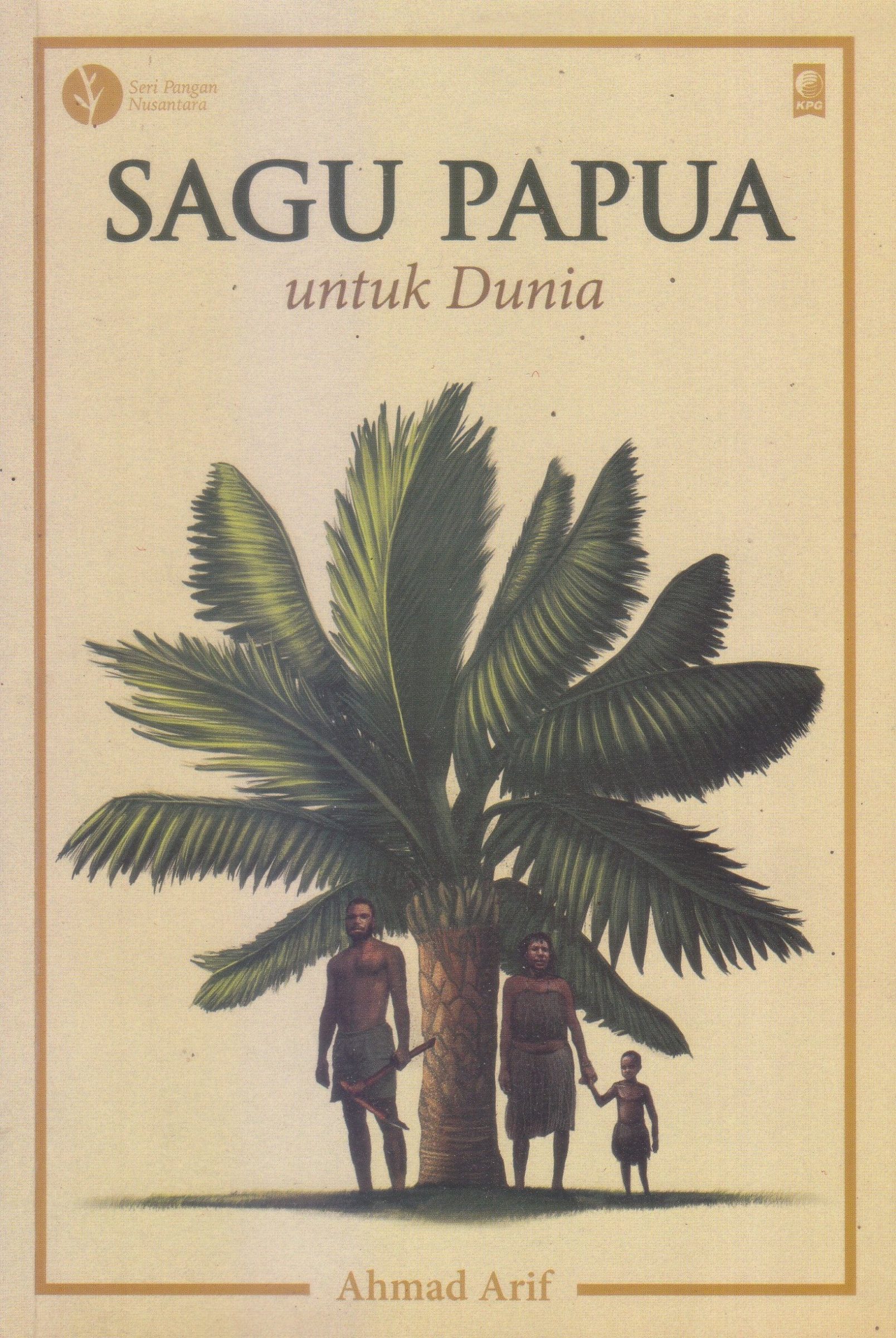Sejarah politik dan agama di Indonesia mencantumkan nama Junus Jahja di posisi terhormat. Ia ada di alur pemuliaan Indonesia dengan pilihan beragama Islam. Perbedaan tata cara untuk menjadi Indonesia pernah memicu polemik di masa pemerintah Soekarno dan Soeharto. Junus Jahja tampil di depan menjadi pendakwah, penganjur, dan penggerak.
Pada 1963, berdirilah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dengan ketua umum bernama Abdul Karim Oey. Perkumpulan itu berdakwah di kalangan Tionghoa. Seruan iman dan takwa digencarkan berbarengan situasi politik pelik.
PITI terus berkembang dan memiliki peran di awal pembentukan rezim Orde Baru. Keinginan memajukan dakwah memunculkan tokoh-tokoh penting. Junus Jahja menjadi pembeda. Semula, orang-orang masuk PITI cenderung dari kalangan tak mampu.
Junus Jahja masuk Islam (1979), memicu kalangan terpelajar dan elite turut menjadi Islam dan bergabung di PITI (Leo Suryadinata, Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia, 2010).
Di PITI, Junus Jahja jadi pengurus memiliki pengaruh besar. Nama pun mulai “berkibar” menandadi ada tema “baru” dalam perbincangan segala hal berkaitan peranakan Tionghoa: politik, bisnis, agama, dan pendidikan.
Ketokohan tercatat di buku berjudul Apa dan Siapa: Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982 susunan Tim Tempo. Dulu, ia bernama Lauw Chuan To, sebelum berganti nama menjadi Junus Jahja. Ia menjadi penggerak awal asimilasi.
Gerakan dimulai saat menempuh studi di Belanda masa 1950-an, tergabung di Persatuan Peladjar Indonesia. Sikap itu menandai “hakikat gong awal asimilasi.” Junus Jahja mengartikan itu babak sejarah terpenting sebagai manusia Indonesia. Babak penting lanjutan adalah keputusan masuk Islam, 23 Juni 1979. Ia pun lekas turut dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menunaikan haji pada 1980.
Espisode-episode hidup dicatat Junus Jahja dalam buku berjudul Catatan Seorang WNI: Kenangan, Renungan, dan Harapan (1988). Buku dokumentatif mengenai tokoh dan Indonesia. Dalih penulisan buku adalah pemastian pada orang-orang agar bangga berseru: “Aku Indonesia!”
Di buku, ia mengenang pemikiran dan gerakan diri bersama teman-teman di masa 1950-an. “Sewaktu kami di tahun 1950-an mencetuskan ide asimilasi sebenarnya prinsipnya sama. Yaitu menganjurkan dan melaksanakan pergaulan ‘campur’ pri-non pri secara intensif dan melembaga. Kami mulai menolak pergaulan atau cara berhimpun berdasarkan etnisitas, persamaan ras, dan ikatan darah,” tulis Junus Jahja.
Sejarah masuk Islam pernah menjadi kejutan meski kita mengerti pilihan memeluk agama Islam di kalangan peranakan Tionghoa di Nusantara sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Ketokohan Junus Jahja menjadikan peristiwa masuk Islam di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta, mengundang pelbagai komentar.
Pada masa Orde Baru, peristiwa itu justru menggamblangkan keinginan orang-orang mengerti menjadi Indonesia. Pengertian itu memang pernah agak rancu dengan sebutan WNI (Warga Negara Indonesia).
Di kalangan pergerakan, keputusan Junus Jahja mendapat sambutan baik. Keinginan memajukan asimilasi dan penentuan menjadi Indonesia berdasarkan religiositas sampai ke pemahaman inklusif.
Ia mendapat sepucuk surat dari sahabat berdinas di Amsterdam. Kita mengutip isi surat dari Gartiwa Surjaatmadja untuk Junus Jahja:
“Pertama-tama saya mengucapkan selamat masuk agama Islam yang saya anuti pula, meskipun saya sendiri ibadahnya secara bebas disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Kedua, saya kagum atas kerelaan dan keuletan karena Saudara. Ketiga, saya tercengang, sedikit kikuk karena tidak mengira sama sekali. Keempat, saya gembira karena saudara satu umat dengan saya dan seperjuangan dengan saya di segala bidang.”
Surat itu dianggap berkesan dan memberi penguatan dalam ikhtiar beriman-bertakwa dan menjadi Indonesia alias “aku Indonesia”.
Sejarah di Indonesia memang sering memunculkan sebutan atau diksi-diksi belum tentu terang dan rancu. Keinginan menjadi Indonesia dengan sebutan WNI tentu rancu dan mendapatkan penggamblangan di tahun-tahun kejatuhan rezim Orde Baru (1998). WNI tetap saja mengandung pembeda berkaitan cap pribumi atau non-pribumi. Sejarah itu ingin diralat setelah kejatuhan Soeharto melalui pelbagai studi, diskusi, dan gerakan bersama.
Sebutan agak membingungkan: “Muslim Tionghoa”. Dulu, sebutan itu wajar, tak terjebak di polemik sengit mengusung ribuan argumentasi. Junus Jahja memberi renungan dari pengawetan sebutan Muslim Tionghoa pada masa Orde Baru:
“Sebutan Muslim Tionghoa oleh umat dipakai sebagai semacam nama kesayangan bagi ikhwan barunya untuk antara lain menunjukkan kebahagiaan dengan mulai banyaknya keturunan Tionghoa yang memeluk Islam. Sebab kita semua tahu, tadinya seakan-akan Islam dan Tionghoa di Indonesia sangat jauh satu sama lain. Tapi, alhamdulillah, kini makin terasa bahwa Islam adalah agama universal yang pula untuk kawan-kawan keturunan Tionghoa.”
Pengakuan lembut dan terbuka. Ia menginginkan ada percakapan dengan bahasa saling “merangku” tanpa ada debat-debat tak keruan. Pengakuan sebagai orang Islam dan Indonesia memastikan misi asimilasi semakin maju. Kesadaran memilih bahasa dan menampilkan sikap dalam pembauran di masa Orde Baru memungkinkan keutamaan bersama, bukan perbedaan dijadikan pemicu sengketa, diskriminasi, atau perpecahan.
Kebersamaan menjadi Indonesia pernah ditunjukkan dengan pujian dan penghormatan pada Auwjong Peng Koen atau PK Ojong, pemeluk agama Katolik dan penggerak berpengaruh dalam pers di Indonesia. Tokoh itu dikenal dengan terbitan Keng Po, Star Weekly, Intisari, dan Kompas. Peran-peran di pers dan keintelektualan PK Ojong mendapat pujian dari Junus Jahja:
“Tapi yang almarhum tinggalkan bukan saja koran yang terbesar oplahnya di Indonesia, tapi juga segudang pemikiran yang cemerlang dan pengabdian yang tulus terhadap tanahairnya yang baru Indonesia.”
Kini, kita mengenang (lagi) Junus Jahja di lembaran-lembaran sejarah Indonesia. Mengenang saat hari-hari berhujan dan politik semakin sengit. Sejarah asimilasi itu berlangsung dengan pesan terbesar bagi kita agar penuh dan bergairah menjadi Indonesia. Begitu.