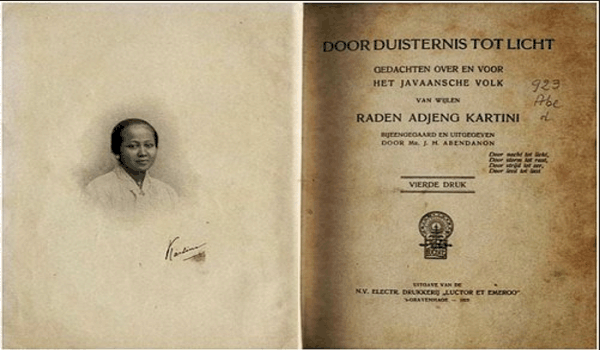
Nama Kartini kerap diasosiasikan dengan emansipasi perempuan, pendidikan, dan perlawanan terhadap feodalisme Jawa. Namun sayangnya, narasi publik tentangnya seringkali berhenti pada kutipan “Habis Gelap Terbitlah Terang”—yang sebenarnya bukan kata-kata Kartini, melainkan judul yang disusun Abendanon.
Jika kita mau dan mampu menilik lebih jauh, aspek paling mendalam dari Kartini justru terletak pada spiritualitasnya: seorang pencari iman yang kritis, pembaca Quran yang reflektif, dan sosok religius yang berakar kuat pada tanah dan tradisi lokalnya.
Kartini tumbuh di Jepara, kota pelabuhan kuno dan titik pertemuan budaya. Ia lahir dalam keluarga bangsawan Jawa yang hidup dalam tradisi Islam sinkretik—tempat kejawen, tasawuf, dan adat lokal menyatu dalam keselarasan. Surat-surat Kartini memperlihatkan ketertarikannya yang dalam terhadap Islam, bahkan saat ia mempertanyakan formalisme keagamaan yang menurutnya dangkal dan mekanis.
Dalam suratnya kepada Stella Zeehandelaar, 6 November 1899, Kartini menulis: “Di sini orang diajari membaca Al-Qur’an, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya… Saya menganggap itu pekerjaan gila; mengajari orang membaca tanpa mengajarkan makna yang dibacanya.”
Ini bukan cerminan sikap antireligius, tetapi upaya menggali makna iman secara jujur dan otentik. Bagi Kartini, agama tidak bisa dipisahkan dari pemahaman; ia bukan dogma untuk dihafal, melainkan jalan untuk menghidupkan jiwa.
Epistemologi Nusantara
Pertemuan Kartini dengan Kiai Sholeh Darat, ulama sufi Semarang yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Jawa dengan aksara Pegon, menjadi momen penting dalam pencarian spiritualnya. Saat memahami makna Al-Fatihah untuk pertama kalinya, Kartini merasa disinari terang. Di sinilah lahir kesadaran bahwa iman bisa membumi lewat bahasa sendiri, bukan hanya melalui Arabisasi atau kerangka Barat (“Kartini, Santriwati Kesayangan Mbah Sholeh Darat”, kemenag.go.id, 2021)
Pengetahuan dalam pandangan Kartini bukan monopoli Barat maupun ulama tradisional. Ia merumuskan Islam yang inklusif, reflektif, dan penuh welas asih. Baginya, Tuhan adalah yang mengilhami pencarian, bukan yang membungkam nalar. Spiritualitas Kartini bersifat eksistensial, menjadikan iman sebagai laku batin, bukan sekadar kepatuhan lahiriah. Ia menulis bahwa agama “harus menghidupkan jiwa,” bukan menundukkan akal.
Pendekatan spiritual Kartini merefleksikan epistemologi khas Nusantara, di mana kebenaran tidak datang dari otoritas dogmatis, tetapi dari pengalaman, permenungan, dan keterhubungan dengan alam serta sesama. Dalam kerangka ini, perempuan bukanlah objek hukum moral, melainkan subjek pengetahuan yang menentukan arah hidupnya.
Spirit ini menjadikan Kartini bagian dari lanskap religiositas lokal yang panjang—yang tampak dalam suluk pesantren, Serat Centhini, hingga tarekat pedalaman. Ia hidup dalam tradisi yang tak mengenal dikotomi Barat-Timur, Islam-kafir. Di tangannya, menyulam, membaca, berdoa, dan bermimpi menjadi satu tarikan napas spiritual. Kartini tidak mengasingkan diri dari Barat atau dari Islam, tetapi merajut keduanya dalam tenunan spiritualitas yang cair namun kokoh.
Sayangnya, banyak pembacaan terhadap Kartini kini terjebak dalam dua kutub ekstrem. Ia dimitoskan sebagai ikon nasional tanpa ruang kritis, atau disingkirkan karena dianggap terlalu liberal dan tidak Islami. Padahal justru kekuatan Kartini ada pada keberaniannya mempertanyakan, mencintai Islam tanpa harus tunduk pada tafsir dominan.
Dalam suratnya kepada Ny. van Kol (21 Juli 1902), ia menyatakan: “Saya bertekad memperbaiki citra Islam yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah.”
Pembebasan melalui Spiritualitas
Kartini bukan hanya melawan kolonialisme eksternal, tetapi juga dominasi internal dalam bentuk patriarki agama dan eksklusivisme pengetahuan. Ia menggagas pembebasan melalui spiritualitas, bukan dengan slogan ideologis, tapi dengan membumikan Quran dalam bahasa ibu dan mengangkat peran perempuan sebagai pelaku sejarah iman.
Ketika kita membaca ulang Kartini dalam konteks religiositas Nusantara, kita sedang membuka ruang baru bagi diskusi keberagamaan di Indonesia hari ini. Di tengah kebisingan purifikasi, politisasi, dan skripturalisme, Kartini menawarkan iman yang tidak represif, tidak identitarian, dan tidak bising. Bagi Kartini, iman adalah proses kontemplatif. Ia bukan ekspresi kuasa, tetapi kerja sunyi untuk memahami hidup.
Model religiositas Kartini ini senada dengan praktik spiritual tarekat yang menekankan zikir sebagai pengolahan batin, bukan sekadar ritus. Atau ajaran Wali Songo yang memadukan Islam, budaya, dan seni dalam satu tarikan napas. Seperti mereka, Kartini tidak memandang iman sebagai tembok pemisah, tetapi jembatan welas asih.
Azyumardi Azra (2004) mencatat bahwa Islam Nusantara lahir dari interaksi budaya yang kosmopolit dan dialogis. Kartini berdiri dalam tradisi ini—seorang perempuan Jawa yang menjadikan iman sebagai wujud kepedulian sosial dan pengakuan atas kompleksitas manusia. Dalam pendekatannya, spiritualitas tidak tinggal di ruang sakral, tapi hadir dalam tubuh yang dibungkam, dalam renungan malam, dan dalam usaha membuka sekolah bagi sesama perempuan.
Spiritualitas perempuan, sebagaimana yang diteladani Kartini, melampaui dikotomi privat-publik, rasional-emosional, atau Barat-Timur. Ini adalah spiritualitas yang tumbuh dari luka dan cinta: dari pingitan, dari menyulam dalam diam, dari menyaksikan ketidakadilan tanpa kehilangan keyakinan pada keadilan Tuhan. Kartini tidak menjadikan agama sebagai alat sensor moral atau kuasa politik, tapi sebagai ruang untuk menyelami dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.
Namun dalam iklim keberagamaan kontemporer yang sering skripturalis, spiritualitas semacam ini kerap dianggap menyimpang. Padahal justru di sinilah keistimewaan Kartini: ia tidak berteriak dalam dominasi, tetapi menyuarakan iman dalam kesunyian. Ia hadir bukan untuk menang, tapi untuk menyinari. Dan itu membuatnya begitu relevan di masa kini.
Pandangan religius Kartini tidak lahir dari fakultas teologi atau institusi resmi. Ia datang dari pengalaman perempuan dalam ruang domestik: dari pingitan, dari tanggung jawab rumah, dari membaca diam-diam, dan dari mengamati ketidakadilan. Kartini membentuk teologi yang tak tertulis, tapi hidup—teologi yang tumbuh dari tubuh dan keseharian, bukan dari diktat dan ceramah.
Lebih dari itu, proyek spiritual Kartini bersifat terbuka dan lintas batas. Ia berkawan dengan Haji Agus Salim, membaca Tolstoy, dan berdialog dengan perempuan Eropa. Kartini menghayati iman sebagai sikap hidup, bukan sekadar klaim keanggotaan dalam identitas keagamaan. Ia menunjukkan bahwa iman sejati adalah yang membuka ruang, bukan membentengi.
Hari ini, kita butuh Kartini lebih dari sebelumnya. Bukan hanya sebagai nama jalan atau wajah di poster, melainkan sebagai warisan epistemologis: iman yang reflektif, spiritualitas yang membebaskan, dan keberanian untuk bertanya dalam sunyi. Sebab sebagaimana ditulisnya, “habis gelap terbitlah terang” bukan semata tentang kolonialisme, melainkan juga tentang spiritualitas yang ditemukan dalam lorong-lorong gelap pencarian.
Kartini adalah sosok yang menggali cahaya bukan dari luar, tapi dari dalam batin. Dan dalam dunia hari ini—yang penuh dengan pertarungan tafsir, sensor moral, dan politisasi agama—ketulusan semacam itu menjadi pelita yang paling langka.









