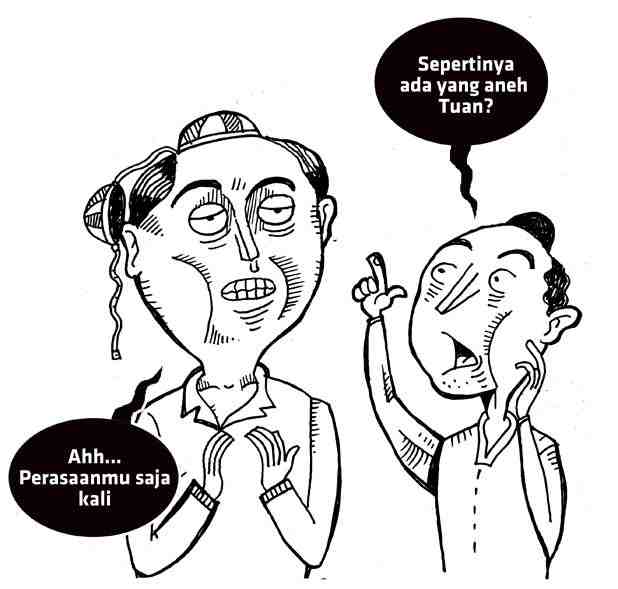Mendiang Presiden Yasser Arafat, Penjaga Mimpi Palestina
PLO menjelma menjadi payung besar perjuangan. Arafat menjadi figur utama yang menggerakkan mesin itu.

Pada suatu malam yang lembap di Beirut, suara dentum artileri memenuhi udara seperti gema masa silam yang tak mau padam. Di sebuah ruangan kecil yang diterangi lampu minyak, Yasser Arafat duduk di atas kursi kayu yang mulai retak.
Ia menekuk tubuhnya ke depan, menatap peta Palestina yang terbentang di atas meja. Tangan kirinya menggenggam pensil kecil yang ujungnya hampir habis. Di balik janggut yang mulai memutih, terlihat mata yang letih namun tetap menyala. Di luar sana, dunia menganggapnya ancaman. Di dalam ruangan itu, ia hanyalah seorang manusia yang mencoba merawat mimpi yang terus membara. Mimpi yang melampaui dirinya. Mimpi tentang tanah yang hilang. Mimpi tentang pulang.
Arafat tidak pernah menunggu sejarah menjemputnya. Ia mengejarnya dengan langkah yang penuh risiko. Ia mencintai Palestina dengan cara yang keras. Ia hidup dalam gelanggang yang setiap saat dapat merenggut nyawa. Dalam banyak catatan sahabat dekatnya, sosok Arafat selalu hadir sebagai manusia yang tidak mau menyerah. Bassam Abu Sharif dalam bukunya Arafat and the Dream of Palestine: An Insider’s Account(2009: 7) menulis bahwa kekuatan Arafat terletak pada “kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan” dan keberaniannya untuk menanggung segala risiko demi masa depan bangsanya. Dari sanalah cerita panjang perjuangannya bermula. Dari keyakinan yang nyaris tak dapat dipatahkan.
Sang Pemimpin
Tatkala Palestina terpecah akibat perang dan pendudukan, jutaan orang kehilangan rumah, tanah, dan masa depan. Arafat tumbuh dari gelombang kehilangan itu. Pengalaman masa kecilnya menjadi alasan mengapa ia begitu berkeras mempertahankan identitas Palestina di setiap panggung dunia. Tahun 1948 adalah badai pertama yang menandai perjalanan panjangnya. Nakba merobek tatanan sosial. Keluarga tercerai berai. Kamp pengungsian menjadi wajah baru Palestina. Generasi muda tumbuh tanpa kepastian. Arafat menyaksikan semua itu dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk hidup.
Pada pergantian dekade, ia bergabung dengan gerakan mahasiswa dan organisasi nasionalis Arab. Ia bertemu dengan banyak tokoh yang kelak menjadi rekan sekaligus pesaingnya. Abu Sharif menulis bahwa pada masa itu Arafat aktif dalam gerakan Arab Nationalist Movement yang berupaya membentuk kesadaran kolektif dan membangunkan kembali semangat rakyat melalui pendidikan politik (Abu Sharif, 2009, hlm. 37). Ia belajar di sana bahwa perjuangan tidak bisa hanya dilakukan lewat senjata. Perjuangan juga memerlukan ide
Pengalaman itu mematangkan cara pandangnya tentang bangsa. Ia memahami bahwa Palestina bukan sekadar tanah dalam peta tetapi juga ingatan nan hidup. Ingatan yang berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ingatan yang tidak dapat dihancurkan oleh penjara atau tank. Ingatan itu menjadi napas perjuangan.
Bangkitnya Fatah
Fatah lahir bukan dari ruang rapat tetapi dari lorong gelap perkampungan. Dari pertemuan kecil para pengungsi. Dari hasrat untuk melawan tanpa harus bergantung pada negara Arab yang mandam dengan urusan internal. Arafat menjadi jantung dari organisasi itu. Perlahan Fatah tumbuh menjadi kekuatan yang mampu menyatukan berbagai faksi perlawanan. Dengan kemampuan komunikasi yang kuat, Arafat membangun jaringan yang melintasi Yordania, Lebanon, Suriah, dan Mesir. Ia hadir di mana pun rakyat Palestina berkumpul.
Arafat selalu tampil dengan kefasihan yang disertai sikap bersahaja. Ia hidup bersama rakyatnya. Ia tidur di kamp pengungsi. Ia makan makanan yang sama. Ia berjalan di antara tenda dan reruntuhan. Dalam banyak memoar, Arafat dilukiskan sebagai sosok yang dapat menyerap kemarahan, harapan, dan kegelisahan rakyatnya. Abu Sharif menegaskan bahwa Arafat “mewakili penderitaan dan mimpi rakyat Palestina” (Abu Sharif, 2009, hlm. 8). Inilah alasan mengapa ia begitu dihormati. Ia seperti cermin tempat rakyat Palestina memantulkan luka mereka.
Di mata banyak orang, Arafat juga membawa warna anyar dalam geopolitik Timur Tengah. Ia menampilkan wajah perlawanan yang terorganisir. Fatah menjadi kekuatan politik yang tak bisa diabaikan. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, PLO menjelma menjadi payung besar perjuangan. Arafat menjadi figur utama yang menggerakkan mesin itu.
Perlawanan & Diplomasi
Arafat tidak hanya bertarung dengan senjata tetapi juga dengan kata. Dunia sering melihatnya sebagai pemimpin gerilya. Padahal ia juga seorang diplomat yang tangguh. Banyak orang menilai kemampuannya membaca situasi internasional sebagai keunggulan besar. Ia mampu menjalin hubungan dengan negara-negara besar. Ia dapat berbicara pada banyak bahasa politik. Ia mahir mengolah citra.
Peristiwa Black September, pengepungan Beirut, dan serangkaian konflik dengan Israel membuat nama Arafat terus menjadi sorotan. Namun sorotan itu tidak selalu negatif. Pada tahun-tahun berikutnya, ia perlahan berhasil menggeser narasi global tentang Palestina. PLO mulai dianggap sebagai representasi sah rakyat Palestina. Bukan sebagai kelompok yang dituduh melakukan kekerasan. Salah satu momen penting adalah ketika Arafat mendorong lahirnya dokumen yang disusun Bassam Abu Sharif untuk memperkenalkan gagasan solusi damai yang realistis. Dokumen itu menjadi strategi politik untuk menunjukkan kepada publik dunia bahwa PLO mempunyai niat baik dan telah meninggalkan strategi yang destruktif (Abu Sharif, 2009, hlm. 170).
Reaksi internal PLO terhadap dokumen itu beragam. Abu Iyad menolak gagasan tersebut karena merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunannya dan menganggapnya sebagai tindakan yang gegabah (Abu Sharif, 2009, hlm. 14). Dinamika internal itu memperlihatkan betapa sulitnya membangun kesepakatan dalam tubuh gerakan yang penuh tekanan. Di tengah perbedaan itu, Arafat tetap berpegang pada keyakinannya bahwa Palestina membutuhkan strategi diplomasi untuk mengubah persepsi global.
Sebagai pemimpin, ia memahami bahwa dunia tidak bergerak hanya oleh letusan senjata. Dunia bergerak oleh opini. Dunia bergerak oleh dukungan moral. Dunia bergerak oleh keyakinan yang memerlukan penjelasan logis. Ia meyakini bahwa keberhasilan perjuangan ditentukan oleh bagaimana dunia memandang Palestina.
Intifada
Intifada pertama membawa perubahan besar dalam cara Arafat melihat masa depan. Ia terkesima oleh keberanian anak-anak muda yang berdiri melawan tentara Israel hanya dengan batu di tangan. Abu Sharif mencatat bahwa rakyat Palestina tidak berhenti melawan meski mengalami pembunuhan, penangkapan, dan berbagai bentuk hukuman kolektif (Abu Sharif, 2009, hlm. 163). Bahkan ancaman penghancuran rumah dan penggusuran pohon zaitun tidak membuat mereka mundur (Abu Sharif, 2009, hlm. 163).
Arafat membaca Intifada sebagai suara moral yang menuntut perubahan strategi. Ia merasa bahwa perjuangan rakyat harus diikuti dengan langkah politik yang terukur. Ia tidak ingin pengorbanan generasi muda itu berakhir sia-sia. Ia menawarkan arah anyar. Arah yang lebih pragmatis. Arah yang dapat diterima dunia internasional.
Dalam suasana itu, Arafat menyadari bahwa Israel tidak akan menghilang. Ia memahami bahwa realitas geopolitik telah berubah. Abu Sharif menjelaskan bahwa Arafat menerima kenyataan bahwa Palestina dalam versi utuh tidak akan pernah kembali dan satu-satunya jalan adalah menerima negara yang lebih kecil sebagai langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah (Abu Sharif, 2009, hlm. 34). Keputusan ini memicu perdebatan di internal PLO. Banyak yang merasa pilihan itu terlalu kompromistis. Namun Arafat tetap berjalan pada keyakinannya bahwa ini adalah jalan yang paling mungkin.
Damai yang Penuh Risiko
Oslo mengubah arah sejarah Palestina secara mendasar. Arafat menandatangani kesepakatan yang membuka jalan bagi pendirian Otoritas Palestina. Kesepakatan itu juga mengizinkan kembali pemerintahan lokal Palestina di beberapa wilayah. Ia berjabat tangan dengan Yitzhak Rabin di Washington. Dunia menyambutnya sebagai langkah megak.
Namun di balik layar, kegelisahan menjalarnya. Banyak tokoh Palestina menilai bahwa kesepakatan itu memberi terlalu sedikit. Mereka takut hal itu akan melemahkan tuntutan besar seperti hak kembali para pengungsi. Arafat menanggung seluruh kritik itu. Ia berdiri di tengah badai yang terus bergerak. Ia menjadi sasaran kemarahan rakyatnya sendiri dan tekanan dari negara-negara lain. Walakin ia tetap mempertahankan keyakinan bahwa perdamaian adalah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan masa depan Palestina.
Arafat menjalani hari-harinya dengan penuh kegelisahan. Ia berpindah dari satu pertemuan ke pertemuan lain. Dari satu kantor ke kantor lain. Dari satu ancaman ke ancaman lain. Ia tidak pernah merasakan tenang. Hidupnya tidak pernah berada di ruang yang aman.
Pengepungan & Kesendirian
Pada awal 2000-an, Arafat kembali menghadapi situasi yang sulit. Israel mengepung markasnya di Ramallah. Ia terperangkap di sebuah bangunan yang sudah retak. Ia tidur di ruangan kecil. Ia hidup bersama bau lembap dari tembok yang mulai rapuh. Dunia menyaksikan peristiwa itu dengan simpati yang bercampur kebingungan. Abu Sharif mendedah bahwa Arafat menghadapi hari-hari terakhirnya dalam kondisi terisolasi namun tetap memegang teguh keyakinannya tentang masa depan Palestina (Abu Sharif, 2009, hlm. 249).
Arafat menjadi simbol yang berdiri di antara harapan dan kegelapan. Ia bukan hanya pemimpin tetapi juga saksi bagi sejarah bangsanya. Ketika ia dirawat di Prancis, tubuhnya mulai melemah. Banyak pertanyaan muncul. Tidak ada jawaban yang pasti. Ketika ia wafat, dunia merasakan kehilangan yang sulit diukur. Palestina merasakan kehilangan yang jauh lebih besar. Mereka kehilangan simbol yang selama puluhan tahun menjaga mimpi mereka tetap hidup.
Arafat dalam Lensa Sejarah
Arafat bukan figur yang mudah untuk dijelaskan. Ia menyimpan banyak lapisan. Ia adalah pemikir, pemimpin, pejuang, diplomat, dan warga negara dunia. Dalam satu waktu ia bisa tampil keras. Pada waktu lain ia menunjukkan kelembutan yang tidak banyak diketahui publik. Sejarah mencatatnya sebagai tokoh penuh dinamika. Pengaruhnya tidak hanya bersifat politis tetapi juga moral. Ia menanamkan gagasan bahwa identitas Palestina tidak bisa dihancurkan.
Dalam refleksi panjang yang ditulis oleh orang-orang terdekatnya, Arafat muncul sebagai figur yang bekerja dalam batas kemampuan manusia. Ia bekerja di tengah tekanan yang tak henti. Ia berjuang untuk membangun negara yang tidak punya tanah pasti. Ia menulis masa depan di atas peta yang terus berubah. Dalam konteks itu, perannya menjadi sangat besar.
Arafat membuka pintu untuk diplomasi. Ia mengubah wajah PLO. Ia membangun jaringan internasional yang menjadi fondasi diplomasi Palestina hingga kiwari. Ia membawa nama Palestina ke panggung global. Ia hadir dalam sidang PBB dengan sorban khas dan jas militer. Ia mengangkat suara rakyatnya ke telinga dunia yang sebelumnya tidak ingin mendengar.
Warisan yang Terus Hidup
Hari-hari setelah Arafat wafat adalah hari-hari yang penuh kabut. Palestina berusaha menata ulang arah perjuangan. Banyak tokoh muncul namun tidak ada yang memiliki kombinasi karisma, ketahanan, dan kecerdikan politik seperti dirinya. Dunia berubah dengan cepat. Namun nama Arafat tetap hadir. Ia hadir di poster. Ia hadir di mural. Ia hadir dalam lagu anak-anak muda. Ia hadir dalam doa orang tua di kamp pengungsian.
Arafat adalah ingatan yang enggan hilang. Ia bukan hanya bagian dari sejarah Palestina. Ia adalah bagian dari jantungnya. Ia pernah berkata bahwa Palestina bukan sekadar tanah tetapi rumah bagi sukma setiap warganya. Ia menjaga rumah itu dengan seluruh tenaga. Ia tidak pernah berhenti meski keadaan sering memaksanya untuk bertekuk lutut. Dalam banyak hal, ia mengajarkan bahwa perjuangan tidak pernah selesai. Perjuangan hanya berganti bentuk.
Warisan terbesar Arafat tidak terletak pada jabatan atau perjanjian politik. Warisan itu terletak pada keyakinannya bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk bermimpi dan bangkit. Ia mengajarkan bahwa mimpi itu perlu dirawat dengan keberanian. Ia membuktikan bahwa mimpi tidak pernah mati selama ada satu manusia yang bersedia menjaganya.
Sampai hari ini, mimpi itu masih hidup.