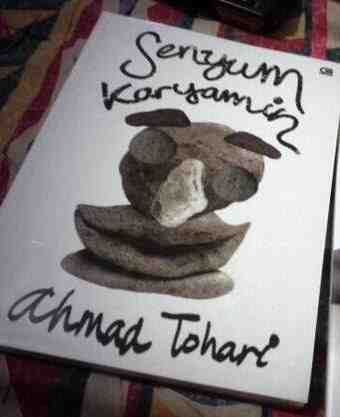Buku & Kita
|
Politik
Meneroka Denyut Bumi Jawa dalam Buku Adam Bobbette
Muhammad Iqbal
Minggu, 14 September 2025 | 02:49 WIB
Bumi bukan hanya tanah di bawah kaki kita, ia adalah politik itu sendiri.
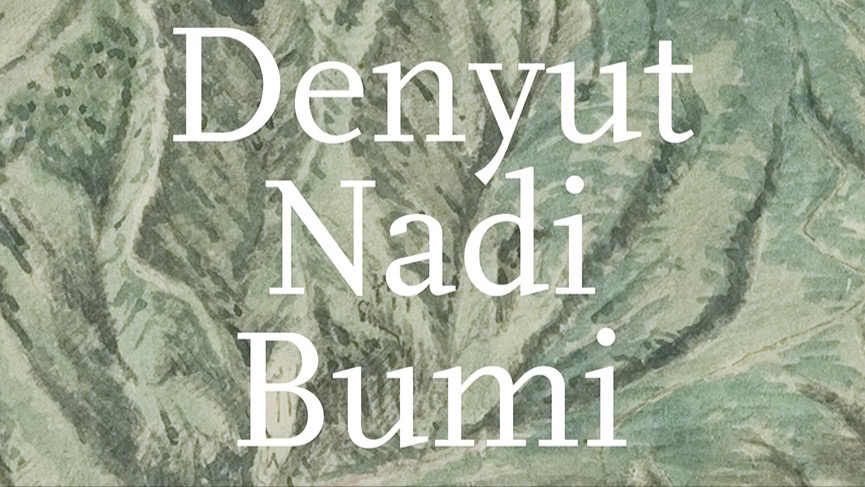
Bumi di Jawa tidak pernah hanya sebidang tanah. Ia bernafas. Ia berdenyut. Ia murka. Ia indah dan menenangkan. Gunung Merapi misalnya, bukan sekadar kerucut batu yang meletuskan lava. Ia adalah tetua yang dihormati, tempat para juru kunci mendengarkan bisikan, sekaligus ancaman yang setiap saat bisa menelan desa-desa dalam sekejap.
Merapi tidak bisa dipisahkan dari kisah Mataram kuno, dari runtuhnya kerajaan abad kesepuluh, dari ingatan kolektif yang menautkan bencana alam dengan pergeseran kekuasaan politik. Di tanah ini, alam dan sejarah bukan dua jalan paralel, melainkan anyaman rapat yang terus saling menjalin.
Buku Adam Bobbette berjudul Denyut Nadi Bumi: Geologi Politik di Jawa (Marjin Kiri, September 2025) menyingkap lapisan-lapisan itu: bagaimana bumi bukan sekadar panggung pasif, melainkan aktor politik yang menulis ulang sejarah dengan letusan, peta, dan mitos. Bobbette menantang kita membaca geologi bukan sebagai ilmu alam yang netral, melainkan sebagai praktik politik yang teranyam dengan kolonialisme, spiritualitas Jawa, dan mimpi-mimpi modernitas. Ia menulis bahwa bumi, khususnya di Jawa, memiliki denyut yang tidak hanya geologis, melainkan juga kosmologis dan politis.
Seperti novel besar tanpa akhir, pulau ini selalu digambarkan ulang: oleh peta Belanda yang memandangnya sebagai tambang kekayaan, oleh ilmuwan yang menafsirkan pergerakan tektonik, oleh para spiritualis yang merasakan “roh” gunung, hingga oleh penyintas bencana yang menafsirkan letusan sebagai tanda zaman. Bobbette merangkum semua ini, dan mengingatkan kita: Jawa adalah pusat denyut bumi, dan denyut itu selalu politis.
Metodologi Geologi Politik
Bobbette memulai bukunya dengan membangun sebuah metode yang ia sebut “geologi politik” (political geology). Bagi sebagian orang, geologi mungkin hanya urusan batu, lempeng tektonik, stratigrafi. Akan tetapi bagi Bobbette, geologi adalah cara memahami hubungan antara bumi, kekuasaan, dan pengetahuan. Ia menolak pandangan yang memisahkan “alam” dan “politik,” karena di Jawa keduanya selalu tumpang tindih. Bumi di sini tidak netral: ia dipetakan oleh kolonial, ditafsirkan oleh ilmuwan, dan dihormati oleh kosmologi lokal (Bobbette, 2025, hlm. 5-7).
Bobbette memulai bukunya dengan membangun sebuah metode yang ia sebut “geologi politik” (political geology). Bagi sebagian orang, geologi mungkin hanya urusan batu, lempeng tektonik, stratigrafi. Akan tetapi bagi Bobbette, geologi adalah cara memahami hubungan antara bumi, kekuasaan, dan pengetahuan. Ia menolak pandangan yang memisahkan “alam” dan “politik,” karena di Jawa keduanya selalu tumpang tindih. Bumi di sini tidak netral: ia dipetakan oleh kolonial, ditafsirkan oleh ilmuwan, dan dihormati oleh kosmologi lokal (Bobbette, 2025, hlm. 5-7).
Metodologi ini terasa radikal, karena menempatkan bumi bukan hanya sebagai objek penelitian, melainkan sebagai subjek yang ikut menentukan arah sejarah. Ia mendedah, misalnya, tentang bagaimana letusan Merapi tahun 1006 dikisahkan dalam babad sebagai penyebab runtuhnya Mataram Kuno. Di sinilah politik dan geologi berkain-kelindan erat: kekuasaan kerajaan dipahami runtuh bukan hanya karena konflik manusia, tetapi juga karena bumi memutuskan demikian. Narasi semacam ini bertahan ratusan tahun, membentuk cara masyarakat Jawa memandang bencana bukan sekadar malapetaka, melainkan tanda kosmik yang mengubah tatanan politik (Bobbette, 2025, hlm. 12).
Lebih jauh, Bobbette menekankan bahwa ilmu pengetahuan modern seperti geologi kolonial Belanda, observatorium gunung api, teori tektonik lempeng, tidak pernah berdiri sendiri. Ia tumbuh dengan bernegosiasi dengan kosmologi Jawa, dengan spiritualitas yang percaya bahwa gunung dan bumi memiliki roh. Inilah yang membuat geologi politik unik: ia bukan sekadar menelaah stratifikasi batu, tetapi juga stratifikasi makna.
Dengan kerangka ini, Bobbette memaksa kita melihat bahwa bencana alam, letusan, bahkan peta geologi, bukan hanya urusan ilmiah, melainkan juga instrumen politik. Ilmu geologi, dalam konteks Jawa, adalah sekaligus alat kolonialisme dan jendela spiritualitas, sekaligus sarana dominasi dan ruang perlawanan.
Pulau Peta dan Imajinasi
Setiap peta adalah narasi, dan setiap garis yang ditarik adalah klaim kuasa. Dalam bab “The Origins of Java in Four Maps,” Bobbette menunjukkan bagaimana Jawa mula-mula hadir di mata kolonial bukan sebagai rumah manusia, melainkan sebagai laboratorium bumi. Pulau ini digambarkan silih berganti: kadang sebagai reruntuhan purba, kadang sebagai pulau muda yang baru lahir dari letusan, kadang sebagai arsip bencana yang menunggu dibaca. Peta-peta itu bukan sekadar dokumen teknis; mereka adalah imajinasi politik yang menyatakan bahwa bumi Jawa bisa ditata, diukur, dan dikuasai (Bobbette, 2025, hlm. 45-49).
Setiap peta adalah narasi, dan setiap garis yang ditarik adalah klaim kuasa. Dalam bab “The Origins of Java in Four Maps,” Bobbette menunjukkan bagaimana Jawa mula-mula hadir di mata kolonial bukan sebagai rumah manusia, melainkan sebagai laboratorium bumi. Pulau ini digambarkan silih berganti: kadang sebagai reruntuhan purba, kadang sebagai pulau muda yang baru lahir dari letusan, kadang sebagai arsip bencana yang menunggu dibaca. Peta-peta itu bukan sekadar dokumen teknis; mereka adalah imajinasi politik yang menyatakan bahwa bumi Jawa bisa ditata, diukur, dan dikuasai (Bobbette, 2025, hlm. 45-49).
Dalam pandangan kolonial Belanda, peta Jawa mengandung janji sekaligus ancaman. Janji berupa kekayaan tanah vulkanik yang subur, kopi dan tebu yang bisa diekspor, serta mineral yang terkubur dalam-dalam. Ancaman berupa gempa, letusan, tsunami yang sewaktu-waktu bisa mengguncang. Kolonial dengan peta mencoba mengendalikan keduanya: memetakan peluang dan menaklukkan risiko. Namun bagi masyarakat Jawa, bumi tidak bisa direduksi menjadi garis koordinat. Bumi adalah ibu, adalah penentu nasib, adalah kekuatan yang tak tunduk pada logika survei.
Bobbette menyelipkan kontras ini dengan indah: di satu sisi, arsip kolonial penuh dengan kalkulasi dan garis batas; di sisi liyan, kosmologi Jawa penuh dengan cerita tentang gunung sebagai makhluk hidup, tentang laut sebagai penjaga keseimbangan, tentang roh yang tidak bisa dipenjarakan dalam skala peta. Maka, setiap peta kolonial tak hanya merepresentasikan Jawa, tetapi juga memisahkannya dari dirinya sendiri. Peta mengubahnya dari dunia kosmologis menjadi objek teknis.
Kosmologi, Spiritualitas, & Lempeng Tektonik
Namun, bagi Bobbette, geologi tidak bisa dibatasi hanya pada perhitungan ilmiah. Dalam bab “Interkalasi: Geografi Politik dan Spiritual Tektonik Lempeng,” ia memperlihatkan bagaimana teori tektonik lempeng, yang lahir dari modernitas ilmiah, berkelindan dengan kosmologi spiritual masyarakat Jawa.
Namun, bagi Bobbette, geologi tidak bisa dibatasi hanya pada perhitungan ilmiah. Dalam bab “Interkalasi: Geografi Politik dan Spiritual Tektonik Lempeng,” ia memperlihatkan bagaimana teori tektonik lempeng, yang lahir dari modernitas ilmiah, berkelindan dengan kosmologi spiritual masyarakat Jawa.
Di sini, bumi bukan hanya susunan batu yang bergerak. Ia adalah tubuh kosmik dengan denyut spiritual. Gunung berapi, dalam pandangan ilmiah, adalah hasil gesekan lempeng dan tekanan magma. Akan tetapi dalam pandangan kosmologis, gunung adalah poros dunia, penghubung antara alam manusia, roh leluhur, dan yang ilahi. Bobbette memperlihatkan bagaimana kedua pandangan ini tidak saling meniadakan, melainkan hidup berdampingan: observatorium Belanda mengukur suhu lava, sementara juru kunci mendengarkan bisikan Merapi. Keduanya sama-sama menafsirkan bumi, hanya dengan bahasa berbeda (Bobbette, 2025, hlm. 78-82).
Yang menarik, Bobbette tidak menempatkan ilmu kolonial sebagai superior. Ia menegaskan bahwa spiritualitas Jawa memberi kerangka alternatif untuk memahami bumi, bahwa geologi bisa menjadi politik karena ia juga kosmologi. Letusan gunung tidak hanya menghancurkan desa, tetapi juga menandai pergeseran kosmos, menuntut ritual, doa, dan perjanjian baru dengan alam.
Dengan menyandingkan tektonik lempeng dan kosmologi Jawa, Bobbette memperlihatkan betapa rapuh klaim sains modern sebagai satu-satunya cara membaca bumi. Ilmu geologi di Jawa tumbuh bukan dengan menyingkirkan kosmologi, melainkan dengan bernegosiasi dengannya. Di titik itulah, geologi menjadi politik: ia adalah arena di mana sains, kekuasaan, dan spiritualitas berkelindan, saling memengaruhi, saling membentuk.
Letusan Tahun 1006 dan Budaya Bencana
Dalam bab “1006 M Geodeterminisme: Budaya Bencana dan Cerita tentang Sebuah Tanggal,” Adam Bobbette menyoroti bagaimana bencana tidak hanya dicatat sebagai peristiwa alam, melainkan dijadikan fondasi bagi mitologi politik Jawa. Tahun 1006 menjadi titik ingatan kolektif yang tidak pernah sepenuhnya pasti: sebuah letusan besar yang sering disebut berasal dari Merapi diyakini menelan ibu kota kerajaan Mataram Kuno. Seperti semua mitos, detailnya kabur, tetapi kekuatannya terletak pada keyakinan bahwa bumi dapat menjungkirbalikkan kerajaan hanya dengan satu dentuman (Bobbette, 2025, hlm. 101-105).
Dalam bab “1006 M Geodeterminisme: Budaya Bencana dan Cerita tentang Sebuah Tanggal,” Adam Bobbette menyoroti bagaimana bencana tidak hanya dicatat sebagai peristiwa alam, melainkan dijadikan fondasi bagi mitologi politik Jawa. Tahun 1006 menjadi titik ingatan kolektif yang tidak pernah sepenuhnya pasti: sebuah letusan besar yang sering disebut berasal dari Merapi diyakini menelan ibu kota kerajaan Mataram Kuno. Seperti semua mitos, detailnya kabur, tetapi kekuatannya terletak pada keyakinan bahwa bumi dapat menjungkirbalikkan kerajaan hanya dengan satu dentuman (Bobbette, 2025, hlm. 101-105).
Bobbette memanggungkan bagaimana narasi bencana ini diulang dalam teks-teks sejarah, babad, dan cerita rakyat, hingga menjadi kerangka berpikir: bahwa politik Jawa selalu rapuh di bawah amarah gunung. Inilah yang ia sebut geodeterminisme—gagasan bahwa geologi menentukan sejarah manusia. Walakin ia juga memperingatkan bahwa kisah ini bukan sekadar determinisme ilmiah; ia adalah konstruksi budaya. Tahun 1006 adalah tanggal yang diproduksi untuk memberi makna, untuk menjelaskan mengapa sebuah kerajaan runtuh, untuk menegaskan bahwa kekuasaan manusia hanyalah tamu singkat di rumah bumi (Bobbette, 2025, hlm. 107).
Budaya bencana ini membentuk pola pikir Jawa: letusan bukan sekadar malapetaka, melainkan peristiwa kosmik yang menandai perubahan zaman. Masyarakat membacanya sebagai peringatan, sebagai koreksi terhadap kesombongan manusia, sebagai tanda bahwa bumi memiliki politiknya sendiri. Bobbette menulis dengan kepekaan antropologis, bahwa catatan bencana bukan hanya tentang korban, melainkan juga tentang cara sebuah masyarakat memahami dirinya di hadapan alam yang hidup.
Geopoetika Johannes Umbgrove
Dari sejarah bencana, Bobbette beralih ke figur Johannes Umbgrove, seorang ahli geologi Belanda yang melihat bumi bukan sekadar objek ilmiah, melainkan karya seni kosmik. Dalam bab “Geopoetika: Ilmu Kosmik dan Estetika Johannes Umbgrove,” Bobbette mengangkat gagasan geopoetika, sebuah cara melihat bumi sebagai teks puitis, penuh ritme, harmoni, dan tragedi (Bobbette, 2025, hlm. 137-141).
Dari sejarah bencana, Bobbette beralih ke figur Johannes Umbgrove, seorang ahli geologi Belanda yang melihat bumi bukan sekadar objek ilmiah, melainkan karya seni kosmik. Dalam bab “Geopoetika: Ilmu Kosmik dan Estetika Johannes Umbgrove,” Bobbette mengangkat gagasan geopoetika, sebuah cara melihat bumi sebagai teks puitis, penuh ritme, harmoni, dan tragedi (Bobbette, 2025, hlm. 137-141).
Umbgrove, yang pernah bekerja di Hindia Belanda, menulis tentang bumi dengan gaya yang nyaris sastra. Ia membayangkan lapisan tektonik sebagai simfoni, letusan gunung sebagai orkestra kosmik, dan benua sebagai panggung drama purba. Bagi Umbgrove, ilmu geologi tidak cukup hanya memetakan batu; ia harus mengungkap keindahan laten, estetika dari kekacauan alam. Bobbette membaca ini bukan sekadar romantisisme, melainkan upaya untuk merekonsiliasi ilmu dengan kepekaan spiritual, sesuatu yang juga hadir dalam kosmologi Jawa (Bobbette, 2025, hlm. 145).
Namun geopoetika Umbgrove sarat ambivalensi. Ia di satu sisi membuka ruang bagi sains yang puitis, yang mengakui misteri bumi. Ia di sisi liyan tetap bagian dari proyek kolonial: seorang ilmuwan Belanda yang mengubah Jawa menjadi laboratorium, yang puisinya tentang bumi lahir dari penguasaan atas tanah jajahan. Di sinilah Bobbette jeli: geopoetika bisa menjadi jembatan, tapi juga bisa menjadi tirai yang menutupi relasi kuasa.
Meski begitu, Umbgrove meninggalkan warisan penting: ia menolak melihat geologi sebagai kalkulasi kering. Dalam tulisannya, bumi bernapas, bergerak, bergetar laksana makhluk hidup. Di titik inilah ia bersinggungan dengan pandangan kosmologis Jawa, di mana gunung dan bumi memang dianggap memiliki roh. Bobbette memperlihatkan ironi indah: bahwa sains kolonial yang ingin merasionalisasi bumi justru menemukan dirinya kembali dalam ranah mistis, dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ilmiah, melainkan puitis.
Observatorium Gunung Api
Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menyaksikan perjumpaan antara sains dan spiritualitas selain observatorium gunung api di Jawa. Dalam bab “Observatorium Gunung Berapi: Kedekatan dan Jarak dalam Sains dan Mistisisme,” Bobbette menggambarkan bagaimana pos-pos pengamatan Merapi berdiri seperti menara penjaga: penuh instrumen, sensor, peta seismograf yang merekam denyut bumi dari dalam perut gunung (Bobbette, 2025, hlm. 175-178). Akan tetapi di luar tembok laboratorium itu, ada juru kunci, sang penjaga tradisi nan duduk bersila, membaca tanda dari kabut, arah angin, dan bunga tidur.
Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menyaksikan perjumpaan antara sains dan spiritualitas selain observatorium gunung api di Jawa. Dalam bab “Observatorium Gunung Berapi: Kedekatan dan Jarak dalam Sains dan Mistisisme,” Bobbette menggambarkan bagaimana pos-pos pengamatan Merapi berdiri seperti menara penjaga: penuh instrumen, sensor, peta seismograf yang merekam denyut bumi dari dalam perut gunung (Bobbette, 2025, hlm. 175-178). Akan tetapi di luar tembok laboratorium itu, ada juru kunci, sang penjaga tradisi nan duduk bersila, membaca tanda dari kabut, arah angin, dan bunga tidur.
Bagi ilmuwan, letusan adalah data: angka yang naik di seismograf, grafik yang menanjak. Bagi juru kunci, letusan adalah pesan kosmik: bumi sedang bicara, roh sedang bernegosiasi dengan manusia. Bobbette menunjukkan bahwa keduanya tidak selalu saling meniadakan. Tatkala Merapi meletus dahsyat pada 2010, Mbah Maridjan, juru kunci legendaris, memilih bertahan di rumahnya di kaki gunung. Ia menolak mengungsi karena merasa tugasnya adalah menemani Merapi, bukan lari darinya. Ia tewas, tetapi kisahnya menjelma legenda: bahwa kesetiaan pada gunung bisa lebih kuat daripada angka-angka ilmiah (Bobbette, 2025, hlm. 182-184).
Observatorium dan juru kunci, sains dan mistisisme, dalam pandangan Bobbette bukanlah oposisi, melainkan dua cara mendengarkan denyut bumi. Sains membawa jarak, mistisisme membawa kedekatan. Sains mengukur, mistisisme merasakan. Keduanya membentuk lanskap politik geologi Jawa, di mana keputusan hidup dan mati sering diambil dalam ketegangan antara data dan iman.
Adam Bobbette menulis bukunya laksana seorang penyair yang menyusuri patahan bumi. Ia memperlihatkan bahwa geologi Jawa bukan hanya kisah batu dan magma, tapi juga kisah kuasa, kosmologi, kolonialisme, dan spiritualitas. Dari peta kolonial yang mengurung Jawa dalam garis-garis kuasa, hingga mitos tahun 1006 yang menautkan bencana dengan runtuhnya kerajaan; dari geopoetika Umbgrove yang mencari estetika dalam gempa bumi, hingga observatorium Merapi yang hidup berdampingan dengan juru kunci. Semua berpadu menjadi simfoni perihal bagaimana bumi menulis politik (Bobbette, 2025, hlm. 201-205).
Bobbette mengingatkan kita bahwa bumi bukanlah panggung bisu tempat manusia bermain. Ia adalah aktor dengan bahasa sendiri: bahasa magma, abu, dan gempa. Bahasa itu di Jawa diterjemahkan ke dalam doa, babad, peta, dan grafik seismograf. Semua adalah upaya untuk memahami denyut bumi. Denyut yang kadang menenangkan, kadang mematikan, tetapi selalu politis.
Di situlah kekuatan Denyut Nadi Bumi. Ia menolak melihat bumi sebagai benda mati, menolak sains sebagai kebenaran tunggal, menolak sejarah sebagai milik manusia semata. Ia menghadirkan bumi sebagai makhluk yang ikut berunding dalam politik, ikut menentukan jalannya sejarah.
Tatkala manusia di era Antroposen merasa berkuasa penuh atas planet ini, buku yang diterjemahkan dengan indah oleh Endah Raharjo ini datang sebagai teguran. Ia berkata: dengarkan bumi. Ia berdenyut, ia menulis, ia melawan. Jika kita terus mengabaikannya, bumi akan kembali berbicara dengan cara paling radikal dengan letusan, gempa, dan banjir yang mengubah sejarah.
Seperti Merapi yang tak pernah tidur, hantu geologi Jawa terus bernafas. Dalam setiap denyutnya, kita mendengar gema peringatan: bumi bukan hanya tanah di bawah kaki kita, ia adalah politik itu sendiri.