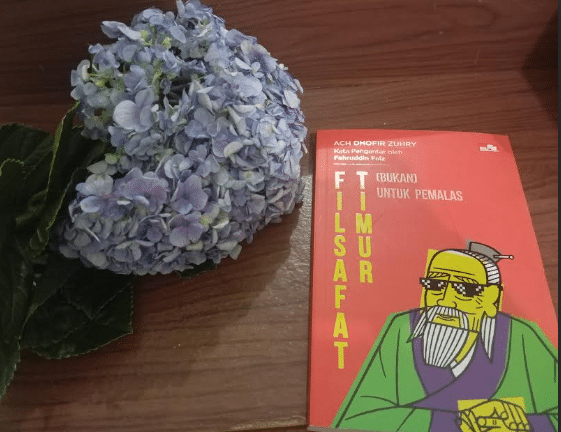Berawal dari sela waktu istirahat yang kadang hanya guling-guling saja. Aku singgah dari kamar tidur ke perpustakaan MJS, ruang bagian depan asrama MJS. Saat melewati buku yang berjejeran di rak perpus, tanganku tiba-tiba mengambil buku yang bahkan tak kusadari. Buku ‘Terjemah Rasa #2’ karya Pak Faiz, pengasuh Ngaji Filsafat MJS. Merupakan buku ke-2 dari serial Terjemah Rasa.
Mungkin naluriku berpikir kalau buku ini tipis, jadi mudah dan cepat untuk dibaca. Dan benar, buku ini kubaca hanya sekali duduk, kurang lebih tiga setengah jam. Bahasa yang digunakan begitu ringan, akrab di telinga, dan terasa dekat dengan pengalaman hidup sehari-hari. Gaya Pak Faiz dalam menulis tak menggurui, tetapi justru mengajak pembaca berdialog dengan dirinya sendiri.
Menjelajahi Rasa: Dari Hidup, Cinta, hingga Kerinduan
Buku setebal 114 halaman ini menyuguhkan setidaknya enam bagian pembahasan utama: Hidup, Kebersamaan, Belajar Bersama, Kesendirian, Kerinduan, dan Suara Hati Seorang Ayah. Namun, secara pribadi saya lebih suka menyederhanakannya dalam tiga bagian besar: Rasaku-Rasa Kita-Rasa Rindu dan Tanggung Jawab.
Di bagian awal, Pak Faiz banyak berbicara tentang kehidupan, dengan segala dinamika, kerumitan, dan keindahannya. “Hidup adalah simfoni, yang diciptakan oleh waktu dalam notasi takdir,” tulis beliau. Kalimat ini bukan hanya puitis, tetapi juga filosofis. Ia mengajak kita tidak sekadar menjalani hidup, melainkan merasakannya sebagai bagian dari keutuhan ciptaan.
Lalu beranjak ke bagian tengah, pembaca diajak menyelami rasa cinta, kesendirian, kebersamaan, dan kerinduan. Tidak dengan gaya klise ala motivator, tetapi dengan jernihnya pengalaman batin yang dibagikan seperti secangkir teh hangat di sore hari. Kita merasa menjadi bagian dari “kita”, bukan hanya “aku”.
Dan pada bagian akhir, buku ini memberi kejutan lembut: nasihat-nasihat seorang ayah. Nasihat yang ditulis dengan penuh kasih, jujur, dan terasa sangat tulus. Membacanya, saya merasa seperti sedang duduk di depan Pak Faiz, sebagai anak yang sedang mendengarkan wejangan hidup. Barangkali inilah pesan tersirat buku ini: setelah hidup dijalani, cinta dimaknai, maka tibalah saatnya memikul tanggung jawab-memberi nasihat, menjaga warisan rasa.
Saat Kekalahan Menjadi Guru
Salah satu pelajaran paling jujur dalam buku ini adalah tentang bagaimana kita bersikap saat kalah. Saat hidup tak sesuai harapan, rencana gagal, atau kenyataan terlalu jauh dari impian.
“Engkau adalah bagian dari keajaiban yang disebut kehidupan, dan keberadaanmu adalah alasan untuk bersyukur dan bahagia. Jangan menyerah. Aku percaya, kamu bisa melewatinya.”
Begitulah kata Pak Faiz, seperti suara yang pelan namun dalam. Ia tidak memaksa kita untuk terus kuat, tapi justru mengingatkan bahwa kekalahan bukan akhir segalanya. Tak lupa bumbu filsafat pun beliau suguhkan dalam pola tulisannya. Seperti Nietzsche yang berkata, “Apa yang tidak membunuhmu, tidak membuatmu lebih kuat,” atau Aristoteles yang meyakini bahwa kebajikan datang dari menghadapi kesulitan, bukan menghindarinya.
Dalam buku ini, kekalahan justru dikulik sebagai bagian penting dari proses menjadi pribadi yang lebih bijak. Ia tidak mendefinisikan siapa kita, tapi menunjukkan bahwa kita sedang tumbuh bagaimana meresponsnya.
Menertawakan Hidup: Seni Melewati Hari-hari
Ada satu bagian dalam buku ini yang membuat saya tersenyum lebar tentang menertawakan hidup walau sulit menghampiri.
“Sebenarnya bisa dihitung dengan jari, berapa banyak rencana kita yang benar terjadi.”
Betapa akurat kalimat ini menggambarkan kenyataan. Kita merancang banyak hal, tapi hidup sering kali berjalan tak mujur. Maka daripada sibuk mengeluh dan merasa gagal, mengapa tidak kita tertawakan saja?
Menertawakan hidup bukan berarti menyerah, tapi justru bentuk penerimaan yang dewasa. Ia adalah seni bersikap ringan terhadap kenyataan yang kadang pahit.
Menertawakan hidup membuat kita sadar bahwa tidak semua hal perlu dimaknai secara mendalam. Kadang cukup diterima dan dilewati. Ia mengajarkan kita bahwa tak ada manusia yang selalu benar, sempurna, atau mengagumkan dan itu tidak apa-apa.
Keistimewaan Buku dan Catatan Kecil
Kekuatan buku ini ada pada kemampuannya menyapa hati pembaca yang lelah. Ia tidak banyak teori, tapi penuh pengalaman. Ia tidak sibuk dengan istilah rumit, tapi menghadirkan kata-kata yang mampu menguatkan.
Namun, tentu masih ada ruang perbaikan, khususnya dari sisi penyuntingan. Beberapa bagian terasa kurang rapi secara tata bahasa dan teknis penulisan. Jika itu dibenahi, buku ini bisa lebih nikmat dibaca tanpa terganggu alur kalimat.
Untuk Kamu yang Sedang Penuh Keluh
Buku ini bukan untuk mereka yang sedang baik-baik saja. Buku ini terasa lebih bermakna bagi kamu yang sedang kehilangan arah, merasa kosong, atau sekadar ingin duduk sejenak dari sibuknya dunia.
Ia tidak mengajakmu kabur dari masalah, tapi mengajakmu menerima, memahami, dan kembali berdiri dengan cara yang lebih bijak. Dan ya, mungkin kalau kamu pede dengan baca buku ini sejenak mengadopsikan dirimu jadi anaknya Pak Faiz yang sedang dinasihati, bukan dengan keras, tapi dengan rasa.
“Rasa itu tak perlu dibunyikan, karena ia akan sampai pada hati yang bersedia merasakannya.”