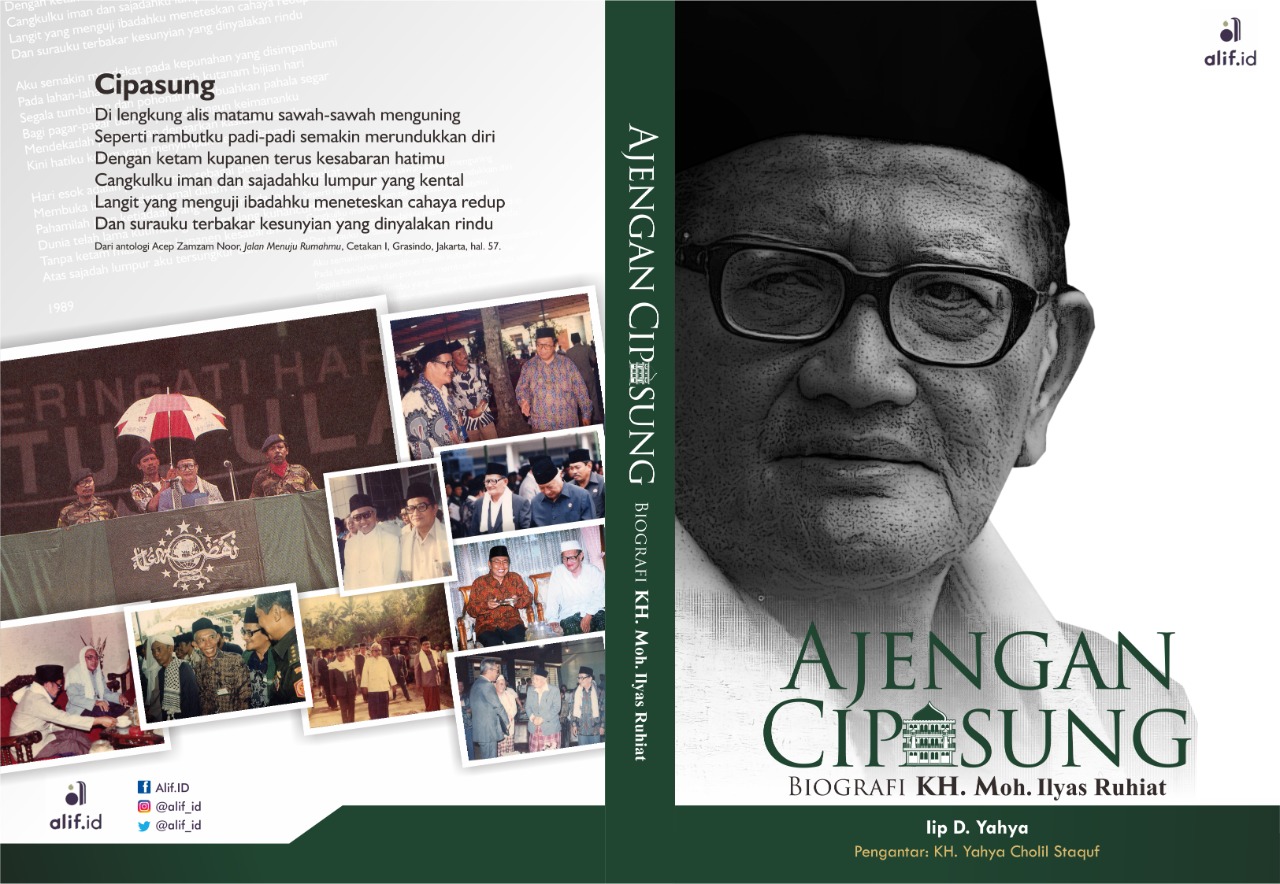Anak-anak kecil di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, terlihat riang menyaksikan pertunjukan angklung. Di pelosok desa yang berjarak tak kurang 60 km dari kota Banyuwangi itu, mereka juga lancar menyanyikan lagu Genjer-Genjer dan lagu-lagu lainnya.
Peristiwa yang terjadi pada dekade 60-an itu, memantik keprihatinan dari Muhammad Madrawi. Ia adalah guru ngaji di kampung tersebut. Ketertarikan anak-anak yang notabane para santrinya itu menyulut alarm bahaya pada dirinya. Kesenian angklung, lagu Ganjer-Genjer dan beberapa kesenian daerah lainnya yang digandrungi santrinya itu, begitu identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal demikian, berarti preseden buruk bagi kelompoknya yang terafiliasi dengan Partai Nahdlatul Ulama (NU).
Sebagaimana dikisahkan oleh putranya, KH. Masykur Ali dalam “The Authorized Biography of Masykur Ali: Jalan Pengabdian” (2018: 6-7), Madrawi lantas membangun menara di dekat suraunya. Di menara tersebut, ia beri pengeras suara. Tiap santrinya digilir naik menara itu.
Selain untuk mengumandangkan adzan, juga dipergunakan untuk melantunkan Selawat Badr. Dari upayanya tersebut, anak-anak kecil itu mulai mengalihkan perhatiannya. Mereka tak lagi menyanyikan Genjer-Genjer, tapi sudah beralih untuk melantunkan Selawat Badr.
Perebutan wacana kebudayaan di tengah masyarakat memang sedang bergejolak pada masa itu. Partai Komunis Indonesia (PKI) memanfaatkan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) sebagai instrumentasi kebudayaan guna mendukung kepentingan ideologis dan politik mereka. Hal ini kemudiaan menyulut partai-partai lain untuk mengadaptasinya. Partai Nasional Indonesia (PNI) mendirikan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Masyumi dengan Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) dan Nahdlatul Ulama dengan Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi).
Banyuwangi menjadi tempat yang subur dalam menyemai persaingan kebudayaan tersebut. Kabupaten di ujung timur pulau Jawa itu, memang sarat dengan unsur kesenian. Baik yang berbasis tradisi, agama, maupun yang pop-kultur. PKI dengan Lekra-nya, sukses mengkapitalisasi kesenian semacam gandrung, angklung, janger, tari-tarian dan lagu-lagu daerah menjadi sarana untuk mempropagandakan ideologi dan kepentingan politiknya.
Melalui kelompok seni yang bernama Sri Muda (Seni Rakyat Indonesia Muda), Lekra hampir tiap hari menggelar pertunjukkan di Banyuwangi. Genjer-Genjer yang merupakan lagu gubahan M. Arif dari Banyuwangi itu, menjadi maskot pertunjukan.
Bahkan, lagu tersebut juga dilengkapi dengan tarian Genjer-Genjer yang dikarang oleh Slamet Abdul Rozak atau dikenal dengan Slamet Menur. Tak ayal hal ini, semakin menarik minat banyak orang untuk menontonnya. Hampir setiap penampilan selalu dipadati pengunjung.
Tak mau ketinggalan, Partai Nahdlatul Ulama pun menggalakkan kesenian sebagai media propagandanya. Salah satunya adalah kesenian Kuntulan. Yaitu sebuah tarian yang diiringi dengan tabuhan rebana. Tariannya menyiratkan gerakan seperti orang yang sedang berwudu, salat hingga aktivitas kerja hariaan. Sedangkan lagu pengiringnya adalah bacaan selawat dan syair-syair bermuatan dakwah sekaligus kampanye politik.
Salah satunya adalah syair yang digubah oleh KH. Shonhaji Rasyid dari Kopenbayah, Giri, Banyuwangi yang berbahasa Jawa berikut ini:
Pilihan umum wes diwiwiti
kaum muslimin kang ati-ati
uga muslimat pada miliyo
marang daftaran ojo tan oro
lamuno nyoblos golongan dewe
ono ing kamar sopo kancane
lamun wes metu menengo wae
lamuno ngomong akeh fitnahe
arape nyoblos teko syetana
gudho dek ati milih liyane
kalah lan menang opo jare Tuhan
jalaran kitha nuruti peraturan
lamuno kalah jok na meksane
asal wes nyoblos ana ganjarane
Sholli was sallim sebagai nabi kitha
Nabi Muhammad itu yang mulia
***
Tak jarang persaingan tersebut, menimbulkan bentrokan fisik atau aksi saling gugat satu sama lain. Seperti yang ditulis oleh Iwan Gardono Sudjatmiko dalam disertasinya di Universitas Harvard (1992), “The Destruction of The Indonesian Communist Party (PKI): a Comparative Analysis of East Java and Bali”. Pada 8 Februari 1965, sekira 500 warga Nahdliyin yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor mengepung kantor desa Jambewangi. Mereka marah karena pertunjukan wayang kulit yang di gelar PKI beberapa hari sebelumnya telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Dalam sambutan di pagelaran wayang kulit itu, mereka memplesetkan lafadz “Laa raiba fih” dalan ayat Alquran menjadi “rai babi” yang berarti wajah babi.
Di tengah kerasnya perebutan wacana kebudayaan dan konstituen antara Partai NU dan PKI pada rentang dekade 50 hingga 60-an itulah, Selawat Badr lahir.
Para aktivis NU Banyuwangi pada masa itu, mendesak KH. Ali Manshur untuk menciptakan karya yang bisa menandingi hegemoni lagu Genjer-Genjer. Saat itu, Kiai Ali Manshur merupakan Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi yang dikenal memiliki suara yang indah dan kemampuan ilmu Arudl (fan ilmu kasusastraan Arab) yang mumpuni.
Latar belakang penggubahan lagu Selawat Badr sebagai respons perebutan hegemoni kebudayaan di Banyuwangi (khususnya) kala itu, tersiar cukup luas di kalangan sepuh yang hidup pada masa itu. Seperti halnya kesaksian salah seorang santrinya, H. Masduki Mahdi. Saat wawancara dengan penulis pada Maret lalu (2018), ia mengakui jika Selawat Badr dijadikan instrumen untuk menandingi popularitas lagu Genjer-Genjer.
Hal ini diperkuat dengan rentang waktu penciptaannya. Dalam sebuah catatan harian yang ditulis oleh Kiai Ali Manshur yang menggunakan aksara pegon dan berbahasa Jawa, ia menulisnya pada 1960.
“Saya membuat lagu Selawat Badr adalah setelah saya kembali dari Makkah al-Mukarramah (haji) yang saya bacakan pertama kali pada acara Lailatul Qiro’ah dengan mengundang KH. Ahmad Qusyairi beserta para muridnya. Bertepatan pada malam Jumat 1960, tetangga saya sama bermimpi melihat serombongan Sayyid atau Habaib masuk ke rumahku, dan istri saya, Khotimah, juga bermimpi melihat Nabi Muhammad berpelukan dengan al-faqir (saya).”
(Terjemah tersebut berdasar buku “Sang Pencipta Shalawat Badar: KHR. Ali Manshur (LTN Pustaka: 2017)” yang ditulis oleh Saiful Islam. Manuskripnya sendiri tersimpan di Saiful Islam yang tak lain adalah putra dari Kiai Ali)
Memang ada pendapat lain yang menyebutkan jika Selawat Badr tak diciptakan secara khusus untuk merespons persaingan budaya dan politik tersebut. Namun, karena ritmenya yang heroik, dianggap sebagai instrumen yang tepat untuk dijadikannya sebagai tandingan atas berbagai produk kesenian yang diproduksi PKI maupun pihak-pihak lainnya. Gagasan tersebut diajukan kepada Kiai Ali dan disetujuinya.
Terlepas pendapat mana yang benar, namun kehadiran Selawat Badr sebagai instrumen untuk melawan propaganda komunisme lewat kebudayaan adalah satu fakta yang terjadi.
Hal ini juga diperkuat oleh kajian linguistik terhadap Selawat Badr oleh RM Imam Abdillah dalam tesisnya yang berjudul “Puisi Keagamaan dan Politik: Studi Selawat Badar dan Politik Nahdlatul Ulama di Indonesia Masa Orde Lama”.
Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu, mengkaji 28 bait selawat tersebut. Dari sana, ada beberapa kosakata yang berkaitan erat dengan konteks saat itu.
الهي نجيناواكشف # جميع اذية واصرف
مكاءدالعد والطف # باهل البدرياالله
(ilahii najjinaa waksyip # jamii’a adiyyatin washrif
Makaa’ida walthuf # biahlil badriyaa Allah)
Lafadz “makaa’id” (مكاءد) yang berarti “tipu daya” dalam bait kedelapan tersebut, memiliki makna konotatif yang menyiratkan pada upaya “tipu daya” yang dilakukan PKI masa itu. Salah satunya adalah doktrin tujuh setan desa. Di mana, mereka menganggap para pemilik tanah yang cukup luas dianggap sebagai setan yang harus direbut dan didistribusikan kepada rakyat. Dari doktrinasi yang demikian, banyak rakyat yang terperdaya sehingga melakukan aksi sepihak.
Aminuddin Kasdi dalam “Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/ BTI di Jawa Timur 1960-1965” mencatat perihal aksi sepihak PKI di Banyuwangi. Seperti yang dialami oleh H. Saleh dari Sumbersari, Srono. Salah seorang magersari-nya yang merupakan anggota BTI, Seran, tak mau membagi hasil panen sebagaimana kesepakatan semula. Seran menginginkan pembagiaan sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (2001: 201-3).
Kejadian demikian hampir terjadi di berbagai tempat di Banyuwangi. Seperti di Genteng, Tegaldlimo, Cluring, Kalibaru, Rogojampi dan beberapa tempat lainnya.
Masih merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Imam Abdillah, lafadz lain yang memiliki makna konotatif pada konteks saat itu, adalah lafadz al-‘ashiin (العاصين). Secara harfiah, lafadz tersebut bermakna “orang-orang yang memberontak”.
Dalam sejarah republik, PKI tercatat dua kali melakukan pemberontakan. Selain pada 1965, juga pernah melakukannya pada 1948 di Madiun. Hal ini menimbulkan trauma yang cukup mendalam di benak kaum santri. Lebih-lebih pada masa itu, banyak kalangan kiai dan santri yang menjadi korban keganasan Muso cs. Pandangan yang demikian, besar kemungkinan, juga dialami oleh Kiai Ali Manshur. Sehingga ia mengabadikannya pada bait kesembilan shalawat tersebut.
الهي نفس الكربا # من العصين والعطبا
(Ilahii nafsil kurba # minal ‘ashiina wal uthba)
“Ya Tuhanku, lenyapkanlah kesusahan dan kerusakan akibat dari perbuatan orang-orang yang memberontak”. (*)