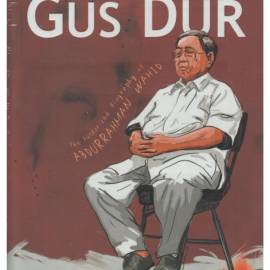Di awal reformasi dulu mendiang Dono Warkop, dalam satu acara yang juga dihadiri Gus Dur (GD), bilang kurang lebih gini: “gimana kalo panggilan populer Anda saya ganti jadi Gus Wah? Biar lebih asyik.” Tentu saja GD tertawa.
Begitulah. Selain suka “ngerjain” orang, GD kadang juga dikerjain koleganya. Dan itu biasa. Mungkin itu cara GD untuk berupaya mendesakralisasi dirinya, atau setidaknya, membuat suasana jadi cair.
Ketika mahasiswa doktoral dulu (paruh 80-an), saya pernah bekerja di kantor Pan Asia Research (PAR), di bilangan Patal Senayan, Jakarta. Kantor itu diinisiasi dan dipimpin oleh Bang Eki Syachrudin. Bang Eki, aktifis angkatan 66, jurnalis, salah satu dedengkot HMI, yang kemudian aktif di Golkar dan berkarir sebagai diplomat sebelum wafat.
Di kantor PAR itu, selain kerja-kerja profesional, Bang Eki acap mengundang koleganya angkatan 66. Bahkan ada semacam pertemuan rutin eksponen 66 di sana, kalau tak salah setiap setelah salat Jumat. Eks komandan Laskar Arief Rahman Hakim, mendiang Louis Wangge, hingga mendiang Amir Biki, acap hadir di sana.
Saya punya kesan positif untuk Amir Biki. Orangnya ramah, royal, suka nraktir makan siang sate kambing Senayan. Makanya saya kaget dan tidak mengerti kenapa beliau dibunuh aparat.
Nah, terkait GD, di kantor PAR ini juga Bang Eki pernah bikin pertemuan “Tiga Orang Gila Dari Jombang.” Mereka adalah Gus Dur, Cak Nur, dan Emha Ainun Najib. Ketiga orang itu diminta bang Eki untuk mempresentasikan “kegilaan” masing-masing di acara itu. Gayeng dan rasanya dapat liputan media-media cetak mainstream.
Usai pertemuan inilah GD dikerjain bang Eki.
Kadang saya diajak numpang mobil impala tua bang Eki, ketika pulang kerja. Hanya sampai terminal Blok M, selanjutnya saya sambung dengan bis ke Ciputat.
Usai acara di atas tadi, GD ditawari bang Eki numpang mobilnya. GD mau, hanya sampai Blok M. Beliau mau cari musik klasik di Blok M. Saya juga diajak bang Eki, numpang. Saya duduk di belakang, nguping perbincangan para tokoh di depan saya. Bang Eki tidak punya sopir. Beliau selalu menyetir sendiri kendaraannya.
Setelah mobil bergerak, mereka berdua mulai ngobrol soal musik klasik. Seperti anak Jakarta, mereka pakai “lu-gue.” Senang rasanya dengar GD pakai “lu-gue” ketika ngobrol. Langka. Mungkin gak banyak yang pernah dengar. Konon, ketika jadi presiden, ke sohib sejak kecilnya di Matraman, Marsilam Simanjuntak, GD juga suka ber-“lu-gue” dengan Marsilam.
Kembali ke mobil. Lama-lama obrolan GD dan bang Eki mulai nyerempet ke politik. Sampai juga ke peran-peran HMI dan kader-kader NU dalam dinamika politik. Mereka pun mulai saling ledek. Kelihatan bang Eki merasa lebih senior dari GD, karena kadang dia nyeletuk “lu tau apa sih, Gus? Lu masih pake celana pendek kan, ketika itu.”
Tapi GD jago berkelit dan selalu bisa ngekik balik. “Biar gue masih remaja, tapi gue tinggal di Jakarta pusat. Nggak kaya lu di Ujung Kulon, betemen sama badak.”
Saling ledek dan ngekik itu terus berlanjut dalam obrolan mereka.
Saya tidak ingat persis apa pemicunya, begitu mobil mendekati perempatan CSW Kebayoran, bang Eki menghentikan mobilnya, dan meminta GD turun.
“Lu turun di sini aja, Gus. Daripada kita berantem beneran, ntar. Blok M ude deket. Jalan kaki aja lu.”
“Yaelah, Ki. Jahat lu. Ude tinggal dikit lagi ke Blok M…”
Bang Eki tidak menghiraukan. Dia minta saya pindah ke depan, dan wush!
“Kasian GD, bang. Kenapa diturunin?”
“Biarin aja, Leh. Sekali-sekali tu orang kudu dikerjain. Lagian jalan kaki bagus buat dia. Udah mulai kegemukan dia.”
Kita tahu bagaimana GD juga dulu lumayan dekat dengan Dawam Raharjo, Adi Sasono, dan alumni HMI lainnya. Murid-murid terbaiknya di Fak Adab IAIN Ciputat, seperti Badri Yatim dan Iqbal Abdul Rauf Saimima adalah para dedengkot HMI Ciputat. Bahkan skripsi Badri yang dibimbing GD, tentang Sukarno dan pemikiran keislaman, diterbitkan menjadi buku di mana GD juga memberi pengantar.
Kenangan kecil ini saya buat sambil nunggu panggilan di Sarjito, untuk melengkapi kegelisahan Safar Nurhan sebagai kader militan HMI. Yakusa, Far!