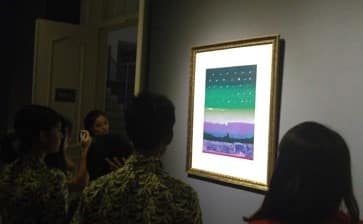Diskursus mengenai krisis iklim kini kian mendesak untuk direspons secara serius dan mendalam. Pada Juli 2025, beberapa wilayah di Indonesia mengalami anomali iklim berupa curah hujan yang tinggi di saat seharusnya memasuki musim kemarau. Bahkan terjadi banjir di beberapa wilayah.
Kendati demikian, respons terhadap krisis iklim acap kali terjebak pada pendekatan teknokratis semata. Nampak pada transisi energi baru maupun kebijakan karbon yang justru menyisakan problem ekologis baru. Misalnya kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel untuk baterai kendaraan listrik. Hal ini makin mempertajam kritik dari Seyyed Hossen Nasr (1996) yang mengatakan bahwa manusia modern kerap memosisikan diri sebagai penguasa alam, alih-alih pelayan atau penjaganya.
Dalam konteks ini, pendekatan ekoteologi menjadi alternatif yang sangat perlu. Secara singkat, ekoteologi merupakan pendekatan teologi (ketuhanan) yang mempertemukan ajaran-ajaran agama maupun spiritualitas dengan isu-isu lingkungan. Dalam pendekatan ini, alam tidak hanya dipandang sebagai benda pasif atau sumber daya yang dapat kita eksploitasi, melainkan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai spiritual.
Menemukan Kesadaran Ekologis di Antara Kematian dan Kemenyatuan dengan Tanah
Lokalitas yang membudaya di Indonesia salah satunya dapat kita temui pada praktik ziarah kubur. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ziarah kubur bukan hanya laku mendatangi kuburan dan mendoakan mereka yang telah terkubur. Ziarah kubur di Indonesia pada kenyataannya telah menjadi suatu budaya tersendiri dan mendapat panggung yang sakral di benak masyarakat.
Ziarah kubur bukan melulu ritual doa. Dalam laku ziarah kubur terdapat pengalaman spiritual yang menyadarkan manusia akan asal dan tujuannya: dari tanah, kembali ke tanah. Ziarah kubur juga menjadi pengingat atas kesementaraan manusia serta menanam kesadaran akan keterhubungan manusia dengan alam semesta. Meminjam bahasa Nasr (1994), krisis ekologi tak akan teratasi tanpa mengembalikan kita pada prinsip-prinsip spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan alam.
Oleh karenanya ziarah kubur menjadi suatu laku yang merangkum beberapa hal yang perlu dipotret dalam kerangka ekoteologis. Pertama, kesadaran ekologis bahwa semua berasal dari tanah (bumi) dan akan kembali ke sana. Kedua, dalam ziarah kubur, kita senantiasa mengingat kematian dan kesementaraan, sehingga ada ruang untuk merefleksikan bahwa manusia bukanlah segala-galanya dalam semesta ini (kritik antroposentrisme. Ketiga, umumnya kuburan atau makam-makam di Jawa, khususnya makam tua, selalu banyak pepohonan yang disakralkan oleh masyarakat setempat.
Makam Tempat Ziarah sebagai Lanskap Sakral dan Ekologis
Banyak makam-makam di Jawa yang memiliki lingkungan sejuk dan menyegarkan. Tak jarang pula makam yang terletak di dataran tinggi, seperti makam Sunan Muria, makam Gunung Pring Magelang, dan banyak lagi makam-makam yang dilingkupi pepohonan tua serta berukuran besar.
Selain itu makam-makam tersebut juga terkesan sunyi dan hening. Sehingga menimbulkan suatu kenyamanan tersendiri bagi peziarah. Tak jarang pula di tempat pemakaman umum kita temui kerindangan dengan banyaknya pohon yang tumbuh di sana.
Bagi masyarakat Jawa, pohon-pohon di area makam bukan pohon sembarangan. Tak jarang juga banyak pohon yang disakralkan dan tidak boleh ditebang sembarangan. Bahkan banyak anjuran-anjuran di makam yang mengatakan bahwa pengunjung tak boleh merusak tanaman yang ada di area makam secara sembarangan. Hal tersebut yang lambat laun menjadi narasi-narasi yang, sayangnya, kerap dianggap mitos belaka.
Padahal tanpa disadari, narasi-narasi mitologis serta hal-hal sakral seputar ruang ziarah kubur telah menjadi kawasan konservasi budaya dan ekologis. Tanpa ada aturan atau regulasi resmi terkait larangan penebangan pohon pun masyarakat lokal akan mafhum dengan sendirinya bahwa menebang pohon di sekitar kuburan merupakan suatu yang tak elok, pamali, dan membahayakan.
Kesadaran tersebut merupakan refleksi mendalam dan sebuah titik temu antara spiritualitas, tradisi, ajaran agama, dan ekologis. Ziarah kubur pun dalam hal ini menjadi suatu simbol harmoni antara manusia, tanah, dan transendensi. Tak hanya itu, ziarah kubur menjadi perekat manusia dengan yang lampau, dengan dirinya dan muasalnya. Tak ayal bahwa kesadaran mendalam atas laku ziarah kubur ini perlu didedah dan dimaknai mendalam secara kolektif.
Menggali Etika Ziarah Kubur sebagai Etika Ekologis
Bagi masyarakat Jawa, ziarah ke makam seseorang, baik tokoh atau keluarga, bahkan orang asing sekali pun, tak boleh dilakukan sembarangan. Bahkan dalam benak anak-anak kecil—seperti yang saya temui di kampung saya—etika dalam berziarah ke makam telah menubuh. Seperti halnya tidak boleh melangkahi makam, tidak ramai dan berbicara kotor di makam, tidak merusak tanaman serta menjaga kebersihan di lingkungan makam.
Oleh karena itu dalam ziarah kubur ada beberapa etika universal yang diamini oleh mayoritas masyarakat Jawa, di antaranya (1) tidak merusak makam; (2) menjaga kebersihan dan ketenangan; (3) sikap hormat pada tanah dan sesama makhluk.
Etika ziarah kubur tersebut dapat menjadi sebuah etika ekologis yang sudah sepatut-layaknya tak hanya diberlakukan di kubur. Melainkan juga perlu dilaksanakan di pelbagai tempat guna kelanjutan ekologis.