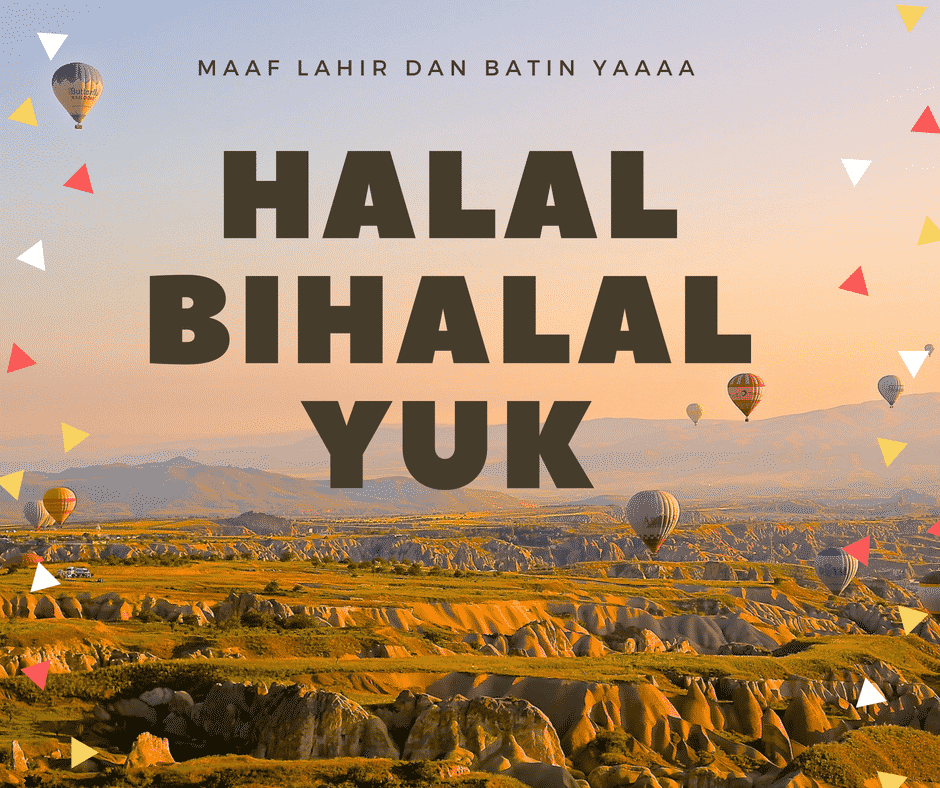Sesekali, Mari Membincangkan Ayam yang Kita Makan

Selama hayat masih bertemu Ramadan, ayam-ayam masih turut mengisari waktu-waktu suci ini. Ayam terbit bukan sebagai pembangun waktu sahur atau membawa keresahan akan nelek di lantai teras rumah. Di bulan Ramadan, ayam tetaplah menu yang memasuki kardus-kardus takjil, meja-meja restoran, warung lesehan, atau meja rumah kita.
Pengorbanan ayam yang suci selama sebulan penuh menentukan kadar raga kita mengartikan lapar. Meski pasar
mengabarkan harga daging ayam atau telur ayam naik, Ramadan selalu butuh ayam hingga Lebaran tiba.
Keterjangkauan telah membuat ayam menjadi menu yang mudah diolah dan didapat dalam momentum yang bersifat syukur dan bersama; slametan, kenduri, bancakan, syukuran, dan akhirnya buka bersama.
Menu yang ditentukan dalam cething, kardus, atau prasmanan tidak mungkin meluputkan olahan unggas ini. Pun hampir dapat dipastikan bahwa kebanyakan orang tidak mengajukan keberatan atau mengalami gangguan kesehatan parah. Ayam tetap diterima tanpa perlawanan meski, sesekali, ada decak kebosanan.
Sebelum ayam lebih menjejak sebagai menu, kolonialisme di Indonesia pernah memiliki kisah yang aneh ihwal ayam. Kaum kulit putih yang sedemikian rasis dan diskriminatif terhadap kaum pribumi, ternyata begitu memuja ayam hitam Sumatra atau Black Sumatra, fauna khas Pulau Sumatra. Sekitar 1888, ayam-ayam hitam ini dikapalkan ke negeri Belanda (Media Indonesia, 19 Desember 2017).
Pesona Black Sumatra hadir dari penampakan ‘kebangsawanan’ fisik; bulu hitam legam dan bulu belakang menjuntai. Ayam-ayam diakui sebagai pendatang kehormatan yang mendapatkan kedudukan paten meski mereka tidak bergelar raden, datuk, baginda raja, atau student.
Di Indonesia, black sumatra justru mengalami kepunahan. Mereka harus dipulangkan dan dinasionaliskan dengan ongkos yang cukup besar.
Misi Sosial
Ayam adalah binatang paling sosialis yang berkisar di keseharian dari soal kultural, pengasuhan keluarga, sampai spiritualitas. Seperti peristiwa slametan atau syukuran di Jawa, selalu ada sajian ayam yang menggenapi solidaritas masyarakat. Ingkung atau sesembahan ayam utuh selalu dipercaya sebagai bentuk penyerahan diri.
Kita pun mengingat biografi masa kecil yang seringkali bersentuhan dengan ayam sebagai bentuk pengasuhan keluarga.
Ada ayam sebagai hadiah hari kelahiran, pamrih atas prestasi, atau perayaan hari Lebaran yang sering membuat anak-anak menjadi makhluk paling kaya di jagat raya. Bocah-bocah di masa lalu biasanya membelanjakan uang Lebaran untuk ayam.
Memelihara ayam pun serupa ujian sekaligus keseruan. Bukan benda lain sengaja dibeli dan diberikan karena orangtua ingin anak mengaktualisasikan tanggung jawab, kedewasaan, keprigelan, dan kasih.
Kita cerap saja cerita yang kocak sekaligus agak intelek Bakdi Soemanto (2002) dalam cerpen “Ayam Petelur”.
Si tokoh aku bercerita bahwa pada usia sembilan tahun diberi oleh ibunya ayam petelur sebagai hadiah ulang tahun. Ayam menjadi anggota keluarga baru yang merekam kejahilan masa kanak sekaligus mengusik kepriyayian sang bapak yang lebih mengidolakan ayam bekisar nan molek. Apalagi, ayam itu sering usil masuk ke kamar buku bapak.
Si tokoh melanjutkan pengasuhan ayam meski sering kesal oleh ulah si ayam. Sampai suatu hari terjadilah si ayam bertelur di kamar buku, tepatnya di atas Encyclopedia Britanica.
Bapak justru memberi selamat dan mengatakan, “Ayam kamu telah melahirkan bakal kehidupan.”
Kekesalan telah berganti ketakjuban dan si anak merasai kelahiran yang juga bisa dikatakan sebagai rasa kepuasan batin mengantarkan pada kehidupan baru. Tentu, ayam tidak lagi populer sebagai hadiah ulang tahun atau pamrih atas prestasi.
Selain tata sosial dan lingkungan keluarga yang tidak mendukung, hadiah ayam hidup lebih akan menghadirkan konflik daripada pengajaran. Bagi anak-anak urban, akan lebih mudah memelihara ayam dalam bentuk virtual, entah lewat gim atau emotikon.
Ayam-ayam itu yang didaulat menghimpun poin- poin keberhasilan daripada sebuah petuah kecil; bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam!
Gizi umat penghayat Ramadan memang tertentukan oleh aneka sajian mahasuci; ayam geprek, ayam peyet, ayam bakar, ayam goreng, ayam balado, ayam kentaki, mi ayam, ayam teriyaki, sop ayam, rica ayam, dan nuget ayam. Namun, masa depan ayam juga membawa arti bagi masa depan petuah, tamsil, atau perumpamaan.
Kita masih membutuhkan ayam bukan saja sebagai hidangan siap santap di meja kuliner yang aduhai nikmat. Pun, bukan ayam dalam gambar yang telah terpotong di setiap bagiannya dan berlumur tepung kriuk. Kita membutuhkan ayam sebagai entitas, pengantar pada manifestasi spiritual sehari-hari.