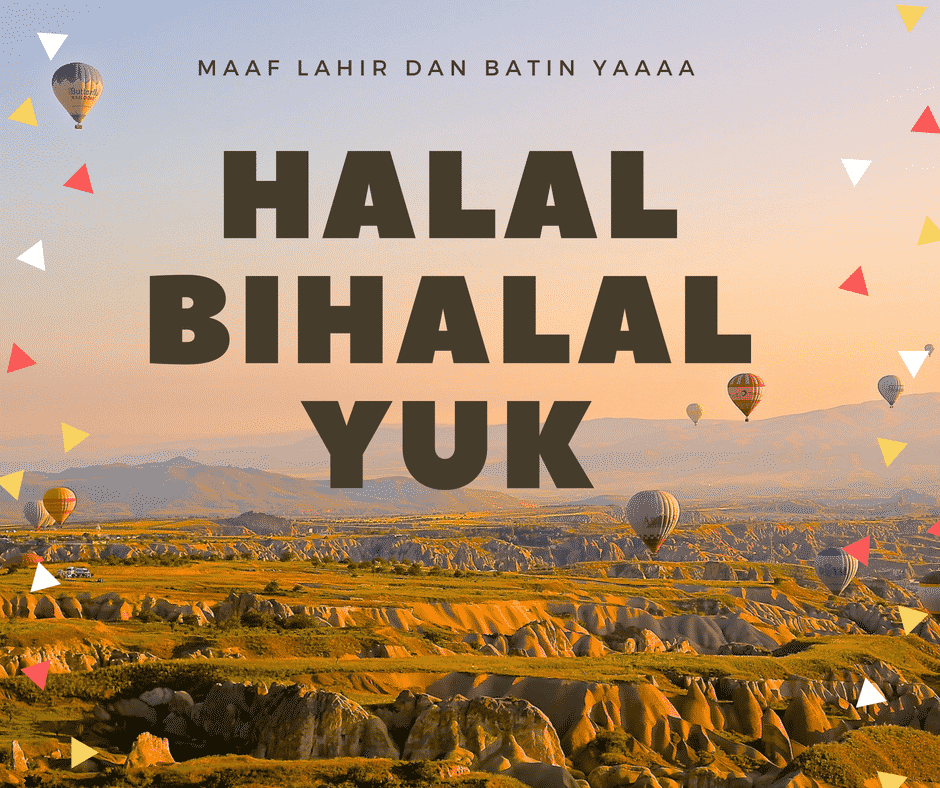Di memoar berjudul Emakku Bukan Kartini (2018) oleh akademikus Hasanudin Abdurakhman, dikisahkan pengalaman yang unik ihwal mudik. Hasanudin mengalami masa kanak di kampong Teluk Nimbung, Kalimantan Barat. Semasa kecil tahun 1970-an, dia mengalami “mudik” bukan sebagai peristiwa pulang ke kampung.
Mudik bagi Hasanudin dan emak adalah pergi ke kota Pontianak setiap sebulan atau dua bulan sekali untuk membeli barang-barang dagangan. Perjalanan memuat persiapan yang sama istimewa, dari bekal makanan di kapal sampai baju ganti yang pantas atau bagus. Selain itu, tidak banyak juga orang kampong pernah ke kota.
Peristiwa mudik tetap membawa diri pada makanan yang khas. Di kota, ada sajian sate berikut penjualnya yang khas, semacam menempati biografi khusus pada diri Hasanudin. Dia menulis, “Potongan isi ketupat ia tempatkan di dalam pinggan. Lalu ia menuangkan sesendok besar kuah ke piring, kemudian meletakkan sepuluh tusuk sate daging sapi di atas potongan ketupat. Sesedok bumbu kacang dan beberapa iris timun serta bawang goreng ia tambahkan kemudian.”

Hasanudin bukan bocah yang sering menikmati makanan di warung. Dia menuliskan alasan terkenang akan sate, dengan menguatkan peran ibu sebagai sumber pertama masakan enak.
Rasa sate ini, manis bercampur gurih, enak sekali. Emak pandai memasak. Aku selalu lahap bila makan masakan Emak. Tapi Emak tak pernah masak sate, karena tak pandai. Di berbagai pesta hajatan di kampong juga tak ada orang menghidangkan sate, pun tak ada yang menjualnya di kampong kami. Aku baru bisa makan sate kalau sedang ke kota seperti sekarang.”
Ada penegasan jarak dan peralihan raga untuk menunjukkan makna mudik. Juga secara tidak langsung, mudik selalu lekat mengajak pulang kepada makanan yang dicitrakan dengan khas, entah rasa, cara penyajian, wadah, atau tukang masaknya. Makanan membuat pulang terasa bertuah.
Meski makanan sebagai produk industrial gencar memasuki meja rumah-rumah sejak dua dekade terakhir, tetap ada yang dibuat dengan mengandalkan tradisi. Seperti masih saya temukan di desa saya; tape ketan, jenang, jadah, karang gesing.
Tangan kuliner sakti para tetua sungguh belum terkalahkan oleh mesih pabrik, “Yang akan Anda temukan adalah makanan segar dan utuh yang dipanen pada puncak kualitas rasa dan nutrisi—jenis-jenis makanan yang akan dikenali nenek buyut, atau bahkan nenek moyang Anda, sebagai makanan. Jenis makanan yang hidup dan akhirnya akan membusuk” (Michael Pollan, 2011).
Di buku Kembali ke Jati Diri, Ramadhan dan Tradisi Pulang Kampung dalam Masyarakat Muslim Urban (2013), akan didapati sekian pengakuan dari para tokoh dan intelektual Muslim di masa menjalani Ramadan dan Lebaran. Sekian pengakuan merujuk pada makanan sebagai pengisahan di masa lalu bergerak ke masa kini.
Ismed Natsir, mantan editor di LP3ES dan Grafiti Press, bercerita bahwa kesibukan menjelang Lebaran berpusat di dapur oleh ibu, anak, dan kerabat. Ismed bercerita,
“Ibu saya juga mengajari kami untuk ikut menyiapkan kue-kue untuk hidangan di Hari Raya. Saya membantu mengupas kacang bawang dan membantu memarut kelapa untuk membuat dodol.”
Makanan tidak muncul secara instan. Mekanisme menyiapkan makanan menghendaki kesabaran. Kampung halaman Ismed di Lampung menahbiskan dodol sebagai menu tradisi bersamaan dengan makanan ala Minang; rendang dan lemang tapai.
Namun, kita juga dihadapkan pada rutinitas membawa oleh-oleh atau hantaran mudik. Rumah menciptakan makanan, pemudik tetap membawa makanan yang biasanya ingin mengesankan beda dan istimewa.
Koran Suara Merdeka 3 Juni 2019 menampilkan liputan kuliner Lebaran berjudul “Sensasi Telur Asin Empat Varian Rasa Khas Brebes.” Liputan mewartakan bahwa arus mudik dan balik Lebaran membuat permintaan telur asin naik. Orang tidak lagi dibuat ingin menikmati telur asin (original), tapi juga telur asin panggang, telur asin asap, dan telur asin pindang dengan bumbu menempel di cangkang telur.
Brebes menyisakan ingatan sebagai pusat kuliner Lebaran, bukan lagi kota yang hanya dilewati. Di hari biasa, telur asin dipersepsikan biasa saja. Lebaran bisa membuatnya menjadi sajian religius dan kekeluargaan sekalipun secara material bisa menambahi bawaan.
Pembauran
Rumah sebagai sumber kepulangan berperan dalam pemilihan menu. Namun, lokalitas tidak menampik modernisasi untuk menyesuaikan dengan lidah masa kini. Inilah yang dilakukan oleh buku kumpulan resep edisi Lebaran seperti Femina yang menerbitkan Hidangan Lebaran ’99 (1999). Resep lumayan lengkap menampilkan hidangan dari daging dan ayam, olahan sayur, kue basah dan kering, minuman, dan juga puding.

Di pengantar dikatakan, “Lewat edisi khusus femina, Hidangan Lebaran 1999, Anda dapat menyusun menu jamuan, atau antaran Lebaran yang istimewa. Resep-resep warisan nenek-nenek kita tempo dulu kami kumpulkan, lalu diubah di sana-sini agar lebih cocok dengan selera orang masa kini.”
Buku resep lahir di masa-masa krisis moneter, redaksi pun meyakinkan terutama para ibu bahwa ada resep-resep yang bahannya mudah didapatkan dan pasti ekonomis. Untuk momentum Lebaran yang sering melipatkan ongkos kebutuhan, godaan ini tentu sangat persuasif. Lodeh pepaya muda, kari ayam, atau rempeyek kedelai hitam menempati status (sosial) hidangan pertengahan. Tidak terlalu mewah, tapi pantas.
Edisi lebih lawas, Femina pernah menerbitkan Hidangan Lebaran Indonesia (1990). Sejak judul, ada penegasan wilayah sebagai penentu lokalitas, kekhasan bumbu, atau bahan yang digadang “asli” secara kultural. Lebaran harus menghidangkan makanan Indonesia, bukan sajian ke-Arab-an apalagi western.
Meski Lebaran lebih lekat dengan peristiwa keagamaan, hidangan yang berkesan kultural-nasionalis adalah muasal. Daftar isi di antaranya memuat Hidangan Lebaran Banten, Hidangan Lebaran Lampung, Hidangan Lebaran Ternate, juga menyajikan kemungkinan pembauran budaya karena bisa memasak keragaman hidangan dari pulau lain. Buku resep juga mengobati rasa kangen orang-orang urban yang tidak bisa pulang ke kampung halaman dan rindu menyajikan sendiri hidangan asalnya.
Pulang ke makanan (Lebaran) adalah naluri primordial manusia setara dengan bertemu orangtua, kerabat, tetangga, atau teman masa kecil. Dalam momentum semacam ini, bukan saja kekenyangan duniawi-biologis perlu dirayakan. Juga ada perayaan kultural dan kekeluarga bersifat esensial ingin direngguk meski dengan susah payah.